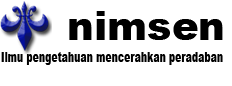Oleh : Drs. J A S M A N
“Sebenarnya ide itu dulu asalnya dari Rudini, lalu
Pak Habibie mau mewujudkannya. Disaat saya presentasikan naskah UU No. 22 itu
didepan sidang kabinet, Pak Habibie kemukakan usul itu (dengan alasan efisiensi
dan stabilitas politik) dan sudah disetujui semua anggota kabinet. Saya sendiri
yang tidak setuju dan menjelaskan bahwa kalau itu dilakukan, kita akan mundur
ke zaman kolonial. Jadi turun kelas namanya. Lagi pula menghapus 27 propinsi
(waktu itu) adalah tidak sederhana. Semua Parpol akan bereaksi negative karena
kehilangan kursi. Akhirnya kabinet menerima argument saya. Jadilah propinsi
tetap otonom, walau sifatnya terbatas karena Gubernur tetap merangkap sebagai
wakil pemerintah pusat”.
(SMS Prof. DR. H. M. RYAAS RASYID, MA tanggal 22 Februari 2007
pukul 17.27 WIB kepada Penulis)
Itulah pendapat Ryaas Rasyid waktu saya minta komentarnya tentang wacana yang digelindingkan Gamawan Fauzi yang juga seorang Gubernur Sumatera Barat tentang penghapusan Pemerintahan (bukan Pemerintah) tingkat Propinsional.
Dalam hal ini saya tidak akan ikut-ikutan berdebat guna memperdebatkan pendapat St. Zaili, Suharizal dan lain-lain orang-orang cerdik cendikia di Sumatera Barat tentang wacana Gamawan tersebut, tetapi lebih menelisik kepada substansi atas sejarah timbulnya ide tersebut (minus Gamawan), dan saya tidak akan terjun menelaah pasal demi pasal dalam UU No. 32 sehingga pada ujung-ujungnya nanti saya akan lebih banyak berkutat tentang ide siapa dan kapan sebenarnya wacana penghapusan pemerintahan tingkat Propinsi itu dilontarkan.
Coba simak baik-baik pernyataan (bukan pendapat) Ryaas Rasyid tersebut diatas. Sebenarnya tampa saya uraikan lebih detail maksud SMS tersebut, kalangan manapun akan mampu menafsirkannya tampa perlu pasal penjelasan. Disini tergambar jelas bahwa ide Gamawan itu bukanlah hal yang baru (kalau boleh dikatakan tidak orisinil lagi), tetapi telah ada sejak zamannya Pak Rudini menjabat Mendagri. Ide ini kemudian dilanjutkan oleh Habibie (terlepas dari berbagai polemik tentang keabsahannya sebagai Presiden) dengan alasan efisiensi dan stabilitas politik, dan perlu dicatat bahwa mayoritas kabinet telah menyetujuinya, kecuali seorang Ryaas Rasyid yang memandang dari sudut lain.
Dari beberapa perbincangan dan diskusi saya dengan Ryaas Rasyid (pada waktu reuni Ikatan Alumni Pendidikan Pamong Praja se Sumatera Barat yang diprakarsai oleh Walikota Solok yakni Bapak Syamsu Rahim bertempat di Hotel Taufina Kota Solok bulan April 2006), sebenarnya beliau dan beberapa teman-teman dari kalangan akademisi, birokrat serta politisi telah terlalu kecewa dengan perjalan otonomi pada saat kesekarangan ini, walaupun telah diperbaiki dengan UU No. 32 tahun 2004.
Sehingga wajar banyak pendapat dari kalangan manapun tentang perjalanan otonomi, sehingga wajar juga jika seorang Gamawan-pun “terlanjur” berpendapat bahwa pemerintahan (bukan pemerintah) tingkat propinsi ini dihapuskan saja, Gubernur adalah wakil pemerintah pusat dan cukup ditunjuk oleh pusat. Alasan beliau adalah demi efisinesi dana, banyaknya kewenangan antara Kabupaten/Kota yang saling bertabrakan, sehingga tidak jelas siapa yang bertanggung jawab terhadap kewenangan tersebut karena adanya tumpang tindih dalam pelaksanaannya.
Tetapi mungkin perlu dilihat implikasi dari pendapat Gamawan tersebut. Akan ada ratusan peraturan perundang-undangan yang akan lenyap dan untuk pengaturan lebih lanjut dan akan muncul ratusan peraturan perundang-undangan yang baru sebagai pengganti aturan yang lama. Yang paling krusial adalah termasuk mengamandemen UUD 1945 pasal 18 yang mengatur masalah otonomi daerah. Melihat hal yang demikian, maka akibat pelaksanaan ide Gamawan (atau lanjutan cetusan ide Rudini) akan membutuhkan energi nasional yang sangat besar, baik disegi dana, waktu dan belum lagi dampak politis serta gejolak yang tumbuh ditengah-tengah masyarakat. Saya rasa Pak Gubernur menyadari dampak yang multi effect tersebut, tetapi yang namanya buah pikiran, halal saja cetusan ide ini dilontarkan ketengah-tengah khalayak.
Sebelumnya saya akan coba mengajak pemikiran kita flash back pada saat proses reformasi menjadi jargon, konsep dan bahkan landasan perspektif di semua lini. Dalam berbagai pembahasan persepektif ekonomi, perspektif hukum, politik dan lain-lain, maka eforia reformasi bergema dan bergaung keras kemana-mana, seolah-olah kata-kata reformasi adalah kata-kata suci yang mesti mau tak mau atau suka tak suka harus dijadikan landasan acuan untuk mengimplentasikan berbagai kebijakan. Berbagai persepsi diapungkan, berbagai penafsiran didefinisikan untuk ikut “nimbrung” masalah reformasi atau agar kita jangan dianggap sebagai orang tidak reformis maka kata-kata reformasi harus diselipkan disetiap pidato, pokok pikiran tulisan-tulisan dan lain-lain.
Makanya berbagai tuntutan dari Daerah bermunculan seiring dengan makin nyaringnya alunan reformasi bernyanyi di tengah-tengah jagad politik Negara kita. Tuntutan kepada pusat yang mengemuka sebenarnya bukan pada perubahan bentuk Negara (tata pemerintahan), tetapi lebih kepada menuntut keadilan dalam pembagian hasil kekayaan alam secara berimbang . Walaupun pada mulanya yang muncul kepermukaan adalah wacana Negara federal yang mengerucut pada pemisahan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetapi pada akhirnya diketahui bahwa substansi sebenarnya adalah minta keadilan dalam berbagai hal. Adil dalam artian tidak sama besar, tetapi adil yang proporsional.
Makanya kemudian muncul UU No. 22 tahun 1999 yang menurut pemerintah pusat agak “lepas kendali” dan “terlalu desentralistik” karena terpengaruh eforia reformasi sehingga sangat mengurangi kekuasaan pemerintah pusat ke daerah dan propinsi tidak punya power apapun terhadap pemerintah Kabupaten/Kota. Disamping adanya kekhawatiran pemerintah pusat akan terjadinya bias terhadap persepsi otonomi daerah itu sendiri. Tetapi yang sebenarnya adalah, pemerintah pusat merasa ditinggalkan oleh anak-anaknya, sebab dibanyak kasus ada beberapa daerah Kabupaten/Kota yang dianggap keblablasan dalam mengimplementasikan otonomi itu sendiri. Untuk itu perlu dikendalikan lagi dengan instrument baru, UU No. 22 tahun 1999 harus direvisi. Maka dibuatlah isu tentang kegagalan UU No. 22/1999 tersebut yang akhirnya berujung dengan direvisi dan bahkan mengubah beberapa pasal-pasal “liberal” sehingga menjadi UU yang agak jinak dan bisa dikendalikan oleh pemerintah pusat.
Kembali kita kembali pada substansi pembicaraan pada tulisan ini, bahwa idealnya dengan keluarnya UU No. 32 tahun 2004 tersebut adalah : secara politis, pergeseran penyelenggaraan pemerintahan dari sentralistik ke desentralistik akan dapat meningkatkan kemampuan dan tanggungjawab politik daerah, membangun proses demokratisasi (kompetisi, partisipasi dan transparansi), konsolidasi integrasi nasional (menghindari konflik pusat daerah dan antar daerah). Secara administrative akan mampu meningkatkan kemampuan daerah merumuskan perencanaan dan mengambil keputusan strategis, meningkatkan akuntabilitas public dan pertanggungjawaban public. Secara ekonomis akan mampu membangun keadilan di semua daerah (membangun bersama), mencegah eksploitasi pusat terhadap daerah, memberikan public good and services serta meningkatkan kemampuan daerah.
Dengan demikian sah-sah saja rasanya jika seorang Gamawan berpandangan lain tentang idealisme konsepsi keotonomian yang ada sekarang dalam bentuk UU No. 32 Tahun 2004. Mungkin hal ini didasari karena pengalaman empiric beliau sebagai birokrat. Mungkin lain halnya jika beliau tidak seorang birokrat karena tidak mempunyai pengalaman langsung di lapangan.
Saya masih ingat dengan ujar-ujar pada waktu masih kuliah, seorang dosen yang merupakan mantan Kepala Daerah menyatakan : bahwa apa yang anda perdapat hari ini tidaklah akan relevan dilapangan. Karena kenyataan dilapangan akan sangat berbeda dengan teori yang dipelajari hari ini.
Nah, mungkin dari kaca mata inilah seorang birokrat pada level tertinggi di tingkatan Propinsi (walaupun disebut juga pejabat politis, dan hal ini tidak perlu kita perdebatkan disini) yang berpendapat dan berpandangan berbeda dengan konstitusi otonomi daerah yang ada saat ini, yaitu UU No. 32 tahun 2004. Karena pada kenyataannya sampai hari ini, ide-ide yang ada di UU No. 32 Tahun 2004 tidaklah dapat menjembatani semangat otonomi itu kepada tataran yang diharapkan.
Wacana ini bisa saja muncul ketika seorang Gubernur merasa terlalu banyak diatur oleh pemerintah pusat. Banyak persoalan-persoalan di daerah sekarang yang harus mendapat persetujuan dari pusat. Kurangnya ruang gerak (flexibility space) daerah, tarik-menarik (kompabilitas) antara pusat dengan propinsi atau propinsi dengan Kabupaten/Kota. Banyaknya kewenangan yang “bahimpik-himpik” antara propinsi dengan Kabupaten/Kota. Disamping tidak efektifnya pembelajaan daerah. Kita masih ingat dengan pernyataan Pak Rudini kala itu yang menyatakan: DPRD Propinsi dibubarkan !!! Langsung semua daerah geger dan memberikan interprestasi yang beragam. Beliau juga menyatakan bahwa apa yang diurus propinsi lagi, karena masyarakat itu berada di daerah Tk. II (waktu itu). Domainnya propinsi mana ? Rakyat propinsi mana ? Wilayah atau daerah mana yang diurus propinsi ? Kan semua telah diurus oleh daerah Tingkat II. Jadi Propinsi cukup wakil pemerintah pusat, tidak perlu dipilih rakyat yang berkonsekwensi tidak perlu ada DPRD Tk. I.
Dalam perjalanan selanjutnya, isu ini dianggap tidak popular dan tidak mendapat respon yang cukup kuat di parlemen karena adanya kepentingan antara politisi daerah dengan pusat. Kemudian berbagai regulasi diluncurkan seiring dengan perkembangan politik dalam negeri, sampai terakhir lahir UU No. 32 tahun 2004 yang oleh sebagian politisi, akademi dan praktisi masih dianggap belum mampu mengimplementasikan otonomi itu sendiri, dalam artian masih ada pasal-pasal yang carut marut.
Dan timbulnya ketakutan (maaf, ini hanya dari perspektif saya saja ketika menangkap sinyal dari beberapa tulisan para pakar kita di berbagai media massa lokal) dari beberapa kalangan, mungkin karena dikhawatirkan Negara kita ini menjadi Negara Federal. Padahal ide Negara federal bukanlah hantu yang harus ditakutkan, karena kalau kita lihat proses penyusunan ketatanegaraan kita dulunya, wacana federalisme sesungguhnya pernah muncul ke the founding fathers hendak merumuskan bentuk Negara Indonesia di dalam UUD 1945, hanya seorang M. Yamin yang menolak bentuk Negara federal dan kemudian diperkuat oleh Soepomo.
Dalam perjalanan selanjutnya dengan kasat mata kita melihat adanya ketakutan pemerintah pusat yang mungkin merasa “tagurajai” dengan keluarnya UU No. 22 Tahun 1999. Entah ketakutan apa yang mendasari pemerintah pusat sehingga beberapa kewenangan kembali di “ambil” dari daerah. Bila kita bandingkan UU No. 22 tahun 1999 dengan UU No. 32 tahun 2004, maka terlihat jelas bahwa pada UU No. 32 tahun 2004, pemerintah pusat pelan-pelan telah menarik berbagai kekuasaan daerah atas daerahnya sendiri, dalam artian pemerintah pusat masih ¼ (seperempat) hati (bukan setengah hati) memberikan otonomi untuk daerah. Walaupun ada beberapa kewenangan yang diberikan pada Propinsi, tetapi saya menganggap itu merupakan kewenangan basa-basi atau kewenangan penghibur belaka agar ada jugalah senjata Propinsi kepada Kabupaten/Kota. Bak kata anak-anak muda tempo doeloe “pado indak sajo”.
Padahal inti dari pelaksanaan otonomi daerah adalah terdapatnya keleluasaan pemerintah daerah (discretionary power) untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri atas dasar prakarsa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya yang disesuaikan dengan potensi daerahnya masing-masing. Mungkin diskursus tentang hal ini telah banyak dikalangan akademisi dan praktisi, namun belum dapat dituangkan dalam peraturan yang ada.
Berangkat dari pernyataan Ryaas Rasyid tersebut, bahwa sesungguhnya wacana Gamawan telah ada sejak zamannya Pak Rudini, lalu kenapa sekarang ketika Gamawan mereview kembali suara masa lalu dengan nyanyian sama dengan musik yang berbeda, kok ada beberapa orang merasa aneh dan mencak-mencak, kemudian ingin jadi pahlawan dan menyatakan ketidaksetujuannya.
Persoalannya sekarang, apakah pernyataan Gamawan tersebut telah menjadi keputusan ? Kan belum, lalu kenapa rebut-ribut. Terlepas dari salah atau benarnya pendapat beliau, maka wacana tersebutkan hanyalah baru sebatas pendapat, belum tentu diambil hati oleh pemerintah pusat dan belum tentu semua daerah merespon dan mendukungnya. Karena implikasi politiknya sangat tinggi, maka tingkat kehati-hatian menalaah wacana ini-pun sangat hati-hati pula. Kesalahan Gamawan hanyalah tidak menyatakan bahwa ide ini adalah ide Rudini, murni bukan terlahir dari pemikiran beliau.
Dalam hal ini saya tidak berperan sebagai pembela pendapat Gamawan, tetapi lebih kepada objektivitas terhadap pemikiran atau pendapat akademis beliau sebagai seorang praktisi, yang walaupun dulu telah pernah menjadi agenda ditingkat nasional. Lalu kenapa kita harus jungkir balik mendengar pendapat seseorang yang mungkin bagi beberapa kalangan dianggap tabu dan aneh. Dimana rasa saling menghargai pendapat dikalangan masyarakat Minangkabau yang dianggap paling demokratis di dunia ini (bahkan dibandingkan dengan Negara Amerika).
Mungkin yang perlu kita pertanyakan ke seorang Gamawan adalah, dia itu mengeluarkan ide sebagai Gubernur, sebagai masyarakat atau sebagai akademisi ? Kalaulah dia berpendapat sebagai Gubernur, memang banyak interpretasi akibat pernyataannya tersebut, karena berada dalam koridor yang kurang tepat, sebab seorang Gubernur sampai saat ini masih diikat dan bahkan akan selalu terikat dengan tata keprotokolan. Kalau dia berpendapat sebagai masyarakat atau akademisi itu rasanya sah-sah saja. Tetapi persoalannya sekarang walau dia menyatakan bahwa pendapatnya itu sebagai rakyat atau akademisi, perlu dicatat bahwa budaya kita belum bisa membedakan antara individu dengan jabatan seseorang. Jadi kedepan saya minta Pak Gubernur berhati-hati dengan ucapannya. Kalau mau bicara secara akademis sebaiknya carilah saluran yang tepat. Secara bercanda saya pernah katakan, pensiun dulu jadi Gubernur baru bisa berpendapat demikian.
Ada juga yang berpendapat Pak Gubernur ingin menarik perhatian Pak Presiden karena adanya isu reshuffle cabinet, untung-untung dengan wacana ini ada harapan untuk jadi Mendagri. Sebab menurut beberapa kalangan di Pusat akibat PP. 37/2006 yang kontroversial tersebut, keberadaan M. Ma’ruf sebagai Mendagri telah diujung tanduk. Inikan baru satu pendapat, belum lagi pendapat lain yang bermacam-macam, jadi janganlah diambil hati.
Tetapi terlepas dari itu semua, marilah kita coba berdewasa diri dalam konteks pernyataan serta mengkritisi berbagai hal. Sungguh suatu ironi rasanya jika masyarakat Minangkabau yang selama ini terkenal tidak alergi dengan perbedaan pendapat bisa terkayuh ke locus perang tanding yang tak berujung.
Saya masih ingat pendapat Prof. Baharuddin Tjenreng, Prof. Ryaas Rasyid dan Prof. Miriam Budiardjo yang kemudian di perkuat oleh Prof Ichlasul Amal yang menyatakan bahwa: “…beruntunglah kita di Indonesia ini memiliki suatu komunitas suku bangsa yang sangat demokratis, bahkan sebelum konsep demokrasi itu sendiri belum dikonsep oleh para ahli dari Romawi dan Yunani serta Amerika Serikat sendiri, masyarakat Minangkabau telah menjadikan prinsip dan azaz-azaz demokrasi menjadi peradaban dalam kesehariannya. Kalaulah tidak ada komunitas ini yang diwakili oleh Bung Hatta, Syahrir, M. Yamin, Agoes Salim dan lain-lain, entah jadi apa Negara kita sekarang, mungkin pasal 18 UUD 45 tersebut tidak akan pernah ada. Keberadaan pasal ini adalah asli perjuangan besar dan berat oleh komunitas Minangkabau, karena pada saat konstitusi disusun, hampir semua tim yang mayoritas suku Jawa menginginkan Negara dalam bentuk Monarkhi… dstnya”.
Oleh karena itu, biarkan silang pendapat berpendar dalam dunia kita, sepanjang tidak menjurus kepada hal-hal yang pribadi. Karena dengan bersilang pendapat inilah kematangan ilmu dan emosi kita dipertaruhkan, dan jangan akibat perbedaan pendapat akan berimplikasi kepada hal-hal lain yang sangat tidak rasional dan subjektif. Marilah kita berdewasa diri, sesuai dengan ajaran agama kita, karena sesungguhnya perbedaan pendapat itu adalah rahmat.