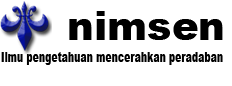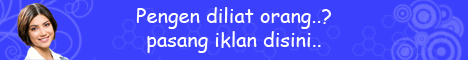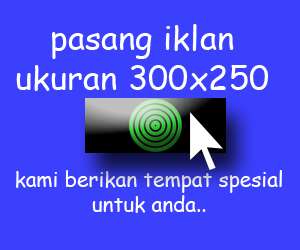Oleh Saiful Arif dan Paring W. Utomo
A. Pengantar: Good Governance dan Demokrasi
Indonesia
adalah bangsa yang direkayasa dan diciptakan sedemikian rupa oleh sistem
ketidakadilan yang berupa penjajahan, karenanya Indonesia adalah kolektifitas
di mana individu bisa hidup (dan berharap untuk hidup) dengan pelbagai
kepentingan, bangsa, agama, dan ideologinya. Dengan demikian, jika ada sebuah
pemerintahan yang diatur berdasarkan kedzaliman politik, tentu ia adalah
pemerintahan yang tidak acceptable oleh rakyatnya. Orde Baru adalah misal
dengan sentralisasi rezim dan kekejaman cara memerintahnya, kalaupun toh ia
berumur panjang, pastilah ia akan menemui ajalnya juga (dengan tak terhormat).
Karena itu, demokrasi di Indonesia menjadi sebuah barang yang mesti ditegakkan
dengan segala resikonya, termasuk kealotan penyelesaian persoalan bangsa,
ketidakefektifan, keruwetan dan sebagainya. Mau tidak mau, demokrasi menjadi
pilihan tak tertolak bagi pemerintahan dewasa ini. Dalam situasi di mana
segenap persoalan bangsa meluap dan minta segera diselesaikan, maka konsep
demokrasi sesungguhnya merupakan konsep yang paling tidak diminati. Di samping
terlalu bertele-tele, tidak efektif dan tidak efisien, demokrasi juga terlalu
banyak menyita waktu yang sebenarnya bisa digunakan untuk memikirkan masalah
yang lebih urgen lagi. Di sinilah titik nadzir yang paling lemah dari
demokrasi. Semua orang dan semua bangsa mengakuinya. Namun kita lantas
bertanya, mengapa demokrasi menjadi satu-satunya konsep yang dipilih hampir
seluruh bangsa di dunia ini untuk menyelesaikan pelbagai macam persoalannya?
Untuk bisa sampai pada jawaban pertanyaan ini, maka satu hal yang mesti kita
sadari bahwa alam ini memang sudah ditaqdirkan Tuhan untuk tidak sama.
Pluralitas suku-bangsa, pluralitas kepentingan, pluralitas ideologi, pluralitas
agama dan pelbagai macam ketidaksamaan yang lain adalah conditio sine qua non.
Kondisi inilah yang menginginkan masyarakat dunia untuk segera merombak cara
berpikir yang sentralistis, cara berpikir yang otoriter dan semaunya sendiri.
Untuk menciptakan demokrasi, tentu tidak hanya melalui jalur kultural seperti
paparan di atas, di jalur struktural pun jika kita jujur dan teliti,
sesungguhnya ada jalur untuk menciptakan demokrasi itu.
Tata
bangsa yang sehat dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme adalah sesuatu
yang pasti dari prinsip good governance ini, dan tentu saja merupakan sesuatu
yang sangat dirindukan masyarakat Indonesia. Terpilihnya pemimpin-pemimpin baru
merupakan bagian dari kehendak rakyat yang menginginkan terciptanya hal itu.
Perdebatan yang sangat sengit ini paling tidak sudah dilakukan di sidang
majelis kita selama sepekan kemarin. Dari upaya bagaimana melakukan amandemen
UUD 1945 sampai pada tata pemilihan yang demokratis. Harapan-harapan rakyat
adalah bagaimana agar mereka bisa hidup lebih sejahtera secara ekonomi maupun
politik. Secara ekonomi, rakyat Indonesia menginginkan kenaikan pendapatan
perkapita, harga-harga kebutuhan pokok (merit goods) yang tidak mahal,
berkurangnya angka kemiskinan, turunnya inflasi dan pelbagai indikasi kemakmuran
lainnya. Secara politik, rakyat berkehendak agar demokrasi bisa berjalan
sebagaimana mestinya: menghargai hak menyampaikan pendapat, menghormati hak
asasi manusia, bebas berkreasi dan berorganisasi, dan penghargaan-penghargaan
terhadap kebebasan berpendapat lainnya. Sebagai manifestasi dari harapan dan
aspirasi rakyat banyak, terpilihnya mereka (yang dianggap reformis) tersebut
tentu saja diiringi oleh berbagai agenda bangsa yang mendesak dan berat. Di
sisi ekonomi, keduanya diharapkan agar mampu mengembalikan kepercayaan (trust)
terhadap investasi, juga untuk mencegah dan mengantisipasi capital flight.
Kepercayaan ini merupakan modal yang sangat penting bagi pembangunan ekonomi
Indonesia masa depan. Kita tahu bahwa untuk mengembalikan kepercayaan yang
hilang, tidak hanya dibutuhkan sosok pemimpin yang tegar, berwibawa dan
dikehendaki rakyat, tapi juga sosok yang mampu berkomunikasi dengan baik di
dunia internasional.
Bersikap jujur pada rakyat adalah titik tolak untuk menciptakan pemerintahan yang tidak hanya kuat (stong government), melainkan juga pemerintahan yang bersih dan berwibawa (good governance). Dengan kesadaran baru, Indonesia masa depan harus dibangun dengan mentalitas dan budaya berdemokrasi yang baru pula. Sehingga agenda mendesak pemerintahan kali ini adalah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab. Tentu saja bertanggungjawab pada rakyat.
B. Otonomi Daerah
“It
is a given perception that decentralization is the most popular government system. In the latest annual report, The World Bank stated that 95 percent of democratic nations have now elected sub-national governments, and countries everywhere – large and small, rich and poor are developing political, fiscal
and administrative powers to sub-national tiers of government”.
Kebijaksanaan
pemerintah pusat yang selama ini mengesankan adanya sistem pemerintahan dan
pembangunan yang sentralistik, pada dasarnya adalah faktor penjelas
berkembangnya keinginan beberapa daerah untuk memisahkan diri dari wilayah NKRI.
Seperti yang dijelaskan oleh E. Koswara, dampak dari reformasi total ini, ditinjau dari segi politik dan ketatanegaraan, adalah terjadinya pergeseran paradigma dari sistem pemerintahan yang bercorak sentralistik ke arah sistem pemerintahan yang desentralistik.2 Apa yang digambarkan tersebut, tentu bukanlah sesuatu yang berlebihan. Kepemimpinan politik dan pemerintahan yang dijalankan secara sentralistik oleh rezim Orde Baru adalah cikal bakal bagi terselenggaranya sistem pemerintahan yang tidak memberi kesempatan kepada daerah untuk maju dan berkembang. Dalam tataran reformasi, maka wajar bila terjadi perubahan pada salah satu substansi dari sistem pemerintahan sentralistik itu.
“Decentralization
and local autonomy may be better understood against the opposite tendency of
decentralization. Excesessive centralization or centralism is by definition bad
for any organism and organization. Decentralization is also a natural tendency
that may occur with centralism, simultaneously or alternately….. Under a centralist
regime, of course, there is hardly, if any local autonomy. Central control
stifles any initiative, discretion or self reliance that to begin with their
identity having been suppressed by the dominance or primacy of the central
government”
“The decentralization interprets as a bargaining process between central and sub-nation government and in their report, The World Bank describes that one of primary objectives of decentralization is to maintain political stability in the face of pressure for localization. Then it is acknowldged that when a country finds itself deeply divided, especially along geographic or ethnic lines, decentralization provides an institutional mechanism for bringing opposition groups into a formal, rule-bound bargaining process”.
Berkembangnya
wacana tentang perlunya memikirkan kembali desentralisasi dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan di Indonesia, dianggap relevan bukan hanya karena
faktor reformasi semata. Jika kita merujuk kepada aturan main 1 The World Bank Report
1999 – 2000, Decentralization Rethinking Government. yang tertuang dalam
konstitusi (UUD 1945), jelas bisa ditemukan bahwa desentralisasi tidak cuma
konsep yang bersifat politis, tapi juga konsep yang anti-sentralistik. Hal
inilah yang pada akhirnya membawa kita pada sebuah kesepakatan untuk
merealisasikannya dalam wujud otonomi daerah. Berangkat dari argumen bahwa
masalah otonomi adalah masalah masyarakat, perilaku hidup, perilaku aspirasi
masyarakat setempat,5 maka apa yang dinamakan sebagai ketegangan antara
pemerintah pusat dengan pemerintah daerah semestinya bukan lagi merupakan
fenomena politik yang menarik. Sebagai wujud nyata dari konsep desentralisasi,
otonomi daerah adalah topik utama yang wajib dibicarakan dan diimplementasikan
sedini mungkin. Mengakhiri ketegangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah
daerah tampaknya bukan hanya telah menemukan ruang yang tepat, tapi juga
sekaligus menjadikannya sebagai kenangan politis masa lalu yang perlu dicatat
oleh sejarah. Karakter hubungan antara pusat dan daerah yang terjadi ketika
Orde Baru berkuasa, sangatlah miris. Pada saat itu, pemerintah pusat adalah
segala-galanya dan memiliki berbagai senjata untuk mengebiri pemerintah daerah.
Dalam pandangan Pratikno, sentralisasi sumberdaya politik dan ekonomi di tangan
sekelompok kecil elit di pemerintah pusat adalah konsekuensi yang melekat dari
sistem politik otoritarian tersebut.6 Walaupun beberapa penjelasan lain
memberikan kesimpulan yang tidak jauh berbeda, karakter ini jelas tidak dapat
dibantah lagi kebenarannya. Otonomi daerah yang digembar-gemborkan Orba,
kenyataannya belum diikuti political will para aktor pelaksananya.
“There
is no doubt that Indonesia is in a chronic state of crisis. However, the
Indonesian nation-state is unlikely to disintegrate at the moment. This
situation could change in the future if the authority of the Abdurrahman regime
wanes, if the decentralisation laws fail when implemented and if Aceh and Papua
succeed in their bids to achieve independence”7
“Indonesia has not yet reached the point where it can take its national unity for granted. In reality it is unlikely to arrive at such a point, but it does not follow that Indonesia will fracture and collapse (Robert Cribb; 1995)
“Indonesia has not yet reached the point where it can take its national unity for granted. In reality it is unlikely to arrive at such a point, but it does not follow that Indonesia will fracture and collapse (Robert Cribb; 1995)
Semangat
inilah yang mengongkritkan implementasi otonomi daerah di era reformasi ini,
dan selayaknya harus mendapatkan dukungan yang memadai. Lahirnya UU No. 22/1999
tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pusat dan Daerah,8 adalah bukti masih terdapatnya semangat yang kuat dan
idealisme yang tinggi dari para penyelenggara negara untuk tidak sekedar
mengurusi kekuasaannya semata.
Di
sisi lain dominasi pemerintah pusat yang selalu berhasil dalam mempolitisasi
otonomi daerah, diyakini atau tidak, merupakan salah satu sebab belum
terealisasinya otonomi daerah secara empirik. Seperti yang diungkapkan Afan
Gaffar, upaya untuk mewujudkan otonomi bagi daerah dalam rangka negara kesatuan
sedikit banyak ditentukan oleh “political configuration” pada suatu kurun waktu,9
menunjukkan betapa kuatnya posisi politik pemerintah pusat dalam mengendalikan
jalannya pemerintahan secara nasional.
Dalam pemikiran lain yang lebih praktis, Kimura Hirotsune menjelaskan tentang munculnya dua persepsi yang berlawanan tentang otonomi daerah. Pertama, di satu sisi, otonomi daerah dianggap akan memenuhi kebutuhan daerah yang selama ini mengalami kekecewaan akibat praktek sentralisasi kekuasaan birokrasi yang opresif selama masa 32 tahun pemerintahan Presiden Soeharto. Kedua, pada sisi yang lain, otonomi daerah justru sebaliknya dianggap akan membangkitkan semangat separatisme sehingga bila tidak bisa terkendalikan maka akan mengakibatkan krisis politik nasional.
Ungkapan
bernada pesimis ini tentu bukan tanpa alasan mendasar. Pertama, konfigurasi
politik di suatu negara yang tengah menuju demokrasi, hampir selalu didominasi
oleh sifat kepemimpinan yang otoriter. Akibatnya, stabilitas politik dan
ekonomi tampak selalu dikedepankan, yang pada gilirannya menjadikan segala
policy pemerintah selalu pasti bersifat sentralistik. Kedua, konfigurasi
politik yang tidak diimbangi oleh adanya lembaga kontrol yang ketat, menjadikan
setiap kebijakan pemerintah pusat selalu memperoleh pembenaran absolut. Ini
berarti, pandangan Afan Gaffar di atas, membuktikan bahwa “political
configuration” benar-benar merupakan faktor yang sangat menentukan terhadap
sukses-tidaknya implementasi otonomi daerah.
Pemikiran
Kimura Hirotsune ini, mungkin bisa mewakili pandangan lain masyarakat tentang
otonomi daerah. Dalam tataran praktis, pandangan ini memberikan tawaran kepada
kita, apakah otonomi daerah itu merupakan solusi, atau justru sebuah problem.
Sebagai konsep yang sejak diberlakukannya UU No. 5 tahun 1974 tentang
Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah sama sekali belum dioperasionalisasikan,
jelas otonomi daerah bisa dikategorikan sebagai sebuah solusi terhadap fenomena
penyelenggaraan pemerintahan yang sentralistik. Tetapi pada saat yang berbeda,
yakni dengan lahirnya UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah –di mana
pemerintah pusat tengah membiarkan proses demokratisasi berlangsung secara
terbuka–, maka bisa jadi otonomi daerah telah berubah menjadi sebuah problem
baru yang perlu segera dipecahkan. Ada 2 alasan politis yang bisa menjelaskan
sosok otonomi daerah saat ini teramat rentan menjadi sebuah problem besar.
Pertama, otonomi daerah tetap konsekwen dengan keharusan daerah untuk mandiri
dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan pendapatan asli daerah (PAD).
Permasalahannya adalah tidak semua daerah
Tabel Pembagian Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Lokal- Central Government and Provinces Local Government
1. Foreign Affairs 1. Public Services
2. National Defense 2. Public Health
3. Judiciary 3. Culture and Education
4. Fiscal and Monetary 4. Agriculture
5. Religion 5. Local Transportation
6. National Planning & Develpmnt Cntrl 6. Trade and Industry
7. Balancing Funds 7. Investment
8. Economic and Administrative System 8. Cooperative Enterprises
9. Human Resources Development 9. Land Utilization –Administ.
10. Natural and Strategic Resources 10. Environment
11. National Conservation 11. Workforces
12. National Standardization
Tabel 2 Jenis Penerimaan Daerah dan
Pusat
No Jenis Penerimaan Alokasi Penerimaan
Pemda Pempus
1 Pajak Bumi dan Bangunan 90 % 10 %
2 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 80 % 20 %
3 SDA Kehutanan, Pertambangan Umum, Perikanan 80 % 20 %
4 Pertambangan Minyak Bumi 15 % 85 %
5 Pertambangan Gas Alam 30 % 70 %
6 Dana Reboisasi 40 % 60 %
No Jenis Penerimaan Alokasi Penerimaan
Pemda Pempus
1 Pajak Bumi dan Bangunan 90 % 10 %
2 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 80 % 20 %
3 SDA Kehutanan, Pertambangan Umum, Perikanan 80 % 20 %
4 Pertambangan Minyak Bumi 15 % 85 %
5 Pertambangan Gas Alam 30 % 70 %
6 Dana Reboisasi 40 % 60 %
C.
Kritik Otonomi Daerah
Cukup menarik mendiskusikan statemen Wapres Megawati12 dalam Pembukaan Rapat Konsolidasi Pembangunan Nasional di Jakarta (Rabu, 16 Mei 2001), yang mengritik UU No. 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah yang pelaksanaannya banyak disalahtafsirkan. Salah satu kritik yang paling mengena adalah ditangkap adanya tandatanda berlangsungnya semacam pembangkangan dari Kepala Daerah otonom kabupaten atau kota terhadap Kepala Daerah tingkat propinsi. Wapres juga mencontohkan memiliki potensi SDA yang potensial, sehingga bagi daerah yang miskin SDA, otonomi daerah bukanlah merupakan sebuah solusi. Kedua, keberadaan pelembagaan politik daerah yang menempatkan lembaga legislatif (DPRD I dan DPRD II) pada posisi yang cenderung lebih berdaya dan lembaga eksekutif (Bupati, Walikota, Gubernur) pada posisi yang cenderung kurang berdaya, telah memberi kesempatan yang besar bagi legislatif untuk menjadi penguasa baru yang otoriter. Pada posisi ini, permasalahan yang sangat krusial adalah kepada siapa legislatif mempertanggungjawabkan tugas-tugasnya. Dua alasan politis yang dipaparkan di atas, adalah beberapa argumen penting yang bisa mendukung pemikiran Kimura Hirotsune tentang munculnya dualisme persepsi masyarakat yang saling kontradiktif terhadap otonomi daerah. pelanggaran pasal 3 UU No. 22/1999 tentang peraturan wilayah laut, yang kemudian menimbulkan aksi pengkaplingan wilayah laut oleh masing-masing Kabupaten. Juga pada pasal 45 tentang laporan pertanggungan jawab Kepala Daerah setiap akhir tahun anggaran yang pada praktiknya ditangkap sebagai upaya penjatuhan Kepala Daerah. Seterusnya Wapres sangat menghargai adanya penyempurnaan UU Otoda yang baru tersebut. Di masa di mana UU No. 22/1999 seakan-akan dianggap sebagai dewa penolong yang utama bagi daerah untuk mengelola sumberdaya-nya sendiri, lontaran dari Wapres tersebut semestinya disambut hangat dan dijadikan diskursus demi perbaikan di masa mendatang.
Memang kita ketahui bahwa sejak merdeka 55 tahun lebih, Indonesia telah memiliki 6 buah UU Pemerintahan Daerah: UU No 1/1945, UU No.22/1948, UU No. 1/1957, UU No. 18/1965, UU No. 5/1974 dan terakhir UU No. 22/1999. Selanjutnya, munculnya UU No.22/1999 ditambah UU No. 25/1999 diharapkan mampu menjadi momen untuk memperbaiki relasi pusat-daerah yang timpang selama ini. Otonomi daerah diasumsikan sebagai satu-satunya jalan keluar yang harus ditempuh. Namun pertanyaannya ialah, benarkah otonomi daerah secara praksis, setidaknya sesuai dengan aturan UU No. 22/1999, mampu menjadi obat yang sesungguhnya, yang benar-benar mampu membalik keadaan dari sentralistik menjadi desentralistik?
Harapan besar akan terwujudnya demokrasi dalam UU Otoda ini, harus dipertanyakan kembali, jika roh dan semangat yang melandasi mekanisme penyelenggaraan pemerintahan masih seperti yang tercermin dalam UU No. 5/1974, penuh dengan KKN. Apalagi harus kita catat bahwa legislatif daerah yang dihasilkan dari Pemilu ’99 kemarin adalah personal legislatif yang sangat baru, yang dengan demikian sangat rentan terhadap politik uang (money politics). Juga, banyaknya kepentingan yang harus diwakili, yang direpresentasikan atas partai-partai yang ada, bukan merupakan jaminan demokrasi akan terselenggara dengan baik, malah justru jika tidak hati-hati akan memperkeruh keadaan dan mereduksi nilai substansi demokrasi itu sendiri. Jadi, urgensi otonomi daerah, jika hanya ditunjukkan melalui euforia kita terhadap UU No. 22/1999, tentu tidak hanya akan melestarikan praktek-praktek KKN, tapi juga menumbuhsuburkannya di daerah-daerah. Bukti tentang hal ini, secara riil bisa kita saksikan di lapangan akhir-akhir ini. Protes masyarakat atas pemilihan Kepala Daerah yang baru menjadi konsumsi media secara tak henti-henti.
Seperti diketahui bersama bahwa UU 22/99 tidak menggunakan sistem otonomi bertingkat. Tidak diberlakukannya sistem otonomi bertingkat atau residual seperti tercermin dalam UU No. 5/1974, merupakan sesuatu yang baru. Maksudnya, Gubernur tidak lagi merupakan atasan dari para Bupati atau Walikota yang ada. Ini memang baik, meski tetap harus dijelaskan lagi.
1 Bahwa keberadaan Gubernur di Propinsi menjadi tidak banyak fungsinya. Jika dikatakan bahwa fungsi Propinsi adalah untuk menyelenggarakan urusan-urusan yang bersifat lintas kabupaten atau kota, pada intinya justru bisa kita katakan bahwa daerah Tk II masing-masing bisa menyelenggarakannya tanpa dibantu oleh propinsi.
2 Kalaupun Propinsi dihapus, langkah ini harus dipahami tidak hanya menghapus institusinya belaka. Hubungan Gubernur sebagai atasan para Bupati yang dibangun selama berpuluh-puluh tahun dulu, sebenarnya telah menghasilkan sebuah bangunan mentalitas yang sangat feodal. Ini tentu tak bisa dihilangkan begitu saja, sebab menghancurkan hubungan itu melalui sebuah UU jelas memerlukan waktu yang sangat lama.
3 Menjadi tak ada gunanya menghapus hubungan feodal antara Bupati-Gubernur, yang dianggap sebagai inefisien itu, jika lantas inefisiensi ulang diciptakan melalui hubungan yang lebih vertikal lagi yakni dengan pemerintah pusat. Seperti disebutkan Pratikno (2000) bahwa UU No. 22/1999 ternyata tidak banyak melakukan perubahan besar, misalnya status propinsi, sehingga posisi Gubernur masih tetap berfungsi ganda yakni sebagai aparat daerah dan aparat pusat. Kami mencatat bahwa ada beberapa paradoksi yang mesti ditinjau ulang dalam hal ini. Misalnya pasal 38, pasal 40 ayat 3 dan pasal 46 ayat 3. Pasal-pasal itu masih membuka ruang yang lebar bagi adanya intervensi orang-orang pusat terhadap eksistensi Kepala Daerah. Hal ini tercermin dalam kalimat-kalimat seperti “dikonsultasikan kepada presiden. Pada pasal 46 ayat 3 yang dinyatakan bahwa pemberhentian kepala daerah adalah otoritas dari presiden, sedangkan DPRD hanya sekedar mengusulkan saja; atau pasal 52 yang mengatakan bahwa pemberhentian kepala daerah oleh presiden adalah mutlak dan tidak dapat dibatalkan lagi; atau pasal 55 yang mengatakan bahwa tindakan kriminal / pidana yang dilakukan oleh kepala daerah, pengusutannya harus dilakukan dengan seizin presiden. Hal ini menunjukkan betapa UU No. 22/1999 masih jauh dari kata sempurna.
D.
Desentralisasi Politik
Sentralisme
rezim Orba, dari sudut pandang ekonomi, bisa dibuktikan dari besarnya produksi
sumber daya alam yang mesti disetorkan ke pusat. Sementara dari sisi politik,
sentralisme Indonesia bisa mewujud dalam berbagai macam bentuk; mulai dari pemaksaan
konstitusi sampai pada pemangkasan-pemangkasan hak politik daerah. Setelah
reformasi bergulir, setelah pembusukan sentralisme yang korup berhasil sedikit
demi sedikit diungkap, maka bergaunglah otonomi daerah (seluas-luasnya). Bahkan
sampai pula pada perdebatan tentang bentuk negara, federasi atau kesatuan.
Namun, di sela-sela perdebatan itu kita tentu menginginkan suatu solusi yang
adil. Bisa kita sepakati bahwa munculnya problem federasi adalah karena
sentralisme; yakni ketidakadilan pusat pada daerah. Oleh karena itu, akar
persoalan ini sesungguhnya adalah pada, bagaimana mengatasi persoalan
ketidakadilan secara efektif dan proporsional. Ini dilakukan karena dalam
negara federasi pun, jika sentralisme kekuasaan politik masih diemban pusat,
maka jangan berharap akan ada keadilan.
Otonomi
daerah seluas-luasnya mungkin bisa dijadikan alternatif yang cukup baik untuk
mengatasi persoalan itu. Namun tampaknya juga harus dimengerti bahwa konsep
‘otonomi seluas-luasnya’ sebetulnya hanya konsep yang diproduksi pemerintah
Indonesia. Dalam dunia akademik, tidak pernah dikenal wacana ‘otonomi
seluasluasnya’. Sedangkan kalimat yang paling dekat dasn representatif untuk
mendeskripsikan konsep otonomi seluas-luasnya adalah devolution atau
desentralisasi politik.13 Istilah ini populer di AS tahun 1994 ketika Richard
P. Nathan menjulukinya sebagai Devolution Revolution, meski substansi
sesungguhnya sudah dikenal lebih kurang 2 dekade lalu. Desentralisasi politik
yang dimaksud ini adalah bagaimana mendelegasikan wewenang pengambilan
keputusan kepada badan perwakilan yang dipilih melalui pemilihan lokal. Jadi ia
adalah kemampuan unit pemerintah yang mandiri dan independen. Dalam kondisi
seperti ini, tentu saja pusat mesti melepas fungsi-fungsi tertentunya untuk
menciptakan unit-unit pemerintahan yang otonom. Statusnya berada di luar
kontrol langsung dari pemerintah pusat.
Pemerintahan
lokal yang otonom dan mandiri memiliki mensyaratkan hal-hal seperti berikut,
bahwa pemerintah lokal mempunyai teritorium yang jelas, memiliki status hukum
yang kuat untuk mengelola sumberdaya dan mengembangkan lokal sebagai lembaga
yang mandiri dan independen. Ini tentu harus didukung oleh kebijakan yang
menyiratkan bahwa kewenangan pemerintah pusat sangat kecil dan pengawasan yang
dilakukannya lebih bersifat tak langsung.
Denis Rondinelli (1981)14 mengatakan bahwa desentralisasi politik adalah peralihan kekuatan ke unit-unit geografis pemerintah lokal yang terletak di luar struktur komando secara formal dari pemerintahan pusat. Dengan demikian, desentralisasi politik menyatakan bahwa konsep-konsep pemisahan, dari berbagai struktur dalam sistem politik secara keseluruhan. Pemerintah lokal harus diberi otonomi dan kebebasan serta dianggap sebagai level terpisah yang tidak memperoleh kontrol langsung dari pemerintah pusat. Pada saat yang sama, pemerintah lokal harus memiliki batas-batas geografis yang ditetapkan secara hukum dan jelas di mana mereka (unit-unit tersebut) menerapkan wewenangnya dan melaksanakan fungsi-fungsi publik. Dalam desentralisasi politik, pemerintah lokal juga harus mencerminkan kebutuhan untuk menciptakan diri sebagai lembaga. Pengertiannya adalah bahwa lembaga ini dianggap rakyat lokal sebagai organisasi yang menyediakan layanan yang memenuhi kebutuhannya dan sebagai unit-unit pemerintah yang berpengaruh. Selanjutnya yang harus diingat adalah bahwa desentralisasi politik merupakan suatu rancangan di mana terdapat hubungan yang saling menguntungkan antara pemerintah lokal dan pemerintah pusat. Pemerintah lokal memiliki kemampuan untuk saling berinteraksi dengan unit-unit yang lain dalam sistem pemerintahan yang merupakan bagiannya.
Desentralisasi politik juga merupakan cara untuk lebih mendekatkan pembangunan pada rakyat yang lebih mengetahui situasi dan kebutuhan mereka sendiri. Sedangkan menurut Lenny Goldberg, Come The Devolution, The American Propect, Winter (1996) agar tujuan itu bisa dicapai adalah dengan:
1 Mengembalikan hak-hak sipil dan kebebasan sipil pada rakyat,
2 Pemerintah pusat memberikan hak pengelolaan dana pada pemerintah daerah,
3 Preferensi dari pusat atas sektor pembangunan harus fleksibel dengan preferensi dari daerah,
4 Pemerintah pusat harus dapat mengembangkan standar-standar baru yang dapat
memperkuat tanpa mendikte. Mengapa demikian? Biasanya pemerintah pusat
seringkali tidak memiliki kepercayaan pada kemampuan pemerintah daerah. Ini
bisa ditunjukkan pada perlakuan terhadap SOP (standart operating procedures),
atau di sini lebih dikenal dengan istilah Juklak/Juknis, yang sangat
berlebihan. Realitasnya, Pemerintah daerah sering tidak dapat segera
menjalankan program-program tertentu bila juklak/juknis belum turun dari pusat.
5 Berusaha memberikan kekuasaan kepada rakyat.
Desentralisasi politik dalam konteks operasionalnya adalah penegakan kedaulatan pada legislatif di daerah atas nama basis rakyatnya. Parameter dari penegakan ini adalah:
1 Political will pemerintah pusat dan derajat transfer kewenangan bagi daerah
2 Derajat budaya, perilaku dan sikap yang kondusif bagi pembuatan keputusan dan administrasi yang decentralized
3 Kesesuaian kebijakan dan program yang dirancang bagi pembuatan keputusan dan manajemen yang decentralized
4 Derajat ketersediaan sumberdaya finansial, manusia dan fisik bagi organisasi yang mengemban tanggung jawab yang diserahkan. (Hermawan Sulistiyo; 1998).
Pada
umumnya sistem nasional dibagi menjadi tiga tingkat dan dua sektor pemerintah
lokal. Ada pusat-pusat nasional, propinsi atau ibukota yang bertindak sebagai
perantara lokal. Lokal dibagi menjadi sektor-sektor pedesaan dan perkotaan
walaupun pembagian seperti itu di banyak negara sekarang sering hanya merupakan
sisa dari pertanian di masa lalu. Dalam beberapa negara,
persyaratan-persyaratan khusus dibuat untuk pemerintahan lokal dari pusat-pusat
perkotaan yang luas. Perkecualian terhadap tiga pola tingkatan adalah sistem
pemerintahan militer, dengan kontrol langsung terhadap lokalitas-lokalitas,
meski dewasa ini sistem pemerintahan militer sudah jarang.
Mawhood (1987) misalnya secara tegas mendefinisikan desentralisasi sebagai devolusi kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, the devolution of power from central to local government. 15 Oleh karenanya dapat dimengerti, bila Mawhood kemudian merumuskan tujuan utama dari kebijaksanaan desentralisasi sebagai upaya untuk mewujudkan political equality, local accountability, dan local responsiveness. Di antara prasyarat yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan tersebut adalah pemerintah daerah harus memiliki teritorial kekuasaan yang jelas (legal territorial of power); memiliki pendapatan daerah sendiri (local own income); memiliki badan perwakilan (local representative body) yang mampu mengontrol eksekutif daerah; dan adanya kepala daerah yang dipilih sendiri oleh masyarakat daerah melalui pemilu. Dengan rumusan definisi dan tujuan desentralissai seperti dikemukakan di atas, para pendukung political decentralisasi perspektif percaya bahwa keberadaan kebijaksanaan desentralisasi akan mampu menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis, atau apa yang disebut oleh Vincent Ostrom sebagai the features of a system of governance that would be appropriate to circumstance where people govern rather than presuming that government govern(1991:6). Argumen dasarnya adalah, dengan konsep tersebut diasumsikan society akan memiliki akses yang lebih besar dalam mengontrol penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Sementara, pada sisi lain, pemerintah daerah sendiri, akan lebih responsif terhadap berbagai tuntutan yang datang dari komunitasnya.
E. Good Governance
Jika
prasyarat desentralisasi sudah bisa dipenuhi seperti itu, maka cukup bisa
dipastikan akan diperoleh hasil bahwa daerah dan pemerintah pusat berbesar hati
untuk mewujudkan hal tersebut. Sehingga masalah yang kemudian harus diagendakan
penangananya oleh daerah adalah tentang pelaksanaan good governance
(penyelenggaraan negara yang baik), khususnya dalam pengelolaan SDA yang
menjadi aset andalan pembangunan daerah. Belajar dari bad governance
(penyelenggaraan negara yang buruk) di masa lalu yang telah menyebabkan porak-porandanya
sistem ekonomi, sosial-bodaya dan sistem ekologi, kita sepakat bahwa di masa
depan pengelolaan SDA dan pembangunan daerah haruslah mengacu kepada
prinsip-prinsip penyelenggaraan negara yang bersifat good and clean governance
(baik dan bersih).
Menggunakan prinsip good governance, titik tekannya (emphasize) mesti mengandung kesadaran sustainable (berkelanjutan). Di manapun, pembangungan dengan kaidah good and clean governance itu ditujukan guna memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengorbankan kepentingan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya. Konsep dari pembangunan berkelanjutan ini merupakan respon atas berbagai kerusakan lingkunan yang disebabkan oleh pembangunan yang memacu pertumbuhan dan tidak menginterasikan aspek lingkungan dalam kebijakannya.
Prinsip-prinsip good and clean governance yang banyak diperbincangkan saat ini adalah:
1 Lembanga perwakilan (DPRD) yang mampu menjalankan fungsi kontrol dan penyaluran aspirasi masyarakat
2 Sistem peradilan yang fair,
mandiri dan profesional
3 Birokrasi yang profesional,
responsif dan akomodatif terhadap kebutuhan masyarakat; dan tatanan masyarakat
sipil yang kuat sehingga mampu melaksanakan fungsi kontrol terhadap negara
Intinya, good and clean governance yang juga mengintegrasikan prinsip keberlanjutan
ekosistem dalam sistemnya tersebut akan berfungsi sangat baik untuk menuju
pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup bersama di daerah. Maka,
refleksi kita bersama adalah adalah bagaimana menanamkan komitmen yang kuat
untuk bisa berperan maksimal sesuai dengan kapasitas masing-masing elemen
mewujudkan good and clean governance, bukan hanya sebagai retorika tapi menjadi
paradigma sistem negara.
Good
governance merupakan sebuah konsep yang akhir-akhir ini banyak diperkenalkan
sebagai upaya merumuskan pemerintahan yang baik. Di era otonomi daerah seperti
ini, kita melihat tampaknya ada tempat khusus bagi perbaikan kinerja
pemerintahan yang ada, terutama pemerintah lokal, di mana nanti diharapkan akan
mendukung proses demokrasi ke arah yang sesungguhnya. Seperti ditunjukkan oleh
Meuthia-Ganie Rachman (2000), bahwa good governance mempunyai
indikator-indikator yang dimaksudkan sebagai:
1 Penjamin situasi keterbukaan (transparancy)
2 Pertanggungjawaban publik (public accountability) dan,
3 Kontrol dalam proses ekonomi maupun politik
Konsep
ini sendiri sebenarnya telah banyak dikembangkan oleh berbagai badan
internasional. Secara umum, konsep good governance mengundang keterlibatan
masyarakat sebagai pendorong pemerintah (jalur struktur) untuk lebih menghargai
sekaligus menempatkan masyarakat sebagai subyek kebijakan, bukan hanya obyek
yang bisa diatur ke mana arah kebijakan dirumuskan.
Memang, bahwa konsep good governance (yang dirumuskan oleh negara-negara maju-kapitalis itu) tidak sepenuhnya bisa diterapkan di Indonesia. Konsep ini sendiri harus dipadankan dengan situasi di Indonesia agar jalan menuju terwujudnya demokrasi yang dicita-citakan semakin lempang. Untuk bisa sampai pada apa yang dicita-citakan sebagai “pemerintahan yang baik”, nyaris semua aspek yang terlibat dalam pembangunan Indonesia harus dilibatkan. Aktivis parpol, Ornop, LSM, pemerintah, politisi, pengusaha, agamawan, dan masyarakat secara luas mesti memahami arah dan tujuan pencapaian pembangunan Indonesia. Hal ini mutlak diperlukan, sebab akan menjadi sangat ironis jika antarelemen bangsa justru tidak padu. Bahkan tidak hanya tidak padu, melainkan sulit dimengerti dalam rangka mewujudkan demokrasi yang sehat, jalan-jalan yang tidak sehat tetap digunakan. Ironisnya lagi, itu dianggap sebagai sah sebab mereka mengatasnamakan “pembawa aspirasi demokrasi”.
Urgensi
sesegera mungkin membahas konsep good governance bagi pemerintahan (terutama
lokal) di Indonesia sulit ditolak. Salah satu urgensi itu adalah bagi
pembentukan masyarakat sipil yang bertanggung jawab di satu sisi, dan
penciptaan pemerintahan yang baik di lain pihak. Sehingga problematikanya, mana
yang lebih dulu diciptakan? Good governance atau civil society? Sekiranya
pertanyaan ini bukanlah merupakan pertanyaan pilihan, di mana kita harus
memilih salah satunya. Keduanya adalah satu: Satu komponen dalam pengembangan
masyarakat bangsa secara adil. Memilih salah satunya untuk didahulukan pada
akhirnya juga akan menegasikan yang lain. Orde Baru adalah contoh yang baik
untuk kita bisa mengerti bahwa rezim pada saat itu memilih salah satunya.
Mereka berusaha terlebih dahulu untuk menciptakan “pemerintahan yang baik” di
satu sisi, yang lantas mengabaikan “keberdayaan masyarakat” di lain pihak. Dari
sini bisa kita mengerti bahwa upaya keras untuk menciptakan demokrasi harus
didukung oleh kedua jalur itu; tidak hanya satu. Satu jalur berkeinginan keras
untuk menciptakan demokrasi, sementara di sisi lain terlihat enggan untuk
berpartisipasi dalam meraih demokrasi, di samping fatal, hal ini tentunya akan
senjang dan timpang. Inilah yang jarang kita sadari. Sering kita terjebak pada
fatamorgana bahwa demokrasi hanya akan bisa terwujud melalui aksi massa rakyat
pada pemerintah yang korup.
F. Penutup: Peluang Menuju Demokrasi
Secara
normatif demokrasi menurut Robert A. Dahl adalah sistem yang benarbenar atau
hampir mutlak bertanggung jawab kepada semua warga negaranya. Secara lebih
empirik demokrasi menurut Joseph A. Schumpeter adalah sistem, di mana para
pengambil keputusan kolektifnyua yang paling kuat dipilih melalui pemilu
periodik, di mana para calon bebas bersaing untuk merebut suara dan di mana
hampir semua orang dewasa berhak memilih. Dari pengertian ini dapat disimpulkan
bahwa demokrasi mengandung dua dimensi penting, yaitu persaingan dan
partisipasi. Sementara leboih dahulu dari mereka, Plato, telah mengingatkan
bahwa demokrasi itu penuh sesak dengan kemerdekaan dan kebebasan berbicara dan
setiap orang dapat berbuat sekehendak hatinya. Bahkan demokrasi diidentikan
dengan cara-cara pemborosan dan membosankan serta mengandung resiko besar.
Dengan
demokrasi yang diiringi globalisasi perekonomian yang semakin nyata menunjukkan
bahwa interdependensi berbagai negara dan masyarakat bangsa-bangsa semakin kuat
dan nyata. Kenichi Ohmae (1999) mengingatkan bahwa saat ini kita sedang dan
akan memasuki era dunia tanpa batas. Secara ringkas dunia tanpa batas ini
ditandai dengan semakin terfokusnya masalah ke dalam 5 C yang strategik:
1 Customer
2 Company
3 Competition
4 Currency
5 Country.
2 Company
3 Competition
4 Currency
5 Country.
Aspek
country tetap menempati posisi yang penting dalam globalisasi nanti sebagai
penyiap berbagai lingkungan hidup dan institutional arrrangement yang
memungkinkan organisasi-organisasi global dapat berperan di dalamnya. Reasoning
di atas mengatakan bahwa negara dianggap berperan pada wilayah akselerator
publik, penghubung antara kepentingan masyarakat dengan kepentingan
multinasional.
[ . . . ]
Biografi Penulis
Saiful
Arif, Lahir di Lamongan 1976. Tahun 1998, menyelesaikan pendidikan S1-nya di
Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas
Muhammadiyah Malang (UMM), setelah sempat mampir sebentar di Fakultas Sastra
Inggris Universitas Gajayana Malang. Pernah menjadi Redaktur Pelaksana Jurnal
Kawasan Pusat Studi Kewilayahan (PSK) UMM. Pekerjaan sekarang adalah editor
tetap di Averores Press Malang (suatu komunitas penerbitan yang giat akan
wacana-wacana sosial transformatif di Malang). Karyanya yang sudah diterbitkan
adalah (1) Menolak Pembangunanisme (Averroes Press dan Pustaka Pelajar, 2000);
(2) Demo Bolsyewik: Jaring-jaring Pemikiran Lenin (Averroes Press dan Penerbit
Jendela Yogyakarta, 2001) [nb: sedang mengalami proses depolitisasi]; (3)
Kapitalisme Birokrasi: Kritik Reinventing Government ala Osborne dan Gaebler
(Averroes Press LKiS, 2001). Saat ini sedang menyiapkan tulisan berikutnya,
yakni La Ilusion Democratica, Demitologi Demokrasi Modern.
Paring Waluyo Utomo, Lahir di Surabaya 1977. Menempuh pendidikan S1 di Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) Universitas Brawijaya Malang Aktifitas sekarang, adalah pegiat LSM dan beberapa kelompok kajian di Malang maupun di Surabaya. Anggota Badan Pengkajian Kebijakan Daerah (BPKD) PMII Koordinator Cabang Jawa Timur, Aktif di Divisi Kajian Pusat Studi dan Pengembangan Kebudayaan (PUSPèK) Averroes Malang.
Paring Waluyo Utomo, Lahir di Surabaya 1977. Menempuh pendidikan S1 di Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) Universitas Brawijaya Malang Aktifitas sekarang, adalah pegiat LSM dan beberapa kelompok kajian di Malang maupun di Surabaya. Anggota Badan Pengkajian Kebijakan Daerah (BPKD) PMII Koordinator Cabang Jawa Timur, Aktif di Divisi Kajian Pusat Studi dan Pengembangan Kebudayaan (PUSPèK) Averroes Malang.