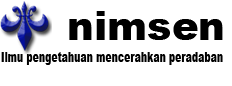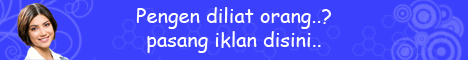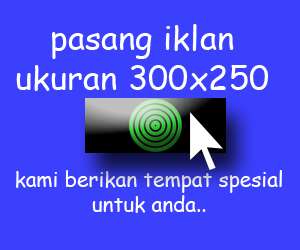Oleh : Kuswanto SA *
Pendahuluan
Memasuki abad 21, terjadi
perubahan-perubahan mendasar dalam kehidupan bernegara di Indonesia, suatu
perubahan yang mungkin tak pernah diduga oleh kebanyakan masyarakat Indonesia
sendiri. Diawali oleh krisis moneter dan ekonomi pada akhir 1997, perubahan-perubahan
penting dalam kehidupan politik, ekonomi, hukum dan sosial masih terus
berlangsung hingga saat ini. Meskipun dampak krisis ekonomi mulai reda dan
kondisi berangsur pulih, suasana serba tak pasti dan kebingungan masih terasa
di mana-mana. Salah satu sumber kebingungan itu adalah proses desentralisasi
yang ikut terpacu oleh dinamika perubahan sebagai akibat krisis ekonomi. Dengan
lahirnya UU No 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dalam situasi krisis,
proses desentralisasi yang sebenarnya sudah dimulai sejak lama meskipun
berjalan lambat, bercampur aduk dengan proses reformasi yang digencarkan sejak
krisis ekonomi terjadi. Gejala lain yang ikut memperumit proses desentralisasi
tersebut adalah munculnya aspirasi beberapa daerah untuk memisahkan diri dari
negara kesatuan RI. Adanya aspirasi ini membuat agenda otonomi daerah berada
dalam dilema yang sulit dipecahkan, yakni antara keinginan untuk meredam
aspirasi semacam itu melalui pemberian otonomi yang luas dan kekhawatiran bahwa
persoalan pusat akan berpindah ke daerah karena ketidak-siapan daerah untuk
menerima otonomi luas.
Meskipun masih sulit membayangkan
wajah Indonesia baru dalam beberapa tahun mendatang, proses desentralisasi dan
perwujudan otonomi daerah yang luas merupakan salah satu faktor yang hampir
pasti akan ikut membentuk wajah tersebut. Dengan demikian, dapat diperkirakan
akan terjadinya pergeseran besar-besaran dalam tata kehidupan masyarakat, dari
tata kehidupan yang bersifat sentralistik ke sifat desentralistik, dari
kecenderungan serba seragam ke warna warni lokal yang plural, dari paradigma
negara kesatuan ke negara kuasi federal. Dalam operasionalisasinya, proses
pergeseran tersebut memerlukan penjabaran yang rumit dan kompromi-kompromi yang
alot dari beragam kepentingan yang terlibat. Hal inilah yang antara lain
menimbulkan suasana serba tak pasti dan gamang sebagaimana tampak khususnya di
kalangan birokrasi pemerintah.
Proses pergeseran yang dimaksud
antara lain juga akan terjadi dalam pengelolaan sumberdaya air. Dalam hal ini,
menarik untuk mempertanyakan, apakah pergeseran ke arah otonomi daerah itu
dapat dimanfaatkan untuk sekaligus memecahkan masalah-masalah yang selama ini
dihadapi dalam pengelolaan sumberdaya air ? Apakah UU No 22 tahun 1999 memberi
landasan hukum yang memadai untuk upaya tersebut ? Tulisan ini akan mencoba
membahas persoalan yang terangkat dari pertanyaan tersebut guna membantu
terselenggaranya upaya perwujudan otonomi daerah yang sekaligus mendukung
penyempurnaan pengelolaan sumberdaya air.
Makna
Penyelenggaraan otonomi daerah
umumnya disambut positif dan didukung banyak pihak. Disamping merupakan amanat
konstitusi, otonomi daerah dirasakan sebagai kebutuhan yang semakin mendesak
dan menjadi jalan keluar bagi tantangan yang akan sulit diatasi jika penyelenggaraan
kehidupan berbegara tetap dalam sistem yang sentralistik. Terdapat tiga manfaat
yang umumnya diharapkan dari penyelenggaraan otonomi daerah melalui
desentralisasi : pertama, prakarsa dan kreativitas daerah dapat lebih
berkembang sehingga masalah dan tantangan yang muncul di daerah dapat lebih
mudah dan cepat diatasi ; kedua, beban persoalan dapat lebih dibagi antara
pemerintah pusat dan daerah sehingga memungkinkan kesempatan yang lebih luas
bagi pusat untuk memusatkan perhatian pada masalah-masalah yang bersifat
strategis; ketiga, membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat di
tingkat lokal dan daerah sehingga mampu meningkatkan rasa keadilan dan tanggung
jawab bersama dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.
Pengalaman dalam mengupayakan
otonomi daerah selama ini menunjukkan alotnya proses yang berlangsung guna
mewujudkan otonomi daerah. Faktor utama penyebabnya adalah keengganan
pemerintah pusat untuk menyerahkan kewenangan ke daerah dengan berbagai alasan,
antara lain keraguan akan kemampuan daerah, kekhawatiran akan berpindahnya
masalah-masalah pusat ke daerah dan sebagainya. Disamping keengganan,
pemerintah pusat terkesan sangat berhati-hati dalam mendorong otonomi daerah.
Ini dapat dibaca dari pesan yang senantiasa melekat dalam mengupayakan otonomi
daerah, misalnya lewat ungkapan-ungkapan seperti otonomi yang nyata dan
bertanggung jawab, otonomi diselenggarakan dengan prinsip-prinsip demokratis,
peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan dan sebagainya.
Keengganan pemerintah pusat untuk
menyerahkan kewenangan dalam rangka otonomi daerah bisa jadi bersumber pada
faktor yang bersifat politis bahwa pusat tidak rela kehilangan kontrol dan
kepentingannya terhadap daerah. Faktor demikian terbukti dapat ditandingi
dengan ancaman beberapa daerah untuk melepaskan diri sehingga muncul dorongan
yang kuat untuk segera mewujudkan otonomi daerah sebagaimana tertuang dalam UU
No 22 tahun 1999. Hal yang tampaknya kurang disadari dalam kegairahan menyambut
otonomi daerah yang luas ini adalah bahwa otonomi daerah dalam beberapa bidang
urusan tertentu dapat justru menimbulkan kerugian disamping keuntungan
sebagaimana secara umum telah dikemukakan. Hal ini dapat dilihat antara lain
dalam pengelolaan sumberdaya air.
Keuntungan dan kerugian yang dapat
ditimbulkan oleh penyelenggaraan otonomi daerah bagi pengelolaan sumberdaya air
dapat dijelaskan dengan mengembalikan makna otonomi daerah sebagai penerapan
azas desentralisasi. Seperti telah dikemukakan, desentralisasi akan membawa
sejumlah manfaat seperti mempermudah dan mempercepat penyelesaian masalah dan
tantangan yang muncul secara lokal, mengurangi beban persoalan di pusat dan
memperluas partisipasi bagi masyarakat lokal dan daerah. Setiap manfaat
tersebut memiliki kondisi atau persyaratan-persyaratan tertentu agar dapat
diperoleh melalui upaya desentralisasi. Persoalannya adalah apakah pengelolaan
sumberdaya air menyediakan persyaratan yang dimaksud ? Satu misal adalah
persyaratan bagi manfaat pertama, desentralisasi akan mampu memberikan manfaat
tersebut bila masalah dan tantangan lokal sulit diramalkan dan heterogen
sifatnya. Bila masalah yang muncul umumnya telah dapat diduga dan dapat dibuat
rumusan secara umum, desentralisasi tak banyak gunanya karena keputusan dapat
ditentukan secara terpusat dan dibakukan. Dengan mengidentifikasi dan
menganalisa persyaratan-persyaratan untuk setiap manfaat yang diharapkan dari
desentralisasi, akan bisa diidentifikasi hal-hal apa dalam pengelolaan
sumberdaya air yang dapat memetik keuntungan dari desentralisasi.
Di pihak lain, perlu disadari
beberapa kerugian yang dapat muncul dari desentralisasi pengelolaan sumberdaya
air. Desentralisasi dapat mendatangkan tiga bentuk kerugian, yakni mengurangi
eksternalitas positif dan meningkatkan eksternalitas negatif; meningkatkan
biaya artikulasi dan mengurangi keuntungan internal. Eksternalitas yang
dimaksud merupakan dampak atau akibat tidak langsung yang ditimbulkan oleh
pengelolaan sumberdaya air terhadap lingkungan secara keseluruhan.
Eksternalitas pengelolaan sumberdaya air dapat bersifat positif misalnya dalam
bentuk dukungan bagi perkembangan ekonomi masyarakat, tingkat kesehatan
rata-rata masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup. Desentralisasi
pengelolaan sumberdaya air dalam bentuk otonomi daerah akan dapat mengurangi
eksternalitas tersebut bila kepentingan masing-masing daerah tidak bisa saling
dipertemukan untuk memaksimalkan nilai kegunaan sumberdaya air yang tersedia
guna mendukung perkembangan ekonomi, kesehatan dan kelestarian lingkungan
hidup. Sebaliknya, eksternalitas negatif yang timbul akibat degradasi
sumberdaya air menjadi semakin sulit ditanggulangi dalam sistem pengelolaan
yang terdesentralisasi.
Artikulasi merupakan proses yang
menghubungkan tindakan unit yang satu dengan tindakan dari unit-unit lainnya
(Benveniste, 1989:230). Desentralisasi akan meningkatkan biaya artikulasi dalam
arti akan lebih banyak waktu, energi serta biaya yang diperlukan untuk
mengkoordinasikan bagian-bagian yang masing-masing memiliki otonomi. Pemborosan
dapat terjadi bila terdapat duplikasi dalam pelayanan. Selain itu, konflik
antar bagian lebih mudah terjadi. Dalam pengelolaan sumberdaya air, biaya
artikulasi akan menjadi tinggi untuk menangani urusan-urusan yang bersifat
lintas daerah, seperti pengamanan catchment area, penanggulangan erosi,
penyusunan rencana tata pengaturan air dalam satu sungai yang melintasi dua
atau lebih daerah otonom dan sebagainya.
Keuntungan internal dapat diperoleh
oleh kesatuan sistem pengelolaan, misalnya pembangunan suatu sistem jaringan
irigasi akan membutuhkan satuan wilayah tertentu yang secara minimal memenuhi
skala ekonomi yang dibutuhkan sehingga tercapai efisiensi biaya. Desentralisasi
yang mengabaikan prinsip ini akan berdampak pada pengurangan atau hilangnya
keuntungan internal yang seharusnya dapat diperoleh. Bentuk keuntungan internal
lain adalah standardisasi dan simplifikasi norma-norma adminsitratif yang tidak
perlu dihilangkan karena alasan desentralisasi.
Desentralisasi atau Sentralisasi ?
Dengan mencermati segi-segi
menguntungkan dan merugikan dari proses desentralisasi, menjadi jelas bahwa
tidak semua hal dalam pengelolaan sumberdaya air yang akan menjadi lebih baik
bila dikelola secara terdesentralisasi. Secara teoritis, sentralisasi dan
desentraalisasi memang berada dalam suatu kontinum (Benveniste, 1989: 234).
Disamping itu terdapat kondisi dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk
memetik keuntungan dari masing-masing pilihan tersebut. Sentralisasi dalam hal
ini dapat berarti terpusat di tingkat nasional atau dalam satu Satuan Wilayah
Sungai (SWS). Sementara desentralisasi berarti menyerahkan sebagian kewenangan
ke tingkat daerah otonom, baik di tingkat propinsi maupun kabupaten dan kota.
Dalam Tabel 1 dicoba diidentifikasi hal-hal dalam pengelolaan sumberdaya air
yang cocok untuk sentralisasi dan desentralisasi, misalnya dalam kasus
pengelolaan sungai dan sistem irigasi.
Peluang
Dengan memusatkan perhatian pada
aspek-aspek urusan yang cocok untuk didesentralisasi, ada dua peluang yang
memberi harapan untuk menemukan jalan keluar bagi permasalahan pengelolaan
sumberdaya air.
Pertama, desentralisasi akan
memungkinkan terpenuhinya biaya Operasi dan Pemeliharaan (O&P) untuk
pendaya-gunaan sumberdaya air dalam jumlah yang lebih memadai dan berkorelasi
langsung dengan tingkat pelayanan yang diberikan. Contoh paling jelas untuk
peluang ini adalah desentralisasi pengelolaan jaringan irigasi, baik dengan
menyerahkan semua urusa pengelolaan jaringan irigasi ke para petani pemakai air
(P3A) maupun dinas pengairan di daerah otonom. Langkah desentralisasi ini sudah
dimulai sejak menjelang akhir tahun 1980-an tetapi masih banyak menghadapi
hambatan. Hambatan yang muncul kebanyakan disebabkan karena terlalu terpaku
pada proses persiapan dan pelaksanaan penyerahan kewenangan. Pada hal disamping
hambatan tersebut, sebenarnya sudah menunggu ancaman dari periode pasca
penyerahan berupa kegagalan lembaga pengelola untuk menjalankan otonominya
dalam pengelolaan jaringan irigasi.
Kedua, desentralisasi akan
meningkatkan efektivitas pengelolaan di tingkat lokal melalui fleksibelitas
yang lebih besar bagi pihak pengelola lokal untuk menyesuaikan bentuk
kelembagaan maupun fungsinya dengan kebutuhan dan kondisi setempat. Dalam kasus
pengelolaan jaringan irigasi, kebebasan untuk menemukan bentuk dan fungsi
kelembagaan P3A sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal akan menghilangkan
kekakuan aturan pusat yang merupakan salah satu sumber kegagalan berfungsinya
lembaga pengelola lokal selama ini.
Dua peluang tersebut merupakan
peluang pokok yang jika dapat dimanfaatkan dengan baik akan memunculkan
peluang-peluang ikutan lainnya, baik yang bersifat langsung maupun tidak
langsung. Terpenuhinya biaya O&P secara memadai misalnya akan memecahkan
kendala keterbatasan pembiayaan pengelolaan sumberdaya air sehingga pada
gilirannya akan menjamin kelangsungan pelayanan air bagi berbagai jenis
penggunaan. Eksternalitas positif akan dengan sendirinya muncul dari
peningkatan pelayanan air tersebut. Begitu juga, efektivitas kelembagaan
pengelola sumberdaya air di tingkat lokal akan berdampak pada perbaikan
pelayanan air dan menjamin kelansungannya.
Disamping peluang, terdapat ancaman
yang secara potensial akan muncul oleh proses desentralisasi. Seperti telah
disinggung di muka, ancaman yang dimaksud pada dasarnya muncul dari kegagalan
menaggulangi sejumlah kerugian yang timbul karena proses desentralisasi.
Ancaman pertama akan muncul dalam bentuk beban pembiayaan lebih berat dan
melampaui proporsi yang harus dipikul oleh masyarakat pengguna air di lokasi
setempat. Ancaman ini muncul oleh orientasi berlebihan pemerintah daerah otonom
setempat untuk menghimpun sumber-sumber pembiayaan Pendapatan Asli daerah (PAD)
agar mampu menyelenggarakan otonomi daerah. Meningkatnya beban pembiayaan
sejauh dimanfaatkan hanya dalam rangka otonomi pengelolaan sumberdaya air dapat
dipahami dan diterima secara wajar. Tetapi dalam praktek dapat terjadi
hilangnya korelasi langsung antara beban yang dipungut dan tingkat pelayanan
yang diberikan karena pemanfaatan untuk hal-hal lain yang tidak berkaitan
dengan urusan pengelolaan sumberdaya air. Orientasi semacam ini bisa
dihilangkan jika proses artikulasi dalam sistem pengelolaan secara utuh dapat
berjalan efektif sehingga tindakan yang bersifat sepihak oleh pemerintah daerah
otonom dapat diimbangi oleh reaksi berlawanan dari bagian lain yang akan
dirugikan.
Ancaman ke dua adalah meningkatnya
konflik antar daerah otonom, khususnya untuk sumberdaya air yang pengelolaannya
bersifat lintas daerah. Hal ini bisa dipahami mengingat perbedaan kepentingan
atau preferensi antar daerah yang dapat meruncing karena didukung oleh
menguatnya basis kewenangan masing-masing. Kunci untuk mengurangi potensi
konflik ini adalah membatasi kewenangan masing-masing daerah untuk hal-hal yang
bersifat lintas daerah. Dengan kata lain, dalam hal-hal semacam itu,
sentralisasi di tingkat SWS akan lebih bermanfaat dibanding desentralisasi.
Ancaman ketiga akan timbul dari
kegagalan menindak-lanjuti proses desentralisasi atau dengan kata lain mengisi
otonomi daerah dengan praktek pengolaan yang sesuai dengan porsi kewenangan
yang telah diterima. Jika kegagalan ini terjadi hasil yang dipetik akan
merupakan back fire yang akan semakin memerosotkan kinerja pengelolaan
sumberdaya air dengan segala akibatnya. Selain persiapan yang matang tetapi
juga tidak menjebak dalam kerumitan-kerumitan baru, perhatian yang besar harus
diarahkan pada upaya-upaya penanggulangan masalah pada periode pasca penyerahan
kewenangan.
Berdasar tinjauan terhadap peluang
dan ancaman di atas, dapat diidentifikasi tantangan-tantangan yang harus
ditanggulangi agar proses desentralisasi untuk mewujudkan otonomi daerah dapat
memberikan makna yang produktif untuk meningkatkan kinerja pengelolaan
sumberdaya air. Pertama, pemetaan masalah secara komprehensif dan rinci untuk
memperoleh gambaran sejelas-jelasnya hal-hal apa yang darus didesentralisasi
dan apa yang tetap harus dipertahanakan secara terpusat pada tingkat yang mana
sebagai dasar konsepsional penyelenggaraan otonomi daerah yang meyangkut
pengelolaan sumberdaya air. Kedua, sosialisasi dan pendekatan ke pihak-pihak
terkait (stakeholder) untuk memproses lahirnya komitmen yang kuat bagi penyelenggaraan
otonomi daerah yang kondusif dan mampu meningkatkan kinerja pengelolaan
sumberdaya air. Ketiga, merumuskan strategi dan program-program yang
berkesinambungan untuk mewujudkan komitmen-komitmen yang diperoleh di tengah
proses persiapan dan penyelenggaraan otnomi daerah yang kini dilakukan oleh
berbagai pihak. Ke empat adalah segera terjun dalam tindakan praktis untuk
mengupayakan perwujudan otonomi daerah sesuai konsep, strategi dan program yang
telah dipersiapkan. Untuk mendukung semua upaya dalam rangka menjawab tantangan
tersebut secara internal perlu digalang komunikasi dan kerjasama yang produktif
dikalangan para penggiat, pemerhati dan mereka yang memiliki kepedulian
terhadap masalah sumberdaya air.
Penutup
Dalam UU N0 22 Tahun 1999, kewenangan
dalam pendaya-gunaan sumberdaya alam yang berarti mencakup sumberdaya air masih
belum termasuk kewenangan yang diserahkan ke daerah dalam rangka otonomi
daerah. Hal ini mungkin disebabkan oleh karena belum terdapat gambaran yang
jelas hal-hal apa yang dapat diserahkan ke daerah tanpa menimbulkan dampak yang
merugikan. Ini sesuai dengan tantangan pertama yang telah dikemukakan dan
menjadi tugas pertama yang harus dilaksanakan oleh mereka yang memiliki
kepedulian terhadap masalah sumberdaya air dalam rangka mendukung perwujudan
otonomi daerah. Kejelasan atas masalah ini niscaya juga akan ikut mengurangi
kebingungan yang saat ini sedang melanda banyak pihak terkait dalam pengelolaan
sumberdaya air, baik di lingkungan internal birokrasi pemerintah maupun yang
ada di luar. Dalam situasi seperti ini dituntut peran aktif para penggiat di
bidang sumberdaya air yang memiliki pemahaman terhadap masalah-masalah
sumberdaya air. Jika tidak, arus desentralisasi akan lebih banyak ditentukan
oleh mereka yang kurang banyak memahami masalah-masalah sumberdaya air sehingga
mungkin akan justru merugikan kepentingan pengelolaan sumberdaya air sendiri.
- Benveniste, GUY, 1989. Birokrasi. Rajawali Pers. Jakarta
- Pasandaran, Efendi. 1991. Irigasi di Indonesia : Strategi dan Pengembangan. LP3ES. Jakarta.
- Sofer, Cyril. 1973. Organizations in Theory and Practice. Heinemann Educational Books Ltd. London.
- Anonim. 1999. Undang-undang Ri No 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. CV Mini jaya Abadi. Jakarta.