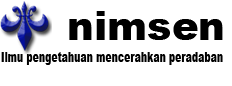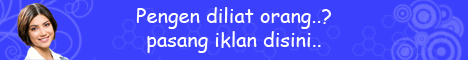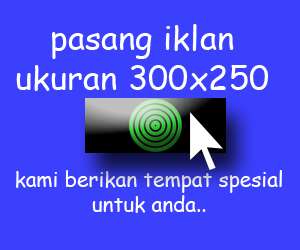Dr. Ade Saptomo, SH.,MA.
Fakultas Hukum dan Intergrated Natural Resources Management
Program Pascasarjana Universitas Andalas Padang
Abstract
his article elaborates the meaning of
certification of land right, which often discussed on legal or not legal aspect
in some certain territorial in Indonesia, particularly in pedalaman. The result
of such analysis is, first, there is a
correlation among of them, that is an effort to get power, rich, famous, and
authority. Second, there is a worry of them, that is afraid of unsafe. To save
it, there is a solution that is usually used to overcome such unsaved. What has
been got, shall be proved by document such as a certificate. Of course, such
certificate phenomena is interpreted that the behind of certificate, there is
an individualism, a hedonism which is brought by the globalism.
Kata kunci:hukum adat, tanah negara, tanah
ulayat, hak eigendom.
Pendahuluan
Hasil penelitian tentang eksistensi dan pola
penguasaan tanah adat di Sumatera Barat, Kalimantan Barat, dan di Nusa Tenggara
Barat menunjukkan bahwa tanah adat masyarakat tempatan masih ada, sekaligus
menunjukkan dinamika penguasaan hak atas tanah beragam.1 Dua hal menarik yang perlu dikemukakan dalam tulisan ini adalah
fenomena model sertifikat hak atas tanah. Di Sumatera Barat misalnya, terdapat
dua jenis model sertifikat, pertama, sertifikat hak atas tanah dengan model kepemilikan bersama.
Model dimaksud berupa selembar sertifikat hak atas tanah dimana di atas lembaran
dimaksud tertulis nama seorang kepala kaum atau suku sebagai penanggung jawab
komunitasnya dan di balik lembaran sertifikat dimaksud tertulis sejumlah nama
anggota kaum suku dimaksud. Kedua, terdapat pandangan
bahwa setiap bidang tanah yang disertifikatkan dianggap sebagai sebagai tanah
“liar”. Alasannya, tanah yang sudah disertifikatkan akan menjadi bebas bagi
pemiliknya untuk dijual, disewa, digadai, dan sejenisnya.
Dalam konsep lokal, memang hubungan antara
warga masyarakat tempatan dengan tanah tidak diukur dengan selembar kertas yang
disebut sertifikat, tetapi riwayat penggarapan tanah secara
turun temurun, pengakuan tokoh-tokoh adat,
dan kesaksian orang lain menjadi faktor penentu. Oleh sebab itu, jumlah warga
masyarakat yang tidak mengerti dan memahami fungsi sertifikat hak atas tanah
mungkin tak terhitung jumlahnya mengingat pembuktian dan bukti ada di tangan
yang secara kultural memang telah berjalan secara turun temurun. Apalagi bagi
mereka yang tak pernah merasa berkepentingan untuk membebaskan diri dari alam
pemikiran hukum adat, tentu dalam peta kognisinya akan berkukuh bulat untuk
tetap merujuk kepada struktur normatif lama.
Kini, permasalahannya adalah sebagian tanah
ulayat telah menjadi tanah negara dan sebagian lain telah mejadi tanah perorangan.
Ini berarti terjadi transformasi tanah ulayat menjadi tanah negara melalui
interaksi antara hukum negara (Agrarian Law) dan hukum lokal (Adat Law) yang hubungannya dibuktikan dengan selembar sertifikat mulai
dari sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan tanah perorangan atau individual
dengan sertifikat Hak Milik (HM). Sertifikat-sertifikat tersebut telah menjadi dokumen
penting dalam realitas sosial sehari-hari yang dapat digunakan untuk
kepentingan ekonomi. Ini berarti ada kecenderungan sebagian orang tidak
mempercayai kepemilikan hak atas suatu tanah tanpa dibuktikan dengan selembar
dokumen tertulis.
Dalam konteks tanah kepemilikan atas
sebidang tanah dengan dokumen selembar sertifikat hak atas tanah. Jika
sertifikat hak atas tanah tersebut dianggap sebagai bukan produk sosial budaya local
dan dipandang sebagai liar atau asing sebagaimana pandangan di atas, maka kini
muncul pertanyaan penting, mengapa harus sertifikat dan apa makna di balik
sertifikasi hak atas tanah.
Kerangka Teoritis
Sebelum menjawab pertanyaan tersebut di
atas, di bawah ini disampaikan lebih dahulu konsep-konsep filosofis4 yang digunakan sebagai alat untuk menjelaskan makna apa yang
terdapat di balik sertifikasi hak atas tanah. Pertama, globalisme. Globalisme sebagai suatu konsep filosofis dapat menunjuk
kepada suatu proses penyebaran sesuatu ke seluruh penjuru dunia yang dikerjakan
oleh suatu kekuatan tertentu. Kekuatan dimaksud mengerjakan suatu proses yang
membawa serta warga masyarakat di seluruh penjuru dunia untuk menerima
peradaban baru, tidak saja dalam bidang teknologi, tetapi juga bidang ekonomi,
sosial, budaya, dan hukum. Dengan begitu ia berisi suatu proses penggantian
filsafat yang telah dianut oleh masyarakat tempatan dengan filsafat luar yang
terbawa serta dalam arus globalisasi.
Kedua, individualisme. Individualisme sebagai konsep filosofis menggerakkan
masyarakat di seluruh dunia untuk menerima sebuah proses menuju kemajuan
materiil dengan sebuah taruhan
beresiko tinggi yang tak dapat terbagi
kepada orang lain. Artinya, secara substansial, ada kekuatan yang mengglobalkan
suatu ide beserta hasil-hasilnya ke dalam kehidupan materi semua umat manusia.
Ketiga, hedonisme. Hedonisme dimaksud diartikan sebagai faham pencapaian
kekayaan, kekuatan, ketenaran, dan kekuasaan. Artinya, petualangan kearah
perbaikan kehidupan manusia dilakukan dengan tujuan menjadikan hidup mereka
serba berkecukupan materi. Fanatisme perjuangan demikian melahirkan sebuah pandangan
bahwa tujuan hidup di dunia tidak lain adalah mencari kehidupan bergelimang
materi. Faham yang menekankan materi demikian ini biasa disebut materialisme (materialism), suatu faham yang memacu mereka untuk
berjuang keras untuk memperoleh harta kekayaan dalam jumlah sebanyak-banyaknya.
Keempat, konsep interaksi antarhukum. Menurut pandangan Moores (1987),
jika hukum negara dan hukum lokal berinteraksi di dalam lokal sosial sama (one social field) diduga akan melahirkan empat kemungkinan.
Kemungkinan dimaksud diasumsikan sebagai integrasi (integrate) yaitu penggabungan sebagian hukum negara dan hukum lokal, inkoorporasi
(incoorporate) yaitu penggabungan sebagian hukum negara
ke dalam hukum adat atau sebaliknya, konflik (conflict) yang tidak terjadi penggabungan sama sekali mengingat hukum
negara dan hukum lokal dimaksud saling bertentangan, dan menghindar (avoidance) yaitu salah satu hokum menghindari kebelakukan hukum yang
lain. Dengan konsepkonsep filosofis dan perspektif pluralisme hukum tersebut
diharapkan dapat menjelaskan apa makna yang ada di balik sertifikasi hak atas
tanah.
Dari Ipso Facto ke Ipso Jure
Mendiskusikan persoalan tanah dan sertifikat
hak atas tanah (agrarian aspect), tentu, satu hal yang harus dicoba untuk
dibayangkan surut ke belakang adalah tentang keadaan alam pertanahan
sekitar jauh sebelum Negara Kesatuan
Republik Indonesia berdiri.
Imajinasi ke belakang yang tertangkap
menggambarkan bahwa kala itu alam pertanahan, apakah lahan tanah itu sendiri,
apa yang ada di atasnya seperti hutan, sungai, dan apa yang ada di dalamnya seperti
tambang, apa yang ada di sampingnya seperti laut, dan ikan tidak atau belum
diatur oleh manusia mengingat jumlah manusia masih amat terbatas. Ketika
manusia lahir, tumbuh, dan beranak pinak sehingga semakin banyak jumlahnya,
maka mulai tumbuh hubungan erat antara manusia dan tanah baik secara
perseorangan maupun kelompok. Ini ditandai dengan upaya membuka lahan, hutan,
dan menentukan luas-sempit tanah yang dikuasai dengan memberi tanda-tanda batas
alam atau tanda buatan lainnya.
Fenomena demikian memperlihatkan bahwa
manusia mulai mengatur tanah dan kebiasaan manusia mengatur tanah semakin mapan,
bahkan sering diikuti oleh yang lain. Pertemuan aturan
satu dan yang lain menjadikan aturan itu
sendiri mulai teratur, diikuti, dan melembaga sehingga akhirnya menjadi hukum
adat. Oleh sebab itu, zaman nenek moyang hubungan antarorang, antara orang dan
alam, tanah, lahan serba diatur oleh apa yang disebut sebagai hukum adat dan
norma kerajaan sedemikian rupa sehingga hukum adat mewarnai semua arena bidang
kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan politik lokal masyarakat tempatan.
Dengan demikian, posisi hukum adat saat itu sangat kuat dan berakar tunjang
jauh ke dalam kultur masyarakat tempatan, sehingga dapat dibayangkan lebih
lanjut tentang suasana adat yang seolah tak bakal tersentuh oleh tangan-tangan
kekuasaan dan kekuatan luar yang datang dari manapun asalnya.
Ketidaktersentuhan itu menjadikan lahan
pertanahan terbentang luas, sekaligus merupakan aset tak bersubjek sehingga siapapun
yang berada di atas tanah dan lahan itu dianggap sebagai subjek secara mutlak (common property). Anggapan demikian muncul menyusul sebuah
pandangan religius bahwa tanah adalah bagian dari alam semesta ciptaan Illahi
untuk kepentingan makhluknya. Manusia sebagai salah satu dari makhluk lain berupaya
mencari dan menggali terus sumber daya alam yang lebih baru dibanding kehidupan
masa sebelumnya. Tanah, tentu dipandang sebagai salah satu sumber daya alam,
namun mengingat lahan pertanahan saat itu tak terukur luasnya maka tanah hanya dapat
dikuasi secara ipso fact. Artinya, tanah dipandang dikuasi apabila
secara nyata tanah dimaksud ditempati, dimanfaatkan, diusahakan, dan dirawat oleh
pemukim dan penggarapnya untuk kesejahteraan manusia.
Semakin lahan pertanahan dimaksud ditempati,
diolah dan dimanfaatkan secara nyata, maka hak penguasaan atas tanah akan semakin
menguat. Sebaliknya, semakin diterlantarkan, maka hak penguasaan dimaksud akan semakin
mengabur. Jika demikian halnya, hak individual itu kembali tertransformasi
menjadi tanah bebas.
Imajinasi dilanjutkan ke arah zaman
raja-raja pribumi beberapa abad lalu. Saat itu, konsep-konsep yang lahir,
hidup, tumbuh, dan berkembang di dalam suasana peradatan. Para raja pribumi bukan
penggarap-penggarap tanah sehingga tidak perlu secara ipso facto menjadi penguasa atas lahan pertanahan. Para
penguasa pribumi hanyalah penguasa atas suatu kawasan yurisdiksi tertentu berikut
penduduk yang berada dan bermukim di dalam lingkungan kawasan dimaksud. Dengan
demikian, pada masa raja-raja pribumi tidak ada perubahan konsep penguasaan hak
atas tanah. Keadaan ini dapat dirasakan keberadaannya, terutama di Jawa,
sementara di luar Jawa tentu suasana hukum adat masih menyelimuti secara utuh.
Pada masa pemerintahan kolonial, kedatangan
pemerintah kolonial di bumi nusantara ini menjadikan suasana hukum adat mengalami
perubahan. Perubahan-perubahan tak terhindarkan lagi mengingat terjadi hubungan
sosial antara masyarakat tempatan dan pemerintah kolonial. Perubahan dimaksud
terjadi menyusul praktek-praktek hubungan sosial, politik, ekonomi, dan hukum
di bawah konsep-konsep negeri Barat. Konsekuensinya, tentu, ia akan menafikkan
konsep-konsep hukum adat yang dalam hal pertanahan telah dinyatakan ipso facto, sementara konsep Barat mendalilkan ipso jure.
Sehubungan dengan itu, Pemerintah Hindia
Belanda yang memang sejak awal berkonsep Barat, hak gubernur (gubernemen) atas tanah pun didalilkan secara ipso jure dari penguasa pribumi lewat kontrak panjang
(lange contracten) atau pernyataan pendek (korte verklaringen).9 Bertitik tolak dari
premis tersebut praktekprektek penguasaan ipso jure dicarikan alat pembenar yuridis berupa Agrarische Wet (Undang-Undang Agraria) pada tahun 1870 Ind.
Stb. 1870 No. 55). Undang-Undang Agraria dimaksud berisi suatu keputusan bahwa
tanah-tanah di Jawa dan Madura, yang di atasnya tak dapat dibuktikan adanya hak
eigendom merupakan
domein negara.
Pada perkembangan waktu kemudian, sebuah
ordonansi yang dikenal dengan sebutan Algemene Domeinverklaring, yang dimuat dalam Agrarische Wet 1875 (Ind. Stb. 1875 No.
1991) diterbitkan. Di sana,
dinyatakan undang-undang agaaia sebelumnya berlaku untuk daerah-daerah di luar
Jawa dan Madura. Faktor yuridis ini menjadi faktor penentu peniadaan kemutlakan
hak-hak adat masyarakat adat dan warganya atas tanah-tanah lahan warisan nenek
moyangnya secara ipso facto.
Namun demikian, aspek penggabungan antara
dua konsep di atas, juga dapat dibaca ketika hak-hak rakyat masih memperoleh pengakuan
de facto sebagai bezitrech yang dapat dimohonkan pengakuan de jure sebagai eigendom. Namun warga masyarakat tempatan tetap saja beranggapan bahwa
apabila keberadaannya di atas tanah-tanah lahan yang mereka tempati telah
berlangsung lama, turun-temurun, sudah cukup kuat untuk membuktikan haknya atas
tanah yang telah ditempati dan dimanfaatkan secara nyata itu.
Kebijakan kolonial mengenai pengakuan hak
atas rakyat yang dikonsepkan sebagai bezitrecht kian lama kian sulit diteruskan. Terutama, pada era
pascakolonial tatkala pembangunan nasional menuntut pemanfaatan tanah-tanah
lahan secara nasional untuk tujuan produktif. Sementara itu keberadaan lahan
pertanahan kian langka dan tidak sebanding dengan akselerasi tingkat kepadatan penduduk.
Perebutan tanah menjadi tak terelakkan lagi dan dalam proses perebutan itu
pembenaran-pembenaran hak berdasarkan hukum sangat menentukan. Satu hal yang
menjadi persoalan kemudian, menurut Wignyosoebroto, adalah hukum manakah yang harus
dijadikan dasar?
Hukum nasional (state law) baik yang dibangun berdasarkan atas sumber-sumber formil dan
materiil tetap saja terpersepsi oleh jutaan orang yang bermukim di pedalaman
sebagai hukum asing, yang tak mudah dikenali, dimengerti, dan dipahami, apalagi
dihayati oleh warga masyarakat tempatan. Dalam persoalan hak atas tanah
misalnya, sertifikat hak atas tanah tidak mudah dimengerti bagaimana mungkin
fakta penguasaan atas tanah yang telah berlangsung turun-temurun bisa tiba-tiba
dikesampingkan begitu saja oleh titel-titel yang termuat dalam sertifikat hak
atas tanah.
Di Balik Sertifikasi Hak Atas Tanah
Ketika orang mencari kehidupan dunia lebih
baik dari sebelumnya, upaya itu dibenarkan oleh sebuah faham hedonisme. Pemahaman
ini dapat ditelusuri ke belakang dengan merujuk pada perspektif filosofi orang
Barat yang menjelaskan bahwa menyusul benua Amerika ditemukan oleh Columbus
pada abad ke XV, orang Eropa Barat datang ke benua baru tersebut untuk
memperbaiki kehidupan sebelumnya. Di dunia Barat, alat untuk mencapai maksud
tersebut dengan rekayasa (engineering), penguasaan teknologi desain di berbagai bidang dan lini
menjadi impian. Apa yang kita lihat, ternyata sebagian impian mewujud menjadi
kenyataan, sebagaimana tampak pada bangsa Amerika dan Eropa saat ini.
Dalam pencapaian (achievement) impian-impian tadi memunculkan suasana
keindividualismean, dalam suasana seperti inipersaingan ketat menjadi unsur
penentu sehingga siapa saja yang berhasil dalam persaingan baik secara orang
perseorangan maupun kolektif, ia menjadi kaya, kekayaan menjadikan kuat,
kekuatan, membawa kekuasaan. Inilah sebagian yang dikehendaki hedonism ala
orang Barat. Namun di balik kesuksesan itu, ada suatu hal yang perlu dicatat
bahwa itu semua telah memunculkan rasa khawatir, was-was, cemas, dan gelisah
terhadap kekayaan materiil, kejayaan, kekuatan, kekuasaan, dan ketenaran yang
telah diperoleh akan terancam berkurang, hilang, bahkan punah baik pada masa
kini maupun pada masa mendatang.
Berkaitan dengan ini, dalam hedonisme ala
orang Barat pilihan keamanan (security) menjadi faktor penentu dalam upaya menjaga keutuhan apa yang
telah diperoleh dan mengamankan praktek realisasi faham-faham yang dimaksud di
kemudian hari. Artinya, faktor keamanan menjadi fokus berikutnya, upaya
penciptaan alat mesin berteknologi canggih, modern, efektif, dan efisien untuk menjaga,
mengamankan apa yang telah digapai segera diwujudkan. Semua ini telah dihasilkan dan kini terus
menerus dikembangmajukan, yang intinya untuk menggapai dan mengamankan
kemakmuran ekonomi, kesejahteraan, dan kebahagiaan yang telah diperoleh secara berkesinambungan.
Hedonisme telah merembes, menerabas, dan merebak ke seluruh bagian negara dan masyarakat di dunia, kecuali sebagian masyarakat lokal pedalaman sehingga rasa khawatir tidak kaya, tidak tenar, tidak berkuasa semakin terasa di benak sebagian warga masyarakat luas, baik kalangan profesi, pejabat negara, pegawai negara maupun yang bukan ketiganya, hampir di semua lapisan
dan lini kehidupan sosial. Hal ini semakin
berlebihan ketika sumber daya yang selama ini dinikmati semakin terbatas, masa
depan tidak begitu jelas, serta persaingan untuk memperoleh hal sama semakin ketat.
Dengan kata lain, rasa kekhawatiran terhadap
apa yang telah diperoleh dengan bekerja keras akan tidak diakui merupakan ancaman
kerangkeng ketidaknyamanan, ketidakamanan. Jika demikian halnya, tentu, hal ini
merupakan kekhawatiran umum yang melanda di setiap kognisi orang dan sekaligus
mencari jalan keluarnya. Hanya persoalannya adalah bagaimana mengatasi rasa kekhawatiran
terhadap ancaman kerangkeng ketidakamanan itu seharusnya dilakukan.
Tindakan mengamankan terhadap apa yang telah
diperoleh yang sesuai dengan pilar keadilan hukum, pilar keadilan sosiologis, dan
filosofis, tentu ke depan menjadi aman adalah sertifikasi hak atas tanah.
Sertifikat hak atas tanah demikian ini dapat diinterpretasi sebagai bukti upaya
seseorang atau sekelompok orang yang mengamankan terhadap apa telah diperoleh
dengan caracara yang sesuai undang-undang, sehingga apa yang dilakukan dengan
pensertifikatan lambat laun menjadi “kebudayaan”.10
Penutup
Jika demikian halnya, maka sertifikasi dapat
diinterpretasi sebagai sebuah fenomena hedonisme. Artinya, ada tesis bahwa (1) di
balik sertifikasi hak atas tanah terdapat individualisme dan hedonisme yang
dibawa oleh globalisme. (2) Sertifikasi dipandang sebagai tindakan pengaman
terhadap apa yang diperoleh dengan kerja keras di masa kini dan masa
berikutnya. Kemudian, asumsi kedua dan ketiga, tentu tidak dapat dijelaskan
mengingat sebagian warga yang tidak bersedia atau menolak (conflict) dan sebagian lain menghindar (avoid) dari kemungkinan interaksi hukum local berinteraksi dengan
hukum negara. Hal ini juga dapat dibaca ketika sebagian warga masyarakat tetap
bersikukuh mempertahankan tanah ulayat dari upaya “pentransformasian” status
hukum tanah ulayat menjadi tanah negara. Dengan munculnya fenomena integrasi
dan inkoorporasi di daerah-daerah lainya di seluruh nusantara, tentu, akan
berimplikasi pada pembangunan hukum nasional, dimana hokum nasional yang
dihasilkan merupakan produk dialogis vertical antara hukum lokal dan hukum
negara, dan sekaligus dialogis horisontal antar-hukum lokal sehingga lewat
proses seperti ini akan ikut serta mendorong penguatan persatuan dan kesatuan
bangsa dan negara Indonesia ke depan. Di balik sertifikat itu juga lahir asumsi
inkoorporasi yaitu hukum adat menerima sebagian unsur hukum negara dan hokum negara
menerima sebagian hukum lokal (adat). Artinya, sebagian warga masyarakat
tempatan bersedia menerima unsur hukum Negara dan hukum negara pun “tidak
keberatan” untuk mengakomodasi keinginan warga. Hal ini dapat ditafsir pada
sebuah fenomena sertifikasi hak atas tanah ulayat di mana di
halaman depan sertifikat tertulis satu nama penghulu suku atau mamak kaum atas
sebidang tanah, sementara di balik sertifikat dimaksud tertuang sejumlah nama-nama
kemenakan penghulu suku sebagai pemilik bersama.
Praktek pentransformasi status sebagian
tanah adat menjadi tanah negara, misal ekstremnya, berlangsung pada bidang
tanah yang kini dimiliki orang Jawa di lokasi transmigrasi sebelum menjadi
milik perorangan. Tentu, sebelumnya tanah dimaksud berstatus tanah ulayat,
kemudian dinegarakan menjadi tanah negara. Akhirnya, ia menjadi tanah milik
perorangan dengan bukti
selembar sertifikat hak atas tanah.
DAFTAR PUSTAKA
Ali, Ahmad, 1998, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum,Jakarta, Yarsif Watampoe.
Budiardjo, Miriam ed, 1984, Kapitalisme, Sosialisme, Demokras,.Jakarta, Gramedia.
Evan, Willian M. ed, 1980. The Sociology of Law: A Social-StructuralPerspective, London, The Free Press.
Griffiths, J., 1986, “What is Legal
Pluralism” in Journal of Legal
Pluralism and Unofficial Law. No. 24/1986. Page 1-55
Koesnoe, Moh., 1997, Hukum Adat: Dalam alam Kemerdekaan Nasional
dan Persoalannya Menghadapi Era Globalisasi, Surabaya, Ubhara Press
Milovanovic, Dragan, 1994, A Primer in The Sociology of Law, New York, Harrow and Newton.
Moorse, Stradford W. and Gordon R Woodman,
1987, Indigeneous Law and
State, Dordrecht Holland:
Foris Publications.
Rahardjo, Satjipto, 1988, Ilmu Hukum, Bandung, Alumni.
————, 2002, Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan
Pilihan Masalah, Surakarta,
Muhammadiyah University Press.
Saptomo, Ade, 1995, Berjenjang Naik Bertangga Turun: Proses Penyelesaian
Sengketa Tanah Adat Dalam Masyarakat Minangkaba,. Tesis 2 .Jakarta, PPs UI
————, 2002, “Jamin”: Konstruksi Sosial Tentang
Integrasi Sukubangsa Jawa Dengan Minangkabau, Yogyakarta, PPs UGM.
Soesanobeng, Herman, 1997, Interpretasi Saat Ini Tentang Hubungan Antara
Hak Ulayat, Hak Komunal dan Tanah Negara. (paper tidak terbit), Jakarta, BPN-Unika
Atmajaya.
Sumardjono, Maria SW, 1998, UUPA dan Ulayat (paper tidak terbit), Jakarta, BPN.
Suparlan, Parsudi, 1999, “Konflik Sosial dan
Alternatif Pemecahannya” dalam Antropologi. Thn. XXIII. No. 59: 8-9.
Von Benda-Beckmann, Keebet, 1984, The Broken Stairways to Concensus, Village Justice and State Coutrs in Minangkabau, Dordrecht, Foris Publications.
Wignjosoebroto, Soetandya, 1996, Tanah Negara: Tanah Adat Yang Dinasionalisasi
(paper tidak terbit),
Jakarta, Elsam.
————, 2002, Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, Jakarta, Elsam dan Huma.