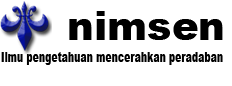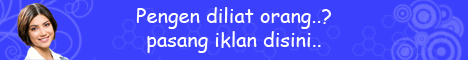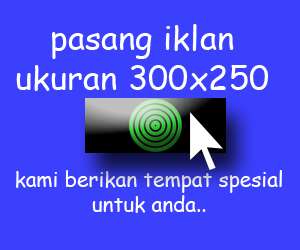(Suatu Kajian dalam Perspektif Filsafat Hukum)
Oleh : Suhartono, S.Ag., SH., MH.
(Hakim PA Martapura)
Abstrak
Oleh : Suhartono, S.Ag., SH., MH.
(Hakim PA Martapura)
Abstrak
Dalam prakteknya, prinsip-prinsip rule of law lebih tercermin pada cara, sifat, sikap dan suasana kebebasan para hakim dalam menyelesaikan perkara yang dihadapi, karena hakim dalam memutus
perkara menggunakan practical reason tentunya sangat dipengaruhi oleh latar belakang masing-masing individu. Sedangkan tak seorangpun mampu menilai rasio praktis kecuali dirinya sendiri mealui nuraninya.
Menurut Paul Scholten, berbicara nilai erat kaitannya dengan integritas moral yang tentunya bersifat relative, sedangkan menurut Hans Kelsen, keadilan yang dapat diwujudkan adalah keadilan yang bersifat relatif sesuai dengan keterbatasan manusia : “My justice, is the justice of freedom, the justice of peace, the justice of democracy – the justice of tolerance”. Jeremy Bentham melihat keadilan bisa terwujud apabila mencakup kebahagiaan sebagian besar individu: “The greatest possible happiness of the greatest possible number of individuals”, sedangkan Roscoe Pound membuat parameter keadilan dengan tingkat pencapaian kepuasan dari suatu putusan hakim. Oleh karena begitu peliknya memaknai keadilan sampai Friedman mengatakan, sejarah hukum alam adalah sejarah kegagalan manusia dalam menemukan keadilan.
Hakim dalam kebebasannya memutus perkara selalu dipengaruhi oleh beberapa atribut yang terus melekat pada dirinya, hakim tidak bisa hanya memegang prinsip legalitas saja (homo yuridicus), karenanya juga mendasarkan pada ethical principle, yakni baik dengan mendasarkan pada keutamaan-keutamaan moral (homo ethicus) maupun keutamaan-keutamaan teologal (homo religious).
Kanta Kunci : Kebebasan Hakim, keadilan, rule of law, etika profesi hakim.
A. Pendahuluan Hakekat kebebasan hakim adalah jika seorang hakim dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dalam menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat serta bebas dari berbagai pengaruh dan berbagai kepentingan baik dari dalam maupun dari luar, termasuk kepentingan dirinya sendiri demi tegaknya hukum dan keadilan. Misi hukum yang diemban oleh hakim sebagaimana tesis Gustav Radbruch adalah hakim berada dalam ranah ideal (das sollen) dan ranah empirik (das sein). Adapaun tugas hakim adalah menarik ranah ideal ke dalam ranah empirik seakan-akan hukum yang ada di dunia kenyataan dihimbau untuk mengikuti hukum yang ada di dunia ide sebagaimana yang dimaksudkan hukum alam. Sebagai suatu proses, penegakan hukum tidak pernah selesai karena salah satu yang ditegakkan adalah keadilan yang merupakan nilai yang tidak dapat dimaknai secara subyektif. Oleh karena itu menurut Soepomo, hakim dalam melaksanakan tugasnya menurut adat terikat dan bebas untuk meninjau secara mendalam apakah putusan-putusan yang diambil pada waktu yang lampau masih dapat dipertahankan berhubung adanya perubahan-perubahan di dalam masyarakat disebabkan adanya pertumbuhan rasa keadilan yang baru dalam masyarakat.
Menurut Bagir Manan1, keadilan subtantif menyangkut isi keadilan itu sendiri. Untuk dapat menemukan secara tepat subtansi keadilan haruslah dibedakan antara keadilan individual (individual justice) dan keadilan social (social justice). Sangat ideal apabila keadilan individual tercermin dalam keadilan social atau sebaliknya keadilan social menjadi tidak lain dari sublimasi keadilan individual. Namun dalam kenyataannya dapat terjadi semacam jarak antara keadilan individual dan keadilan social. Jarak ini dapat diatasi atau dikurangi, apabila dalam sistem penegakan hukum dapat dengan cermat dilekatkan nilai social atau moral dari setiap aturan hukum yang akan ditegakkan. Dengan demikian dalam setiap keadilan individual akan terkandung keadilan social. B. Kebebasan Eksistensial Hakim dalam Menegakkan Hukum dan Keadilan.
Secara etimologis makna bebas menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia2 adalah :
a. Lepas sama sekali (tidak terhalang, terganggu dan sebagainya, sehingga boleh bergerak, bercakap, berbuat dan sebagainya dengan leluasa).
b. Lepas dari kewajiban, tuntutan, ketakutan, tidak dikenakan pajak, hukuman dan sebagainya, tidak terikat atau terbatas.
c. Merdeka (tidak diperintah atau sangat dipengaruhi oleh negara lain).
Arti pada huruf a dan b di atas bersifat umum dan dasariah, sedangkan arti merdeka sudah merupakan arti khusus.
Menurut Rifyal Ka’bah3, Sifat merdeka menunjukkan kemandirian hakim dalam memutuskan perkara yang dihadapkan padanya tanpa campur tangan pihak lain, baik eksekutif maupun legislative atau lainnya, namun kemerdekaan hakim tidaklah bersifat mutlak, tetapi dibatasi oleh hukum yang berlaku. Dus, disamping dipengaruhi oleh integritas dirinya dalam menetapkan apa yang adil dan tidak adil, hakim harus memutus sesuai dengan apa yang dipandang adil oleh hukum.
Menurut Arbijoto4, kebebasan eksistensial bukan berarti lepas dari segala kewajiban atau kekhawatiran dan tangung jawab, melainkan kebebasan sebagai makna eksistensinya selaku manusia, kemandirianya selaku manusia. Sedangkan kebebasan hakim dalam kapasitasnya sebagai makhluk individu mempunyai kebebasan sebagai kesempurnaan eksistensinya sebagai manusia. Adanya paksaan, ikatan, beban adalah merupakan alienasi yang menekan manusia sedemikian rupa sehingga menghalang-alangi pelaksanaan dirinya sebagai manusia yang utuh dan mandiri.5 Manusia sebagai makhluk individu mempunyai kebebasan sebagai kesempurnaan eksistensinya. Jika dikatakan bahwa setiap manusia menginginkan kebebasan bagi dirinya sendiri, maka yang dimaksudkan dengan pernyataan ini bukanlah kebebasan dalam arti “lepas dari segala kewajiban atau kekhawatiran dari tangung jawab” melainkan kebebasan sebagai makna eksistensinya selaku manusia, kemandiriannya selaku manusia.
Kebebasan sebagai arah dan tujuan hidup selaku manusia, adalah kebebasan yang sifatnya sedemikian rupa sehingga orangnya bebas dari aneka ragam alienasi yang menekannya dan bebas pula untuk kehidupan yang utuh, tidak tercela, berdikari dan kreatif, dalam arti kebebasan sebagai kesempurnaan eksistensi manusia.
Menurut pemikiran Albert Camus6, memilih kebebasan bukanlah memilih sesuatu melawan keadilan. Sebaliknya kebebasan dipilih karena adanya orang-orang yang menderita dan berjuang untuk memperoleh keadilan. Memisahkan kebebasan dari keadilan adalah dosa social. Kebebasan harus diisi dengan mendahulukan kewajiban daripada hak dan selanjutnya digunakan untuk mengabdi pada keadilan.
Manusia sebagai makhluk otonom bicara kebebasan adalah menyangkut martabat manusia itu sendiri, itulah sebabnya setiap pemaksaan yang kita rasakan tidak hanya menyakitkan melainkan pula merupakan penghinaan, oleh karenanya pemaksaan berarti pengabaian martabat manusia. Pada masa tatanan lama, hakim dalam menjalankan profesinya tidak dapat dikatakan bebas. Hal ini nyata-nyata termaktub dalam Pasal 19 UU No. 19 Tahun 1964 yang memberikan wewenang kepada Presiden untuk dalam beberapa hal dapat turun atau campurtangan dalam soa-soal pengadilan. Hal ini oleh para hakim dirasakan adanya pembatasan kebebasan. Sehingga dalam MUNAS Luar Biasa bulan November 1966 terjadi konsesus bahwa sesuai dengan azas legalitas dalam suatu negara hukum,maka legitimasi dari kebebasan hakim dalam menjalankan profesinya tidak dapat diamendir dengan alasan apapun7 Jadi yang dimaksud kebebasan eksistensial adalah kemampuan manusia untuk menentukan tindakannya sendiri. Kemampuan itu bersumber pada kemampuan dirinya untuk menentukan tindakannya sendiri. Kemampuan itu bersumber pada kemampuan dirinya untuk berfikir dan berkehendak dan kemudian diimplementasikan dalam tindakannya. Tindakan itu bukan sesuatu di luar dirinya, tindakan itu adalah dengan dirinya sendiri. Pengingkaran terhadap kebebasan hakim dalam menjalankan tugasnya akan menafikan eksistensi hakim sebagai manusia dan ketaatan hakim pada ketentuan perundang-undangan, yang demikian itu akan meniadakan dirinya sendiri. Kebebasan itu disebut eksistensial karena merupakan ssuatu yang menyatu dengan manusia, artinya termasuk eksistensinya sebagai manusia. Kebebasan itu termasuk kemanusiaan kita, karena kebebasan itu merupakan eksistensi kita, kita biasanya tidak sadar bahwa kita memilikinya, kita baru menyadari kebebasan kita apabila ada yang membatasinya.
Menurut Yahya Harahap8, kebebasan hakim jangan diartikan kebebasan yang tanpa batas dengan menonjolkan sikap arrogance of power dengan memperalat kebebasan untuk menghalalkan segala cara, namun kebebasan tersebut relative dengan acuan :
a. Menerapkan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang tepat dan benar dalam menyelesaikan kasus perkara yang sedang diperiksanya, sesuai dengan asas dan statute law must prevail (ketentuan undang-undang harus diunggulkan);
b. Menafsirkan hukum yang tepat melalui cara-cara pendekatan penafsiran yang dibenarkan (penafsiran sistematik, sosiologis, bahasa, analogis dan acontrario) atau mengutamakan keadilan daripada peraturan perundang-undangan, apabila ketentuan undang-undang tidak potensial melindungi kepentingan umum. Penerapan yang demikian sesuai dengan doktrin equity must prevail (keadilan harus diunggulkan);
c. Kebebasan untuk mencari dan menemukan hukum (rechts vinding), dasar-dasar dan asas-asas hukum melalui doktrin ilmu hukum, norma hukum tidak tertulis (hukum adat), yurisprudensi maupun melalui pendekatan “realisme” yakni mencari dan menemukan hukum yang terdapat pada nilai ekonomi, moral, agama, kepatutan dan kelaziman.
Dalam batas-batas tersebut di atas jangkauan kebebasan hakim dalam melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman menyelesaikan sengketa perkara yang diperiksa. Bebas menerapkan hukum yang bersmber dari peraturan perundang-undangan yang “berlaku”, asal peraturan dan perundang-undangan yang bersangkutan tepat dan benar untuk diperlakukan terhadap kasus perkara yang diperiksa. Demikian pula kebebasan dalam menafsirkan hukum tidak dibenarkan menafsirkan hukum diluar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebebasan penafsiran yang dibenarkan harus melalui “pendekatan disiplin” yang diakui keabsahannya oleh teori dan praktek seperti pendekatan sistemik atau sosiologis, hakim juga diperbolehkan menggunakan pendekatan penasiran analogis dan a contrario dalam doktrin hukum Islam disamakan dengan qiyas dan istihsan.
Pendek kata, kebebasan hakim dalam melaksanakan kewajiban profesinya bukanlah bebas semau gue namun dibatasi oleh aturan dan norma, sedangkan kebebasan hakim dalam kapasitasnya sebagai makhluk individu mempunyai kebebasan sebagai kesempurnaan eksistensinya sebagai manusia. Adanya paksaan, ikatan, beban adalah merupakan alienasi yang meekan manusia sedemikian rupa sehingga menghalang-halangi pelaksanaan dirinya sebagai manusia yang untuh dan mandiri. Maksud kebebasan disini adalah secara negative tidak adanya paksaan. Konkritnya sebagai tidak adanya keniscayaan dalam arti determinasi, dan secara positif adanya otonomi.
C. Kebebasan Hakim dalam Perspektif Integritas Moral dan Etika Profesi
Salah satu topik yang menarik dalam kajian filsafat hukum adalah mengenai pembedaan antara hukum dan moralitas. Dalam kajian Hukum Barat, antara hukum dan moralitas memang mempunyai kaitan erat, tetapi hukum tidak sama dengan moralitas. Hukum mengikat semua orang sebagai warga negara, tetapi moralitas hanya mengikat orang sebagai individu.
Apakah moralitas berasal dari pemikiran dan perasaan manusia atau dari Tuhan yang mengetaui hakekat baik dan buruk? Pertanyaan ini yang menyibukkan para filsuf dan moralis sepanjang masa. Teolog Kristen seperti Wlliam Paley (1743-1805) misalnya, begitu pla William of Ockham (1290-1349) dan Martin Luther (1483-154) sebelumnya berpendapat bahwa moralitas ditentukan oleh keinginan Tuhan. Sementara itu para penganut utilitarianisme yang selalu menilai manfaat yang dapat diambil dari segala sesuatu menyatakan bahwa moralitas tersebut ditentukan oleh kebahagiaan hidup yang ditimbulkannya.9 Dalam teori pemisahan antara hukum dan moralitas dikatakan, bahwa hukum adalah suatu hal dan moralitas adalah hal lain, atau dengan kata lain : hukum tidak selalu sisi lain dari mata uang yang sama. Ini berarti bahwa hakim hanya memberikan perhatian terhadap hukum dan tidak memberikan perhatian terhadap moralitas. Sebenarnya hukum yang baik berasal dari moralitas yang baik, dan moralitas yang baik melahirkan hukum yang baik. Apakah bangsa Indonesia juga membuat demarkasi antara hukum dan moralitas? Secara teoritis, hukum Indonesia tidak boleh bertentangan dengan moralitas bangsa Indonesia.
Integritas berasal dari bahasa latin yang berarti “keterikatan yang dalam kepada sebuah kode nilai-nilai moral” (firm adherence to a code of moral values) atau “suatu kualitas atau keadaan yang sempurna, atau tidak tidak terbagi” (the quality or state of being complete or undivided). Integritas mirip dengan kata inggris sincerity10. Selain bermakna ikhlas, kata itu juga mencerminkan sebuah tingkah laku yang wajar dan terikat kepada fakta. Jadi, kata integritas itu sendiri telah mengandung keterikatan kepada nilai-nilai moral. Moralitas adalah tingkah laku yang bermoral (moral conduct) atau aturan-aturan tingkah laku (rues of conduct) atau kecocokan tingkah laku manusia dengan nilai-nilai terbaik (conformity to idealsof right human conduct). Moral sebagai kata sifat adalah sesuatu yang berhubungan dengan prinsip-prinsip baik dan buruk dalam masyarakat. Moral berasal dari bahasa latin moralis, dari kata mos yang berarti kebiasaan atau adat kebiasaan (custom). Moralitas berhubungan dengan prinsip-prinsip baik dan buruk dalam tingkah laku yang dimulai dari kebiasaan dan membutuhkan pembiasaan. Integritas moral seseorang terkait erat dengan pendidikan, lingkungan, mungkin juga keturunan, dan ketaatan kepada nilai-nilai agama. Sikap salah kaprah terhadap moralitas dan agama ini telah menjadi salah satu factor kurangnya integritas individu dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai kasus kebebasan hukum yang kebablasan dilakukan oleh hakim sebagai penegak hukum adalah bukti ketiadaan integritas moral dalam kehidupan bermasyarakat. Moralitas agama berhubungan dengan pikran sehat, hati nurani dan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai tertinggi semua makhluk. Oleh karena itu, integritas kepribadian yang baik tidak mungkin diharapkan diluar agama.
Tujuan pokok rang bekerja adalah memenuhi kebutuhan hidup dengan mengandalkan suatu keahliannya. Jadi perbedaan profesi dan pekerjaan pada umumnya, bahwa profesi menuntut keahlian yang khusus. Kekhususan itu meliputi pelayanan pada manusia atau masyarakat. Kendatipun orang menjalankan profesinya untuk memenuhi haknya maupun kebutuhan keluarganya, namun profesinya menuntut bukan hal tersebut yang menjadi motivasi utamanya melainkan kesediaan untuk melayani sesamanya, oleh karenanya dituntut untuk berbudi luhur.
Seorang hakim dikatakan berbudi luhur dan berakhlak tinggi apabila mempunyai sikap “sepi ing pamrih rame ing gawe” mendahulukan kepentingan para pencari keadilan daripada kepentingan pribadi dengan menjnjung tinggi etika profesi. Agar dalam menjalankan profesinya sesuai dengan etika profesi maka hakim harus:
1. Menjadi orang yang tidak mudah dipengaruhi oleh perasaan takut, malas, malu, emosi dan lain sebagainya. Artinya, ia harus memiliki kepribadian moral yang kuat tidak mudah dipengaruhi oleh tekanan dan kepentingan pihak manapun.
2. Sadar bahwa mempertahankan tuntutan etika profesi merupakan suatu kewajiban yang berat, karena dalam melaksanakan profesinya tidak jarang menghadapi intrik, godaan yang muncul dari dirinya sendiri untuk mendapatkan pamrih atau motivasi hedonisme yang berlebihan, maupun tekanan dari luar, baik berupa intimidasi, rayuan dan sebagainya.
3. Memiliki idealisme yang kuat.
Bertens11 menyatakan, kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesitu di mata masyarakat. Kode etik profesi merupakan produk etika terapan karena dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis atas suatu profesi. Kode etik profesi adalah rumusan norma moral manusia yang mengemban profesi dan menjadi tolak ukur perbuatan anggota kelompok profesi. Kode etik profesi merupakan upaya pencegahan berbuat yang tidak etis bagi anggota.
Setiap kode etik profesi selalu dibuat tertulis yang tersusun secara eratur, rapi, lengkap, dalam bahasa yang baik tetapi singkat sehingga menarik perhatian dan menyenangkan pembacanya. Alasan dibuat tertulis megingat fungsinya sebagai sarana control sosal, pencegah campur tangan pihak lain, dan penceah kesalahpahaman dan konflik. Namun kode etik profesi mempunyai kelemahan, yaitu terlalu idealis yang tidak sejalan dengan fakta yang terjadi disekitar professional, sehingga menimbulkan kecenderungan untuk diabaikan.12
Sanksi terhadap sumpah dan janjinya adalah bersifat psikis dan merupakan sanksi primair yang diderita oleh hakim yang melanggar etika profesinya, sedangkan sanksi yang diberkan oleh asosiasi profesinya baik berupa tegoran, peringatan sampai pada pemecatan sebagai anggota profesi (pemecatan sebagai hakim) adalah bersifat sekunder. Sanksi yang diberikan asosiasi tersebut pelaksanannya dapat dipaksakan, karena bagi hakim yang telah melanggar kode etik tersebut dapat dinyatakan oleh asosiasi profesinya telah ingkar janji terhadap apa yang telah dijanjikannya kepada asosiasi profesinya. Sedangkan janji tersebut bersifat mengikat berlaku sebagai undang-undang, karenanya bagi pelanggarnya berlaku norma hukum bukan hanya norma moral saja, sehingga terhadap pelanggarnya dapat dipaksakan untuk memenuhi janjinya (pacta sunt servanda). Salah satu syarat menjadi professional adalah ketakwaan kepada Allah SWT., yaitu melaksanakan perintah dan menjahi larangan-laragan-Nya. Ketakwaan ini adalah dasar moral hakim. Jika hakim mempertebal iman dan takwa, maka di dalam diri akan tertanam nilai moral yang menjadi rem jika ingin berbuat buruk.
D. Penutup
Kebebasan eksistensial menyatu dengan diri manusia, artinya include eksistensinya sebagai individu. Kebebasan itu termasuk kemanusiaan kita, pengingkaran terhadap kebebasan hakim dalam menjalankan tugasnya berarti menafikan eksistensi hakim sebagai manusia dan ketaatan hakim pada ketetuan perundang-undangan yang demikian itu adalah meniadakan eksistensisi dirinya sendiri. Atribut kebebasan hakim jangan digunakan semau gue karena sikap tersebut adalah bentuk arrogance of power dan pengalpaan eksistensi hakim disamping sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk Tuhan yang diberi amanah sebagai wakil Tuhan di bumi.
Hendaknya setiap ptusan hakim selalu merefleksikan integritas moral yang dilandasi oleh prinsip-prinsip keutamaan moral dan teologal, sehingga keadilan yang diperoleh bukan keadilan yang absurd namun keadilan sesuai dengan yang dirasakan masyarakat luas. Seorang hakim tidak boleh termotivasi sifat hedonisme berlebihan, namun termotivasi melaksanakan cita-cita luhur, yang pada hakekatnya berupa pelayanan pada para pencari keadilan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan etika profesinya.
DAFTAR PUSTAKA
Arbijoto. 2000. Kebebasan Hakim (refleksi Terhadap Manusia Sebagai Homo Relegiosus), Jakarta: Mahkamah Agung RI.
Bertens, K. 1994. Etika. Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama.
Camus, Albert. 1988. Krisis Kebebasan (Terjemahan Edhi Martono). Jakata: Yayasan Obor.
Harahap, M. Yahya. 1994. Beberapa Permasalahan Hukum Acara Pada Peradilan Agama. Jakarta: Al-Hikmah.
------------------------------. 2005. Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama. Jakarta: Sinar Grafika.
Ka’bah, Rifyal. 2004. Penegakan Syariat Islam di Indonesia. Jakarta: Khairul Bayan.
Manan, Bagir. 2007. Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian). Jakarta: Mahkamah Agung RI.
Muhammad, Abdul Kadir. 2001. Etika Profesi Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Poerwadarminta, W.J.S. 1984. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
perkara menggunakan practical reason tentunya sangat dipengaruhi oleh latar belakang masing-masing individu. Sedangkan tak seorangpun mampu menilai rasio praktis kecuali dirinya sendiri mealui nuraninya.
Menurut Paul Scholten, berbicara nilai erat kaitannya dengan integritas moral yang tentunya bersifat relative, sedangkan menurut Hans Kelsen, keadilan yang dapat diwujudkan adalah keadilan yang bersifat relatif sesuai dengan keterbatasan manusia : “My justice, is the justice of freedom, the justice of peace, the justice of democracy – the justice of tolerance”. Jeremy Bentham melihat keadilan bisa terwujud apabila mencakup kebahagiaan sebagian besar individu: “The greatest possible happiness of the greatest possible number of individuals”, sedangkan Roscoe Pound membuat parameter keadilan dengan tingkat pencapaian kepuasan dari suatu putusan hakim. Oleh karena begitu peliknya memaknai keadilan sampai Friedman mengatakan, sejarah hukum alam adalah sejarah kegagalan manusia dalam menemukan keadilan.
Hakim dalam kebebasannya memutus perkara selalu dipengaruhi oleh beberapa atribut yang terus melekat pada dirinya, hakim tidak bisa hanya memegang prinsip legalitas saja (homo yuridicus), karenanya juga mendasarkan pada ethical principle, yakni baik dengan mendasarkan pada keutamaan-keutamaan moral (homo ethicus) maupun keutamaan-keutamaan teologal (homo religious).
Kanta Kunci : Kebebasan Hakim, keadilan, rule of law, etika profesi hakim.
A. Pendahuluan Hakekat kebebasan hakim adalah jika seorang hakim dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dalam menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat serta bebas dari berbagai pengaruh dan berbagai kepentingan baik dari dalam maupun dari luar, termasuk kepentingan dirinya sendiri demi tegaknya hukum dan keadilan. Misi hukum yang diemban oleh hakim sebagaimana tesis Gustav Radbruch adalah hakim berada dalam ranah ideal (das sollen) dan ranah empirik (das sein). Adapaun tugas hakim adalah menarik ranah ideal ke dalam ranah empirik seakan-akan hukum yang ada di dunia kenyataan dihimbau untuk mengikuti hukum yang ada di dunia ide sebagaimana yang dimaksudkan hukum alam. Sebagai suatu proses, penegakan hukum tidak pernah selesai karena salah satu yang ditegakkan adalah keadilan yang merupakan nilai yang tidak dapat dimaknai secara subyektif. Oleh karena itu menurut Soepomo, hakim dalam melaksanakan tugasnya menurut adat terikat dan bebas untuk meninjau secara mendalam apakah putusan-putusan yang diambil pada waktu yang lampau masih dapat dipertahankan berhubung adanya perubahan-perubahan di dalam masyarakat disebabkan adanya pertumbuhan rasa keadilan yang baru dalam masyarakat.
Menurut Bagir Manan1, keadilan subtantif menyangkut isi keadilan itu sendiri. Untuk dapat menemukan secara tepat subtansi keadilan haruslah dibedakan antara keadilan individual (individual justice) dan keadilan social (social justice). Sangat ideal apabila keadilan individual tercermin dalam keadilan social atau sebaliknya keadilan social menjadi tidak lain dari sublimasi keadilan individual. Namun dalam kenyataannya dapat terjadi semacam jarak antara keadilan individual dan keadilan social. Jarak ini dapat diatasi atau dikurangi, apabila dalam sistem penegakan hukum dapat dengan cermat dilekatkan nilai social atau moral dari setiap aturan hukum yang akan ditegakkan. Dengan demikian dalam setiap keadilan individual akan terkandung keadilan social. B. Kebebasan Eksistensial Hakim dalam Menegakkan Hukum dan Keadilan.
Secara etimologis makna bebas menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia2 adalah :
a. Lepas sama sekali (tidak terhalang, terganggu dan sebagainya, sehingga boleh bergerak, bercakap, berbuat dan sebagainya dengan leluasa).
b. Lepas dari kewajiban, tuntutan, ketakutan, tidak dikenakan pajak, hukuman dan sebagainya, tidak terikat atau terbatas.
c. Merdeka (tidak diperintah atau sangat dipengaruhi oleh negara lain).
Arti pada huruf a dan b di atas bersifat umum dan dasariah, sedangkan arti merdeka sudah merupakan arti khusus.
Menurut Rifyal Ka’bah3, Sifat merdeka menunjukkan kemandirian hakim dalam memutuskan perkara yang dihadapkan padanya tanpa campur tangan pihak lain, baik eksekutif maupun legislative atau lainnya, namun kemerdekaan hakim tidaklah bersifat mutlak, tetapi dibatasi oleh hukum yang berlaku. Dus, disamping dipengaruhi oleh integritas dirinya dalam menetapkan apa yang adil dan tidak adil, hakim harus memutus sesuai dengan apa yang dipandang adil oleh hukum.
Menurut Arbijoto4, kebebasan eksistensial bukan berarti lepas dari segala kewajiban atau kekhawatiran dan tangung jawab, melainkan kebebasan sebagai makna eksistensinya selaku manusia, kemandirianya selaku manusia. Sedangkan kebebasan hakim dalam kapasitasnya sebagai makhluk individu mempunyai kebebasan sebagai kesempurnaan eksistensinya sebagai manusia. Adanya paksaan, ikatan, beban adalah merupakan alienasi yang menekan manusia sedemikian rupa sehingga menghalang-alangi pelaksanaan dirinya sebagai manusia yang utuh dan mandiri.5 Manusia sebagai makhluk individu mempunyai kebebasan sebagai kesempurnaan eksistensinya. Jika dikatakan bahwa setiap manusia menginginkan kebebasan bagi dirinya sendiri, maka yang dimaksudkan dengan pernyataan ini bukanlah kebebasan dalam arti “lepas dari segala kewajiban atau kekhawatiran dari tangung jawab” melainkan kebebasan sebagai makna eksistensinya selaku manusia, kemandiriannya selaku manusia.
Kebebasan sebagai arah dan tujuan hidup selaku manusia, adalah kebebasan yang sifatnya sedemikian rupa sehingga orangnya bebas dari aneka ragam alienasi yang menekannya dan bebas pula untuk kehidupan yang utuh, tidak tercela, berdikari dan kreatif, dalam arti kebebasan sebagai kesempurnaan eksistensi manusia.
Menurut pemikiran Albert Camus6, memilih kebebasan bukanlah memilih sesuatu melawan keadilan. Sebaliknya kebebasan dipilih karena adanya orang-orang yang menderita dan berjuang untuk memperoleh keadilan. Memisahkan kebebasan dari keadilan adalah dosa social. Kebebasan harus diisi dengan mendahulukan kewajiban daripada hak dan selanjutnya digunakan untuk mengabdi pada keadilan.
Manusia sebagai makhluk otonom bicara kebebasan adalah menyangkut martabat manusia itu sendiri, itulah sebabnya setiap pemaksaan yang kita rasakan tidak hanya menyakitkan melainkan pula merupakan penghinaan, oleh karenanya pemaksaan berarti pengabaian martabat manusia. Pada masa tatanan lama, hakim dalam menjalankan profesinya tidak dapat dikatakan bebas. Hal ini nyata-nyata termaktub dalam Pasal 19 UU No. 19 Tahun 1964 yang memberikan wewenang kepada Presiden untuk dalam beberapa hal dapat turun atau campurtangan dalam soa-soal pengadilan. Hal ini oleh para hakim dirasakan adanya pembatasan kebebasan. Sehingga dalam MUNAS Luar Biasa bulan November 1966 terjadi konsesus bahwa sesuai dengan azas legalitas dalam suatu negara hukum,maka legitimasi dari kebebasan hakim dalam menjalankan profesinya tidak dapat diamendir dengan alasan apapun7 Jadi yang dimaksud kebebasan eksistensial adalah kemampuan manusia untuk menentukan tindakannya sendiri. Kemampuan itu bersumber pada kemampuan dirinya untuk menentukan tindakannya sendiri. Kemampuan itu bersumber pada kemampuan dirinya untuk berfikir dan berkehendak dan kemudian diimplementasikan dalam tindakannya. Tindakan itu bukan sesuatu di luar dirinya, tindakan itu adalah dengan dirinya sendiri. Pengingkaran terhadap kebebasan hakim dalam menjalankan tugasnya akan menafikan eksistensi hakim sebagai manusia dan ketaatan hakim pada ketentuan perundang-undangan, yang demikian itu akan meniadakan dirinya sendiri. Kebebasan itu disebut eksistensial karena merupakan ssuatu yang menyatu dengan manusia, artinya termasuk eksistensinya sebagai manusia. Kebebasan itu termasuk kemanusiaan kita, karena kebebasan itu merupakan eksistensi kita, kita biasanya tidak sadar bahwa kita memilikinya, kita baru menyadari kebebasan kita apabila ada yang membatasinya.
Menurut Yahya Harahap8, kebebasan hakim jangan diartikan kebebasan yang tanpa batas dengan menonjolkan sikap arrogance of power dengan memperalat kebebasan untuk menghalalkan segala cara, namun kebebasan tersebut relative dengan acuan :
a. Menerapkan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang tepat dan benar dalam menyelesaikan kasus perkara yang sedang diperiksanya, sesuai dengan asas dan statute law must prevail (ketentuan undang-undang harus diunggulkan);
b. Menafsirkan hukum yang tepat melalui cara-cara pendekatan penafsiran yang dibenarkan (penafsiran sistematik, sosiologis, bahasa, analogis dan acontrario) atau mengutamakan keadilan daripada peraturan perundang-undangan, apabila ketentuan undang-undang tidak potensial melindungi kepentingan umum. Penerapan yang demikian sesuai dengan doktrin equity must prevail (keadilan harus diunggulkan);
c. Kebebasan untuk mencari dan menemukan hukum (rechts vinding), dasar-dasar dan asas-asas hukum melalui doktrin ilmu hukum, norma hukum tidak tertulis (hukum adat), yurisprudensi maupun melalui pendekatan “realisme” yakni mencari dan menemukan hukum yang terdapat pada nilai ekonomi, moral, agama, kepatutan dan kelaziman.
Dalam batas-batas tersebut di atas jangkauan kebebasan hakim dalam melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman menyelesaikan sengketa perkara yang diperiksa. Bebas menerapkan hukum yang bersmber dari peraturan perundang-undangan yang “berlaku”, asal peraturan dan perundang-undangan yang bersangkutan tepat dan benar untuk diperlakukan terhadap kasus perkara yang diperiksa. Demikian pula kebebasan dalam menafsirkan hukum tidak dibenarkan menafsirkan hukum diluar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebebasan penafsiran yang dibenarkan harus melalui “pendekatan disiplin” yang diakui keabsahannya oleh teori dan praktek seperti pendekatan sistemik atau sosiologis, hakim juga diperbolehkan menggunakan pendekatan penasiran analogis dan a contrario dalam doktrin hukum Islam disamakan dengan qiyas dan istihsan.
Pendek kata, kebebasan hakim dalam melaksanakan kewajiban profesinya bukanlah bebas semau gue namun dibatasi oleh aturan dan norma, sedangkan kebebasan hakim dalam kapasitasnya sebagai makhluk individu mempunyai kebebasan sebagai kesempurnaan eksistensinya sebagai manusia. Adanya paksaan, ikatan, beban adalah merupakan alienasi yang meekan manusia sedemikian rupa sehingga menghalang-halangi pelaksanaan dirinya sebagai manusia yang untuh dan mandiri. Maksud kebebasan disini adalah secara negative tidak adanya paksaan. Konkritnya sebagai tidak adanya keniscayaan dalam arti determinasi, dan secara positif adanya otonomi.
C. Kebebasan Hakim dalam Perspektif Integritas Moral dan Etika Profesi
Salah satu topik yang menarik dalam kajian filsafat hukum adalah mengenai pembedaan antara hukum dan moralitas. Dalam kajian Hukum Barat, antara hukum dan moralitas memang mempunyai kaitan erat, tetapi hukum tidak sama dengan moralitas. Hukum mengikat semua orang sebagai warga negara, tetapi moralitas hanya mengikat orang sebagai individu.
Apakah moralitas berasal dari pemikiran dan perasaan manusia atau dari Tuhan yang mengetaui hakekat baik dan buruk? Pertanyaan ini yang menyibukkan para filsuf dan moralis sepanjang masa. Teolog Kristen seperti Wlliam Paley (1743-1805) misalnya, begitu pla William of Ockham (1290-1349) dan Martin Luther (1483-154) sebelumnya berpendapat bahwa moralitas ditentukan oleh keinginan Tuhan. Sementara itu para penganut utilitarianisme yang selalu menilai manfaat yang dapat diambil dari segala sesuatu menyatakan bahwa moralitas tersebut ditentukan oleh kebahagiaan hidup yang ditimbulkannya.9 Dalam teori pemisahan antara hukum dan moralitas dikatakan, bahwa hukum adalah suatu hal dan moralitas adalah hal lain, atau dengan kata lain : hukum tidak selalu sisi lain dari mata uang yang sama. Ini berarti bahwa hakim hanya memberikan perhatian terhadap hukum dan tidak memberikan perhatian terhadap moralitas. Sebenarnya hukum yang baik berasal dari moralitas yang baik, dan moralitas yang baik melahirkan hukum yang baik. Apakah bangsa Indonesia juga membuat demarkasi antara hukum dan moralitas? Secara teoritis, hukum Indonesia tidak boleh bertentangan dengan moralitas bangsa Indonesia.
Integritas berasal dari bahasa latin yang berarti “keterikatan yang dalam kepada sebuah kode nilai-nilai moral” (firm adherence to a code of moral values) atau “suatu kualitas atau keadaan yang sempurna, atau tidak tidak terbagi” (the quality or state of being complete or undivided). Integritas mirip dengan kata inggris sincerity10. Selain bermakna ikhlas, kata itu juga mencerminkan sebuah tingkah laku yang wajar dan terikat kepada fakta. Jadi, kata integritas itu sendiri telah mengandung keterikatan kepada nilai-nilai moral. Moralitas adalah tingkah laku yang bermoral (moral conduct) atau aturan-aturan tingkah laku (rues of conduct) atau kecocokan tingkah laku manusia dengan nilai-nilai terbaik (conformity to idealsof right human conduct). Moral sebagai kata sifat adalah sesuatu yang berhubungan dengan prinsip-prinsip baik dan buruk dalam masyarakat. Moral berasal dari bahasa latin moralis, dari kata mos yang berarti kebiasaan atau adat kebiasaan (custom). Moralitas berhubungan dengan prinsip-prinsip baik dan buruk dalam tingkah laku yang dimulai dari kebiasaan dan membutuhkan pembiasaan. Integritas moral seseorang terkait erat dengan pendidikan, lingkungan, mungkin juga keturunan, dan ketaatan kepada nilai-nilai agama. Sikap salah kaprah terhadap moralitas dan agama ini telah menjadi salah satu factor kurangnya integritas individu dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai kasus kebebasan hukum yang kebablasan dilakukan oleh hakim sebagai penegak hukum adalah bukti ketiadaan integritas moral dalam kehidupan bermasyarakat. Moralitas agama berhubungan dengan pikran sehat, hati nurani dan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai tertinggi semua makhluk. Oleh karena itu, integritas kepribadian yang baik tidak mungkin diharapkan diluar agama.
Tujuan pokok rang bekerja adalah memenuhi kebutuhan hidup dengan mengandalkan suatu keahliannya. Jadi perbedaan profesi dan pekerjaan pada umumnya, bahwa profesi menuntut keahlian yang khusus. Kekhususan itu meliputi pelayanan pada manusia atau masyarakat. Kendatipun orang menjalankan profesinya untuk memenuhi haknya maupun kebutuhan keluarganya, namun profesinya menuntut bukan hal tersebut yang menjadi motivasi utamanya melainkan kesediaan untuk melayani sesamanya, oleh karenanya dituntut untuk berbudi luhur.
Seorang hakim dikatakan berbudi luhur dan berakhlak tinggi apabila mempunyai sikap “sepi ing pamrih rame ing gawe” mendahulukan kepentingan para pencari keadilan daripada kepentingan pribadi dengan menjnjung tinggi etika profesi. Agar dalam menjalankan profesinya sesuai dengan etika profesi maka hakim harus:
1. Menjadi orang yang tidak mudah dipengaruhi oleh perasaan takut, malas, malu, emosi dan lain sebagainya. Artinya, ia harus memiliki kepribadian moral yang kuat tidak mudah dipengaruhi oleh tekanan dan kepentingan pihak manapun.
2. Sadar bahwa mempertahankan tuntutan etika profesi merupakan suatu kewajiban yang berat, karena dalam melaksanakan profesinya tidak jarang menghadapi intrik, godaan yang muncul dari dirinya sendiri untuk mendapatkan pamrih atau motivasi hedonisme yang berlebihan, maupun tekanan dari luar, baik berupa intimidasi, rayuan dan sebagainya.
3. Memiliki idealisme yang kuat.
Bertens11 menyatakan, kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesitu di mata masyarakat. Kode etik profesi merupakan produk etika terapan karena dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis atas suatu profesi. Kode etik profesi adalah rumusan norma moral manusia yang mengemban profesi dan menjadi tolak ukur perbuatan anggota kelompok profesi. Kode etik profesi merupakan upaya pencegahan berbuat yang tidak etis bagi anggota.
Setiap kode etik profesi selalu dibuat tertulis yang tersusun secara eratur, rapi, lengkap, dalam bahasa yang baik tetapi singkat sehingga menarik perhatian dan menyenangkan pembacanya. Alasan dibuat tertulis megingat fungsinya sebagai sarana control sosal, pencegah campur tangan pihak lain, dan penceah kesalahpahaman dan konflik. Namun kode etik profesi mempunyai kelemahan, yaitu terlalu idealis yang tidak sejalan dengan fakta yang terjadi disekitar professional, sehingga menimbulkan kecenderungan untuk diabaikan.12
Sanksi terhadap sumpah dan janjinya adalah bersifat psikis dan merupakan sanksi primair yang diderita oleh hakim yang melanggar etika profesinya, sedangkan sanksi yang diberkan oleh asosiasi profesinya baik berupa tegoran, peringatan sampai pada pemecatan sebagai anggota profesi (pemecatan sebagai hakim) adalah bersifat sekunder. Sanksi yang diberikan asosiasi tersebut pelaksanannya dapat dipaksakan, karena bagi hakim yang telah melanggar kode etik tersebut dapat dinyatakan oleh asosiasi profesinya telah ingkar janji terhadap apa yang telah dijanjikannya kepada asosiasi profesinya. Sedangkan janji tersebut bersifat mengikat berlaku sebagai undang-undang, karenanya bagi pelanggarnya berlaku norma hukum bukan hanya norma moral saja, sehingga terhadap pelanggarnya dapat dipaksakan untuk memenuhi janjinya (pacta sunt servanda). Salah satu syarat menjadi professional adalah ketakwaan kepada Allah SWT., yaitu melaksanakan perintah dan menjahi larangan-laragan-Nya. Ketakwaan ini adalah dasar moral hakim. Jika hakim mempertebal iman dan takwa, maka di dalam diri akan tertanam nilai moral yang menjadi rem jika ingin berbuat buruk.
D. Penutup
Kebebasan eksistensial menyatu dengan diri manusia, artinya include eksistensinya sebagai individu. Kebebasan itu termasuk kemanusiaan kita, pengingkaran terhadap kebebasan hakim dalam menjalankan tugasnya berarti menafikan eksistensi hakim sebagai manusia dan ketaatan hakim pada ketetuan perundang-undangan yang demikian itu adalah meniadakan eksistensisi dirinya sendiri. Atribut kebebasan hakim jangan digunakan semau gue karena sikap tersebut adalah bentuk arrogance of power dan pengalpaan eksistensi hakim disamping sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk Tuhan yang diberi amanah sebagai wakil Tuhan di bumi.
Hendaknya setiap ptusan hakim selalu merefleksikan integritas moral yang dilandasi oleh prinsip-prinsip keutamaan moral dan teologal, sehingga keadilan yang diperoleh bukan keadilan yang absurd namun keadilan sesuai dengan yang dirasakan masyarakat luas. Seorang hakim tidak boleh termotivasi sifat hedonisme berlebihan, namun termotivasi melaksanakan cita-cita luhur, yang pada hakekatnya berupa pelayanan pada para pencari keadilan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan etika profesinya.
DAFTAR PUSTAKA
Arbijoto. 2000. Kebebasan Hakim (refleksi Terhadap Manusia Sebagai Homo Relegiosus), Jakarta: Mahkamah Agung RI.
Bertens, K. 1994. Etika. Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama.
Camus, Albert. 1988. Krisis Kebebasan (Terjemahan Edhi Martono). Jakata: Yayasan Obor.
Harahap, M. Yahya. 1994. Beberapa Permasalahan Hukum Acara Pada Peradilan Agama. Jakarta: Al-Hikmah.
------------------------------. 2005. Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama. Jakarta: Sinar Grafika.
Ka’bah, Rifyal. 2004. Penegakan Syariat Islam di Indonesia. Jakarta: Khairul Bayan.
Manan, Bagir. 2007. Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian). Jakarta: Mahkamah Agung RI.
Muhammad, Abdul Kadir. 2001. Etika Profesi Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Poerwadarminta, W.J.S. 1984. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.