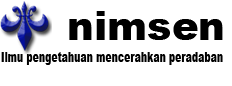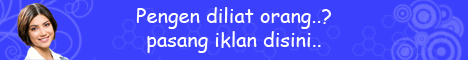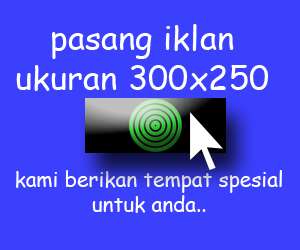1.1 Masa Sebelum Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945
Perbudakan merupakan hubungan kerja yang pernah terjadi dalam sejarah kehidupan bangsa Indonesia. Dalam perbudakan ada unsure pemberi kerja dan penerima/pelaksana kerja. Perbudakan adalah
suatu keadaan dimana seseorang yang disebut budak melakukan pekerjaan di bawah perintah pihak lain yaitu pemilik budak. Seorang budak tidak mempunyai hak apapun dalam hubungan kerja bahkan juga tidak memiliki hak atas kehidupannya. Kewajiban budak adalah melaksanakan segala perintah kerja yang diberikan pemilik budak. Para pemilik budak adalah satu-satunya pihak yang memiliki hak untuk mengatur dan memberi kerja serta hak lainnya atas budak yang dimilikinya.
suatu keadaan dimana seseorang yang disebut budak melakukan pekerjaan di bawah perintah pihak lain yaitu pemilik budak. Seorang budak tidak mempunyai hak apapun dalam hubungan kerja bahkan juga tidak memiliki hak atas kehidupannya. Kewajiban budak adalah melaksanakan segala perintah kerja yang diberikan pemilik budak. Para pemilik budak adalah satu-satunya pihak yang memiliki hak untuk mengatur dan memberi kerja serta hak lainnya atas budak yang dimilikinya.
Secara sosiologis budak adalah manusia, sama seperti pemiliknya namun secara yuridis budak tidak lebih dari barang milik pihak lain yang dapat diperjualbelikan dan dimiliki secara mutlak kehidupan social ekonominya bahkan hidup dan matinya. Pemberian-pemberian pemilik budak kepada budaknya seperti pemondokan, makanan, serta pemberian lainnya tidak dianggap sebagai kewajiban pemilik budak atau hak dari budak tetapi merupakan pemberian yang bersifat kebijaksanaan dan didasarkan atas keluhuran budi pemilik budak.
Pemerintah Hindia Belanda mulai mengatur masalah perbudakan pada tahun 1817 yaitu dengan melarang memasukkan budak ke pulau Jawa guna membatasi bertambahnya budak. Setelah tahun-tahun tersebut pemerintah Hindia Belanda berturut-turut mengeluarkan peraturan-peraturan guna meringankan beban para budak budak. Pada tahun 1825 dikeluarkan peraturan yang membatasi pemilik budak. Dalam. Peraturan tersebut diatur antara lain :
1. Budak yang telah kawin tidak boleh dipisahkan dari anak istrinya;
2. Melarang perdagangan budak dan mendatangkannya dari luar Hindia Belanda;
3. Mengatur hal-hal yang dapat membebaskan budak;
4. Mengatur kewajiban untuk memberi makan, pakaian, dan upah;
5. Mengancam dengan pidana penganiayaan terhadap budak dan ancaman pidana bagi budak yang meninggalkan pekerjaan atau menolak pekerjaan yang layak.
Pada tahun 1854 pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Regeringsreglement (RR) yang menetapkan penghapusan perbudakan. Pasal 115 RR tersebut menetapkan bahwa paling lambat pada tanggal 1 Januari 1860, perbudakan di seluruh Hindia Belanda dihapus.
Selain perbudakan, sejarah ketenagakerjaan di Indonesia diwarnai pula dengan lembaga perhambaan dan lembaga peruluran, serta kerja rodi dan punale sanksi. Perhambaan (pandelingschap) adalah peristiwa dimana seseorang meminjam sejumlah uang dengan cara menggadaikan dirinya sendiri atau orang lain yang berada di bawah kekuasaannya (biasanya anaknya) untuk melakukan pekerjaan di bawah perintah orang yang meminjamkan uang tersebut hingga hutangnya lunas. Pekerjaan yang dilakukan untuk kepentingan orang yang meminjamkan uang ini dapat dijadikan cara untuk melunasi hutang atau bisa juga hanya untuk sekedar membayar bunga hutang.
Peruluran terjadi pada zaman Gubernur Jendral Jan Pieterszoon Coen berkuasa. Pada masa itu Pemerintah Hindia Belanda membagi-bagi tanah-tanah kosong untuk dijadikan kebun (Perk) kepada orang-orang yang disebut perkenir atau ulur. Selama perkenir berada di kebun dan menggarapnya maka dia dianggap sebagai pemiliknya tetapi jika meninggalkan kebun maka haknya hilang. Para perkenir diharuskan menanam tanaman yang hasilnya harus dijual kepada kumpeni dimana harganya telah ditetapkan oleh kumpeni secara sepihak.
Selain peruluran pernah terjadi juga kerja rodi dalam sejarah ketenaga kerjaan di Indonesia. Kerja rodi adalah melakukan pekerjaan untuk kepentingan bersama dalam suatu satuan desa, suku atau kerajaan atau untuk keperluan raja. Pekerjaan yang awalnya merupakan kerja bersama untuk kepentingan bersama-sama (gotong royong) dalam perkembangannya berubah menjadi kerja paksa untuk kepentingan seseorang atau pihak lain dengan tanpa upah. Pemerintah Hindia Belanda memanfaatkan kerja rodi untuk kepentingan membuat pabrik, benteng, jalan, dan kepentingan pegawai pemerintahan. Heandrik Willian Deandels, Gubernur Jendral Hindia Belanda tahun 1807-1811, memanfaatkan kerja rodi untuk membuat jalan dari Anyer, Provinsi Banten, hingga Panarukan di Jawa Timur dengan menelan korban nyata yang tak terbulang. Kerja rodi disebut juga dengan kerja paksa dan pemondokan sebagaimana dalam perbudakan.
Punale sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada pekerja karena meninggalkan atau menolak melakukan pekerjaan tanpa alasan yang dapat diterima dengan pidana denda antara Rp 16,00 (enam belas rupiah) hingga Rp.25,00 (dua puluh lima rupiah) atau dengan kerja paksa selama 7 (tujuh) hari hingga 12 (dua belas) hari. Punale sanksi timbul sebagai akibat diadakannya Agrarisce Wet (Undang-undang Agraria) tahun 1870 yang mendorong munculnya perkebunan-perkebunan swasta besar sehingga membutuhkan pekerja/buruh dalam jumlah banyak. Agar pekebunan memperoleh jaminan bahwa pekerjanya/buruhnya tetap melakukan pekerjaannya maka dileuarkan Algemene Politie Strafreglement (Stabl. 1872 Nomor 3) yang memuat punale sanksi.
Punele sanksi memberikan kedudukan yang tinggi pada para pengusaha dan mudah untuk disalah gunakan mengingat posisi pekerja/buruh yang lemah dan kurangnya pengawasan dalam bidang ketenagakerjaan. Dalam parlemen Belanda pun timbul kecaman terhadap punale sanksi sehingga pada tahun 1879 punale sanksi dicabut.
Pada tahun 1880 keluar peraturan serupa punale sanksi yang disebut Koeli Ordonnantie dan berlaku untuk wilayah Sumatera Timur. Pada tahun-tahun berikutnya peraturan-peraturan serupa juga diberlakukan untuk daerah-daerah lain. Keluarnya peraturan-peraturan tersebut membuat kondisi ketenagakerjaan semakin memprihatinkan karena timbul pemerasan tenaga kerja, penganiayaan pekerja/buruh, dan pengawasan yang selalu berpihak pada pengusaha. Instansi pengawasan di bidang ketenagakerjaan tidak dapat mencegah kondisi yang memprihatinkan tersebut mengingat kondisi ketidakadilan itu sendiri diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Melihat kondisi yang memprihatinkan tersebut maka dikeluarkan peraturan yang mencabutnya pada tahun 1941 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1942.
Pada zaman penjajahan Jepang kondisi ketenagakerjaan di Indonesia sangat memilukan. Banyak rakyat yang disuruh kerja paksa (romusho) untuk membangun jalan, jembatan, bandar udara, dan kepentingan pemerintah pendudukan lain dengan tanpa upah. Para pekerja/buruh diberi sanksi fisik yang keras bila lamban atau kurang baik dalam bekerja sementara makanan yang diberikan tidak memadai. Kondisi ini membuat banyak pekerja/buruh yang jatuh sakit bahkan meninggal duni dilokasi pekerjaan.
1.2 Masa Setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945
Sejak diproklamasikan kemerdekaan, pemerintah Republik Indonesia berusaha memperbaiki kondisi ketenagakerjaan agar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Hal ini sejalan dengan salah satu tujuan didirikannya negara Republik Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum dan ketentuan pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
Guna menghindari kekosongan hukum di bidang ketenagakerjaan, negara Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, masih menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada masa penjajahan. Ketentuan ini dicantumkan dalam pasal 1 aturan Peralihan UUD 1945 yang menyatakan segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini. Dengan ketentuan aturan peralihan ini, semua peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan yang berlaku pada saat pengesahan UUD 1945 tanggal 18 Agustus1945 masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dengan yang baru. Peraturan perundang-undangan yang masih tetap berlaku tersebut adalah buku III bab 7A KUH Perdata yang mengatur masalah ketenagakerjaan beserta peraturan-peraturan lain yang dikeluarkan pada zaman penjajahan Belanda.
Pada awal berdirinya negara Republik Indonesia, ketenagakerjaan belum merupakan masalah serius yang harus segera ditangani. Hal ini karena selain seluruh rakyat masih sibuk dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945, perusahaan-perusahaan penting saat itu masih dikuasai oleh negara sehingga masalah ketenagakerjaan terutama perselisihan antara pengusaha dan pekerja/buruh belum begitu terasa menonjol. Setelah adanya pengakuan kedaulatan oleh pemerintah Belanda lewat Konferensi Meja Bundar, perhatian rakyat terutama pekerja/buruh mulai beralih ke masalah sosial ekonomi. Hingga 1951, dalam bidang ketenagakerjaan baru diundangkan satu undang-undang yaitu Undang-undang Nomor 12 tahun 1948 yang bertitel Undang-undang Kerja. Mengingat saat itu negara Republik Indonesia yang sekarang masih berbentuk negara serikat, maka undang-undang tersebut hanya berlaku untuk negara Republik Indonesia. Baru pada tahun 1951 dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1951 Undang-undang Kerja tahun 1948 tersebut dinyatakan berlaku untuk seluruh Indonesia.
Undang-undang Kerja Nomor 12 Tahun 1948 memuat aturan-aturan dasar tentang pekerjaan yang boleh dilakukan anak, orang muda, dan wanita, aturan tentang waktu kerja, waktu istirahat, dan tempat kerja. Undang-undang ini hanya berlaku untuk pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja/buruh dan tidak berlaku untuk siswa/murid magang yang bersifat pendidikan, orang yang memborong pekerjaan di perusahaan dan narapidana yang dipekerjakan.
Sebelum tahun 1951 tersebut, perselisihan hubungan industrial yang terjadi diselesaikan oleh para pihak yang berselisih sendiri yaitu pekerja/buruh dan pengusaha, campur tangan dari pegawai Kementerian Perburuhan akan dilakukan bila dianggap perlu berdasarkan instruksi Menteri Tenaga Kerja (Menteri Perburuhan saat itu). Hal ini mengakibatkan banyak keresahan di kalangan pekerja/buruh karena pengusaha dengan kedudukan sosial ekonomi yang lebih tinggi selalu dapat memaksakan kehendaknya kepada pekerja/buruh. Akibatnya pada akhir tahun 1950 banyak terjadi pemogokan pekerja/buruh yang mengakibatkan terganggunya perekonomian dan keamanan nasional.
Guna mengatasi keadaan ketenagakerjaan yang tidak kondusif tersebut, pemerintah pada tanggal 13 Februari 1951 mengeluarkan Peraturan Kekuasaan Militer Nomor 1 Tahun 1951 yang membentuk Panitia Penyelesaian Pertikaian Perburuhan ditingkat pusat dan daerah. Walaupun keadaanya menjadi sedikit lebih baik ternyata peraturan kekuasaan militer tersebut belum begitu mampu mengatasi kesulitan-kesulitan yang timbul di bidang ketenagakerjaan. Oleh karena itu pada bulan September 1951 pemerintah mengeluarkan Undang-undang Darurat Nomor 16 Tahun 1651 guna mengganti Peraturan Kekuasaan Militer Nomor 1 Tahun 1951. undang-undang Darurat tersebut memberikan aturan-aturan baru tentang penyelesaian perselisihan perburuhan dan memberikan tugas kepada penyelesaian perselisihan perburuhan dan memberikan tugas kepada pemerintah untuk membentuk Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan di tingkat pusat (P4P) dan di tingkat daerah (P4D).
Undang-undang Darurat Nomor 16 Tahun 1951 tidak bersifat definitif melainkan hanya bersifat peralihan belaka guna mengatasi keadaan ketenagakerjaan saat itu. Dalam perjalanannya pun banyak keberatan yang dilakukan baik oleh pengusaha maupun pekerja/buruh. Berdasarkan hal tersebut pemerintah pada tanggal 8 April 1957, mengesahkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan yang menetapkan P4P dan P4D tersebut sebagai organ yang berwenang menyelesaikan perselisihan perburuhan.
Kondisi ketenagakerjaan saat itu yang mendasari terbentuknya P4D dan P4P banyak diwarnai perselisihan-perselisihan antara pengusaha dan pekerja/buruh. Apalagi pada saat tersebut banyak partai politik yang menggunakan isu-isu perburuhan untuk mencapai tujuan politiknya. Mengingat asas yang dianut saat itu adalah demokrasi liberal maka para pihak yang berseteru saling memaksakan kehendaknya masing-masing lewat kekuatan yang dimiliki. Pekerja/buruh selalu menggunakan kekuatan mogok kerja untuk memaksakan kehendaknya sementara pengusaha selalu menggunakan keunggulan sosial ekonomi dalam menekan pekerja/buruh.
Guna mengatasi keadaan ini pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya adalah Undang-undang Nomor 21 Tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan antara Serikat Buruh dan Majikan (sekarang disebut Perjanjian Kerja Bersama) yang memberikan kedudukan yang seimbang antara pekerja/buruh dengan pengusaha dalam menyusun syarat-syarat kerja di perusahaan. Selain itu juga diundangkan Undang-undang Nomor 7 Pnps Tahun 1963 tentang Pencegahan Pemogokan dan Penutupan (Lock-Out) di Perusahaan, Jawatan dan Badan yang vital, serta Undang-undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta yang melarang pengusaha memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh tanpa izin dari P4D atau P4P.
Pada masa setelah tahun-tahun tersebut kondisi ketenagakerjaan mulai membaik dan jarang ditemui konflik ketenagakerjaan yang berarti. Hal ini juga disebabkan karena bangsa Indonesia saat itu lebih memusatkan perhatiannya pada masalah-masalah politik kenegaraan dimana terjadi pergantian pemerintahan dari pemerintah orde lama ke pemerintah orde baru.
Sejalan dengan perkembangan kehidupan sosial ekonomi masyarakat, pemerintah orde baru mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan guna mengganti ketentuan lama yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan untuk memperbaiki kondisi ketenagakerjaan di tanah air dalam rangka memberikan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan kepada warga negara.
Pada tahun 1969 pemerintah orde baru mengeluarkan Undang-undang Nomor 14 tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Ketenagakerjaan. Undang-undang ini mengatur tentang pokok-pokok yang dijadikan kebijakan dalam mengatur ketenagakerjaan di tanah air. Berdasarkan undang-undang ini dikeluarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja guna mencegah dan meminimalkan kecelakaan kerja yang selalu menimbulkan kerugian pada pihak pekerja/ buruh dan mewajibkan pengusaha untuk melakukan hal-hal yang dapat mencegah terjadinya kecelakaan kerja termasuk memberikan alat-alat keselamatan kerja secara cuma-cuma kepada pekerja/buruh.
Guna lebih memberikan perlindungan kepada tenaga kerja, pada tahun 1977 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977 tentang Asuransi Tenaga Kerja (Astek). Peraturan Pemerintah ini mewajibkan perusahaan untuk mengikutkan pekerjanya/buruhnya pada program asuransi sosial tenaga kerja yang meliputi :
1. Program asuransi kecelakaan kerja.
2. Program tabungan hari tua yang dikaitkan dengan asuransi kematian.
Dalam perkembangan lebih lanjut program asuransi tenaga kerja (Astek) diperbaiki dengan suatu program jaminan sosial yang lebih baik dan diatur dalam suatu undang-undang yaitu Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek). Undang-undang ini mewajibkan pengusaha untuk memberikan perlindungan kepada pekerja/buruh dan keluarganya dalam suatu jaminan sosial yang disebut jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) yang meliputi :
1. Jaminan kecelakaan kerja.
2. Jaminan kematian
3. Jaminan hari tua, dan
4. Jaminan pemeliharaan kesehatan
Program jaminan sosial tersebut diselenggarakan oleh PT. Jamsostek (Persero), sebuah BUMN yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1990.
Pada tahun 1981 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah yang mengatur sistem pengupahan dan hal-hal yang dapat dipotongkan dengan upah. Peraturan Pemerintah ini menegaskan bahwa upah pekerja/buruh merupakan suatu hal yang harus didahulukan sehingga menjamin pekerja/buruh dalam hal penghasilan.
Pada perkembangan lain, pemerintah mengundangkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sebagaimana diketahui sistem peradilan di Indonesia mengenal 4 macam peradilan yaitu Pengadilan Agama, Pengadilan Umum, Pengadilan Militer, dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Putusan P4D dan P4P bukan merupakan suatu putusan lembaga pengadilan sehingga oleh karenanya merupakan putusan yang bersifat administratif. Berhubung merupakan putusan administratif maka putusan tersebut merupakan objek yang dapat digugat pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha dan dimohon kasasi ke Mahkamah Agung Mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial (dahulu perselisihan perburuhan) dengan demikian menjadi tidak efektif dan memerlukan waktu yang lama yaitu mulai dari sejak penyelesaian secara bipartit, anjuran tertulis, P4D, P4P, PT TUN, dan MA. Mengingat masalah ketenagakerjaan merupakan masalah yang harus diselesaikan secara cepat, maka dengan adanya peradilan tata usaha negara perlu dilakukan reformasi di bidang hukum ketenagakerjaan dengan membuat suatu mekanisme penyelsaian perselisihan hubungan industrial baru yang lebih cepat dan dapat diterima baik oleh pengusaha, pekerja/buruh, maupun serikat pekerja/serikat buruh.
Dalam rangka reformasi di bidang ketenagakerjaan tersebut, pemerintah bersama DPR telah mengundangkan beberapa undang-undang yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Undang-undang tersebut adalah Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI). Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 memberikan kebebasan kepada pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, serta menjadi anggota atau tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh guna memperjuangkan kepentingan-kepentingannya.
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan Undang-undang ketenagakerjaan yang bersifat komprehensif dan menyeluruh, mengatur berbagai hal di bidang ketenagakerjaan yang sebelumnya tidak pernah diatur dalam satu undang-undang. Beberapa ketentuan ketenagakerjaan yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sebelumnya dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman termasuk yang merupakan produk kolonial, dicabut dan diganti oleh undang-undang ini. Selain mencabut ketentuan lama, undang-undang ini juga dimaksudkan untuk menampung perubahan yang sangat mendasar di segala aspek kehidupan bangsa Indonesia
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 juga mencabut berlakunya undang-undang serupa sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 dinyatakan berlaku efektif 1 (satu) tahun sejak diundangkan tetapi dalam prakteknya undang-undang ini tidak pernah berlaku di Indonesia. Hal ini karena setelah bergulirnya reformasi, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 banyak diprotes karena dianggap banyak merugikan pekerja/buruh. Akhirnya dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang dikuatkan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1998 jo. Undang-undang Nomor 28 2000, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 ditunda masa berlakunya hingga akhirnya dicabut dan diganti dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) memberikan mekanisme baru dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan mencabut dan mengganti mekanisme penyelesaian lewat P4D dan P4P yang dianggap sudah tidak efektif lagi. Undang-undang tersebut memberikan kebebasan kepada para pihak yang berselisih untuk menyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Penyelesaian lewat pengadilan dilakukan melalui Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung, sedang penyelesaian di luar pengadilan dapat dilakukan lewat mediasi, konsiliasi, dan arbitrasi.
Tugas : Setelah memperoleh materi mahasiswa dapat menjelaskan :
1. Jelaskan sejarah hokum ketenagakerjaan sebelum Proklamasi kemerdekaan ?
2. Jelaskan sejarah ketenagakerjaan setelah Proklamasi kemerdekaan ?
PERTEMUAN KE II
PARA PIHAK DALAM HUKUM KETENAGAKERJAAN
TIK : Pada akhir perkuliahan mahasiswa diharapkan mampu
1. menjelaskan pihak-pihak yang ada dalam hukum ketenagakerjaan
2. menjelaskan pengertian buruh/pekerja
3. menjelaskan pengertian pengusaha
Pokok Bahasan : Para pihak dalam hukum ketenagakerjaan
Deskripsi Singkat : Dalam perkuliahan ini mahasiswa akan mempelajari pihak-pihak yang terkait dalam hukum ketenagakerjaan, baik itu pihak buruh/pekerja maupun pihak pengusaha.
Pihak dalam hukum ketenagakerjaan sangat luas, yaitu tidak hanya pengusaha dan pekerja/buruh saja tetapi juga pihak-pihak lain yang terkait. Luasnya para pihak ini karena masing-masing pihak yang terkait dalam hubungan industrial saling berinteraksi sesuai dengan posisinya dalam menghasilkan barang dan/atau jasa. Para pihak dalam hukum ketenagakerjaan tersebut adalah pekerja/buruh dan pengusahaan tentang masing-masing pihak tersebut dijelaskan dalam pembahasan sebagai berikut :
2.1 Pekerja/Buruh
Pekerja/buruh dewasa (biasa disebut pekerja/buruh) adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dalam definisi tersebut terdapat dua unsur yaitu unsur orang yang bekerja dan unsur menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Hal ini berbeda dengan definisi tenaga kerja yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.
Pengertian tenaga mencakup pekerja/buruh, pengawai negeri, tentara, orang yang sedang mencari pekerjaan, orang-orang yang berprofesi bebas seperti pengacara, dokter, pedagang, penjahit, dan lain-lain. Masing-masing profesi tersebut berbeda satu dengan yang lain walaupun semuanya termasuk dalam kategori tenaga kerja. Hal ini karena hubungan hukum dan peraturan yang mengaturnya juga berlainan. Bagi pekerja/buruh hubungan hukum dengan pemberi kerja bersifat keperdataan yaitu dibuat diantara para pihak yang mempunyai kedudukan perdata. Hubungan hukum antara kedua pihak selain diatur dalam perjanjian kerja yang mereka tanda tangani (hukum otonom) juga diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh instansi/lembaga yang berwenang untuk itu (hukum heteronom). Bagi pegawai negeri sipil dan tentara, hubungan hukum dan antara mereka dengan pemerintah didasarkan pada hukum publik yang bersifat heteronom.
Pekerja/buruh merupakan bagian dari tenaga kerja yaitu tenaga kerja yang belerja di dalam hubungan kerja, di bawah perintah pemberi kerja (bisa perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya) dan atas jasanya dalam bekerja yang bersangkutan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dengan kata lain tenaga kerja disebut sebagai pekerja/buruh bila ia melakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja dan di bawah perintah orang lain dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain tetapi tidak berada di dalam hubungan kerja seperti misalnya tukang semir sepatu atau tukang potong rambut, bukan merupakan pekerja/buruh.
Istilah pekerja dan buruh secara yuridis sebenarnya adalah sama dan tidak ada perbedaan diantara keduanya. Kedua kata tersebut dipergunakan dan digabungkan menjadi “pekerja/buruh” dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan untuk menyesuaikan dengan istilah “serikat pekerja/serikat buruh” yang terdapat dalam UU. No. 21 Tahun 2000 yang telah diundangkan sebelumnya. Pada zaman Hindia Belanda istilah buruh hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang melakukan pekerjaan tangan atau pekerjaan kasar seperti kuli, tukang, mandor, dan lain-lain yang di dunia barat dikenal dengan istilah blue collar. Orang yang melakukan pekerjaan halus terutama yang mempunyai pangkat Belanda dinamakan pegawai dan diberi kedudukan sebagai priyayi yang di dunia barat dikenal dengan istilah white collar.
Perbedaan kedua istilah ini bisa kita lihat dalam KUH Perdata buku III afdeling 4 yang hanya mengatur soal pelayan dan tukang (dienstbod en enwerkleiden). Baru pada tanggal 1 Januari 1927 istilah pekerja/buruh halus dan kasar tidak dibedakan dalam buku III bab 7A KUH Perdata diberlakukan bilamana bekarja pada pengusaha atau majikan Eropa dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh pekerja/buruh Eropa, sedang apabila bekerja sebagai pelayan dan pekerja yang berlaku adalah bab 7 bagian 5 buku III KUH Perdata.
Pembedaan perlakuan peraturan tersebut menunjukkan bahwa KUH Perdata bersifat diskriminatif terhadap pekerja/buruh Indonesia. Guna menghilangkan diskriminasi tersebut maka setelah kemerdekaan, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 1963 yang menegaskan penggunaan bab 7A buku III KUH Perdata sebagai pedoman dalam hubungan kerja antara pengusaha/majikan dengan pekerja/buruh bagi seluruh warga negara Indonesia.
Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak membedakan antara pekerja/buruh halus (white collar) dengan pekerja/buruh kasar (blue collar). Pembedaan pekerja/buruh dalam Undang-Undang ini hanya didasarkan pada jenid kelamin (pekerja/buruh perempuan dan laki-laki) dan usia (pekerja/buruh anak). Pembedaan ini dilakukan bukan dalam rangka diskriminatif tetapi untuk melindungi pekerja/buruh yang lemah daya tahan tubuhnya dan untuk menjaga norma-norma kesusilaan.
2.1.1 Pekerja/Buruh Perempuan
Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003 memberikan beberapa keringanan kepada pekerja/buruh perempuan. Keringan ini diberikan untuk melindungi pekerja/buruh perempuan karena secara kodrati perempuan mempunyai tugas dan fungsi lain yang lebih penting dalam mesyarakat yaitu reproduksi. Kondisi dan daya tahan tubuh perempuan pun secara medis juga lebih lemah dari laki-laki sehingga wajar jika pekerja/buruh perempuan memperoleh fasilitas kemudahan yang antara lain :
a. pekerja/buruh perempuan yang berusia kurang dari 18 (delapan belas) tahun dilarang diperkerjakan antara pukul 23.00 hingga pukul 07.00;
b. pekerja/buruh perempuan yang hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan diri dan kandungannya jika bekerja malam hari, dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 hingga pukul 07.00;
c. pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 hingga 07.00 wajib :
1) memberikan makanan dan minuman bergizi yang bervariasi, diberikan pada waktu istirahat antara jam kerja serta tidak dapat digantikan dengan uang. Penyajian makanan dan minuman, peralatan dan ruangan makan harus layak serta memenuhi syarat higienis dan sanitasi;
2) menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja dengan cara menyediakan petugas keamanan di tempat kerja dan menyediakan kamar mandi/wc yang layak dengan penerangan memadai serta terpisah antara pekerja/buruh perempuan dan laki-laki;
d. pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh perempuan yang berangkat dan pulang kerja antara pukul 23.00 hingga pukul 05.00. Penjemputan dilakukan di tempat penjemputan ke tempat kerja dan sebaliknya dengan lokasi penjemputan dan pengantaran yang mudah dijankau dan aman bagi pekerja/buruh perempuan. Kendaran antar jemput harus dalam kondisi layak dan terdaftar di perusahaan.
Pelanggaran terhadap ketentuan ini merupakan tindak pidana pelanggaran yang diancam pisana kurungan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan penjara dan paling lama 12 (dua belas) bulan penjara dan/atau denda paling sedikit Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2.1.2 Pekerja/Buruh Anak
Anak dalam hukum ketenagakerjaan adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 tahun. Pada prinsipnya pengusaha dilarang memperkerjakan anak. Hal ini disebutkan dalam pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Larangan mempekerjakan anak dimaksudkan untuk melindungi anak agar tidak terganggu pertumbuhan dan kesehatannya. Daya tahan tubuh anak sangat rentan terhadap lingkungan kerja, apalagi bila sering berhubungan dengan bahan-bahan kimia. Penelitian pada industri sepatu di Jawa Barat menunjukkan bahwa orang-orang yang bekarja sejak anak-anak sebagian besar meninggal dunia sebelum berusia 50 (lima
Larangan mempekerjakan anak ini dapat disimpangi bila anak yang bekerja tersebut berusia antara 13 (tiga belas) tahun hingga 15 (lima
a. ada izin tertulis dari orang tua/wali;
b. ada perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
c. waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam per hari;
d. dilakukan siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
e. kesehatan dan keselamatan kerjanya diutamakan;
f. adanya hubungan kerja yang jelas; dan
g. menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pelanggaran terhadap ketentuan ini merupakan tindak pidana kejahatan yang dapat dipidana penjara sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Ketentuan tentang pekrja/buruh anak tersebut tidak berlaku pada anak yang bekerja pada usaha keluarga.
Pekerja/buruh anak dilarang dipekerjakan dan dilibatkan dalam pekerjaan-pekerjaan terburuk yang meliputi :
a. segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan dan sejenisnya;
b. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak dalam pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;
c. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan atau
d. semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.
Menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. No. KEP.235/MRN/2003, jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, dan moral anak adalah sebagai berikut :
Pekerjaan yang membahayakan kesehatan dan keselamatan anak :
a. Pekerjaan yang berhubungan dengan mesin, pesawat, instalasi, dan peralatan lainnya yang meliputi : pekerjaan pembuatan, perakitan/pemasangan, pengoperasian, perawatan, dan perbaikan;
1) Mesin-mesin
i. mesin perkakas seperti mesin bor, mesin gerinda, mesin potong, mesin bubut, mesin skrap;
ii. mesin produksi seperti : mesin rajut, mesin jahit, mesin tenun, mesin pak, mesin pengisi botol
2) Pesawat
i. pesawat uap, seperti : ketel uap, bejana uap;
ii. pesawat cairan panas, seperti : pemanas air, pemanas oli;
iii. pesawat pendingin, pesawat pembangkit gas karbit;
iv. pesawat angkat dan angkut, seperti : keran angkat, pita transpor, ekskalator, gondola, forklift, loader;
v. pesawat tenaga, seperti : mesin diesel, turbin, motor bakar gas, peswasat pembangkit listrik.
3) Alat berat, seperti : traktor, pemecah batu, grader, pencampur aspal, mesin pancang.
4) Instalasi, seperti : instalasi pipa bertekanan, instalasi listrik, instalasi pemadam kebakaran, saluran listrik.
5) Peralatan lainnya, seperti : tanur, dapur peleburan, lift, perancah.
6) Bejana tekan, botol baja, bejana penimbun, bejana pengangkut, dan sejenisnya.
b. Pekerjaan yang dilakukan pada lingkungan kerja yang berbahaya yang meliputi :
1) Pekerjaan yang mengandung bahaya fisik
i. pekerjaan di bawah tanah, di bawah air atau dalam ruangan tertutup yang sempit dengan ventilasi yang terbatas (confined space) misalnya sumur tanki;
ii. pekerjaan yang dilakukan pada tempat ketinggian lebih dari 2 (dua) meter;
iii. pekerjaan dengan menggunakan atau dalam lingkungan yang terdapat listrik bertegangan di atas 50 volt;
iv. pekerjaan dengan menggunakan peralatan las listrik dan/atau gas;
v. pekerjaan dalam lingkungan kerja dengan suhu dan kelembapan ekstrim atau kecepatan angin yang tinggi;
vi. pekerjaan dalam lingkungan kerja dengn tingkat kebisingan atau getaran yang melebihi nilai ambang batas (NAB);
vii. pekerjaan menangani, menyimpan, mengangkut, dan menggunakan bahan radioaktif;
viii. pekerjaan yang menghasilkan atau dalam atau dalam lingkungan kerja yang terdapat bahaya radiasi magion;
ix. pekerjaan yang dilakukan dalam lingkungan kerja yang berdebu;
x. pekerjaan yang dilakukan dan dapat menimbulkan bahaya listrik, kebakaran dan/atau peledakan.
2) Pekerjaan yang mengandung bahaya kimia
i. pekerjaan yang dilakukan dalam lingkungan kerja yang terdapat pajangan (exposure) bahan kimia berbahaya;
ii. pekerjaan dalam menangani, menyimpan, mengangkut, dan menggunakan bahan-bahan kimia yang bersifat toksik, eksplosif, mudah terbakar, mudah menyala, oksidator, korosif, iritatif, karsinogenik, mutagenik, dan/atau teratogenik;
iii. pekerjaan yang menggunakan asbes;
iv. pekerjaan yang menangani, menyimpan, menggunakan dan/atau mengangkut pestisida.
3) Pekerjaan yang mengandung bahaya biologis
i. pekerjaan yang terpajan dengan kuman, bakteri, virus, fungi, parasit dan sejenisnya misalnya pekerjaan dalam lingkungan laboratorium klinik, penyamakan kulit, pencucian getah/lkaret;
ii. pekerjaan di tempat pemotongan, pemrosesan, dan pengepakan daging hewan;
iii. pekerjaan yang dilakukan di perusahaan peternakan seperti memarah susu, memberi makan ternak, dan membersihkan kandang;
iv. pekerjaan di dalam silo atau gudang penyimpanan hasil-hasil pertanian;
v. pekerjaan penangkaran hewan buas.
c. Pekerjaan yang mengandung sifat dan keadaan berbahaya tertentu
1) pekerjaan konstruksi bangunan, jembatan, irigasi, atau jalan;
2) pekerjaan yang dilakukan dalam perusahaan pengolahan kayu seperti penebangn, pengangkutan, dan bongkar muat;
3) pekerjaan mengangkat dan mengangkut secara manual beban di atas 12 kg untuk anak laki-laki dan di atas 10 kg untuk anak perempuan;
4) pekerjaan dalam bangunan tempat kerja yang terkunci;
5) pekerjaan penangkapan ikan yang dilakukan di lepas pantai atau perairan laut dalam;
6) pekerjaan yang dilakukan di daerah terisolir atau terpencil;
7) pekerjaan di kapal;
8) pekerjaan yang dilakukan dalam pembuangan dan pengolahan sampah atau daur ulang barang-barang bekas;
9) pekerjaan yang dilakukan antara pukul 18.00 hingga 06.00
Sedang jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan moral anak adalah :
a. Pekerjaan pada usaha bar, diskotik, karaoke, bola sosdok, bioskop, panti pijat, atau lokasi yang dapat dijadikan tempat porstitusi.
b. Pekerjaan sebagai iklan untuk promosi minuman keras, obat perangsang seksualitas, dan/atau rokok.
Pelanggaran terhadap larangan-larangan ini merupakan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Anak dianggap bekerja apabila berada di tempat kerja kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Apabila anak dipekerjakan bersama-sama pekerja/buruh dewasa maka tempat kerja anak harus dipisahkan dengan tempat kerja pekerja/buruh dewasa. Anak diperkenankan melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan dan pelatihan bila :
a. paling sedikit 14 (empat belas) tahun;
b. diberi petunjuk yang jelas tentang cara melaksanakan pekerjaan, serta memperoleh bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan; dan
c. diberi alat perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.
Apabila anak melakukan pekerjaan dalam rangka untuk mengembangkan bakat dan minatnya maka pengusaha dapat mempekerjakannya sepanjang :
a. di bawah pengawasan langsung orang tua atau wali;
b. waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam per hari; dan
c. kondisi serta lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, dan waktu sekolah.
Kriteria pekerjaan dalam rangka mengembangkan bakat dan minat anak adalah pekerjaan yang :
a. biasa dikerjakan anak sejak dini;
b. diminati anak;
c. didasarkan kemampuan anak;
d. dapat menumbuhkan kreativitas dan sesuai dengan dunia anak.
Pengusaha yang memperkerjakan anak yang berumur kurang dari 15 (lima belas) tahun dalam rangka mengembangkan bakat dan minat wajib untuk :
a. membuat perjanjian kerja secara tertulis dengan orang tua/wali yang mewakili anak dan membuat kondisi serta syarat kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
b. mempekerjakan di luar waktu sekolah;
c. waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari dan 12 (dua belas) jam seminggu;
d. melibatkan orang tua/wali di lokasi tempat kerja untuk melakukan pengawasan langsung;
e. menyediakan tempat dan lingkungan kerja yang bebas dari peredaran dan pengguanaan narkotika, perjudian, minuman keras, prostitusi, dan hal-hal sejenis yang memberikan pengaruh buruk terhadap perkembangan fisik, mental, dan sosial anak;
f. menyediakan fasilitas tempat istirahat selama waktu tunggu. Waktu tunggu paling lama 1 (satu) jam dan apabila melebihi 1 (satu) jam maka dihitung sebagai waktu kerja;
g. melaksanakan syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja
Pelanggaran terhadap ketentuan ini merupakan tindak pidana pelanggaran yang diancam pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2.1.3 Pekerja/Buruh Tenaga Kerja Asing
Tenaga kerja asing (TKA) adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia Indonesia
Izin mempekerjakan tenaga kerja asing tersebut harus sesuai dengan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang telah disahkan oleh pejabat yang ditunjuk, yang permohonannya sekurang-kurangnya memuat :
a. alasan penggunaan tenaga kerja asing;
b. jabatan dan/atau kedudukan tenaga kerja asing dalam struktur organisasi perusahaan;
c. jangka waktu penggunaan tenaga kerja asing;
d. penggunaan tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai pendamping (counter part) tenaga kerja asing yang dipekerjakan. Tenaga kerja pendamping yang ditunjuk harus mempunyai latar belakang pendidikan yang sesuai dengan jabatan yang akan diduduki TKA. Tenaga kerja pendamping ini tidak secara otomatis menggantikan atau menduduki jabatan tenaga kerja asing yang didampinginya tetapi lebih dititik beratkan untuk alih teknologi dan alih keahlian agar tenaga pendamping memiliki kemampuan sehingga pada waktunya diharapkan dapat menggantikan tenaga kerja asing yant didampingi.
RPTKA tidak berlaku bagi instansi pemerintah, badan-badan internasional, dan perwakilan negara asing. Badan internasional yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah badan-badan internasional yang tidak mencari keuntungan seperti lembaga-lembaga yang bernaung di bawah PBB misalnya ILO, UNICEF, WHO, dan lain-lain.
2.2 Pengusaha
Pengusaha adalah :
a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
b. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
c. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar Indonesia.
Maksud dari definisi tersebut adalah :
· Orang perseorang adalah orang pribadi yang menjalankan atau mengawasi operasional perusahaan;
· Persekutuan adalah suatu bentuk usaha yang tidak berbadan hukum seperti CV, Firma, maatschap, dan lain-lain. Baik yang bertujuan untuk mencari keuntungan maupun tidak;
· Badan Hukum (recht persoon) adalah suatu badan yang oleh hukum dianggap sebagai orang, dapat mempunyai harta kekayaan secara terpisah, mempunyai hak dan kewajiban hukum dan berhubungan hukum dengan pihak lain. Contoh badan hukum adalah hukum perseroan terbatan (PT), yayasan (stichting), koperasi, pemerintah daerah, negara, dan lain-lain.
Pada prinsipnya pengusaha adalah pihak yang menjalankan perusahaan, baik milik sendiri maupun bukan. Secara umum istilah pengusaha adalah orang yang melakukan suatu usaha (enterpreneur). Istilah yang dipergunakan dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya asalah majikan yaitu orang atau badan yang mempekerjakan buruh (lihat UU No. 21 Tahun 1954 jo. UU No. 22 Tahun 1957).
Sebagai pemberi kerja pengusaha adalah seorang majikan dalam hubungannya dengan pekerja/buruh. Pada sisi yang lain pengusaha yang menjalankan perusahaan bukan miliknya adalah seorang pekerja/buruh dalam hubungannya dengan pemilik perusahaan atau pemegang saham karena bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
Perlu pula dibedakan antara pengusaha dan perusahaan karena ada pengusaha yang sekaligus pemilik perusahaan dan ada yang tidak. Menurut UU No. 13 Tahun 2003 perusahaan adalah :
a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
b. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
Tugas : Setelah memperoleh materi mahasiswa dapat menjelaskan :
1. Jelaskan hubungan dan definisi dari para pihak dalam system hokum ketenagakerjaan ?
2. Jelaskan pengertian buruh/pekerja menurut ketentuan ketenagakerjaan ?
3. Jelaskaepada hak-hak yang harus diberikan oleh pengusaha kepada buruh perempuan berkaitan dengan posisi keperempuannya ?
4. Jelaskan konsepsi ketentuan ketenagakerjaan terhadap realitas pekerja anak ?
5. Jelaskan pekerjan-pekerjaan terburuk yang dilarang dilakukan oleh anak ?
6. Jelaskan pengertian dari pengusaha dan apa tanggung jawab pengusaha terhadap buruh ?
PERTEMUAN KE III
HUBUNGAN INDUSTRIAL
TIK : Pada akhir perkuliahan mahasiswa diharapkan mampu
1. menjelaskan dan memahami pengertian hubungan industrial
2. menjelaskan dan memahami keberadaan lembaga kerjasama Bipartit dan Tripartit
3. menjelaskan keberadaan peraturan perusahaan
4. menjelaskan pengertian dan bentuk-bentuk perjanjian bersama
Pokok Bahasan : Hubungan Industrial
Deskripsi Singkat : Dalam perkuliahan ini mahasiswa akan mempelajari pengertian.dari hubungan industrial, keberadaan dan fungsi dari lembaga Bipartit dan Tripartit, keberadaan dari peraturan perusahaan dan pengertian dan bentuk-bentuk dari perjanjian bersama.
Pengertian
Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pengusaha sebagai pimpinan perusahaan berkepentingan atas kelangsungan dan keberhasilan perusahaan dengan cara meraih keuntungan setinggi-tingginya sesuai modal yang telah ditanamkan dan menekan biaya produksi serendah-rendahnya (termasuk upah pekerja/buruh) agar barang dan/atau jasa yang dihasilkan bersaing dipasaran. Bagi pekerja/buruh perusahaan adalah sumber penghasilan dan sumber penghidupan sehingga akan selalu berusaha agar perusahaan memberikan kesejahteraan yang lebih baik dari yang telah diperoleh sebelumnya. Kedua kepentingan yang berbeda ini akan selalu mewarnai hubungan antara pengusaha dan pekerja/buruh dalam proses produksi barang dan/atau jasa.
Perbedaan kepentingan ini harus dicarikan harmonisasi antara keduanya karena baik pekerja/buruh maupun pengusaha mempunyai tujuan yang sama yaitu menghasilkan barang dan/atau jasa sehingga perusahaan dapat terus berjalan. Apabila karena satu dan lain hal perusahaan terpaksa ditutup, maka yang rugi bukan hanya pengusaha karena telah kehilangan modal, tetapi juga pekerja/buruh karena kehilangan pekerjaan sebagai sumber penghidupan.
Didorong adanya tujuan yang sama ini maka timbul hubungan yang saling tergantung antara pengusaha dengan pekerja/buruh dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang kita kenal dengan istilah hubungan industrial. Dalam melaksanakan hubungan industrial pengusaha dan organisasi pengusaha mempunyai fungsi menciptakan kemitraan, mengembangkan usaha, memperluas lapangan kerja, dan memberikan kesejahteraan kepada pekerja/buruh secara terbuka, demokratis, dan berkeadilan. Pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan keterampilan dan keahliannya, serta memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarga. Fungsi pemerintah dalam hubungan industrial adalah menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Peranan pemerintah dalam hal ini penting sekali mengingat perusahaan bagi pemerintah betapapun kecilnya merupakan bagian dari kekuatan ekonomi yang menghasilkan barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan sebagai salah satu sumber serta sarana dalam menjalankan program pembagian pendapatan nasional.
Hubungan industrial dapat dilakukan melalui sarana :
1. Serikat pekerja/serikat buruh
2. Organisasi pengusaha
3. Lembaga kerja sama bipartit
4. Lembaga kerja sama tripartit
5. Peraturan perusahaan
6. Perjanjian kerja bersama
7. Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan
8. Lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial
Pembahasan tentang serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi pengusaha telah diuraikan dalam pembahasan tentang para pihak dalam hukum ketenagakerjaan pada bab 2. Oleh karena itu dalam bab ini tidak dibahas lagi. Sarana hubungan industrial yang lain tersebut akan dibahas satu persatu dalam bab ini sebagai berikut :
3.2.Lembaga Kerja Sama Bipartit (LKS Bipartit)
Lembaga kerja sama bipartit (LKS Bipartit) adalah forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu perusahaan yang anggotanya terdiri dari unsur pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh yang sudah tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau dari unsur pekerja/buruh.
Pada setiap perusahaan yang mempekerjakan 50 (Lima puluh) orang pekerja/buruh atau lebih wajib membentuk LKS Bipartit. Persyaratan 50 (Lima puluh) orang ini dimaksudkan karena pada perusahaan dengan pekerja/ buruh kurang dari 50 (Lima puluh) orang komunikasi dan konsultasi dianggap bisa dilakukan secara individual dengan baik dan efisien. Sedang jika pekerja/buruh berjumlah 50 (Lima puluh) orang atau lebih komunikasi dan konsultasi secara individual sudah kurang efektif dilakukan sehingga perlu dilakukan dengan cara perwakilan.
Fungsi LKS Bipartit adalah sebagai forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal di bidang ketenagakerjaan yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu perusahaan. Segala hal yang mengangkut proses produksi dan perusahaan serta yang berhubungan dengan kepentingan pekerja/buruh dalam LKS Bipartit tersebut dapat dimusyawarahkan sehingga keresahan yang timbul dapat diselesaikan sedini mungkin dan tercipta ketenangan kerja dan ketenangan berusaha (industrial peace).
LKS Bipartit mengadakan pertemuan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan atau setiap kali bila dipandang perlu. Agenda pertemuan ditetapkan dan dibahas sesuai kebutuhan. Materi pertemuan dapat berasal unsur pengusaha, unsur pekerja/buruh, atau dari pengurus LKS Bipartit itu sendiri.
Menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. Nomor : KEP.225/MEN/2003, tugas LKS Bipartit antara lain :
1. Melakukan pertemuan secara periodik dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
2. Mengkomunikasikan kebijakan pengusaha dan aspirasi pekerja/buruh berkaitan dengan kesejahteraan pekerja/buruh dan kelangsungan usaha:
3. Melakukan deteksi dini dan menampung permasalahan hubungan industrial di perusahaan;
4. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pengusaha dalam penetapan kebijaksanaan perusahaan;
5. Menyampaikan saran dan pendapat pekerja/buruh dan atau serikat pekerja/serikat buruh.
Unsur keanggotaan bila dalam satu perusahaan hanyak terdapat 1 (satu) serikat pekerja/serikat buruh dimana semua pekerja/buruh menjadi anggota, maka secara otomatis pengurus serikat pekerja/serikat buruh menunjuk wakilnya dalam LKS Bipartit. Apabila dalam perusahaan tersebut belum terbentuk serikat pekerja/serikat buruh maka yang diwakili pekerja/buruh dalam LKS Bipartit adalah pekerja/buruh yang dipilih secara demokratis. Apabila dalam satu perusahaan terdapat lebih dari 1 (satu) serikat pekerja/serikat buruh dan seluruh pekerja/buruh dalam perusahaan tersebut menjadi anggota maka yang mewakili pekerja/buruh dalam LKS Bipartit adalah wakil dari masing-masing serikat pekerja/serikat buruh yang ditentukan secara proposional.
Penentuan anggota LKS Bipartit dari unsur pekerja/buruh apabila dalam perusahaan terdapat 1 (satu) serikat pekerja/serikat buruh dan ada pekerja/buruh yang tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh, dilakukan dengan cara serikat pekerja/serikat buruh tersebut menunjuk wakilnya dan pekerja/buruh yang tidak menjadi anggota serikat pekerja/ serikat buruh, maka masing-masing serikat pekerja/serikat buruh menunjuk wakilnya secara proposional dan pekerja/buruh yang tidak menjadi anggota menunjuk wakilnya secara demokratis.
Komposisi keanggotaan LKS Bipartit antara perusahaan dan pekerja/ buruh ditetapkan dengan perbandingan 1 : 1 dimana jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dengan ketentuan paling sedikit 6 (enam) orang dan paling banyak 20 (dua puluh) orang. Susunan pengurus LKS Bipartit sekurang-kurangnya terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, dan anggota. Jabatan ketua LKS Bipartit dapat dijabat secara bergantian antara wakil pengusaha dan wakil pekerja/buruh. Masa kerja keanggotaan LKS Bipartit selama 2 (dua) tahun. Pergantian keanggotaan sebelum berakhirnya masa jabatan dapat dilakukan atas usul dari unsur yang diwakilinya.
3.3.Lembaga Kerja Sama Tripartit (LKS Tripartit)
Lembaga kerja sama tripartit (LKS Tripartit) adalah forum komunikasi, konsultasi, dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggota-anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah. Tugas pokok LKS Tripartit adalah memberikan pertimbangan, saran, dan pendapat kepada pemerintah dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan.
Tugas pokok ini diantaranya adalah memberikan masukan-masukan dan pendapat-pendapat dalam pembuatan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan sehingga peraturan perundang-undang yang dikeluarkan tersebut dapat diterima oleh para pihak terkait di bidang ketenagakerjaan dan tidak menimbulkan keresahan baik pada pihak pengusaha maupun pekerja/buruh. Guna mencapai maksud tersebut LKS Tripartit :
1. Melakukan konsultasi dan komunikasi dengan pemerintah, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh untuk menyelesaikan masalah-masalah ketenagakerjaan.
2. Menampung dan mengolah usul-usul dan saran-saran dari pemerintah, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh.
3. Membina kerja sama yang sebaik-baiknya antara pengusaha, gabungan pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh agar tercipta iklim ketenagakerjaan yang kondusif.
4. Menyampaikan masukan-masukan kepada pemerintah dalam membuat keputusan agar bisa diterima semua pihak.
LKS Tripartit dibentuk pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Pada tingkatan tersebut dibentuk pula LKS Tripartit sektoral yaitu LKS Tripartit yang anggotanya berada dalam satu bidang usaha tertentu. LKS Tripartit Nasional dibentuk oleh Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Anggota LKS Tripartit Nasional diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Masa jabatan keanggotaannya selama 3 (tiga) tahun dan setelah itu dapat diangkat kembali untuk satu masa jabatan berikutnya selama 3 (tiga) tahun. Susunan keanggotaan LKS Tripartit Nasional terdiri dari :
1. Ketua merangkap anggota yang dijabat oleh Menteri yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan.
2. Wakil ketua merangkap anggota sebanyak 3 (tiga) orang dijabat oleh anggota yang mewakili unsur pemerintah dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh.
3. Sekretaris merangkap anggota yang dijabat oleh anggota yang mewakili unsur pemerintah dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan
4. Beberapa anggota sesuai kebutuhan
Jumlah seluruh anggota LKS Tripartit sebanyak-banyaknya 24 (dua puluh empat) orang yang penetapannya dilakukan dengan memperhatikan komposisi keterwakilan unsur pemerintah, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh dengan perbandingan 2 : 1 : 1. Komposisi perbandingan yang berbeda ini ditetapkan dengan dilandasi pemikiran bahwa pemerintahlah yang mempunyai tugas untuk membuat regulasi dan menegakkannya.
Pada tingkat provinsi terdapat LKS Tripartit Provinsi yang dibentuk dan bertanggung jawab pada Gubernur. Jumlah anggota LKS Tripartit Provinsi paling banyak 16 (enam belas) orang yang susunannya ditetapkan dengan memperhatikan komposisi perbandingan 2 : 1 : 1 antara unsur dari pemerintah, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh. Masa jabatan anggota LKS Tripartit Provinsi selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan 3 tahun berikutnya.
Pada tingkat kabupaten/kota terdapat LKS Kabupaten/Kota yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota. Anggota LKS Tripartit ini paling banyak 8 orang yang susunannya ditetapkan dengan memperhatikan komposisi perbandingan 2 : 1 : 1 antara unsur pemerintah, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh. Masa jabatan anggota LKS Tripartit Kabupaten/Kota selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan 3 tahun berikutnya.
3.4.Peraturan Perusahaan (PP)
Peraturan Perusahaan (PP) adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan. Peraturan Perusahaan disusun oleh pengusaha dan menjadi tanggung jawabnya. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang, apabila dalam perusahaan tersebut belum memiliki Perjanjian Kerja Bersama, wajib membuat Peraturan Perusahaan. Ketentuan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang pekerja/buruh ini disesuaikan dengan syarat minimum berdirinya serikat pekerja/serikat buruh dalam pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000. Pelanggaran terhadap kewajiban ini merupakan tindak pidana pelanggaran yang dapat dikenai sanksi pidana denda sekurang-kurangnya Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima
Pembuatan peraturan perusahaan walaupun dibuat secara sepihak oleh pengusaha dan pekerja/buruh tidak ikut serta dalam menentukan isinya, tetapi harus tetap dilakukan dengan memperhatikan saran dan pertimbangan dari wakil pekerja/buruh. Saran dan pertimbangan dari wakil pekerja/buruh hanya bersifat masukan sehingga pembuatan peraturan perusahaan tidak dapat diperselisihkan. Wakil pekerja/buruh dapat pula tidak memberikan saran dan pertimbangan pada rancangan peraturan perusahaan yang diajukan pengusaha.
Apabila dalam perusahaan bersangkutan telah terbentuk serikat pekerja/serikat buruh maka wakil pekerja/buruh adalah pengurus serikat pekerja/serikat buruh bersangkutan, tetapi jika belum terbentuk serikat pekerja/serikat buruh, maka wakil pekerja/buruh dipilih secara demokratis oleh pekerja/buruh dari setiap unit kerja yang ada di perusahaan agar dapat mewakili kepentingannya. Apabila dalam perusahaan telah terbentuk serikat pekerja/serikat buruh tetapi keanggotaannya tidak mewakili mayoritas pekerja/buruh di perusahaan tersebut, maka pembuatan peraturan perusahaan harus memperhatikan saran dan pertimbangan dari pengurus serikat pekerja/ serikat buruh dan dari wakil pekerja/buruh yang tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.
Saran dan pertimbangan tersebut harus sudah disampaikan kepada pengusaha dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak rancangan peraturan perusahaan diterima oleh wakil pekerja/buruh. Apabila jangka waktu 14 (empat belas) hari telah terlewati dan wakil pekerja/buruh tidak memberikan saran dan pertimbangan, maka pengusaha dapat mengajukan pengesahan peraturan perusahaan disertai bukti bahwa pengusaha telah meminta saran dan pertimbangan dari wakil pekerja/buruh.
3.4.1. Materi/Isi Peraturan Perusahaan
Dalam satu perusahaan hanya dapat dibuat 1 (satu) peraturan perusahaan yang berlaku untuk semua pekerja/buruh di perusahaan tersebut. Apabila perusahaan tersebut mempunyai cabang, maka dapat dibuat peraturan perusahaan induk yang berlaku di semua cabang perusahaan dan peraturan perusahaan turunan yang berlaku di masing-masing cabang peraturan perusahaan induk memuat ketentuan-ketentuan yang berlaku secara umum di seluruh cabang perusahaan, sedang peraturan perusahaan turunan memuat pelaksanaan peraturan perusahaan induk yang disesuaikan dengan kondisi cabang perusahaan masing-masing. Apabila beberapa perusahaan bergabung dalam satu grup dan masing-masing perusahaan merupakan badan hukum sendiri, maka peraturan perusahaan harus dibuat untuk masing-masing perusahaan tersebut. Peraturan Perusahaan yang dibuat pengusaha sekurang-kurangnya memuat :
a. Hak dan kewajiban pengusaha
b. Hak dan kewajiban pekerja/buruh
c. Syarat kerja
d. Tata tertib perusahaan
e. Jangka waktu berlakunya peraturan perusahaan
Ketentuan yang diatur dalam peraturan perusahaan adalah syarat-syarat kerja yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan dan rincian ketentuan yang mengatur pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Apabila peraturan perusahaan mengatur kembali materi dari peraturan perundang-undangan, maka materi yang diatur tersebut secara kualitatif dan kuantitatif harus lebih baik dari ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila ternyata lebih rendah, maka ketentuan dalam peraturan perusahaan tersebut tidak berlaku dan yang diberlakukan adalah ketentuan yang diatur peraturan perundang-perundangan.
3.4.2. Prosedur Pengesahan dan Masa Berlaku Peraturan Perusahaan
Setelah peraturan perusahaan yang dibuat dengan memperhatikan saran dan pertimbangan wakil pekerja/buruh selesai dikerjakan, pengusaha harus mengajukan peraturan perusahaan dimaksud ke pejabat berwenang di bidang ketenagakerjaan untuk dimintakan pengesahan. Pejabat yang berwenang mengesahkan tersebut adalah :
a. Kepala instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota untuk perusahaan yang hanya terdapat dalam satu kabupaten/kota.
b. Kepala instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan provinsi untuk perusahaan yang terdapat dalam lebih 1 (satu) kabupaten/kota tetapi dalam 1 (satu) provinsi.
c. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial untuk perusahaan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) provinsi.
Pengesahan dimaksud dilakukan dengan suatu surat
Apabila peraturan perusahaan yang diajukan belum memenuhi syarat untuk disahkan, maka pejabat yang berwenang harus memberitahu secara tertulis kepada pengusaha tentang perbaikan yang harus dilakukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan. Perbaikan dimaksud adalah untuk mencegah agar ketentuan-ketentuan dalam peraturan perusahaan tersebut tidak bertentang dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak pemberitahuan perbaikan diterima, pengusaha wajib menyampaikan kembali peraturan perusahaan yang telah diperbaiki kepada pejabat yang berwenang untuk dimintakan pengesahan.
Peraturan Perusahaan berlaku setelah disahkan oleh pejabat yang berwenang. Masa berlaku peraturan perusahaan paling lama 2 (dua) tahun dan wajib diperbaharui setelah masa berlakunya habis (tidak boleh diperpanjang). Setelah pengesahan peraturan perusahaan diperoleh, pengusaha wajib memberitahukandan menjelaskan isi serta memberikan naskah peraturan perusahaan atau perubahannya kepada pekerja/buruh. Apabila selama masa berlakunya peraturan perusahaan, serikat pekerja/serikat buruh yang ada diperusahaan menghendaki perundingan untuk pembuatan perjanjian kerja bersama, maka pengusaha wajib untuk melayaninya. Dalam hal perundingan tersebut tidak mencapai kesepakatan, maka peraturan perusahaan tetap berlaku sampai jangka waktunya habis.
Peraturan perusahaan yang telah berakhir masa berlakunya masih tetap berlaku hingga disahkannya peraturan perusahaan yang baru atau ditandatanganinya perjanjian kerja bersama. Paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum jangka waktu berlakunya peraturan perusahaan berakhir, pengusaha harus mengajukan pembaharuan peraturan perusahaan kepada pejabat yang berwenang. Apabila dalam pembaharuan tersebut terdapat perubahan materi dari peraturan perubahan sebelumnya, maka perubahan tersebut harus didasarkan pada kesepakatan antara pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh dan/atau wakil pekerja/buruh jika diperusahaan tersebut belum ada serikat pekerja/serikat buruh.
Jika sebelum jangka waktu berlakunya peraturan perusahaan berakhir akan dilakukan perubahan, maka perubahan tersebut hanya dapat dilakukan atas dasar kesepakatan pengusaha dengan wakil pekerja/buruh. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendorong dan mempermudah pembuatan perjanjian kerja bersama karena dengan perjanjian kerja bersama perbaikan syarat-syarat kerja dapat dilakukan secara lebih berimbang antara kepentingan pengusaha dengan kepentingan pekerja/buruh. Peraturan Perusahaan dimaksud setelah dirubah dengan kesepakatan dari wakil pekerja/buruh harus dimintakan pengesahan dari pejabat yang berwenang.
3.5.Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
Perjanjian Kerja Bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, serta hak dan kewajiban kedua belah pihak. Istilah yang dipergunakan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 untuk perjanjian kerja bersama ini adalah kesepakatan kerja bersama, sedang Undang-undang Nomor 21 Tahun 1954 menggunakan istilah perjanjian perburuhan untuk menunjuk maksud yang sama.
Perjanjian Kerja Bersama merupakan hasil perundingan para pihak terkait yaitu serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha atau beberapa pengusaha yang mengatur syarat-syarat kerja, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian Kerja Bersama tidak hanya mengikat para pihak yang membuatnya yaitu serikat pekerja/serikat buruh dan pengusaha saja tetapi juga mengikat pihak ketiga yang tidak ikut dalam perundingan yaitu pekerja/buruh, terlepas dari apakah pekerja/buruh tersebut menerima atau menolak isi perjanjian kerja bersama dan apakah pekerja/buruh tersebut menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh yang berunding atau tidak.
Penggunaan istilah bersama dalam perjanjian kerja bersama ini menunjuk pada kekuatan berlakunya perjanjian yaitu mengikat pengusaha, atau beberapa pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh, dan pekerja/buruh itu sendiri. Penggunaan istilah tersebut bukan menunjuk bersama dalam arti seluruh pekerja/buruh ikut berunding dalam pembuatan perjanjian kerja bersama karena dalam proses pembuatan perjanjian kerja bersama pekerja/buruh bukan merupakan pihak dalam berunding.
Pembuatan perjanjian kerja bersama dilakukan secara musyawarah antara para pihak yang berunding. Apabila musyawarah tidak mencapai kesepakatan tentang suatu hal, maka penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Perjanjian Kerja Bersama harus dibuat dalam bentuk tertulis dengan huruf latin dan menggunakan bahasa Indonesia. Dalam hal perjanjian kerja bersama dibuat bukan dengan bahasa Indonesia, maka harus diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi yang telah disumpah dan hasil terjemahan tersebut dianggap sebagai perjanjian kerja bersama yang telah memenuhi syarat perundang-undangan.
Dalam satu perusahaan hanya boleh dibuat 1 (satu) perjanjian kerja bersama yang berlaku untuk pengusaha dan semua pekerja/buruh di perusahaan tersebut. Hal ini dimaksudkan agar dalam satu perusahaan tidak terdapat perbedaan syarat-syarat kerja antara pekerja/buruh satu dengan pekerja/buruh lainnya. Apabila perusahaan tersebut mempunyai cabang maka dapat dibuat perjanjian kerja bersama induk yang berlaku di semua cabang perusahaan.
3.5.1. Para Pihak dalam Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama
Perjanjian Kerja Bersama dibuat dengan cara musyawarah antara pengusaha atau beberapa pengusaha dengan serikat pekerja/ serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang telah tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenaga-kerjaan. Apabila dalam satu perusahaan hanya terdapat 1 (satu) serikat pekerja/serikat buruh, maka serikat pekerja/serikat buruh tersebut berhak mewakili pekerja/buruh dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dengan pengusaha jika memiliki anggota lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari seluruh pekerja/buruh yang ada di perusahaan bersangkutan. Keanggotaan serikat pekerja/serikat buruh tersebut harus dibuktikan dengan kartu anggota. Apabila anggota serikat pekerja/ serikat buruh tersebut kurang dari 50% (lima puluh perseratus) dari seluruh pekerja/buruh yang ada di perusahaan, maka serikat pekerja/ serikat buruh tersebutdapat mewakili pekerja/buruh dalam pembuatan perjanjian kerja bersama jika memperoleh dukungan lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari seluruh jumlah pekerja/buruh yang ada di perusahaan bersangkutan melalui pemungutan suara. Apabila dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum dilaksanakan pemungutan suara, ternyata serikat pekerja/serikat buruh dapat membuktikan bahwa keanggotaannya telah memenuhi lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari seluruh pekerja/buruh di perusahaan bersangkutan, maka pemungutan suara tidak perlu dilakukan. Apabila dukungan sebesar lebih dari 50% (lima puluh perseratus) tidak tercapai dalam pemungutan suara, maka perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama tidak dapat dilaksanakan.
Setelah melampaui waktu 6 (enam) bulan sejak pemungutan suara tersebut dilakukan, serikat pekerja/serikat buruh bersangkutan dapat mengajukan perjanjian kerja bersama dengan tetap disyaratkan memperoleh dukungan lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari seluruh pekerja/buruh yang dibuktikan dalam pemungutan suara ulangan. Pemungutan suara untuk memperoleh dukungan diselenggarakan oleh panitia yang terdiri dari wakil-wakil pekerja/ buruh dan pengurus serikat pekerja/serikat buruh yang disaksikan oleh pengusaha dan pejabat yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
Apabila di satu perusahaan terdapat lebih dari 1 (satu) serikat pekerja/serikat buruh, maka yang berhak mewakili pekerja/buruh dalam pembuatan perjanjian kerja bersama adalah serikat pekerja/ serikat buruh yang mempunyai anggota lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari seluruh pekerja/buruh yang ada di perusahaan bersangkutan. Apabila ketentuan keanggotaan minimal ini tidak ada yang memenuhi, maka serikat pekerja/serikat buruh yang ada di perusahaan tersebut dapat melakukan koalisasi sehingga tercapai jumlah lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari seluruh pekerja/ buruh yang ada. Apabila dengan kedua prosedur tersebut jumlah serikat pekerja/serikat buruh yang ada membentuk tim perundingan yang keanggotaannya ditentukan secara proposional berdasarkan jumlah anggota dari masing-masing serikat pekerja/serikat buruh.
3.5.2. Perundingan dan Pengesahan Perjanjian Kerja Bersama
Pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh menunjuk tim perunding pembuatan perjanjian kerja bersama sesuai kebutuhan dan paling banyak masing-masing terdiri atas 9 (sembilan) orang dengan kuasa penuh. Apabila terdapat serikat pekerja/serikat buruh yang tidak terwakili dalam tim perunding maka serikat pekerja/serikat buruh tersebut dapat menyampaikan aspirasinya secara tertulis kepada tim perunding sebelum dimulainya perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama. Perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama dimulai dengan menyepakati tata tertib perundingan yang sekurang-kurangnya memuat :
a. Tujuan pembuatan tata tertib;
b. Susunan tim perunding;
c. Lamanya masa perundingan;
d. Materi perundingan;
e. Tempat perundingan;
f. Tata cara perundingan;
g. Cara penyelesaian apabila terjadi kebuntuan perundingan;
h. Sahnya perundingan; dan
i. Biaya perundingan.
Apabila perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama tidak selesai dalam jangka waktu yang telah disepakati dalam tata tertib, maka para pihak dapat menjadwal kembali perundingan dengan waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah perundingan gagal. Apabila dengan penjadwalan kembali tersebut perundingan masih belum selesai, maka para pihak harus membuat pernyataan tertulis bahwa perundingan tidak dapat selesai dalam jangka waktu yang telah disepakati dengan memuat :
a. Materi perjanjian kerja bersama yang belum disepakati;
b. Pendirian para pihak;
c. Risalah perundingan; dan
d. Tempat, tanggal, dan tanda tangan para pihak.
Salah satu pihak atau kedua pihak melaporkan ke instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan perihal gagalnya perundingan tersebut untuk diselesaikan sesuai mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Instansi di bidang ketenagakerjaan dimaksud adalah :
a. Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota untuk perjanjian kerja bersama yang lingkup berlakunya hanya dalam satu kabupaten/kota;
b. Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan tingkat provinsi untuk perjanjian kerja bersama yang lingkup berlakunya lebih dari satu kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.
c. Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial pada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi apabila lingkup berlakunya perjanjian kerja bersama lebih dari 1 (satu) provinsi.
Apabila penyelesaian pada instansi tersebut dilakukan mediasi dan para pihak atau salah satu pihak tidak menerima anjuran mediator, maka atas kesepakatan para pihak, mediator melaporkan kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan untuk menetapkan langkah-langkah penyelesaian. Laporan kepada menteri tersebut memuat :
a. Materi perjanjian kerja bersama yang belum dicapai kesepakatan;
b. Pendirian para pihak;
c. Kesimpulan perundingan;
d. Pertimbangan dan saran penyelesaian.
Menteri setelah menerima laporan, menunjuk pejabat tertentu untuk menyelesaikan pembuatan perjanjian kerja bersama. Apabila penyelesaian melalui pejabat tertentu tersebut tidak mencapai kesepakatan, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial di wilayah hukum tempat pekerja/ buruh bekerja. Apabila daerah hukum tempat pekerja/buruh tinggal tersebut melebihi 1 (satu) wilayah hukum Pengadilan Hubungan Industrial, maka gugatan diajukan pada Pengadilan Hubungan Industrial yang daerah hukumnya meliputi tempat domisili perusahaan.
Setelah perundingan perjanjian kerja bersama mencapai kesepakatan, maka pengusaha mendaftarkan naskah perjanjian kerja yang dibuat dalam rangkap 3 (tiga), bermaterai cukup dan telah ditandatangani oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh ke :
a. Kepala instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota untuk perusahaan yang terdapat hanya dalam satu kabupaten/kota;
b. Kepala instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan tingkat provinsi untuk perusahaan yang terdapat pada lebih dari satu kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;
c. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial pada Departemen Tenaga Kerja dan Tansmigrasi untuk perusahaan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) provinsi.
Pejabat dimaksud meneliti kelengkapan formal dan materi naskah perjanjian kerja bersama yang didaftarkan dalam jangka watu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan. Apabila kelengkapan persyaratan formal terpenuhi dan materi perjanjian bersama tidak ada yang bertentangan dengan peraturan perundangan maka pejabat dimaksud harus sudah menerbitkan surat surat
3.5.3. Materi/Isi Perjanjian Kerja Bersama
Perjanjian Kerja Bersama yang dibuat oleh para pihak sekurang-kurangnya memuat :
a. Nama, tempat kedudukan, alamat serikat pekerja/serikat buruh, serta nomor dan tanggal pencatatan serikat pekerja/serikat buruh pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota;
b. Nama, tempat kedudukan, serta alamat perusahaan;
c. Hak dan kewajiban pengusaha;
d. Hak dan kewajiban serikat pekerja/serikat buruh serta pekerja/buruh;
e. Jangka waktu dan tanggal berlakunya perjanjian kerja bersama; dan
f. Tanda tangan para pihak pembuat perjanjian kerja bersama.
Apabila ketentuan dalam perjanjian kerja bersama ada yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ketentuan dalam perjanjian kerja bersama tersebut batal demi hukum dan yang diberlakukan adalah ketentuan-ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan.
Pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, dan pekerja/buruh wajib melaksanakan semua ketentuan yang ada dalam perjanjian kerja bersama. Pengusaha diwajibkan untuk mencetak dan membagikan naskah perjanjian kerja bersama kepada setiap pekerja/buruh atas biaya perusahaan. Pelanggaran atas kelalaian untuk mencetak dan membagi naskah perjanjian administratif. Pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh wajib memberitahukan isi perjanjian kerja bersama kepada seluruh pekerja/buruh yang ada diperusahaan bersangkutan.
3.5.4. Jangka Waktu Berlakunya Perjanjian Kerja Bersama
Perjanjian Kerja Bersama dibuat untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang masa berlakunya untuk paling lama 1 (satu) tahun berdasarkan kesepatan tertulis antara pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh. Perjanjian Kerja Bersama mulai berlaku pada tanggal penandatanganan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian kerja bersama tersebut. Setelah ditandatangani oleh para pihak yang membuatnya, perjanjian kerja bersama didaftarkan oleh pengusaha ke instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
Apabila selama masa berlakunya perjanjian kerjsa abersama kedua pihak sepakat untuk mengadakan perubahan, maka perubahan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian kerja bersama yang sedang berlaku. Jika masa berlaku perjanjian kerja bersama akan habis, maka perundingan kembali untuk membuat perjanjian kerja bersama berikutnya dapat dimulai paling cepat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerja bersama yang sedang berlaku. Apabila perundingan ini tidak mencapai kesepatan sampai batas waktu berlakunya perjanjian kerja bersama yang sedang berjalan habis, maka perjanjian kerja bersama yang sedang berlaku tetap berlaku untuk paling lama 1 (satu) tahun berikutnya.
Apabila setelah berakhirnya masa berlaku perjanjian kerja bersama akan dilakukan perpanjangan atau akan diperbaharui dan di perusahaan tersebut hanya ada 1 (satu) serikat pekerja/serikat buruh, maka perpanjangan atau pembaharuan tersebut tidak perlu mensyaratkan ketentuan keanggotaan atau dukungan lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari seluruh jumlah pekerja/buruh yang ada diperusahaan tersebut. Akan tetapi jika di perusahaan tersebut terdapat lebih dari 1 (satu) serikat pekerja/serikat buruh dan serikat pekerja/serikat buruh yang dulu berunding tidak lagi memenuhi kerja bersama dilakukan serikat pekerja/serikat buruh yang anggotanya lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari seluruh jumlah pekerja/buruh bersama-sama dengan serikat pekerja/serikat buruh yang membuat perjanjian kerja bersama terdahulu. Dalam hal tidak ada satupun serikat pekerja/serikat buruh yang memenuhi syarat keanggotaan minimal, maka dilakukan koalisi serikat pekerja/serikat buruh yang ada hingga mencapai syarat keanggotaan 50% (lima puluh perseratus) dari seluruh pekerja/buruh atau dibentuk tim perunding yang anggotanya ditentukan secara proposional berdasarkan jumlah anggota masing-masing serikat pekerja/serikat buruh bersangkutan.
Apabila karena satu dan lain hal terjadi pembubaran serikat pekerja/serikat buruh atau terjadi pengalihan kepemilikan perusahaan, maka perjanjian kerja bersama masih tetap berlaku sampai jangka waktunya habis. Bila terjadi penggabungan perusahaan (merger) dan masing-masing perusahaan yang bergabung mempunyai perjanjian kerja bersama maka perjanjian kerja bersama yang berlaku adalah perjanjian bersama yang lebih menguntungkan pekerja/buruh. Jika penggabungan perusahaan tersebut dilakukan antara perusahaan yang mempunyai perjanjian kerja bersama dengan perusahaan yang tidak mempunyai perjanjian kerja bersama, maka perjanjian kerja bersama masih tetap berlaku pada perusahaan hasil penggabungan sampai dengan jangka waktu perjanjian kerja bersama, berakhir.
Selama di suatu perusahaan masih ada serikat pekerja/serikat buruh, maka pengusaha dilarang mengganti perjanjian kerja bersama dengan peraturan perusahaan. Apabila serikat pekerja/serikat buruh tidak ada lagi di dalam perusahaan dan perjanjian kerja bersama diganti dengan peraturan perusahaan, maka ketentuan yang ada dalam peraturan perusahaan tidak boleh lebih rendah dari ketentuan yang ada dalam perjanjian kerja bersama yang digantikan.
Tugas : Setelah memperoleh materi mahasiswa dapat menjelaskan :
1. Jelaskan pengertian dari hubungan industrial ?
2. Jelaskan pengertian dan fungsi dari lembaga Bipartit ?
3. Jelaskan pengertian dan fungsi dari lembaga Tripartit
4. Jelaskan pengertian peraturan prerusahaan ?
5. Jelaskan prosedur pengesahan peraturan peusahaan ?
6. Jelaskan pengertian dan prosedur pengesahan dari perjanjian kerja bersama ?
PERTEMUAN KE IV
PERJANJIAN KERJA DAN UPAH
TIK : Pada akhir perkuliahan mahasiswa diharapkan mampu
1. menjelaskan pengertian perjanjian kerja dan macam-macam perjanjian kerja
2. menjelaskan pengertian upah beserta komponen upah dan cara penghitunagnnya
Pokok Bahasan : Perjanjian Kerja dan Upah
Deskripsi Singkat : Dalam perkuliahan ini mahasiswa akan mempelajari pengertian dari perjanjian kerja. Macam-macam perjanjian kerja, pengertian upah, komponen-komponen dari upah serta cara penhitungan upah.
Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Prof. Imam Soepomo, S.H. Berpendapat bahwa hubungan kerja yaitu hubungan antara buruh dan majikan, terjadi setelah diadakan perjanjian oleh buruh dengan majikan, dimana buruh menyatakan kesanggupannya untuk bekerja pada majikan dengan menerima upah, dan dimana majikan menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjana buruh dengan membayar upah.
Dari pengertian tersebut di atas jelaslah bahwa hubungan kerja terjadi setelah adanya perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja/buruh yang memuat unsur pekerjaan, upah, dan perintah yang akan dibahas satu persatu dalam bab ini.
Perjanjian Kerja
Pengertian Perjanjian Kerja
Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Perjanjian kerja tidak mesyaratkan bentuk tertentu, bisa dibuat secara tertulis yang ditandatangani kedua pihak atau dilakukan secara lisan. Dalam hal perjanjian kerja dibuat tertulis, maka harus dibuat sesuai peraturan perundangan yang berlaku, misalnya perjanjian yang mengatur perjanjian kerja waktu tertentu, antar kerja antar daerah, antar kerja antar negara, dan perjanjian kerja di laut. Biaya yang diperlukan dalam pembuatan perjanjian kerja menjadi tanggung jawab pengusaha.
Perjanjian kerja harus dibuat berdasarkan :
1. Kesepakatan kedua belah pihak;
2. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;
3. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan;
4. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundangan yang berlaku.
Keempat unsur perjanjian kerja tersebut merupakan syarat sahnya perjanjian secara umum sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. Unsur pertama dan kedua merupakan syarat subjektif dari sahnya suatu perjanjian kerja yati syarat yang berkaitan dengan subjek perjanjian. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi, maka dapat dimintakan pembatalan oleh pihak yang merasa dirugikan (vernietigbara).
Pekerja/buruh dan pengusaha dalam suatu perjanjian kerja harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri dalam perjanjian kerja. Kemauan yang bebas untuk membuat kesepakatan dianggap tidak ada apabila dalam pembuatan perjanjian kerja terdapat unsur paksaan, kekhilafan, dan penipuan.
Unsur kedua adalah kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum baik bagi pekerja/buruh maupun pengusaha. Pada dasarnya setiap orang adalah mampu dan cakap melakukan perbuatan hukum kecuali oleh undang-undang ditentukan lain. Bagi pekerja/buruh anak yang oleh undang-undang dinyatakan belum cakap melakukan perbuatan hukum, maka yang menandatangani perjanjian kerja adalah orang tua atau walinya.
Unsur ketiga dan keempat dalam perjanjian kerja, yaitu adanya pekerjaan yang diperjanjikan dimana pekerjaan tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan syarat objektif dari sahnya suatu perjanjian kerja yaitu syarat yang berkaitan dengan objek perjanjian. Apabila syarat objektif ini tidak dipenuhi, maka perjanjian kerja tersebut batal demi hukum yang artinya dari semula perjanjian kerja tersebut sudah batal dan oleh hukum dianggap tidak pernah ada (nietigbaar). Hakim Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial karena jabatannya berwenang mengucapkan pembatalan tersebut meskipun tidak diminta/dituntut oleh salah satu pihak.
Adanya pekerjaan yang diperjanjikan merupakan hal pokok/ esensial dari perjanjian kerja. Pasal 54 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan mensyaratkan bahwa jabatan atau jenis pekerjaan dan tempat pekerjaan harus dicantumkan dalam perjanjian kerja. Pekerjaan yang diperjanjikan tersebut harus dikerjakan sendiri oleh pekerja/buruh dan tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain tanpa seizin pengusaha. Pekerjaan yang dilakukan pekerja/buruh bersifat sangat pribadi karena menyangkut pengetahuan, keahlian, dan keterampilan kerja. Oleh sebab itu jika pekerja/buruh meninggal dunia maka perjanjian kerja putusa demi hukum.
Perjanjian kerja tidak boleh menjanjikan pekerjaan yang bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundangan yang legal dan tidak melanggar norma susila yang berlaku. Apabila pekerja/buruh melakukan pekerjaan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka selain perjanjian kerja tersebut batal juga tidak menutup kemungkinan pekerja/buruh dituntut secara pidana dengan dakwaan membantu (medeplichtige) suatu kejahatan misalnya pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan pembuat oli palsu, pembajakan kaset atau VCD, dan sebagainya.
Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis oleh kedua pihak sekurang-kurangnya memuat :
a. Nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha;
b. Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh;
c. Jabatan atau jenis pekerjaan;
d. Tempat pekerjaan;
e. Besarnya upah dan cara pembayaran;
f. Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh;
g. Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;
h. Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat;
i. Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja;
Ketentuan-ketentuan yang harus tercantum dalam perjanjian kerja tersebut terutama ketentuan tentang besarnya upah dan cara pembayaran serta syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban para pihak tidak boleh bertentangan (dalam arti lebih rendah secara kualitatif maupun kuantitatif) dengan peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Perjanjian kerja dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diberikan pada masing-masing pihak. Perjanjian kerja yang telah ditandatangani tidak boleh ditarik kembali dan/atau diubah kecuali atas persetujuan para pihak. Ketentuan ini sejalan dengan pasal 1338 KUH Perdata yang menetapkan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Hal ini berarti perjanjian kerja tersebut mengikat kedua belah pihak dan tidak dapat ditarik kembali atau diubah tanpa persetujuan kedua belah pihak kecuali oleh sebab tertentu yang diatur dengan undang-undang.
Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu (PKWT)
Sebagaimana ketentuan yang mengatur masalah ketenagakerjaan sebelumnya, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga mengatur hubungan kerja untuk waktu tertentu yaitu hubungan kerja yang didasarkan pada perjanjian kerja untuk waktu tertentu (PKWT). Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat didasarkan pada :
1. Jangka waktu tertentu
2. Selesainya suatu perkerjaan tertentu
Perjanjian kerja untuk waktu tertentu harus dibuat secara tertulis dalam huruf latin dengan menggunakan bahasa Indonesia
Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak dibuat dalam bentuk tertulis dengan huruf latin dan tidak menggunakan bahasa Indonesia maka dinyatakan sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu sejak terjadinya hubungan kerja. Apabila perjanjian kerja tersebut dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing (biasanya untuk tenaga kerja asing), maka apabila terjadi perbedaan penafsiran antara keduanya, yang berlaku adalah perjanjian kerja yang dibuat dalam bahasa Indonesia Indonesia
Perjanjian kerja waktu tertentu dilarang mensyaratkan adanya masa percobaan. Apabila syarat masa percobaan tersebut dicantumkan, maka syarat tersebut batal demi hukum. Perjanjian kerja jenis ini hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu menurut jenis, sifat, dan kegiatan pekerjaan akan selesai dalam waktu tertentu, jadi bukan pekerjaan yang bersifat tetap. Pekerjaan dikatakan bersifat tetap apabila pekerjaan tersebut sifatnya terus-menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu, dan merupakan bagian dari suatu proses produksi dalam suatu perusahaan atau pekerjaan yang bukan bersifat musiman.
Macam pekerjaan tertentu yang dapat diperjanjikan dalam perjanjian kerja waktu tertentu adalah :
a. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
b. Pekerjaan yang diperkirakan dapat diselesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
c. Pekerjaan yang bersifat musiman; yaitu suatu pekerjaan yang tergantung pada cuaca atau kondisi tertentu. Suatu pekerjaan yang terus-menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu dan merupakan bagian dari proses produksi tetapi tergantung pada cuaca atau apabila pekerjaan tersebut dibutuhkan bila ada kondisi tertentu maka pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan musiman;
d. Pekerjaan yang berhubungan dengan produksi baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.
Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan pada jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. Paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu tersebut berakhir, pengusaha wajib memberitahukan maksudnya untuk memperpanjang waktu perjanjian kepada pekerja/buruh.
Ketentuan-ketentuan tentang perjanjian kerja waktu tertentu sebagai mana diuraikan tersebut di atas apabila tidak dipenuhi, maka demi hukum perjanjian kerja waktu tertentu berubah menjadi perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu. Perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu ini hanya dapat diterapkan untuk jenis kegiatan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam masa percobaan atau penjajakan. Terhadap perjanjian kerja jenis ini tidak dapat dilakukan pembaharuan setelah perjanjian tersebut berakhir.
Perjanjian kerja waktu tertentu dapat pula diterapkan pada pekerjaan yang sekali selesai atau bersifat sementara atau berdasarkan selesainya suatu pekerjaan tertentu. Perjanjian kerja jenis ini dapat dibuat untuk paling lama 3 (tiga) tahun dan harus mencantumkan batasan pekerjaan tersebut dinyatakan selesai. Apabila pekerjaan tertentu dalam perjanjian tersebut dapat diselesaikan lebih cepat dari yang diperjanjikan maka perjanjian tersebut putus demi hukum pada saat selesainya pekerjaan. Apabila karena kondisi tertentu pekerjaan tersebut belum dapat diselesaikan setelah jangka waktunya berakhir maka dapat dilakukan pembaharuan perjanjian untuk paling lama 2 (dua) tahun. Pembaharuan ini baru dapat dilakukan setelah melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak berakhirnya perjanjian kerja. Selama tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut tidak ada hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha.
Untuk pekerjaan yang bersifat musiman, perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dapat diterapkan bila pekerjaan tersebut tergantung pada musim atau cuaca dan dilakukan untuk satu jenis pekerjaan pada musim tertentu. Untuk pekerjaan yang dilakukan dalam rangka memenuhi pesanan atau target tertentu seperti saat order sedang ramai sehingga volume pekerjaan bertambah banyak bisa dilakukan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) khusus hanya untuk pekerjaan tambahan tersebut. Terhadap perjanjian kerja jenis ini tidak dapat dilakukan pembaharuan perjanjian.
Pada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang berubah-ubah baik dalam hal waktu maupun volume pekerjaan dan upah dibayarkan atas dasar kehadiran pekerja/buruh maka dapat dilakukan perjanjian kerja harian lepas dengan syarat pekerja/buruh tersebut bekerja kurang dari 21 (dua puluh satu) hari dalam 1 (satu) bulan. Apabila pekerja/buruh bekerja 21 (dua puluh satu) hari atau lebih selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih maka perjanjian kerja harian lepas berubah menjadi perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu (PKWTT) atau menjadi pekerja/buruh tetap. Perjanjian pekerja harian lepas harus dibuat secara tertulis yang dapat berupa daftar pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan dan sekurang-kurangnya memuat :
a. Nama/alamat perusahaan atau pemberi kerja
b. Nama/alamat pekerja/buruh
c. Jenis pekerjaan yang dilakukan
d. Besarnya upah dan imbalan lainnya
Daftar pekerja/buruh tersebut harus disampaikan ke instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota setempat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak pekerja/buruh dipekerjakan.
Perjanjian kerja jangka waktu tertentu terakhir setelah selesainya jangka waktu yang diperjanjikan atau setelah selesainya pekerjaan tertentu yang diperjanjikan. Pembahasan lebih detail tentang berakhirnya perjanjian kerja jenis ini akan diuraikan pada pembahasan tentang pemutusan hubungan kerja pada akhir bab ini.
Upah
Menurut pasal 1 ayat (30) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundangan yang berlaku, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atau suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa :
a. Upah adalah hak pekerja/buruh sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
b. Upah yang diterima pekerja/buruh harus dinyatakan dengan uang.
c. Upah dibayarkan sesuai dengan perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan.
d. Tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya merupakan komponen dari upah.
Pengusaha dalam menetapkan upah dilarang mengadakan diskriminasi antara pekerja/buruh laki-laki dengan pekerja/buruh perempuan untuk pekerjaan yang sama nilainya atau yang mempunyai uraian jabatan (job description) yang sama.
Komponen Upah
Penghasilan pekerja/buruh yang didapat dari pengusaha ada yang berupa upah dan bukan upah. Menurut Surat
Penghasilan upah komponennya terdiri dari :
a. Upah Pokok, yaitu imbalan dasar yang dibayar kepada pekerja/buruh menurut tingkat atau jenis pekerja yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
b. Tunjangan Tetap, yaitu suatu pembayaran yang teratur berkaitan dengan pekerjaan yang diberikan secara tetap untuk pekerja/buruh dan keluarganya serta dibayarkan dalam satuan waktu yang sama dengan pembayaran upah pokok seperti tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan jabatan, dan lain-lain. Tunjangan tetap pembayarannya dilakukan secara teratur dan tidak dikaitkan dengan kehadiran pekerja/buruh atau pencapaian suatu prestasi kerja tertentu.
c. Tunjangan tidak tetap yaitu suatu pembayaran yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan pekerja/buruh yang diberikan secara tidak tetap untuk pekerja/buruh dan keluarganya serta dibayarkan menurut satuan waktu yang tidak sama dengan waktu pembayaran upah pokok seperti tunjangan transpor atau tunjangan makan apabila diberikan berdasarkan kehadiran pekerja/buruh.
Penghasilan yang bukan upah yang terdiri atas :
a. Fasilitas, yaitu kenikmatan dalam bentuk nyata/natura yang diberikan perusahaan oleh karena hal-hal khusus atau untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh seperti fasilitas kendaraan, pemberian makan secara Cuma-Cuma, sarana ibadah, tempat penitipan bayi, koperasi, kantin, dan lain-lain.
b. Bonus, yaitu pembayaran yang diterima pekerja dari hasil keuntungan perusahaan atau karena pekerja menghasilkan hasil kerja lebih besar dari target produksi yang normal atau karena peningkatan produktivitas, besarnya pembagian bonus diatur berdasarkan kesepakatan.
c. Tunjangan hari raya (THR), gratifikasi, dan pembagian keuntungan lainnya.
Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, oleh karena itu pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh yang meliputi :
a. Upah minimum
b. Upah kerja lembur
c. Upah tidak masuk kerja karena berhalangan
d. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaan
e. Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya
f. Bentuk dan cara pembayaran upah
g. Denda dan potongan upah
h. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah
i. Struktur dan skala pengupahan yang proporsional
j. Upah untuk pembayaran pesangon
k. Upah untuk pembayaran pajak penghasilan
Upah Minimum
Pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Upah minimum dapat terbagi atas;
a. Upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota
Besar upah ini untuk tiap wilayah provinsi atau kabupaten/kota tidak sama, tergantung nilai kebutuhan hidup layak (KHL) di daerah yang bersangkutan. Kebutuhan hidup layak adalah standar kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak, baik secara fisik, non fisik, dan sosial. Setiap kabupaten/kota tidak boleh menetapkan upah minimum di bawah upah minimum provinsi yang bersangkutan.
b. Upah minimum berdasarkan sektor/sub sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota
Upah minimum sektoral ditetapkan berdasarkan kelompok usaha tertentu misalnya kelompok usaha manufaktur dan non manufaktur. Upah minimum sektoral ini tidak boleh lebih rendah dari upah minimum di daerah yang bersangkutan.
Upah minimum ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota. Pengusaha dilarang membayar upah pekerja/buruh dibawah upah minimum daerah dimana pekerja/buruh tersebut bekerja, termasuk kepada pekerja/buruh yang sedang dalam masa percobaan 3 (tiga) bulan pertama. Pelanggaran terhadap ketentuan ini merupakan tindak pidana yang dapat diancam pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Dalam hal apabila pengusaha belum mampu membayar upah sebesar upah minimum maka dapat mengajukan penundaan ke instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan untuk kurun waktu tertentu.
Permohonan penangguhan pelaksanaan upah minimum diajukan pengusaha kepada Gubernur melalui instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan tingkap provinsi paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal upah minimum berlaku. Permohonan penangguhan diajukan berdasarkan kesepakatan tertulis antara pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat dan berhak melakukan perundingan dengan pengusaha. Apabila dalam perusahaan tersebut belum terbentuk serikat pekerja/serikat buruh, maka perundingan untuk menyepakati penundaan pemberlakuan upah minimum dilakukan antara pengusaha dengan pekerja/buruh yang mendapat mandat untuk mewakili lebih dari 50% (lima puluh perseratus) pekerja/buruh yang menerima upah minimum di perusahaan bersangkutan. Permohonan penangguhan harus dilampiri dengan :
a. Naskah asli kesepakatan tertulis antara pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh atau pekerja/buruh pada perusahaan bersangkutan;
b. Laporan keuangan perusahaan yang terdiri dari neraca, perhitungan laba/rugi, beserta penjelasan-penjelasan untuk 2 (dua) tahun terakhir. Apabila perusahaan tersebut telah berbadan hukum, maka laporan keuangan harus diaudit oleh akuntan publik;
c. Salinan akta pendirian perusahaan;
d. Data upah menurut jabatan pekerja/buruh;
e. Jumlah pekerja/buruh seluruhnya dan jumlah pekerja buruh yang dimohonkan penangguhan pelaksanaan upah minimumnya;
f. Perkembangan produksi dan pemasaran selama 2 (dua) tahun terakhir, serta rencana produksi dan pemasaran untuk 2 (dua) tahun yang akan datang.
Apabila diperlukan, Gubernur dapat meminta akuntan publik untuk memeriksa keadaan keuangan perusahaan guna membuktikan ketidakmampuan tersebut. Gubernur dapat menerima atau menolak permohonan penangguhan tersebut setelah menerima saran dan pertimbangan dari Dewan Pengupahan Provinsi. Persetujuan penangguhan diberikan oleh Gubernur untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan yang dapat berupa ketetapan untuk :
a. Membayar upah minimum sesuai upah minimum lama, atau;
b. Membayar upah minimum lebih tinggi dari upah minimum lama tetapi lebih rendah dari upah minimum baru, atau;
c. Menaikkan upah minimum secara bertahap.
Setelah selesainya jangka waktu penangguhan, pengusaha harus membayar upah minimum yang berlaku.
Persetujuan atau penolakan Gubernur terhadap permohonan penangguhan upah minimum harus sudah diberikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya permohonan secara lengkap oleh Gubernur. Apabila setelah lewat jangka waktu tersebut Gubernur belum memberikan keputusan, maka permohonan dianggap telah disetujui. Selama permohonan masih dalam proses penyelesaian, maka pengusaha harus tetap membayar upah sebesar upah yang biasa diterima pekerja/buruh. Apabila permohonan penangguhan ditolak Gubernur, maka pengusaha harus membayar upah sekurang-kurangnya sebesar upah minimum yang berlaku terhitung sejak mulai berlakunya upah minimum tersebut.
Menurut peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 01/MEN/1989 pada pasal 1 huruf (a) tentang pengertian upah minimum disebutkan bahwa upah minimum adalah upah pokok ditambah tunjangan tetap. Komposisi upah pokok serendah-rendahnya 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari upah minimum. Sebagai contoh misalnya untuk DKI Jakarta yang untuk upah minimum umpamanya ditetapkan sebesar Rp800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah) per bulan. Perusahaan X yang berada di DKI Jakarta menetapkan upah sebagai berikut :
Upah Pokok : Rp600.000,00
Tunjangan Tetap : Rp200.000,00
Jumlah : Rp800.000,00
Penetapan upah ini sesuai dengan ketentuan karena komposisi upah pokok sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari seluruh jumlah upah.
Apabila perusahaan X tersebut menetapkan upah sebagai berikut :
Upah Pokok : Rp560.000,00
Tunjangan Tetap : Rp240.000,00
Jumlah : Rp800.000,00
Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan karena komposisi upah pokok di bawah 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari upah minimum yaitu sebesar 70% (tujuh puluh perseratus).
Apabila suatu daerah menggunakan pengertian upah minimum adalah upah pokok, maka harus diartikan bahwa upah pokok tersebut sebagai bagian dari upah minimum yang nilainya berdasarkan perbandingan upah pokok 75% (tujuh puluh lima perseratus) dan tunjangan tetap 25% (dua puluh lima perseratus). Dengan demikian tingkat upah minimum untuk daerah tersebut harus ditambah 1/3 (satu per tiga) dari upah pokok.
Misalnya :
Jika upah pokok minimum untuk daerah X ditetapkan sebesar Rp720.000,00, maka tingkat upah minimum untuk daerah tersebut adalah Rp 720.000,00 + (1/3 X Rp 720.000,00) = Rp 960.000,00.
Ketentuan tentang upah minimum ini berlaku untuk semua pekerja/buruh harian, bulanan, kontrak/borongan, dan pekerja/buruh yang masih dalam masa percobaan 3 (tiga) bulan pertama. Bagi pekerja/buruh yang masih berada dalam masa latihan kerja (training) dapat diberi upah di bawah upah minimum tetapi jumlahnya tidak boleh kurang dari 80% (delapan puluh perseratus) dari upah minimum denga ketentuan latihan tersebut diadakan secara tersendiri tidak dalam rangka proses produksi dan hasil produksi dari latihan (training) tidak dianggap sebagai hasil produksi dan tidak dijual bersama-sama hasil produksi lain. Apalagi latihan (training) dilakukan di dalam proses produksi (on the job training) dan hasil produksinya disamakan dengan hasil produksi biasa, maka terhadap pekerja/buruh dalam masa latihan kerja tersebut harus diberi upah sekurang-kurangnya sebesar upah minimal yang berlaku.
Upah Kerja Lembur
Menurut pasal 77 Undang-undang Ketenagakerjaan, jumlah waktu kerja adalah :
a. 7 (tujuh) jam per hari dan 40 (empat puluh) jam seminggu untuk perusahaan yang menerapkan hari kerja 6 (enam) hari kerja per minggu; atau
b. 8 (delapan) jam kerja per hari dan 40 (empat puluh) jam kerja semingga untuk perusahaan yang menerapkan hari kerja 5 (lima
Ketentuan waktu kerja tersebut tidak berlaku untuk sektor usaha atau pekerjaan tertentu seperti pekerjaan di pengeboran minyak lepas pantai, sopir angkutan jarak jauh, pekerjaan di kapal, penebangan hutan, dan sejenisnya.
Apabila pengusaha mempekerjakan pekerja/buruh melebihi ketentuan waktu kerja tersebut maka kelebihan waktu kerja tersebut disebut sebagai waktu kerja lembur. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi ketentuan waktu kerja (kerja lembur) harus memenuhi syarat :
a. ada persetujuan dari pekerja/buruh bersangkutan; dan
b. waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam perhari dan 14 (empat belas) jam dalam satu minggu tidak termasuk kerja lembur yang dilakukan pada hari libur istirahat mingguan atau hari nasional.
Melebihi ketentuan waktu kerja lembur yang telah ditetapkan tersebut merupakan tindak pidana pelanggaran pengusaha yang melanggarnya dapat diancam sanksi denda paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima
Menurut Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I No. Kep-102/MEN/VI/2004 tanggal 25 Juni 2004, tentang waktu kerja lembur dan upah kerja lembur, pengusaha yang mempekerjakan pekerja melebihi waktu kerja (kerja lembur) harus membayar upah kerja lembur, memberi kesempatan untuk istirahat secukupnya serta memberi makanan dan minuman sekurang-kurangnya 1.400 kalori apabila kerja lembur dilakukan selama 3 jam atau lebih dimana makanan dan minuman tersebut tidak dapat diganti dengan uang. Komponen upah yang dijadikan dasar perhitungan upah kerja lembur adalah sebagai berikut :
a. Upah pokok
b. Tunjangan jabatan
c. Tunjangan kemahalan
d. Nilai pemberian catu (upah berupa barang untuk keperluan hidup) untuk pekerja/buruh itu sendiri.
Jumlah nilai komponen yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan upah kerja lembur tersebut tidak boleh kurang dari 75% (tujuh puluh lima
Upah Pokok : Rp 15.000,00
Tunjangan Jabatan : Rp 5.000,00
Tunjangan kemahalan : Rp 2.500,00
Nilai pemberian catu : Rp 3.000,00
Tunjangan transpor : Rp 2.000,00
Tunjangan makan : Rp 5.000,00
Jumlah : Rp 32.500,00
Komponen upah sebagai dasar perhitungan upah kerja lembur tersebut adalah Rp 25.500,00 yang berasal dari Rp (15.000,00 + 2.500,00 + 3.000,00), karena jumlah komponen upah tersebut lebih besar dari 75% X Rp 32.500,00.
Apabila nilai komponen upah yang dipergunakan untuk perhitungan upah kerja lembur tidak mencapai 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah keseluruhan upah yang dibayarkan maka perhitungan upah lembur didasarkan atas 75% dari keseluruhan upah yang dibayarkan. Sebagai contoh misalnya sebagai berikut :
Upah pokok : Rp 10.000,00
Tunjangan jabatan : Rp 5.000,00
Tunjangan kemalahan : Rp 2.000,00
Nilai pemberian catu : Rp 1.000,00
Tunjangan transpor : Rp 6.000,00
Tunjangan makan : Rp 9.000,00
Jumlah : Rp 33.000,00
Komponen upah tetap tersebut hanya sebesar Rp 18.000,00 yang berasal dari Rp (10.000,00+5.000,00+2.000,00+1.000,00) yang berarti di bawah 75% dari keseluruhan upah, sehingga dasar perhitungan upah kerja lembur yang dipakai adalah : 75% X Rp 33.000,00 = Rp 24.750,00. hasil perhitungan akhir dari 75% X keseluruhan upah ini tidak boleh lebih rendah dari upah minimum yang berlaku. Apabila lebih rendah, maka yang dipergunakan adalah upah minimum yang berlaku.
Cara perhitungan upah kerja lembur untuk kerja lembur hari biasa berbeda dengan perhitungan pada hari libur mingguan atau libur resmi, sebagai berikut :
a. Upah kerja lembur pada hari kerja biasa :
1. Untuk jam kerja lembur pertama, upah kerja lembur harus dibayar sebesar 1,5 (satu setengah) kali upah 1 (satu) jam
2. Untuk jam kerja lembur berikutnya, upah kerja lembur harus dibayar sebesar 2 (dua) kali upah 1 (satu) jam
b. Upah kerja lembur pada hari istirahat mingguan atau libur resmi untuk waktu kerja 7 (tujuh) jam sehari 6 (enam) hari kerja seminggu atau 40 (empat puluh) jam semingga maka :
1. Untuk 7 (tujuh) jam kerja lembur pertama upah kerja lembur harus dibayar 2 (dua) kali upah 1 (satu) jam, jam lembur kedelapan dibayar 3 (tiga) kali upah perjam serta jam lembur kesembilan dan seterusnya dibayar 4 (empat) kali upah perjam.
2. Apabila hari libur resmi tersebut jatuh pada hari terpendek pada salah satu hari kerja dalam 6 (enam) hari kerja seminggu, maka upah kerja lembur untuk 5 (lima) jam pertama dibayar 2 (dua) kali upah perjam, jam keenam dibayar 3 (tiga) kali upah 1 (satu) jam serta jam keenam dibayar 3 (tiga) kali upah 1 (satu) jam serta kerja lembur ketujuh dan seterusnya dibayar 4 (empat) kali upah sejam.
c. Untuk perusahaan yang menerapkan jam kerja 8 (delapan) jam sehari 5 (lima) hari kerja seminggu atau 40 (empat puluh) jam seminggu, maka upah kerja lembur pada hari istirahat minggu atau hari libur resmi untuk 8 (delapan) jam pertama dibayar 2 (dua) kali upah sejam, jam kerja lembur kesembilan dibayar upah 3 (tiga) kali upah sejam serta jam kesepuluh dan seterusnya upah kerja lembur harus dibayar 4 (empat) kali upah 1 (satu) jam
a. Bagi pekerja/buruh harian, upah sebulan adalah upah sehari dikalikan 25 (dua puluh lima) bagi pekerja/buruh harian yang bekerja 6 (enam) hari kerja seminggu atau dikalikan 21 (dua puluh satu) bagi pekerja/buruh harian yang bekerja 5 (lima) hari kerja seminggu;
b. Bagi pekerja/buruh yang upahnya dibayar berdasarkan satuan hasil, maka upah sebulan adalah upah rata-rata selama 12 (dua belas) bulan terakhir. Apabila pekerja/buruh bekerja kurang dari 12 (dua belas) bulan, maka upah sebulan dihitung berdasarkan upah rata-rata selama bekerja dengan ketentuan tidak boleh lebih rendah dari upah minimumnya yang berlaku.
Pelanggaran terhadap ketentuan cara perhitungan upah kerja lembur ini (membayar upah kerja lembur lebih rendah dari ketentuan yang telah ditetapkan) merupakan tindak pidana pelanggaran yang diancam pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
Tugas : Setelah memperoleh materi mahasiswa dapat menjelaskan :
1. Jelaskan pengertian dari perjanjian kerja ?
2. Jelaskan yang dimaksud dengan perjanjian kerja waktu tertentu ?
3. Jelaska pembatasan-pembatasan kerja atas perjanjian kerja waktu tertentu ?
4. Jelaskankan pengertian dari upah ?
5. Jelaskan komponen-komponen dari upah ?
PERTEMUAN KE V
PRINSIP PERLINDUNGAN TENAGA KERJA
TIK : Pada akhir perkuliahan mahasiswa diharapkan mampu
1. menjelaskan pengertian perlindungan tenaga kerja
2. menjelaskan jenis dan obyek dari perlindungan tenaga kerja
Pokok Bahasan : Prinsip Perlindungan Tenaga Kerja
Deskripsi Singkat : Dalam perkuliahan ini mahasiswa akan mempelajari pengertian dari perlindungan tenaga kerja, jenis-jenis perlindungan tenaga kerja dan obyek dari perlindungan tenaga kerja.
Tujuan Perlindungan Tenaga Kerja
Tujuan perlindungan tenaga kerja adalah untuk menjamin berlangsung nya sistem hubungan kerja secara harmonis tanpa disertai adanya tekan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Untuk ini pengusaha wajib melaksanakan ketentuan perlindungan tenaga kerja tersebut sesuai tperaturan perundang-undangan yang berlaku.
Adapun dasar perlindungan tenaga kerja antara lain :
1. Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
2. Undang-undang No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
3. Undang-undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan
4. Undang-undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga kerja
5. Undang-undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh
6. Undang-undang no. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
7. Undang-undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
8. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1950 tentang Waktu Kerja dan Waktu Istirahat
9. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1954 tentnag Istirahat Tahunan bagi Buruh
10. Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja RI dan Kepala Kepolisisn RI No. Kep-275?Men/1989 dan No. Pol.04/V/1989tentang Pengaturan Jam Kerja, Shift dan kerja istirahat serta Pembinaan Tenaga.
A. PRINSIP PERLINDUNGAN TENAGA KERJA
Perlindungan tenaga kerja sangat mendapat perhatian dalam hukum ketenagakerjaan. Beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di.antaranya mengatur hal itu.
1. Salah satu tujuan pembangunan ketenagakerjaan adalah memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan (Pasal 4 huruf c).
2. Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan (Pasal 5).
3. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha (Pasal 6).
4. Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, clan kemampuannya melalui pelatihan kerja (Pasal 11).
5. Setiap pekerja/buruh memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan kerja sesuai dengan bidang tugasnya (Pasal 12 ayat (3)).
6. Setiap tenaga kerja mempunyai hak clan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan clan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri (Pasal 31).
7. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlindungan atas keselamatan clan kesehatan kerja, moral clan kesusilaan, clan perlakuan yang sesuai dengan harkat clan martabat manusia serta nilai-nilai agama (pasal 86 ayat (1)).
8. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang me menuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 88 ayat (1)
9. Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja (Pasal 99 ayat (1)).
10. Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh (Pasal 104 ayat (1)).
Ketentuan Pasal 5 secara yuridis memberikan perlindungan bahwa setiap tenaga kerja berhak dan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap para penyandang cacat. Sedangkan Pasal 6 mewajibkan kepada pengusaha untuk memberikan hak dan kewajiban pekerja/buruh tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, warna kulit, dan aliran politik.
Mengenai asas pemberlakuan ketentuan ketenagakerjaan terhadap semua pekerja, di mana disebutkan bahwa semua ketentuan,ketenagakerjaan berlaku terhadap semua pekerja tanpa membedakan statusnya (Pasal 3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-06/Men/1985 tentang Perlindungan Pekerja Harian Lepas). Memang peraturan ini sudah tidak berlaku setelah berlakunya peraturan baru, tetapi jiwanya dapat ditemukan lagi pada ketentuan:
a) Pasal 2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep-100/Men/VI/2004 yang menyebutkan bahwa syarat kerja yang diperjanjikan dalam PKWT, tidak boleh lebih rendah daripada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku
b) Pasal 5 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep-220/Men/X/2004 yang menyebutkan bahwa setiap perjanjian pemborongan pekerjaan wajib memuat ketentuan yang menjamin terpenuhinya hak-hak pekerja/buruh dalam hubungan kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku
B. JENIS DAN OBJEK PERLINDUNGAN TENAGA ` KERJA
1. Jenis Perlindungan Tenaga Kerja
Menurut Soepomo dalam Asikin (1993: 76) perlindungan tenaga kerja dibagi menjadi tiga macam, yaitu:
a. Perlindungan ekonomis
Yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk penghasilan yang ' cukup, termasuk bila tenaga kerja tidak mampu bekerja di luar ke- ~ hendaknya.
b. Perlindungan sosial
Yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk jaminan kesehatan ~ kerja, clan kebebasan berserikat clan perlindungan hak untuk berorganisasi.
c. Perlindungan teknis
Yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk keamanan clan keselamatan kerja.
Ketiga jenis perlindungan di atas mutlak harus dipahami clan dilaksanakan sebaik-baiknya, oleh pengusaha sebagai pemberi kerja. Jika pengusaha melakukan pelanggaran, maka dikenakan sanksi.
2. Objek Perlindungan Tenaga Kerja
Objek perlindungan tenaga kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 meliputi:
a. Perlindungan atas hak-hak dalam hubungan kerja;
b. Perlindungan atas hak-hak dasar pekerja/buruh untuk berunding dengan pengusaha, clan mogok kerja;
c. Pelindungan keselamatan clan kesehatan kerja;
d. Perlindungan khusus bagi pekerja/buruh perempuan, anak dan penyandang cacad
e. Perlindungan tentang upah, kesejahteraan, clan jaminan sosial tenaga kerja; dan
f. Perlindungan atas hak pemutusan hubungan tenaga kerja.
Berikut dibawah ini diuraikan perlindungan khusus bagi pekerja/buruh perempuan, anak dan penyandang cacad berdasarkan Undang-undang No. 13 tahun 2003.
a. Perlindungan pekerja/buruh perempuan
1) Pengusaha dilarang mempekerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan 07.00 terhadap pekerja/buruh pei'empuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun (Pasal 76 ayat
(1)).
2) Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan clan keselamatan kandungannya maupun dirinya, apabila bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan 07.00 (Pasal 76 ayat (2)).
3) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan 07.00 (Pasal 76 ayat (3)) wajib:
· Memberikan makanan dan minuman bergizi; dan
· Menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja
4) Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh perempuan yang berangkat clan pulang bekerjaantara pukul 23.00 sampai dengan 05.00 (pasal 76 ayat (4)).
Sebagai tindak lanjut Pasal 76 ayat (3) clan ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah diterbitkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja clan Transmigrasi Nomor. Kep-224/Men/ 2003 tentang Kewajiban Pengusaha yang Mempekerjakan Pekerja/Buruh Perempuan antara Pukul 23.00 sampai dengan Pukul 07.00.
b. Perlindungan anak
Pengertian anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan ,. belas) tahun (Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ~ tentang Ketenagakerjaan). '
1) Pengusaha dilarang mempekerjaan anak (Pasal 68).
2) Ketentuan Pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak berumur antara tiga belas tahun sampai dengan lima belas tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan clan kesehatan fisik, mental, clan sosial (Pasal 69 ayat (1)).
3) Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan harus memenuhi persyaratan (Pasal 69 ayat (2)):
· Izin tertulis dari orang tua atau wali;
· Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali.
· Waktu bekerja maksimum tiga jam sehari;
· Dilakukan pada siang had clan tidak mengganggu waktu sekolah;
· Keselamatan dan kesehatan kerja; Adanya hubungan kerja yang jelas; clan
· Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4) Dalam hal anak dipekerjakan bersama-sama pekerja/buruh dewasa, maka tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja pekerja/ buruh dewasa (Pasal 72).
5) Anak dianggap bekerja bilamana berada di tempat kerja, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya (Pasal 73)
6) Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk (Pasal 74 ayat (1)) meliputi segala pekerjaan :
· Dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya
· Yang memanfaatkan, menyediakan atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno atau perjudian
· Yang memanfaatkan, menyediakan atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnyadan
· Yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak.
Sedangkan jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja clan Transmigrasi Nomor Kep-235/Men/2003 sebagai berikut:
1) Jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan dan keselamatan anak
a. Pekerjaan yang berhubungan dengan mesin, pesawat, instalansi dan peralatan lainnya meliputi :
Pekerjaan pembuatan, perakitan, pengoperasian, perawatan dan perbaikan
(i) Mesin-mesin
(ii) Pesawat
(iii) Alat berat seperti : traktor, pemecah batu grader, pencampur aspal, mesin pancang
(iv) Instalasi pipa bertekanan, instalasi listrik, instalasi pemadam kebakaran, saluran listrik
(v) Peralatan lainnya seperti : tanur, dapur peleburan, lift, perancah
(vi) Bejana tekan, botol baja, bejana penimbun, bejana pengangkut dan sejenisnya.
b. Pekerjaan yang dilakukan pada lingkungan kerja
(i) Pekerjaan yang mengandung bahaya fisik
(ii) Pekerjaan yang mengandung bahan kimia
(iii) Pekerjaan yang mengandung bahaya biologis
c. Pekerjaan yang mengandung sifat dan keadaan berbahaya
· Pekerjaan konstruksi bangunan, jembatan, irigasi atau jalan
· Pekerjaan yang dilakukan dalam perusahaan pengolahan kayu
· Pekerjaan mengangkat dan mengangkut secara manual beban diatas 12 kg untuk anak laki-laki dan 10 kg untuk anak perempuan
· Pekerjaan dalam bangunan tempat kerja yang terkunci
· Pekerjaan penangkapan ikan yang dilakukan di lepas pantai atau di perairan dalam
· Pekerjaan yang dilakukan didaerah terisolir dan terpencil
· Pekerjaan di kapal
· Pekerjaan yang dilakuakan dalam pembuangan dan pengolahan sampah atau daur ulang barang-barang bekas
· Pekerjaan yang dilakukan antara pukul 18.00-06.00
2) Jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan moral anak
a. Pekerjaan pada usaha bar, diskotik, karaoke, bola sodok, bioskop, panti pijat atau lokasi yang dapat dijadikan tempat prostitusi.
b. Pekerjaan sebagai model untuk promosi minuman keras, obat perangsang seksualitas dan/atau rokok.
c. Perlindungan penyandang cacat
Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacad wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kecacadannya (pasal 67 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003). Bentuk perlindungan tersebut seperti penyediaan aksebilitas, pemberian alat kerja dan alat pelindung diri.
Tugas : Setelah memperoleh materi mahasiswa dapat menjelaskan :
1. Jelaskan tujuan perlindungan tenaga kerja ?
2. Jelaskan pengertian perlindungan tenaga kerja ?
3. Jelaskan jenis-jenis perlindungan tenaga kerja ?
4. Jelaskan obyek dari perlindungan tenaga kerja ?
PERTEMUAN KE VI
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
TIK : Pada akhir perkuliahan mahasiswa diharapkan mampu
1. menjelaskan pengertian keselamatan dan kesehatan kerja
2. menjelaskan pengertian dan prosedur dari program jaminan kesehatan
Pokok Bahasan : Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Deskripsi Singkat : Dalam perkuliahan ini mahasiswa akan mempelajari pengertian dari keselamatan dan kesehatan kerja, program jaminna kesehatan serta prosedur dari program jaminana kesehatan.
1. Maksud dan Tujuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Upaya keselamatan dan kesehatan kerja (disebut K3) dimaksudkan untuk memberikan jaminan keselamatan clan meningkatkan derajat kesehatan para pekerjalburuh dengan cara pencegahan kecelakaan clan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan, dan rehabilitasi.
Sedangkan tujuan upaya keselamatan clan kesehatan kerja adalah untuk melindungi keselamatan pekerjalburuh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal, dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan, clan rehabilitasi.
Dengan demikian eksistensi peraturan perundang-undangan keselamatan dan kesehatan kerja adalah:
1. Melindungi pekerja dari risiko kecelakaan kerja.
2. Meningkatkan derajat kesehatan para pekerja/buruh.
3. Agar pekerja/buruh clan orang-orang di sekitarnya terjamin keselamatannya.
4. Menjaga agar sumber produksi dipelihara clan dipergunakan secara aman dan berdaya guna.
2. Ruang Lingkup Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Ruang lingkup keselamatan dan kesehatan kerja adalah di segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun diudara, dalam wilayah negara Republik Indonesia. Keselamatan dan kesehatan kerja harus diterapkan dan dilaksanakan di setiap tempat kerja.
Unshur tempat kerja ada tiga yaitu :
a. Adanya suatu usaha baik bersifat ekonomis maupun sosial
b. Adanya sumber bahaya
c. Adanya tenaga kerja yang bekerja di dalamnya, baik terus-menerus maupun sewaktu-waktu
Penanggung jawab keselamatan clan kesehatan kerja di tempat kerja ialah i pengusaha atau pimpinan atau pengurus tempat kerja. Pelaksanaan ke• i selamatan clan kesehatan kerja di tempat kerja dilakukan secara bersama oleh pimpinan atau pengurus perusahaan clan seluruh pekerja/buruh.
Pengawasan atas pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja dilaku• kan oleh pejabat/petugas yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja, yaitu:
a. Pegawai pengawas keselamatan clan kesehatan kerja, sebagai pegawai teknis berkeahlian khusus dari Depnaker.
b. Ahli keselamatan clan kesehatan kerja, sebagai ahli teknis berke• ahlian khusus dari luar Depnaker.
3. Kewajiban Para Pihak
Kewajiban pihak-pihak dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja secara umum diatur sebagai berikut:
a. Kewajiban pengusaha
1) Terhadap pekerja/buruh yang baru masuk, pengusaha wajib menunjukkan clan menjelaskan hal-hal:
· Tentang kondisi dan bahaya yang dapat timbul dilingkungan kerja
· Semua alat pengaman dan pelindung yang digunakan
· Cara dan sikap yang aman dalam melakukan pekerjaan
· Memeriksa kesehatan baik fisisk maupun mental pekerja yang bersangkutan
2) Terhadap pekerja/buruh yang telah atau sedang dipekerjakan :
· Melakukan pembinaan dalam hal pencegahan kecelakaan kerja, penanggulangan kebakaran, pemberian P2K3 dan peningkatan usaha keselamatan dan kesehatan keda pada umumnya.
· Memeriksakan kesehatan pekerja secara berkala
3) Menyediakan secara cUma-cuma semua alat perlindungan diri yang diwajibkan untuk tempat kerja yang bersangkutan bagi seluruh pekerja/buruh.
4) Memasang gambar dan Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta bahan pembinaan lainnya di tempat kerja sesuai petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan dan kesehatan kerja.
5) Melaporkan setiap peristiwa kecelakaan kerja termasuk peledakan, kebakaran, dan penyakit akibat kerja yang terjadi akibat kerja yang terjadi di tempat kerja kepada kantor Departemen Tenaga Kerja
6) Membayar biaya pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja ke Kantor Pembendaharaan Negara setempat setelah mendapat penetapan besarnya biaya oleh Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja setempat.
7) Menaati semua persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja, baik yang diatur dalam undang-undang maupun yang ditetapkan oleh pegawai pengawas.
b. Kewajibandan hak pekerja/buruh
1. Kewajiban pekerja/buruh
· Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan dan kesehatan kerja.
· Memakai alat pelindung diri yang diwajibkan.
· Memenuhi dan menaati persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja yang berlaku di tempat kerja yang bersangkutan,
2. Hak pekerja/buruh
· Meminta kepada pimpinan atau pengurus perusahaan agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan di perusahaan yang bersangkutan
· Menyatakan keberatan melakukan pekerjaan, bila syarz keselamatan clan kesehatan kerja serta alat pelindung di yang diwajibkan tidak dipenuhi, kecuali dalam toleran; khusus, yang ditetapkan lain oleh pegawai pengawas
4. Program Jamninan Sosial Tenaga Kerja
Pengertian Jaminan Sosial Tenaga Kerja menurut ketentuan Pasal 1, ayat (1)) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti ; sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang clan pelayanan se• bagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa' kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, had tua clan meninggal dunia
Berdasarkan uraian di atas jelas. bahwa program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (program Jamsostek) merupakan bentuk perlindungan ekonomis : dan perlindungan sosial. Dikatakan demikian, karena program ini memberikan perfindungan dalam bentuk. santunan berupa uang atas berkurangnya penghasilan clan perlindungan dalam bentuk pelayanan pe-' rawatan/pengobatan pada saat seorang pekerja tertimpa risiko-risiko tertentu.
Program Jamsostek merupakan kelanjutan program Asuransi Sosial Tenaga Kerja yang didirikan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 33' Tahun 1977. Secara yuridis penyelenggaraan program Jamsostek dimaksudkan sebagai pelaksanaan Pasal 10 clan Pasal 15 Undang-Undang' Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja (yang sekarang sudah dicabut dan diganti dengan Undang•' Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan).
Sebelum tahun 1977 sebenarnya sudah terdapat beberapa ketentuan' yang mewajibkan pengusaha untuk memberikan jaminan clan ganti rugi', bila terjadi musibah atau risiko yang menimpa pekerjanya (Budiono,.' 1995: 235), antara lain:
- Peraturan Kecelakaan (OngeVallenregeling)1939;
- Peraturan Kecelakaan Pelaut (Schepen Ongevallenregeling) 1940; clan
- Undang-Undang Kecelakaan Nomor 33 Tahun 1947.
Tugas : Setelah memperoleh materi mahasiswa dapat menjelaskan :
1. Jelaskan pengertian keselamatan dan kesehatan kerja ?
2. Jelaskan maksud dan tujuan adanya ketentuan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja ?
3. Jelaskan ruang lingkup dari keselamatan dan kesehatan kerja ?
4. Jelaskan kewajiban pengusaha terkait dengan keselamatan kesehatan pekerjanya ?
5. Jelaskan pengertian dari program jaminna sosial tenaga kerja ?
6. Jelaskan ketentuan ketenagakerjaan terkait program jamninan sosial tenaga kerja ?
PERTEMUAN KE VII
PEMBORONGAN KERJA
TIK : Pada akhir perkuliahan mahasiswa diharapkan mampu
1. menjelaskan pengertian pemborongan pekerjaan ?
2. menjelaskan kondisi tenaga kerja Indonesia saat ini dan posisi tawarnya terhadap pengusaha
3. menjelaskan pembedaan pelaksanaan pemborongan pekerjaan yang dilakukan di dalam negeri dan di luar negeri
4. menjelaskan bentuk-bentuk pekerjaan yang dapat dilakukan pemborongan
Pokok Bahasan : Pemborongan Pekerjaan
Deskripsi Singkat : Dalam perkuliahan ini mahasiswa akan mempelajari pengertian pemborongan pekerjaan, kondisi realitas pekerja Indonesia, pembedaan pelaksanaan pemborongan pekerjaan di dalam negeri dan di luar negeri dan bentuk bentuk pekerjaan yang dapat diborongkan
Pengertian dan Kondisi Realitas
INTERPRETASI GRAMATICAL:
OUT-SOURCING = SUMBER = TEMPAT ADANYA SDM
DALAM UU NO.13 TH.2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN è tidak terdapat definisi dalam ketentuan umum (pasal 1), sehingga interpretasi formal tidak dapat dilakukan. Tapi pada BAB VI pasal 31-38 memuat aturan tentang out-sourcing (di letakkan di bab tentang Penempatan Tenaga Kerja).
Pemborongan pekerjaan (Outsourcing) adalah penyerahan sebagian pekerjaan dari perusahaan pemberi pekerjaan kepada perusahaan penerima pemborongan pekerjaan atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh melalui perjanjian pemborongan pekerjaan secara tertulis.
Kondisi pasar tenaga Kerja di Indonesia :
G DI INDONESIA JUMLAH PENDUDUK MENINGKAT DENGAN CEPAT, WALAUPUN PROGRAM KELUARGA BERENCANA BERHASIL SAMPAI-SAMPAI PRESIDEN SUHARTO DI BERIKAN AWARD SEBAGAI “BAPAK PEMBANGUNAN” PADA DEKADE ’90-AN.
G AKIBATNYA JUMLAH ANGKATAN KERJA JUGA MENINGKAT DENGAN CEPAT.
G PADA HAL JUMLAH KESEMPATAN KERJA MENURUN SEJAK KRISIS MONETER MELANDA DUNIA DAN DI INDONESIA KRISIS TERSEBUT BERAKIBAT TERHADAP TERJADINYA KRISIS MULTIDIMENSI.
G SALAH SATU AKIBAT LANJUTAN DARI KRISIS ADALAH TERJADINYA GERAKAN MASYARAKAT YANG DIMOTORI OLEH MAHASISWA YANG MENGAKIBATKAN JATUHNYA PEMBERINTAHAN SUHARTO DAN MUNCULNYA GERAKAN UNTUK MEREFORMASI SISTEM PEMERINTAHAN SUPAYA MENJADI LEBIH DEMOKRATIS.
G WALAUPUN DEMOKRATISASI BERJALAN, TAPI TERNYATA KKN MASIH SULIT DIBERANTAS, LAGIPULA PENEGAKAN HUKUM JUGA MASIH BELUM BERJALAN DENGAN BAIK, SEHINGGA PARA PENANAM MODAL TIDAK MAU MENANAMKAN MODALNYA DI INDONESIA, BAHKAN YANG ADA DI INDONESIA MALAH MERELOKASIKAN KE NEGARA LAIN YANG LEBIH MENJANJIKAN
AKIBAT DARI SEMUA KONDISI YANG TERJADI ADALAH :
SEMAKIN MENURUNNYA KESEMPATAN KERJA DAN SEMAKIN MENINGKATNYA JUMLAH ANGKATAN KERJA YANG MENCARI PEKERJAAN.
AKIBAT SELANJUTNYA ADALAH :
MENINGKATNYA POSISI TAWAR MAJIKAN è SEBALIKNYA è
MENURUNNYA POSISI TAWAR BURUH
Proses Rekruting di Dalam Negeri dan di Luar Negeri
1. DI DALAM NEGERI
ADANYA KEBIJAKAN PEMERINTAH YANG MEMBERIKAN KESEMPATAN BAGI PERUSAHAAN UNTUK MEMPERMUDAH DAN MENGHEMAT PENGELUARAN:
v OUT-SOURCING à AWALNYA UNTUK MEMPERMUDAH BERTEMUNYA PASAR TENAGA KERJA TERHADAP ADANYA PERMINTAAN DAN PENAWARAN
v PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU OUT-SOURCING BERIMPLIKASI NEGATIF BAGI BURUH:
v DALAM PRAKTEK BURUH MENGELUARKAN BIAYA UNTUK PELATIHAN
v KESULITAN DALAM PENGORGANISASIAN BURUH
v MEMPERSULIT PELAKSANAAN PEMOGOKAN
2. DI LUAR NEGERI
I KARENA LOKASI KESEMPATAN KERJANYA JAUH (NEGARA LAIN), MAKA MUNCUL PERANTARA PASAR TENAGA KERJA:
(1) AGEN YANG MENCARI MAJIKAN DI NEGARA TUJUAN
BEKERJA
(2) PJTKI YANG MENCARI BURUH DI INDONESIA
I DAFTAR MAJIKAN YANG MEMBUTUHKAN BURUH (JOB-ORDER = JO) DALAM PERATURAN DIWAJIBKAN UNTUK MENDAPAT PENGESAHAN DARI PERWAKILAN INDONESIA DI LUAR NEGERI, BISA KEDUTAAN ATAU KONSULAT
I OLEH AGEN JO-NYA DIBERIKAN PADA PJTKI MITRANYA à PADA KONDISI NYATA JO INI YANG DIPERLIHATKAN KEPADA CALON TKI BUKAN YANG ASLI, MELAINKAN YANG FOTO-KOPIAN
I PJTKI SELALU MEREKRUT CALON TKI; SETELAH DILAKUKAN PELATIHAN, MEREKA MENUNGGU DI PENAMPUNGAN, SAMPAI LAMA (3-20 BULAN)
I TIDAK JADI DIBERANGKATKAN SERING DIALAMI OLEH CALON TKI
Hukum Positif – UU No. 13 Tahun 2003
PEMBERI KERJA: (pasal 35 ayat (1))
# Dapat merekrut sendiri
# Dapat merekrut melalui “pelaksana penempatan tenaga kerja”
KEWAJIBAN: (pasal 35 ayat (2) dan (3))
PELAKSANA PENEMPATAN è melindungi calon buruh sejak saat rekrut sampai penempatan
PEMBERI KERJA è melindungi buruh: kesejahteraan, keselamatan, kesehatan (fisik dan mental)
PELAKSANA PENEMPATAN è LEMBAGA: (pasal 37 + pasal 38)
] INSTANSI PEMERINTAH – DEPNAKER/DISNAKER è dilarang memungut biaya
] LEMBAGA SWASTA YANG BERBADAN HUKUM à wajib izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk è boleh memungut biaya dari pengguna + dari tenaga kerja untuk tenaga kerja golongan dan jabatan tertentu
TUGAS PELAKSANA PENEMPATAN: (pasal 35)
Memberikan pelayanan penempatan – unsur-unsurnya:
≈ Pencari kerja
≈ Lowongan kerja
≈ Informasi pasar kerja
≈ Mekanisme antar kerja
≈ Kelembagaan penempatan tenaga kerja
Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan pemborong pekerjaan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
a. Dilakukan terpisah dari kegiatan utama, baik manajemen maupun kegiatan pelaksanaan pekerjaan;
b. Dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi kerja, hal ini dimaksudkan untuk memberi penjelasan tentang cara melaksanakan pekerjaan agar sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan pemberi pekerjaan;
c. Merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan, artinya kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang mendukung dan memperlancar pelaksanaan pekerjaan sesuai alur kegiatan kerja di perusahaan pemberi pekerjaan;
d. Tidak menghambat proses produksi secara langsung, artinya kegiatan tersebut merupakan kegiatan tambahan yang apabila tidak dilakukan oleh perusahaan pemberi pekerja, maka proses produksi tetap berjalan sebagaimana mestinya; dan
e. Perusahaan pemborong pekerjaan tersebut harus merupakan perusahaan yang berbadan hukum kecuali untuk pemborong pekerjaan di bidang pengadaan barang dan pemborong pekerjaan dibidang jasa pemerliharaan dan perbaikan serta jasa konsultasi yang dalam melaksanakan pekerjaannya mempekerjakan pekerja/buruh kurang dari 10 (sepuluh) orang.
SYARAT LAIN:
- MEMPUNYAI PERLINDUNGAN DAN SYARAT-2 KERJA YANG MINIMAL SAMA DENGAN PERUSAHAAN PEMBERI KERJA ATAU SESUAI DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU;
- HUBUNGAN KERJANYA DIATUR DALAM PERJANJIAN KERJA ANTARA PERUSAHAAN PEMBORONG ATAU PENYEDIA JASA DENGAN PERUSAHAAN PEMBERI KERJANYA;
- BILA PERSYARATAN PENYERAHAN PEKERJAAN (1-4) TIDAK TERPENUHI, MAKA HUBUNGAN KERJA, Batal
Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka demi hukum hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan penerima pekerjaan beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan perusahaan langsung dengan proses produksi adalah kegiatan diluar kegiatan pokok usaha (core business) suatu perusahaan. Kegiatan tersebut misalnya : kegiatan penyediaan makanan bagi pekerja/buruh (catering service) yang diserahkan kepada perusahaan catering; penyediaan angkutan pekerja/buruh yang diserahkan kepada perusahaan transportasi dan kegiatan-kegiatan lain yang tidak berhubungan langsung dengan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain wajib membuat alur kegiatan proses pekerjaan yang memuat kegiatan-kegiatan utama dan penunjang serta melaporkannya ke instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerajaan kabupaten/kota setempat.
Dalam pelaksanaannya perusahaan penerima pekerjaan dapat pula menyerahkan lagi sebagian pekerjaan yang diterima dari perusahaan pemberi pekerjaan ke perusahaan penerima pekerjaan lain yang tidak berbadan hukum. Dalam hal seperti ini apabila perusahaan penerima pekerjaan yang tidak berbadan hukum tersebut tidak memenuhi hak-hak pekerja/buruh atau syarat-syarat kerja dalam hubungan kerja, maka kewajiban tersebut beralih menjadi tanggung jawab perusahaan yang berbadan hukum. Oleh karena itu setiap perjanjian pemborongan pekerjaan wajib memuat ketentuan-ketentuan yang menjamin terpenuhinya hak-hak pekerja/buruh dalam hubungan kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Perusahaan dapat pula menggunakan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh untuk menyelesaian kegiatan-kegiatan tertentu di perusahannya. Dimaksud perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh adalah perusahaan berbadan hukum yang mempunyai kegiatan/usaha menyediakan jasa pekerja/buruh untuk dipekerjakan di perusahan pemberi kerja. Pekerja/ buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tidak boleh digunakan oleh perusahaan pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang langsung berhubungan dengan proses produksi. Kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi tersebut adalah kegiatan jasa penunjang seperti tenaga pengamanan (satpam); jasa pelayanan kebersihan (cleaning service); jasa pelayanan taman (gardening service); dan lain kegiatan yang tidak berhubungan dengan proses produksi.
Di bidang jasa penyediaan pekerja/buruh ini tidak terjadi hubungan kerja antara perusahaan pengguna jasa dengan pekerja/buruh yang melaksanakan pekerjaan yang diperjanjikan. Hubungan kerja yang terjalin adalah hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh. Oleh karena itu perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.
Tugas : Setelah memperoleh materi mahasiswa dapat menjelaskan :
1. Jelaskan pengertian pemborongan pekerjaan ?
2. Jelaskan posisi tawar pekerja Indonesia saat ini dengan adanya kebijakan pemborongan pekerjaan ?
3. Jelaskan hal yang melatar belakangi lahirnya kebiajkan pemborongan pekerjaan ?
4. Jelaskan dampak negatif bagi buruh dengan adanya kebijakan pemborongan pekerjaan ?
5. Jelaskan pembedaan pelaksanaan pemborongan pekerjaan di dalam negeri dan di luar negeri ?
6. Jelaskan bentuk-bentuk pekerjaan yang dapat dilakukan pemborongan pekerjaan ?
7. Jelaskan realitas pelaksaan pemborongan pekerjaan di Indonesia ?
PERTEMUAN KE VIII
PENEMPATAN TENAGA KERJA
TIK : Pada akhir perkuliahan mahasiswa diharapkan mampu
1. menjelaskan asas dari penempatan tenaga kerja
2. menjelaskan ruang lingkup dari penempatan tenaga kerja
3. menjelaskan pembedaan pelaksanaan dari enempatan tenaga kerja
Pokok Bahasan : Penempatan Tenaga Kerja
Deskripsi Singkat : Dalam perkuliahan ini mahasiswa akan mempelajari asa penempatan tenaga kerja, ruang lingkup penempatan tenaga kerja, dan pembedaan pelaksanaan penempatan tenaga kerja
Penempatan tenaga kerja merupakan titik berat upaya penanganan masalah ketenagakerjaan. Terlebih Indonesia tergolong negara yang memiliki jumlah penduduk peringkat atas di dunia, sehingga Aenempatan angkatan kerja juga harus diatur sedemikian rupa dan secara terpadu. Untuk itu pemerintah berkewajiban memberikan pelayan penempatan tenaga kerja:
Pelayanan penempatan tenaga kerja adalah kegiatan untuk mempertemukan tenaga kerja dan pemberi kerja agar tenaga kerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya serta pemberi kerja memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan
ASAS PENEMPATAN TENAGA KERJA
Prinsip penempatan tenaga kerja bahwa setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri (Pasal 31 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan). Jadi, menurut ketentuan ini jelas tidak boleh ada perlakuan diksriminasi dalam bentuk apa pun. Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas-asas:
1. Terbuka
Adalah pemberian informasi kepada pencari kerja secara jelas, antara lain, jenis pekerjaan, besarnya upah, dan jam kerja. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi pekerja/buruh serta untuk menghindari terjadinya perselisihan setelah tenaga kerja ditempatkan.
2. Bebas
Adalah pencari kerja bebas memilih jenis pekerjaan clan pemberi kerja bebas memilih tenaga kerja, sehingga tidak ada pemaksaan satu sama lain.
3. Objektif
Adalah pemberi kerja agar menawarkan pekerjaan yang cocok kepada pencari kerja sesuai dengan kemampuan clan persyaratan jabatan yang dibutuhkan, serta harus memperhatikan kepentingan umum dengan tidak memihak kepentingan pihak tertentu.
4. Adil dan Setara Tanpa Diskriminasi
Adalah penempatan tenaga kerja dilakukan berdasarkan kemampuan tenaga kerja clan tidak berdasarkan atas ras, jenis kelamin, warna kulit, agama, dan aliran politik. Selanjutnya, menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 4 Tahun 1970, pengertian pengerahan tenaga kerja ialah:
"Tiap perbuatan yang dilakukan dengan tujuan supaya orang mengadakan perjanjian kerja untuk dipekerjakan, baik di dalam maupun di luar Indonesia, atau pelbagai bidang kegiatan ekonomi atau sebagai seniman/olahragawan atau tenaga ilmiah. "
Sasaran penempatan tenaga kerja adalah untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, clan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi, dan perlindungan hukum (Pasal 32.ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan). Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 4 Tahun 1970 menegaskan bahwa pengerahan tenaga kerja dilarang bila tidak ada izin tertulis dari Menteri Tenaga Kerja atau pejabat yang ditunjuknya. Dalam Pasal 4 mengatur bahwa bagi pelanggar Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3), clan ayat (4) dikenakan sanksi berupa hukuman kurungan tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rpl 00.000,00.
RUANG LINGKUP PENEMPATAN TENAGA KERJA
Menurut ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa ruang lingkup penempatan tenaga kerja meliputi:
1. Penempatan tenaga kerja di dalam negeri, clan .
2. Penempatan tenaga kerja di luar negeri.
Penempatan tenaga kerja di dalam negeri meliputi Antar Kerja Lokal (AKAL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), clan Penempatan Tenaga Kerja Asing. Pengertian Antar Kerja adalah suatu proses kegiatan penempatan tenaga kerja yang meliputi pelayanan informasi pasar kerja (IPK), pendaf taran pencari kerja, pendaftaran lowongan pekerjaan, bimbingan clan penyuluhan jabatan, penempatan, clan dan tindak lanjut penempatan (Pasal 1 huruf d Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep-203/Men/1999).
Sedangkan penerripatan tenaga kerja di luar negeri dilakukan dengan cara mengirim tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Khusus mengenai penempatan tenaga kerja di luar negeri ini diatur tersendiri dengan undangundang, yakni Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempat
an clan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
Pengisian lowongan kerja harus diusahakan semaksimal mungkin berasal dari tenaga kerja setempat (lokal). Apabila ternyata karena berbagai hambatan clan alasan tenaga kerja setempat (lokal) tidak terpenuhi, maka di 'tempuh pengisiannya dari daerah-daerah atau negara lain, baik melalui mekanisme Antar Kerja Lokal (AKAL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), maupun penempatan tenaga kerja asing.
Dalam otonomi daerah ini pengisian lowongan kerja dengan menggunakan tenaga kerja lokal memerl.ukan kearifan pengusaha. Apabila tidak, dampaknya dapat menimbulkan masalah bagi pengusaha sendiri. Memang di satu sisi pengusaha dapat merekrut tenaga kerja dengan kualifikasi tertentu, di sisi lain terkadang kualifikasi yang ditetapkan tidak dapat dipenuhi oleh tenaga kerja lokal. Masalah ini tidak jarang dapat memicu tenagE kerja lokal untuk unjuk rasa, apabila tidak mendapatkan perhatian peng usaha.
1. Antar Kerja Lokal (AKAL)
Antar Kerja Lokal (AKAL) adalah antar kerja antar Kantor Departemer Tenaga Kerja dalam satu wilayah kerja Kantor Wilayah Departemer Tenaga Kerja2 (Pasal 1 huruf e Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomo Kep-203/Men/1999).
Contoh:
a. Kota Surabaya sebagai kota industri - andaikan kekurangan tenaga kerja - dengan pola AKAL menerima tenaga kerja dari kabupater kota di sekitarnya yang masih dalam satu wilayah Provinsi Jawa Timur (Lamongan, Tuban, Mojokerto, Malang, Lumajang, dan sebagainya).
b. Kabupaten Kutai Timur - andaikan kekurangan tenaga kerja dengan pola AKAL menerima tenaga kerja dari kabupaten/kota c sekitarnya yang masih dalam- satu wilayah Provinsi Kalimanta Timur (Samarinda, Bontang dan sebagainya).
Dasar hukum pelaksanaan AKAL ialah:
a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
b. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-04/Men/1970 tentang Pengerahan Tenaga Kerja.
c. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep-203/Men/1999 tentang Penempatan Tenaga Kerja di Dalam Negeri.
'
2. Antar Kerja Antar Daerah (AKAD)
Antar Kerja Antar Daerah (QKAD) adalah antar kerja antar Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja dalam wilayah Republik Indonesia (Pasal 1 huruf f Keputusan Menteri Tenaga Kerja clan Transmigrasi Nomor Kep-203/ Men/1999).
Mekanisme Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) merupakan upaya penyebaran tenaga kerja secara merata dalam rangka akselerasi pembangunan di daerah-daerah potensial sumber daya alam, tetapi kekurangan sumber daya manusia. Dalam praktik mekanisme Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) sering ditempuh oleh daerah yang memiliki sumber daya alam yang banyak, tetapi kekurangan sumber daya manusia.
Contoh di Provinsi Kalimantan Timur, mekanisme Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) ini banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang perkayuan clan kehutanan, termasuk program HTITrans Terpadu, menerima tenaga kerja dari-Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Bali clan sebagainya.
Dasar hukum pelaksanaan Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) ialah:
a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
b. Peraturan Menteri tenaga kerja Nomor Per-04/Men/1970 tentang Pengerahan Tenaga Kerja
c. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep- 203/Men/1999 tentang penempatan Tenaga Kerja di Dalam Negeri
d. Peraturan Menteri Perburuhan Nomor 11 Tahun 1959 tentang Antar Kerja Antar Daerah (AKAD)
e. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep-207/Men/1990 tentang Sistem Antar Kerja
3. Antar Kerja Antar Negara (AKAN)
Pengertian Antar Kerja Antar Negara (AKAN)3 adalah suatu mekanismE pengerahan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri untuk melakukan kegiat an ekonomi, sosial, clan budaya dalam jangka waktu tertentu berdasarkar perjanjian kerja.
Mengingat tingginya angka populasi penduduk Indonesia, alternatif pe nyaluran clan penempatan tenaga kerja di samping mekanisme Antar KerjE Antar Daerah (AKAD) juga ditempuh mekanisme Antar Kerja Antar Negarc (AKAN). Persoalan yang sering timbul dalam mekanisme AKAN adalaF rendahnya kualitas tenaga kerja kita, baik dalam hal pendidikan, keahliar maupun keterampilannya. Oleh sebab itu, sebelum calon tenaga kerja di kirim ke luar negeri, terlebih dahulu diberikan pelatihan-pelatihan sesua dengan kualifikasi jabatan/pekerjaannya.
Mekanisme Antar Kerja Antar Negara (AKAN) di samping ditempuh se bagai upaya perluasan lapangan kerja ke luarnegeri (Manulang, 1995 43), minimal harus memperoleh manfaat:
a. Mempererat hubungan antarnegara (negara pengirim clan negar penerima).
b. Mendorong terjadinya peningkatan pengalaman kerja clan ali teknologi.
c. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja clan keluarganya.
d. Meningkatkan pendapatan di dalam neraca pembayaran negara (devisa).
Dasar hukum pelaksanaan Antar Kerja Antar Negara (AKAN) ialah:
a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
c. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-04/Men/1970 tentang , Pengerahan Tenaga Kerja.
d. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep-204/Men/1999 tentang PenempStan Tenaga Kerja ke Luar Negeri jo. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep-138/Men/2000 tentang Perubahan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep-204/Men/ 1999 tentang Penempatan Tenaga Kerja ke Luar Negeri.
e. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep-207/Men/1990 tentang Sistem Antar Kerja.
f. Keputusan Dirjen Binapenta Nomor Kep-15/BP/1995 tentang Petunjuk Teknis Penempatan Tenaga Kerja ke Luar Negeri.
4. Penempatan Tenaga Kerja Asing
Pengertian tenaga kerja asing adalah warga Negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja diwilayah Indonesia (Pasal 1 angka 13 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan). Sedangkan menurut Budiono (1995 : 259) pengertian tenaga kerja asing adalah tiap orang bukan warga Negara Indonesia yang mampu melakukan pekerjaan, baik didalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Dari pengertian di atas bahwa kendatipun orang tersebut bukan orang warga negara Indonesia dan berada di Indonesia, tetapi tidak bermaksud bekerja di wilayah Indonesia, maka ia bukanlah tenaga kerja asing
Beberapa prinsip penempatan atau penggunaan tenaga kerja asing yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah:
a. Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk (Pasal 42 ayat (1)). Hal ini dimaksudkan agar penggunaan tenaga kerja asing dilakukan secara selektif dalam rangka optimalisasi pendaya gunaan tenaga kerja Indonesia.
b. Pemberi kerja orang perseorangan dilarang mempekerjakan tenag; kerja asing (Pasal 42 ayat (2)).
c. Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalar hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu (Pasal 4; ayat (4)). Ketentuan mengenai jabatan tertentu dan waktu tertenti akan diatur melalui keputusan menteri.
d. Tenaga kerja asing yang masa kerjanya habis clan tidak dapat dipei panjang, dapat digantikan oleh tenaga kerja asing lainnya (Pasal 4; ayat (6)).
e. Pemberi kerja yang menggunakan tenaga kerja asing harus memiliN rencan penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan ofel menteri atau pejabat yang ditunjuk (Pasal 43 ayat (1)).
f. Rencana penggunaan tenaga kerja asing (Pasal 43 ayat (2)) minl mal memuat keterangan:
1) Alasan penggunaan tenaga kerja asing;
2) Jabatan dan/atau kedudukan tenaga kerja asing dalam struktu organisasi perusahaan yang bersangkutan;
3) Jangka waktu penggunaan tenaga kerja asing; dan
4) Penunjukan tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai pendamping tenaga kerja asing yang dipekerjakan.
g. Pemberi kerja tenaga kerja asing wajib menaati ketentuan mengen, jabatan dah,standar kompetensi yang berlaku (Pasal 44 ayat (1)J Ketentuan mengenai jabatan clan standar kompefensi akan thatu dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja.
Pengertian standar kompetensi adalah kualifikasi yang harus dimiliN oleh tenaga kerja asing, antara lain pengetahuan, keahlian, ke terampilan di bidang tertentu, clan pemahaman budaya Indonesia.
h. Pemberi kerja tenaga kerja asing (Pasal 45 ayat (1)) wajib:
1) Menunjuk tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai tenaga pendamping tenaga kerja asing yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian;
2) Melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja warga negara Indonesia pendamping sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki tenaga kerja asing.
i. Ketentuan butir h tidak berlaku bagi tenaga kerja asing yang menduduki jabatan direksi dan/atau komisaris (Pasal 45 ayat (2)).
j. Tenaga kerja asing dilarang menduduki jabatan yang mengurusi personalia dan/atau jabatan-jabatan tertentu (Pasal 46 ayat (1)). Ketentuan mengenai jabatan-jabatan akan diatur melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja.
k. Pemberi kerja tenaga kerja asing wajib membayar kompensasi atas
setiap tenaga kerja asing yang dipekerjakan (Pasal 47 ayat (1)):
setiap tenaga kerja asing yang dipekerjakan (Pasal 47 ayat (1)):
1) Kewajiban membayar kompensasi tersebut tidak berlaku bagi instansi pemerintah, perwakilan tenaga kerja asing, badanbadan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan-jabatan tertentu di lembaga pendidikan (Pasal 47 ayat (2)).
2) Ketentuan mengenai jabatan-jabatan tertentu di lembaga pendidikan diaturdengan keputusan menteri (Pasal 47 ayat (3)).
3) Ketentuan mengenai besarnya kompensasi dan penggunaannya diatur dengan peraturan pemerintah (Pasal 47 ayat (4)).
l. Pemberi keda wajib memulangkan tenaga kerja asing ke Negara asafnya setelah hubungan kerja berakhir (Pasal 48).
Pasal 2 ayat (3) butir 9 dan Pasal 3 ayat (5) butir 8 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Dtonom, menempatkan pemerintah (= pusat) *n pemerintah provinsi hanya memiliki kewenangan terbatas dalam jbidang ketenagakerjaan. Dengan demikian, pemerintah kabupaten/kota 1!emiliki kewenangan sangat luas, termasuk di dalamnya kewenangan mengatur dan mengawasi penempatan tenaga kerja asing berdasarkar kebutuhan di daerah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 20029 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota, disebutkan bahwE kewenangan kabupaten/kota dalam penggunaan Tenaga Kerja Wargz Negara Asing Pendatang (TKWNAP) meliputi:
a. Penelitian kelengkapan persyaratan perizinan;
b. Analisis jabatan yang akan diduduki oleh tenaga kerja asing
c. Pengecekan kesesuaian jabatan dengan position list tenaga kerj, asing yang dikeluarkan oleh Depnaker;
d. Pemberian perpanjangan izin;
e. Pemantauan pelaksanaan kerja tenaga kerja asing; dan f. Pemberian rekomendasi IKTA.
Dasar hukum pengaturan penempatan tenaga kerja asing adalah:
a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
b. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1968 tentang Pengawasan ter hadap Kegiatan Warga Negara Asing yang Melakukan Pekerjaai Bebas di Indonesia.
c. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 tentang Penggunaai Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang.
d. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-04/Men/1984 tentani Rencana Penggunaan Tenaga Kerja dan izin Mempekerjakai Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang.
e. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-03/Men/1990 tentan~ Pemberian izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asin Pendatang.
f. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep-416/Men/1990 tentan, Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomc Per-03/Men/1990 tentang Pemberian izin Mempekerjakan Tenag, Kerja Warga Negara Asing Pendatang
g. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-228 Men/2003 tentang Tata Cara Pengesahan Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
h. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-20/ Men/2004 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
i. Keputusan Menteri Tenaga Kerja clan Transmigrasi Nomor Kep-21/ Men/III/2004 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagai Pemandu Nyanyi/Karaoke.
j. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per-02/ Men/X11/2004 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja Asing.
k. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor SE-04/Men/1992 tentang Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang untuk Pekerjaan yang Bersifat Sementara clan Mendesak
l. .Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep-1 73/Men/2000 tentang Jangka Waktu izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang.
m. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten clan Kota.
Tugas : Setelah memperoleh materi mahasiswa dapat menjelaskan :
1. Jelaskan pengertian penempatan tenaga kerja ?
2. Jelaskan asa-asas penempatan tenaga kerja ?
3. Jelaskan ruang lingkup penempatan tenaga kerja ?
4. Jelaskan pembedaan pelaksanaan penempatan tenaga kerja ?
PERTEMUAN KE IX
ORGANISASI PENGUSAHA DAN SERIKAT KERJA
TIK : Pada akhir perkuliahan mahasiswa diharapkan mampu
1. menjelaskan pengerian dan fungsi organisasi pengusaha
2. menjelaskan pengertian serikat kerja
3. menjelaskan hal yang mlatarbelakangi dibentuknya serikat kerja
4. menjelaskan fungsi serikat kerja
5. menjelaskan prosedur pembentukan serikat kerja
Pokok Bahasan : Pengantar
Deskripsi Singkat : Dalam perkuliahan ini mahasiswa akan mempelajari pengertian dan fungsi organisasi pengusaha, pengerian serikat kerja, hal yang melatar belakangi dibentuknya serikat kerja, fungsi serikat kerja da prosedur pembentukan serikat kerja.
Organisasi Pengusaha
Organisasi pengusaha di Indonesia sebenarnya telah tumbuh sejak zaman misalnya Nederlandsche Indische Maatschappij Voor Nijverheid yang didirikan tahun 1853, Indische Lanbouw Genootschap didirikan tahun 1871 dan Kamers Van Koophandel en Nijverheid in Nederlandsche Indische didirikan tahun 1863. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi setelah proklamasi kemerdekaan, organisasi pengusaha tumbuh dan berkembang sangat pesat. Pada sektor-sektor atau bidang tertentu selalu dibentuk organisasi pengusaha misalnya organisasi pengusaha yang bergerak di bidang tekstil, sepatu, pulp dan kertas, konstruksi dan lain-lain. Keseluruhan organisasi pengusaha tersebut berafiliasi atau merupakan bagian dari Kamar Dagang dan Industri (KADIN) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1973.
Organisasi pengusaha yang bergerak di bidang sosial ekonomi termasuk ketenagakerjaan adalah Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO). Semula APINDO adadlah organisasi di bidang sosial ekonomi yang bernama Stichting Centraal Sociaal Werkgevers Overleg (SCCWO) yang kemudian namanya diubah menjadi Yayasan Badan Permusyawaratan Urusan Sosial Pengusaha di Indonesia (YBPUSPI) dengan Akta Notaris Raden Meester Soewandi Nomor 62 Tahun 1952. Melalui Musyawarah Nasional di Yogyakarta tahun 1982 YBPUSPI diubah menjadi Permusyawaratan Urusan Sosial Ekonomi Pengusaha Indonesia (PUSPI). Nama PUSPI kemudian diubah menjadi Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) pada Musyawarah Nasioanalnya di Surabaya tanggal 29-31 Januari 1985.
APINDO merupakan wakil pengusaha dalam Lembaga Kerja Sama Tripatit, sebuah wadah kerja sama antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh yang bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah sosial ekonomi terutama di bidang ketenagakerjaan dan dibentuk pada tanggal 1 Mei 1968. Kegiatan-kegiatan APINDO antara lain adalah advokasi kepada anggota, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia Indonesia khususnya di bidang ketenagakerjaan dan hubungan industrial. Dalam menjalankan aktivitasnya APINDO juga menjalin kerja sama dengan mitranya, baik dari dalam maupun dari luar negeri.
Serikat Pekerja/Serikat Buruh
Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh, baik di perusahaan maupun di luar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya. Serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan adalah serikat pekerja/serikat buruh yang didirikan oleh para pekerja/buruh di perusahaan atau di beberapa perusahaan, sedang yang di luar perusahaan adalah serikat pekerja/serikat buruh yang didirikan oleh para pekerja/buruh yang tidak bekerja di perusahaan misalnya serikat pekerja/buruh pengemudi angkutan kota atau pembantu rumah tangga.
Serikat pekerja/serikat buruh bersifat bebad berarti sebagai organisasi dalam melaksanakan hak dan kewajiban, serikat pekerja/serikat buruh tidak berada di bawah pengaruh atau tekanan dari pihak lain. Terbuka berarti dalam menerima anggota dan/atau memperjuangkan kepentingan pekerja/buruh tidak membedakan aliran politik, agama, suku bangsa, dan jenis kelamin. Bersifat mandiri maksudnya dalam menjalankan dan mengembangkan organisasi ditentukan oleh kekuatan sendiri tidak ditentukan oleh pihak lain di luar oranisasi. Demokratis yaitu bahwa dalam pembentukan organisasi, pemilihan pengurus, memperjuangkan dan melaksanakan hak dan kewajiban organisasi dilakukan sesuai dengan prinsip demokrasi. Bertanggung jawab berarti bahwa dalam mencapai tujuan dan melaksanakan hak dan kewajibannya, serikat pekerja/serikat buruh bertanggung jawab kepada anggotanya, masyarakat, dan negara.
Tujuan didirikan serikat pekerja/buruh adalah untuk memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya. Guna mencapai tujuan tersebut serikat pekerja/buruh mempunyai fungsi :
a. sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
b. sebagai wakil pekerja/buruh dalam lembaga kerja sama di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya;
c. sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d. sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya;
e. sebagai perencana, pelaksana, dan penanggung jawab pemogokan pekerja/buruh sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
f. sebagai wakil pekerja/buruh dalam memperjuangkan kepemilikan saham perusahaan.
Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 menggunakan istilah serikat pekerja/serikat buruh bukan serikat pekerja atau serikat buruh saja. Kedua istilah tersebut sebenarnya sama dan tidak ada perbedaan. Judul semula yang diajukan Presiden ke DPR melalui suratnya No. R.01/PU/I/2000 adalah RUU tentang Serikat Pekerja. Dalam proses pembahasan di DPR penggunaan istilah serikat pekerja disetujui menjadi serikat pekerja/serikat buruh. Penggunaan kedua istilah tersebut dilakukan untuk mengadopsi keinginan dari berbagai organisasi pekerja/buruh yang menggunakan kedua istilah alternatif tersebut untuk menyebut nama organisasinya masing-masing.
Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 menganut multi union system yaitu memberikan kebebasan kepada pekerja/buruh untuk membentuk serikat pekerja/serikat buruh. Setiap 10 (sepuluh) orang pekerja/buruh menurut undang-undang tersebut telah dapat membentuk suatu serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan dapat memungkinkan terjadinya perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh yang biasanya menyangkut masalah keanggotaan yang akan berdampak pada posisi mayoritas sebuah serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan tersebut.
Diundangkannya UU No. 21 Tahun 2000 merupakan konsekuensi dari ratifikasi konvensi ILO (Internasional Labour Organization) No. 98 tentang dasat-dasar hak untuk berorganisasi dan berunding (Convention concerning the application of the principles of the right to organize and to bargain collectively) yang disahkan dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1956 pada tanggal 29 Agustus 1956 dan Konvensi ILO No. 87 tentang kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi. Materi kedua Konvensi ILO tersebut menjiwai seluruh isi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja/serikat buruh.
Kebebasan berorganisasi bagi pekerja/buruh yang dianut undang-undang ini sepenuhnya mengacu pada kebebasan berserikat yang dianut konvensi ILO tersebut yang berarti seorang pekerja dapat bergabung dengan serikat pekerja/serikat buruh mana saja yang disukai. Pekerja/buruh di perusahaan A tidaj wajib untuk menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan B sepanjang AD/ART serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan B tersebut membolehkan hal itu. Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 28 UUD 1945 yang menyatakan kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang dan ketentuan amandemen kedua UUD 1945 bab XA tentang hak asasi menusia pada pasal 28E ayat (3) yang menjamin hak setiap orang atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
1. Pendirian Serikat Pekerja/ Serikat Buruh
Serikat pekerja/serikat buruh dapat dibentuk oleh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) pekerja/buruh. Pembentukan serikat pekerja/serikat buruh adalah atas kehendak bebas dari pekerja/buruh tanpa tekanan atau campur tangan pengusaha, pemerintah, partai politik, atau pihak manapun. Setiap serikat pekerja/serikat buruh yang dibentuk harus memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang sekurang-kurangnya memuat :
b. nama dan lambang;
c. dasar, asas, dan tujuan;
d. tanggal pendirian;
e. tempat kedudukan;
f. keanggotaan dan kepengurusan;
g. sumber dan pertanggung jawaban keuangan; dan
h. ketentuan perubahan anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga.
Serikat pekerja/serikat buruh dapat dibentuk berdasarkan kesamaan sektor usaha, jenis usaha, atau lokasi tempat kerja dan dapat berafiliasi dengan serikat pekerja/serikat buruh internasional dan atau organisasi internasional lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
Undang-undang No. 21 Tahun 2000 memberi jaminan kepada pekerja/buruh untuk berorganisasi membentuk serikat pekerja/serikat buruh. Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota, dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh dengan cara :
a. melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi
b. tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/buruh
c. melakukan intimidasi dalam bentuk apapun
d. melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja/serikat buruh
Tindakan-tindakan tersebut menurut pasal 43 UU No. 21 Tahun 2000 dikategorikan sebagai kejahatan yang diancam pidana penjara minimal 1 (satu) tahun dan maksimal 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
2. Keanggotaan
Serikat pekerja/serikat buruh harus terbuka untuk menerima anggota tanpa membedakan aliran politik, agama, suku bangsa, dan jenis kelamin. Syarat untuk menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh biasanya telah ditetapkan dalam AD/ART serikat pekerja/serikat buruh bersangkutan tersebut. Seorang pekerja/buruh hanya dapat menjadi anggota pada 1 (satu) serikat pekerja/serikat buruh. Apabila ada pekerja dan ternyata menjadi anggota lebih dari 1 (satu) serikat pekerja/serikat buruh maka yang bersangkutan harus menyatakan secara tertulis untuk memilih salah satu serikat pekerja/serikat buruh yang diinginkan atau bahkan sama sekali tidak memilih salah satu diantaranya.
Pekerja/buruh yang menduduki jabatan tertentu dalam satu perusahaan dimana jabatan tersebut dapat menimbulkan pertentangan kepentingan antara perusahaan dengan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan diri sendiri maka pekerja/buruh yang menduduki jabatan tersebut dilarang menjadi anggota dan pengurus serikat pekrja/serikat buruh di perusahaan bersangkutan. Pekerja/buruh dimaksud adalah Manajer Sumber Daya Manusia personalia, dan Manajer Keuangan sebagaimana disepakati dalam perjanjian kerja bersama. Apabila pekerja/buruh tersebut ingin menjadi anggota dari suatu serikat pekerja/serikat buruh maka yang bersangkutan dapat membentuk atau menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh di luar perusahaan seperti misalnya serikat pekerja/serikat buruh yang beranggotakan Manajer Personalia dalam satu lokasi tertentu.
Pekerja/buruh yang ingin berhenti atau keluar dari keanggotaan suatu serikat pekerja/serikat buruh dapat melaksanakan keinginannya tersebut dengan cara memberikan pernyataan secara tertulis. Pekerja/buruh dapat pula diberhentikan dari suatu serikat pekerja/serikat buruh sesuai dengan AD/ART. Pekerja/buruh yang berhenti atau diberhentikan baik sebagai anggota maupun pengurus, tetap bertanggung jawab atas kewajiban-kewajiban yang belum dipenuhi terhadap serikat pekerja/serikat buruh dan terhadap pihak ketiga.
3. Pemberitahauan dan Pencatatan
Serikat pekerja/serikat buruh yang telah terbentuk harus memberitahukan secara tertulis kepada instasi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota setempat untuk dicatat dengan melampirkan :
a. daftar nama anggota pembentuk;
b. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
c. susunan dan nama pengurus.
Pencatatan serikat pekerja/serikat buruh ini merupakan perkembangan baru dalam kebebasan berserikat. Istilah semula dalam RUU adalah pendaftaran yang mendapat kritik dari berbagai kalangan masyarakat karena berkonotasi adanya campur tangan pemerintah dalam pembentukan serikat pekerja/serikat buruh. Keharusan mendaftar selalu dianggap sebagai usaha menghalangi atau mengurangi kemerdekaan berserikat.
Klausul pendaftaran/pencatatan atau pemberitahuan sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan sepanjang syarat untuk itu dibuat sesederhana mungkin. Apabila kita telaah pasal 15 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2000 yang hanya mensyaratkan pencatatan dengan melampirkan nama pembentuk/pendiri, AD dan ART serta susunan dan nama pengurus, jelas bahwa UU ini sangat memudahkan pelaksanaan hak berserikat bagi pekerja/buruh. Pencatatan bukan merupakan bentuk pengakuan (recognition) bagi serikat pekerja/serikat buruh karena keberadaan serikat pekerja/serikat buruh tentunya diakui sendiri oleh anggotanya sehingga tanpa dicatatpun serikat pekerja/serikat buruh tetap eksis bagi anggotanya. Pemberitahuan dan pencatatan adalah untuk kepentingan serikat pekerja/serikat buruh sendiri dan pihak lain yang berhubungan dengan serikat pekerja/serikat buruh tersebut.
Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota wajib mencatat dan memberikan nomor bukti pencatatan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal diterimanya pemberitahuan. Apabila syarat kelengkapan pencatatan belum terpenuhi maka instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan tersebut dapat menangguhkan pencatatan untuk paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan dengan memberitahukan kelengkapan yang harus dipenuhi. Apabila setelah 14 (empat belas) hari terlewati, serikat pekerja/serikat buruh bersangkutan masih belum melengkapi persyaratan yang belum terpenuhi maka berkas pemberitahuan dikembalikan ke serikat pekerja/serikat buruh bersangkutan dan tidak dilakukan pencatatan.
Apabila terjadi perpindahan domisili, maka pengurus serikat buruh harus memberitahukan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota dimana serikat pekerja/serikat buruh tersebut tercatat harus menghapus nomor bukti pencatatan dan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota tempat domisili baru serikat pekerja/ serikat buruh tersebut setelah menerima pemberitahuan pemindahan domisili harus mencatat dan memberikan nomor bukti pencatatan.
Buku pencatatan serikat pekerja/serikat buruh harus dapat dilihat setiap saat dan terbuka untuk umum. Setelah memperoleh nomor bukti pencatatan dari instansi yang berwenang maka pengurus serikat pekerja/serikat buruh harus memberitahukan secara tertulis keberadaannya kepada mitra kerjanya sesuai dengan tingkatannya. Serikat pekerja/serikat buruh yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan berhak untuk :
a. membuat perjanjian kerja bersama dengan pengusaha;
b. mewakili pekerja/buruh dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial;
c. mewakili pekerja/buruh dalam lembaga ketenagakerjaan;
d. membentuk lembaga atau melakukan kegiatan yang berkaitan dengan usaha peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh seperti mendirikan koperasi, yayasan, atau bentuk usaha lain;
e. melakukan kegiatan lain di bidang ketengakarjaan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Serikat pekerja/serikat buruh yang telah tercatat merupakan badan hukum di bidang ketenagakerjaan dan dapat mempunyai harta kekayaan sendiri terpisah dari harta pengurus dan anggotanya serta melakukan kegiatan usaha yang sah. Pemberian kesempatan kepada serikat pekerja/serikat buruh untuk melakukan kegiatan usaha dengan mendirikan koperasi, yayasan, atau bentuk usaha lain seperti ikut memiliki saham perusahaan dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan pekerja/buruh. Tujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan pekerja/buruh dapat dilakukan serikat pekerja/serikat buruh tidak hanya dalam hubungan kerja dengan pengusaha seperti meminta kenaikan upah tetapi dapat juga dilakukan dengan usaha-usaha lain yang bersifat mandiri.
Hak-hak serikat pekerja/serikat buruh tersebut dapat hilang atau dicabutr apabila nomor bukti pencatatan dicatbut oleh instansi yang berwenang di bidang ketenagakerjaan sebagai sanksi adminstratif terbukti :
a. jumlah pendiri kurang dari yang ditetapkan;
b. tidak malaporkan adanya bantuan dari luar negeri sebagaimana diharuskan;
c. tidak melaporkan perubahan AD dan ART dan perubahan pengurus kepada instansi pemerintah yang berwenang dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan tersebut.
Sedang kewajiban serikat pekerja/serikat buruh kepada anggotanya setelah memperoleh nomor bukti pencatatan adalah :
a. melindungi dan membela anggota dari pelanggaran hak-hak dan memperjuangkan kepentingannya;
b. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan anggota dan keluarganya;
c. mempertanggung jawabkan kegiatan organisasi kepada anggotanya sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
Agar dapat menjalankan roda organisasi dengan baik sesuai dengan fungsi dan tujuan maka pengusaha harus memberi kesempatan pengurus atau anggota serikat pekerja/serikat buruh untuk menjalankan kegiatan organisasi dalam jam kerja. Ketentuan dispensasi penggunaan jam kerja untuk menjalankan kegiatan serikat kerja/serikat buruh ini biasanya telah ditetapkan dalam perjanjian kerja bersama yang mengatur tentang :
a. jenis kegiatan yang diberi kesempatan;
b. tata cara pemberian kesempatan;
c. pemberian kesempatan yang mendapat upah dan yang tidak mendapat upah.
4. Keuangan dan Harta Kekayaan
Keuangan serikat kerja/serikat buruh bersumber dari :
a. iuran anggota yang besarnya ditetapkan dalam AD dan ART;
b. hasil dari usaha yang sah;
c. bantuan dari anggota atua pihak lain yang sah.
Apabila bantuan dari pihak lain tersebut berasal dari luar negeri maka pengurus serikat pekerja/serikat buruh harus memberitahukan secara tertulis kapada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota di wilayah serikat pekerja/serikat buruh tersebut berdomisili dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari seteah bantuan tersebut diterima dan harus digunakan untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan anggota. Keuangan dan harta kekayaan serikat pekerja/serikat buruh harus terpisah dari keuangan dan harta kekayaan pengurus dan anggotanya. Apabila pengurus serikat pekerja/serikat buruh akan memindahkan atau mengalihkan keuangan dan harta kekayaan kepada pihak lain atau menginvestasikan dan atau melakukan suatu usaha maka hal tersebut dapat dilakukan sepanjang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Penggunaan dan pengelolaan keuangan dan harta kekayaan serikat pekerja/serikat buruh harus dibuatkan pembukuan dan dipertanggung jawabkan kepada anggota dalam laporan berkala yang diatur dalam AD dan ART.
5. Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh
Federasi serikat pekerja/serikat buruh adalah gabungan beberapa serikat pekerja/serikat buruh, sedang konfederasi serikat pekerja/serikat buruh adalah gabungan beberapa federasi serikat pekerja/serikat buruh. Federasi serikat pekerja/serikat buruh dapat dibentuk oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) serikat pekerja/serikat buruh. Sedang konfederasi serikat pekerja/serikat buruh dapat dibentuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) federasi serikat pekerja/serikat buruh. Semua ketentuan yang berlaku bagi serikat pekerja/serikat buruh adalah berlaku pula bagi federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh. Perbedaannya terletak pada keanggoaan dari masing-masing, pada serikat pekerja/serikat buruh anggotanya adalah pekerja/buruh sedang pada federasi anggotanya adalah serikat pekerja/serikat buruh, dan pada konfederasi anggotanya adalah federasi serikat pekerja/serikat buruh.
6. Pembubaran Serikat Pekerja/Serikat Buruh
Serikat pekerja/serikat buruh bubar apabila :
a. dinyatakan sendiri oleh anggotanya sesuai AD dan ART;
b. perusahaan dimana dibentuk serikat pekerja/serikat buruh tersebut ditutup atau menghentikan kegiatannya untuk selama-lamanya yang mengakibatkan terputusnya hubungan kerja dengan seluruh pekerja/buruh setelah hak-hak pekerja/buruh terpenuhi;
c. dinyatakan bubar dengan putusan pengadilan.
Pengadilan dapat memutuskan untuk membubarkan serikat pekerja/serikat buruh setelah ada gugatan dari instansi pemerintah apabila serikat pekerja/serikat buruh tersebut mempunyai asas yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 atau apabila pengurus dan/atau anggota atas nama serikat pekerja/serikat buruh terbukti melakukan kejahatan terhadap keamanan negara dan dijatuhi pidana minimal 5 (lima) tahun penjara. Gugatan untuk membubarkan serikat pekerja/serikat buruh karena pengurus dan/atau anggota tesangkut masalah pidana tersebut baru dapat dilakukan setelah vonis hakim pada kasus pidana mempunyai kekuatan hukum tetap.
Setelah putusan pengadilan yang membubarkan serikat pekerja/serikat buruh tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap maka instansi pemerintah yang melakukan gugatan tersebut memberitahukan secara tertulis kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota dimana pemberitahuan tersebut akan dijadikan dasar dalam pencabutan nomor bukti pencatatan.
Pengurus atau anggota serikat pekerja/serikat buruh yang terbukti bersalah menurut keputusan pengadilan yang mnyebabkan serikat pekerja/serikat buruh dibubarkan tidak boleh lagi membentuk dan menjadi pengurus serikat pekerja/serikat buruh selama 3 (tiga) tahun sejak putusan pengadilan mengenai pembubaran serikat pekerja/serikat buruh mempunyai kekuatan hukum tetap. Ketentuan ini bukanlah untuk membatasi hak seseorang untuk berserikat tetapi dilandasi pemikiran untuk melindungi serikat pekerja/serikat buruh secara keseluruhan yaitu untuk mencegak orang yang kualitas mentalnya tidak baik mengendalikan serikat pekerja/serikat buruh yang dapat menjerumuskan serikat pekerja/serikat buruh kembali digugat untuk dibubarkan. Bubarnya serikat pekerja/serikat buruh tidak melepaskan secara para pengurus dari tanggung jawab dan kewajibannya baik terhadap anggota maupun pihak ketiga. Maksud ketentuan ini adalah tanggung jawab dalam bidang administrasi misalnya menyelesaikan pembukuan atau dokumen organisasi, membayar dan menyelesaikan utang piutang, dan sebagainya.
Tugas : Setelah memperoleh materi mahasiswa dapat menjelaskan :
1. Jelaskan pengertian organisasi pengusaha ?
2. Jelaskan fungsi dari organisasi pengusaha ?
3. Jelaskan pengertian serikat kerja ?
4. Jelaskan hal yang melatar belakangi lahirnya serikat kerja ?
5. Jelaskan fungsi serikat kerja ?
6. Jelaskan prosedur pembentukan serikat kerja ?
7. Jelaskan keanggitaan dari serikat kerja
PERTEMUAN KE X
TENAGA KERJA INDONESIA (BURUH MIGRAN)
TIK : Pada akhir perkuliahan mahasiswa diharapkan mampu
1. menjelaskan sejarah pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luarn negeri
2. menjelaskan pengertian TKI
3. menjelaskan prosedur penempatan TKI
4. menjelaskan realitas permasalahan yang dihadapi TKI
Pokok Bahasan : Tenaga Kerja Indonesia
Deskripsi Singkat : Dalam perkuliahan ini mahasiswa akan mempelajari serah pengiriman.TKI ke luar negeri, pengertian TKI, prosedur penempatan TKI dan realitas permasalahan yang dihadapi TKI dalam proses penempatan.
Sejarah Pengiriman Buruh Migran
Setiap manusia berhak untuk bebas berpindah atau bermigrasi untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Alasan utama setiap orang untuk melakukan migrasi adalah untuk memperoleh standart hidup yang lebih baik dari yang sebelumnya.[1]
Dalam pada itu saat ini Indonesia merupakan salah satu negara asal buruh migran yang penting di kawasan Asia, baik karena jumlah buruhnya yang besar, upahnya yang rendah, sikap penurutnya, maupun berbagai permasalahan yang sering timbul karenanya.[2]
Secara makro hal yang sering melatar belakangi para pihak untuk melakukan migrasi adalah jumlah lapanagan pekerjaan yang tersedia sangatlah terbatas, ini berbanding terbalik dengan jumlah tenaga kerja yang tersedia. Oleh karena itu yang terjadi di lapangan adalah terjadinya penumpukan tenaga kerja atau pengangguran.
Kesempatan kerja saat ini merupakan suatu kebutuhan yang mendesak, bukan hanya bagi kepala keluarga, tetapi juga bagi istri dan anak mereka yang telah dewasa. Terjadinya krisis ekonomi akhir-akhir ini juga dianggap sebagai pemicu semakin memingkatnya jumlah pengangguran dan mencari kesempatan kerja ke luar negeri diharapkan sebagai salah satu alternatif pemecahannya di sektor informal.[3]
Pada dasarnya pengiriman tenaga kerja ke luar negeri telah dilakukan sejak zaman Hindia Belanda dengan sistem “koch kontrac” antara lain ke Suriname. Namun pengiriman tenaga kerja yang demikian itu terhenti pada masa perjuangan dan masa kemerdekaan. Pada sekitar tahun-60 an mobilitas tenaga kerja dimulai lagi dengan kurangnya tenaga kerja di “Perusahaan Kayu” di Sumatra dan Kalimantan yang merupakan cikal bakal pengiriman tenaga kerja ke Malaysia, Brunei Darussalam dan Singapura.[4] Berbeda dengan pengiriman pada tahun 60 an, pengiriman tenaga kerja saat ini ternyata lebih didorong oleh adanya tekanan akan keterbatasan peluang kerja saat ini ternyata lebih didorong oleh adanya tekanan akan keterbatasan peluang kerja dan kebutuhan ekonomi keluarga (kemiskinan).
Gejala migrasi internasional pekerja yang terjadi sejak tahun 1970 ada kaitannya dengan rasional ekonomi yang bermotivasi pada perbaikan kondisi kehidupan. Inipun ditunjang dengan kebijakan Pemerintah saat itu yang tertumpu pada pembangunan sektor ekonomi.Hal yang demikian itu telah menyebabkan corak kehidupan yang timpang antara masyarakat kota dan masyarakat desa. Ketimpangan inilah yang membuat masyarakat desa dengan standart pendidikan yang rendah melakukan migrasi ke negara lain pada sektor-sektor informal dengan gaji yang jika diukur dengan nilai rupiah kita sangatlah tinggi,[5] namun apabila diukur dengan standart yang ada di negara tempat mereka bekerja buruh migran Indonesia mendapatkan upah yang terendah.
Awal booming pengiriman buruh migran ke luar negeri yang terjadi pada tahun 1970, yaitu dikirim ke Timur Tengah, lebih didominasi oleh buruh migran laki-laki. Namun pada tahun 1974-1979 jumlah buruh migran Indonesia mulai didominasi oleh kaum perempuan.. Jumlah buruh migran perempuan Indonesia selama ini terbesar bekerja pada sektor-sektor informal, yaitu sebagai pembantu rumah tangga. Sementara dari data yang didapatkan dari Keduataan Indonesia di Jeddah menunjukkan komposisi buruh migran Indonesia adalah 7 % laki-laki, 97 % perempuan dengan perbandingan 1:13.[6]
Pengertian Tenaga Kerja Indonesia
Berawal dari paradigma pengiriman buruh migran Indonesia yang selanjutnya dapat kita tarik suatu pengertian tentang pengertian buruh migran. Pengertian tenaga kerja atau buruh migran adalah seperti apa yang disebutkan dalam Konvensi PBB No. 86 Tahun 1990 tentang Perlindungan Terhadap Pekerja Migran dan Keluarganya, yaitu : [7]
“A migrant worker is a person who is be enganged or has been enganged in a remunarated activity in a state of which he or she is not national “
Pengertian buruh migran menurut Philippus adalah buruh yang berwarganegara Indonesia
Sedangkan pengertia TKI menurut ketentuan UU No. 39 Tahun 2204 tentangPenempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri pada pasa 1 ayat 1berbunyi, Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut TKI adalah setiap warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 4 Tahun 1970, pengerahan tenaga kerja adalah usaha pemenuhan kebutuhan tenaga kerja antar daerah dengan cara memindahkannya antar daerah, yaitu daerah yang kelebihan tenaga kerja ke daerah yang kekurangan tenaga kerja. Kebijakan ini berlaku pula untuk pengerahan tenaga kerja ke luar negeri dan sekaligus membuktikan legitimasi dan pelegalan usaha pengiriman tenaga kerja.[9]
Dalam konteks UU No. 39 Tahun 2004 tidak lagi menyebut istilah pengerahan melainkan penempatan. Berdasar pasal 1 ayat 4 penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai bakat, minat dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai kenegara tujuan, dan pemulangan dari Negara tujuan.
Pengerahan dan penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri, secara prosedural terdiri atas : [10]
1. Pelaksanaa Penempatan Tenaga Kerja
Adapun lembaga pelaksana penempatan tenaga kerja (Pasal 6 Permenaker Nomor PER-104 A/MEN/2002) terdiri dari : [11]
a. PJTKI
b. Instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang penempatan TKI ke luar negeri
2. Badan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BP2TKI)
Badan ini merupakan unit pelaksana teknis pemerintah pusat di daerah yang melaksanakan sebagian kegiatan penempatan tenaga kerja ke luar negeri.. Adapun kegiatannya meliputi :
a. Pra penempatan tenaga kerja
b. Pada saat penempatan tenaga kerja
c. Purna penempatan tenaga kerja
d. Penunjang usaha keberhasilan jasa tenaga kerja Indonesia
e. Penunjang upaya peningkatan profesionalitas
3. Tugas, hak dan Kewajiban
Lembaga pelaksanaan penempatan tenaga kerja melaksanakan tugas kegiatan penempatan tenaga kerja sesuai dengan proses antar kerja.
a. Hak (Pasal 11 Per-02/MEN/1994)
b. Kewajiban (Pasal 12 Per-02?MEN/1994)
Dari keseluruhan proses penempatan tenaga kerja ke luar negeri, maka pihak-pihak yang terkait dalam hal ini adalah :
1. Pihak PJTKI dalam hal ini masih memiliki kepanjangan tangan yang berada di desa basis penyedia TKI yang disebut sponsor
2. Departemen Tenaga kerja
3. BP2TKI
4. Kantor Imigrasi
5. Departemen Luar Negeri atau Perwakilan RI
Dalam UUD 1945 sendiri pada pasal 27 ayat 2 menyatakan “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” demikian juga dengan hasil amandemen UUD 1945. Dari sini terlihat bahwa negara berkewajiban untuk menyediakan pekerjaan bagi warganegaranya guna pencapaian kehidupan yang layak.
Prosedur dan Realitas Permasalahan TKI
Secara realitas uasha proses pengiriman buruh migran ini adalah tindakan dalam proses ini terkait pihak PJTKI, Depnaker dan BP2TKI secara keseluruhan tata cara pengiriman buruh migran adalah

Adapun prosedur pengiriman buruh migran adalah terdiri atas :
1. Pra pemberangkatan
a. Motivasi
b. Pendaftaran
c. Penggunaan surat-surat
d. Dalam penampungan
¨ Pemeriksaan kesehatan
¨ Pendidikan dan pelatihan
¨ Penandatanganan kontrak
¨ Keadaan selama di penampungan
2. Selama di negara tujuan atau masa kerja
3. Purna pemberangkatan
Dalam keseluruhan proses mulai dari pra pemberangkatan sampai dengan purna pemberangkatan, maka kasus yang selama ini menimpa para buruh migran adalah :
1. Pra pemberangkatan
a) Pemberian informasi yang bersifat tidak jujur, yaitu hanya memberikan informasi tentang para buruh migran yang telah berhasil saja.
b) Banyaknya terjadi kasus pemalsuan identitas, ini dilakukan oleh pihak sponsor berkaitan dengan usia dan pendidikan terakhir TKI.
c) Pemberian pinjaman uang oleh para pihak sponsor dengan pengenaan bunga yang cukup tinggi, ini terjadi karena banyak TKI yang ingin bekerja, namun tidak memiliki uang untuk biaya keberangkatannya.
d) Terjadinya tindakan pelecehan seksual selama pemeriksaan kesehatan yang dilakukan pada saat di lokasi penampungan.
e) Terjadinya tindakan pelecehan seksual (diminta berhubungan badan dengan petugas) agar cepat ditempatkan
f) Pemberian pendidikan dengan waktu yang singkat, sekitar 4 jam sehari berupa pendidikan bahasa yang bersifat formal semata. Karena kebanyakan waktu bagi TKI yang berada di lokasi penampungan dihabiskan untuk mengerjakan pekerjaan bersifat domestik saja, seperti membersihkan lokasi penampungan dan memasak.
g) Keadaan selama di penampungan yang tidak manusiawi, seperti tempat tidur yang terbatas, kamar mandi yang jumlahnya sedikit dan makanan yang diberikan bersifat alakadarnya saja. Karena keadaan yang tidak manusiawi ini, maka keberadaan TKI seperti dalam keadaan penyekapan.
h) Pembebanan biaya pada calon buruh migran selama tinggal di penampungan.
i) Adanya larangan untuk pulang ke daerah asal, jadi bila calon TKI sudah berada di lokasi penampungan, maka mereka akan tetap disitu sampai diberangkatkan dan diisolasi dari lingkungan sekitarnya.
j) Ketidaktahuan para calon TKI tentang isi kontrak perjanjian (yang diketahui hanya jenis pekerjaan, lamanya kontrak dan jumlah gaji).
k) Tidak adanya batas waktu yang jelas mengenai sampai berapa lama calon buruh migran berada di penampungan.
2. Selama di negara tujuan atau masa kerja
Berbagai macam permasalahan dialami oleh buruh migran Indonesia selam bekerja di negara tujuan, untuk lebih mudah, maka akan didefinisikan sebagai berikut :
3. Purna pemberangkatan
a. Ancaman pemerasan yang dilakukan oleh aparat.
b. Pembayaran sejumlah uang pada agen untuk alasan yang tidak masuk akal, seperti memayar uang transport ke desa dengan jumlah yang besar.
Penempatan Tenaga Kerja ke Luar Negeri berdasarkan
KEPMENAKERTRANS NOMOR: KEP-104A/MEN/2002
Perusahaan jasa yang menempatkan TKI ke luar negeri.
Biaya Penempatan:
a) Biaya penempatan dibebankan kepada Pengguna dan atau Calon TKI/TKI
b) Komponen biaya penempatan (1) paspor; (2) pelatihan; (3) tes kesehatan; (4) visa kerja; (5) transportasi local; (6) akomodasi dan konsumsi; (7) tiket pemberangkatan; (8) asuransi TKI; (9) biaya pembinaan TKI; (10) company fee.
c) Dalam hal company fee tidak dibayar oleh pengguna, PJTKI dilarang untuk membebankan kepada TKI melebihi dari 1 (satu) bulan gaji.
d) Pembayaran biaya penempatan yang dibebankan kepada TKI dapat dilakukan secara tunai atau angsuran, kalau dilakukan dengan angsuran setiap bulan tidak boleh lebih dari 25% dari gaji yang diterima TKI.
Prosedur rekruting:
1. Siapa yang merekrut, prosedur merekrut. Kantor cabang hanya dapat: (a) melakukan penyuluhan dan pendataan calon TKI; (b) melakukan pendaftaran dan seleksi; (c) menyelesaikan kasus-kasus TKI pada tahap pra/purna penempatan.
2. Substansi penyuluhan kepada pencari kerja adalah: (a) penjelasan umum tentang program penempatan TKI; (b) prosedur dan mekanisme penempatan; (c) persyaratan.
3. Pendataan dilakukan oleh Petugas Kantor Cabang PJTKI kemudian dilaporkan kepada Kabupaten/Kota, kemudian kepada BP2TKI dan Dirjen.
4. Kantor Cabang PJTKI bersama-sama dengan Disnaker setempat melakukan rekrut yang meliputi pendaftaran dan seleksi Calon TKI. Setelah mendaftar Calon TKI harus mengikuti penyuluhan (oleh PJTKI, Disnaker dan Instansi terkait) yang substansinya antara lain: jenis kerja, syarat-syarat kerja, kondisi dan situasi negara tujuan dan tempat kerjanya, hukum, social budaya negara tujuan, hak dan kewajibannya, prosedur dan kelengkapan dokumen, biaya dan persyaratan (usia minimum, pendidikan –SLTP, dll.
5. Medical-test.
6. Calon TKI yang akan ditempatkan wajib mengikuti pelatihan pada BLK/lembaga pelatihan dan lulus uji ketrampilan untuk memperoleh sertifikasi kompetensi.
7. Uji ketrampilan tersebut dilakukan oleh Lembaga Uji Kompetensi Independen yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri (sebelum ada lembaga tersebut dapat diuji oleh lembaga pelatihan yang diakreditasi oleh instansi yang berwenang di bidang pelatihan kerja).
8. PJTKI dan atau Kantor Cabang bersama dengan Disnaker Kabupaten/Kota melaksanakan seleksi administrasi dan ketrampilan terhadap Calon TKI tersebut. Setelah lulus wajib menandatangani perjanjian penempatan. PJTKI dan atau Kantor Cabang mengajukan permohonan rekomendasi pembuatan paspor kepada Disnaker.
9. Sebelum pemberangkatan Calon TKI harus memahami isi dan menandatangani perjanjian kerja yang akan diberlakukan di negara tujuan bekerja di hadapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan atau pejabat yang Ditunjuk oleh BP2TKI daerah asal Calon TKI atau daerah embarkasi/keberangkatan TKIdan mempunyai (KTKLN) Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri yang berfungsi sebagai rekomendasi Bebas Fiskal Luar Negeri.
10. PJTKI wajib memberikan Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) sebelum diberangkatkan ke negara tujuan.
Masa Bekerja di negara Tujuan:
a) PJTKI wajib bertanggungjawab atas perlindungan dan pembelaan terhadap hak dan kewajiban TKI di luar negeri.
b) Dalam melaksanakan perlindungan dan pembelaan PJTKI secara sendiri-sendiri atau bersama-sama wajib menunjuk atau bekerjasama dengan Lembaga Perlindungan TKI yang terdiri dari Konsultan Hukum dan atau Lembaga Asuransi di negara tujuan bekerja.
c) Menunjuk atau bekerjasama tersebut harus dituangkan dalam perjanjian yang minimal memuat ketentuan: (1) menyelesaikan perselisihan; (2) memberikan konsultasi; (3) mengurus gaji TKI yang tidak dibayar; (4) mengurus hak-hak TKI yang di PHK; (5) mengurus jaminan kecelakaan kerja atau kematian; (6) menyelesaikan kerugian TKI non material.
d) PJTKI harus melaporkan perjanjian kerjasama tersebut kepada perwakilan RI setempat.
e) Kewajiban PJTKI yang lain: (1) mengurus TKI yang sakit, mengalami kecelakaan atau meninggal dunia; (2) melaporkan kepada Dirjen; (3) mengurus kepulangan.
f) Keharusan TKI menabung minimal 25% dari gaji sebulan.
g) PJTKI harus membantu kemudahan dan pengamanan atas hak dan kepentingan TKI dengan memperhatikan peraturan di negara tujuan.
Masa Pemulangan Kembali ke Daerah Asal:
1) PJTKI bekerjasama dengan Perusahaan Jasa di negara tujuan bekerja yang merupakan Mitra Usaha dan Perwalu wajib mengurus kepulangan TKI sampai di bandara di Indonesia.
2) PJTKI wajib memberitahukan jadwal kepulangan TKI kepada Perwakilan RI setempat dan Dirjen selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal kepulangan.
3) PJTKI wajib melaporkan setiap kepulangan TKI kepada Dirjen, BP2TKI dan Perwakilan RI yang tembusannya disampaikan kepada Disnaker daerah asal TKI.
Perpanjangan Kontrak:
1. Perpanjangan kontrak oleh TKI dan pengguna yang sama dapat dilakukan maksimum 2 (dua) tahun dengan isi kontrak yang minimal sama atau lebih baik.
2. Pengguna wajib menanggung: (a) biaya asuransi bagi TKI; (b) legalisasi perpanjangan kontrak; (c) company fee; (d) kompenasi cuti berupa tiket pulang pergi dan penggantian hak cuti 12 (dua belas) hari kerja.
3. PJTKI wajib mengurus dan menyelesaikan proses perpanjangan kontrak, dan bertanggung jawab atas kelanjutan penempatan TKI yang berangkutan serta melaksanakan perlindungan dan pembelaannya.
4. Perpanjangan kontrak harus ditandatangani oleh TKI dan Pengguna di hadapan serta dilegalisir oelh Pejabat Perwakilan RI
5. Bila TKI yang kontraknya habis masih tetap ingin bekerja di negara yang bersangkutan tetapi dengan pengguna yang baru, maka mengurusan dapat dilakukan oleh TKI sendiri atau PJTKI; bila pengurusan oleh TKI sendiri PJTKI dibebaskan dari tanggung jawab perlindungan dan pembelaan.
Tugas : Setelah memperoleh materi mahasiswa dapat menjelaskan :
1. Jelaskan sejarah pengiriman TKI ke luar negeri ?
2. Jelaskan pengertian TKI ?
3. Jelaskan prosedur resmi pengiriman TKI ?
4. Jelaskan para pihak yang berperan dalam proses pengiriman TKI ?
5. Jelaskan realitas permasalahan yang dihadapi TKI dalam proses penempatan ?
6. Jelaskan upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah terhadap TKI Indonesia ?
[1] Solidaritas Perempuan Ham Dalam Praktek, Panduan Melawan Perdagangan Perempuan Dan Anak, Jakarta, 2000, hal 13
[2] Data Depnaker , Maret 1998, jumlah buruh migran Indonesia yang bekerja di luar negeri sebanyak 1.049.627 orang , 66,7 % diantaranya adalah perempuan
[3] Majalah Tenaga Kerja, “Promosi Penempatan TKI di Timur Tengah”, Departemen Tenaga Kerja No 35 Agustus- November1998, hal 11
[4] Umu Hilmy, Pentingnya Undang-undangPerlindungan Buruh Migran Indonesia, Makalah, malang, Medio1999, hal 1
[5] Rusdi togaroa, Laporan hasil lapangan, Solidaritas Perempuan, 2000, hal 3
[6] Solidaritas Perempuan, op. cit. hal 141
[7] Sukamdi dkk, Labour Migrant in Indonesia Population Studies Center
[8] Phillipine Migrant Rights Work, 1997
[9] YLBHI, 1998
[10] darwan Prins, SH, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia , Citra Aditya Bhakti, Jakarta
[11] Ibid, hal 84