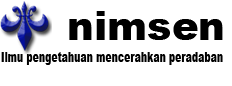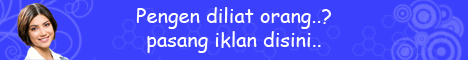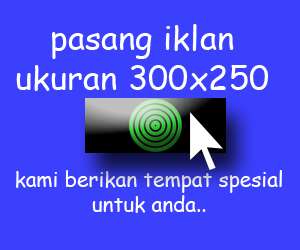HAK-HAK KEAGRARIAAN ADAT DALAM POLITIK HUKUM
AGRARIA INDONESIA ERA GLOBALISASI
(Studi kasus eks marga Benakat, Muara Enim, Sumatera Selatan)
Oleh:
Happy
Warsito
Dosen
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
___________________________________________________________________
Abstrak
: Sejak zaman kolonial hingga kini,
Hak-Hak Keagrariaan Adat kurang diakui keberadaannya. Selain itu, pengakuan
yang diberikan hanya sebatas potensi ekonomisnya sebagai asset yang dapat
dimanfaatkan semaksimal mungkin, bukan sebagai asset yang harus dikelola
sedemikian rupa dan dijaga kelestariannya. Bahkan, di Sumatera Selatan, dengan
dalih pembangunan rejim Orde Baru
mengambil hak-hak keagrariaan masyarakat adat untuk selanjutnya
diserahkan kepada para pengusaha baik nasional maupun asing dengan berbagai
hak, sebagaimana terjadi atas hak ulayat/tanah marga pada masyarakat hukum adat
eks Marga Benakat di Sumatera Selatan, yang selanjutnya dijadikan HTI, walaupun
tindakan tersebut ditentang oleh warga setempat serta LSM seperti LBH dan
Walhi.
Kata
Kunci : Hak-Hak Keagrariaan Adat; Politik Hukum; Globalisasi; Asset; Masyarakat
Hukum Adat.
Pendahuluan
HMN sebagai Lembaga Hukum baru yang
diintrodusir UUPA dinyatakan berasal dari Hak Ulayat Masyarakat / Persekutuan
Hukum Adat yang pada tingkatan tertinggi dijadikan hak
negara atas tanah sebagaimana dirumuskan pada pasal 2, adalah
cerminan pola politik hukum agraria nasional dan berfungsi sebagai pedoman dan
arah bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk bertindak di bidang
keagrariaan. Baerasarkan HMN negara mempunyai 3 (tiga) wewenang untuk mengatur:
1. Penggunaan, persediaan,
peruntukan dan pemeliharaan atas segala sumber keagrariaan atau
tata keagrariaan/ruang;
2. Hubungan hukum antara orang
dengan segala sumber keagrariaan atau hak-hak keagrariaan;
3. Hubungan hukum dan perbuatan
hukum antara orang tentang segala sumber keagrariaan atau transaksi keagrariaan.
Lebih lanjut,
Pasal 2 ayat 4 UUPA menentukan bahwa, pada pelaksanaannya HMN dapat dikuasakan
kepada daerah Swatantra dan Masyarakat Hukum Adat, sekedar diperlukan dan tidak
bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan Peraturan
Pemerintah. Hal ini senafas dengan rumusan Pasal 3 UUPA yang menentukan, bahwa dengan
mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak semacam itu
dari masyarakat-masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada,
harus sedemikian rupa, sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara
yang berdasar atas persatuan bangsa, serta tidak boleh bertentangan dengan
undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. Bahkan, pada pasal 5 UUPA ditegaskan bahwa
hukum yang berlaku atas segala sumber keagrariaan adalah hukum adat sepanjang
tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasar pada
persatuan bangsa serta mengindahkan unsur yang bersandar pada hukum agama misalnya wakaf. Namun sangat disayangkan
hingga saat ini pemerintah belum pernah mendelegasikan kewenangannya tersebut
kepada masyarakat hukum adat. Kondisi demikian mengakibatkan timbulnya berbagai
sengketa dan konflik agraria hampir di seluruh wilayah NKRI.
Pada
kenyataannya, pelaksanaan HMN sering ditafsirkan secara formal dan sempit. Formal dalam arti bahwa semua hak atas tanah
harus dibuktikan dengan alat bukti resmi yang tertulis terutama sertipikat hak atas tanah. Secara
sempit diartikan bahwa apabila tiada alat bukti resmi tertulis itu hak atas
tanah masyarakat tidak diakui. Penafsiran demikian tentunya
bertentangan dengan pasal 5 UUPA serta rasa keadilan masyarakat yang
berpandangan material dan luas. Material karena masyarakat kita belum seluruhnya mengenal alat bukti yang
tertulis sebagai bukti pemilikan hak atas tanah, sedangkan luas artinya
seseorang diakui memiliki sebidang tanah apabila dia nyata-nyata menguasai
sebidang tanah tersebut dan tidak tergantung pada alat bukti
tertulis atas penguasaan tanahnya. Sejak semula alat bukti hak atas tanah
berupa sertipikat tidak dikenal oleh masyarakat yang menafsirkan keadilan dalam penguasaan
sebidang tanah bukan dalam arti kepastian hukum seperti yang diminta oleh hukum barat, namun keseimbangan religio-magis antara dunia yang nyata dan dunia yang tidak
kelihatan
Uraian di atas
menunjukkna bahwa, nampaknya pemerintah berpikir secara abstrak dan lebih maju
dari rata-rata masyarakat pada umumnya, namun kurang memperhatikan pasal 5 UUPA yang menjelaskan bahwa hukum agraria yang
diberlakukan di seluruh wilayah republik Indonesia adalah hukum adat yang
sederhana sesuai dengan rasa keadilan masyarakat atas dasar cara berfikirnya masih sederhana
secara konkret. Dengan pandangan formal dan sempit, pemerintah pusat lewat
aparaturnya di daerah dapat secara
leluasa mengambil sumber keagrariaan masyarakat yang bernilai ekonomis tinggi dan
menyerahkannya pada pengusaha tanpa daya apa pun dari masyarakat, karena
masyarakat tentunya tidak dapat membuktikan haknya secara formal dengan
sertipikat hak atas tanah. Sedangkan pemerintah daerah tidak dapat berbuat
banyak dan lebih memihak pemerintah pusat, karena wewenang keagrariaan adalah
wewenang pemerintah pusat. Biasanya pemerintah daerah hanya berdalih
melaksanakan kebijakan pemerintah pusat.
Pengambilan tanah-tanah masyarakat adat
lebih diperparah lagi dengan diundangkannya Undang Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Kehutanan (yang
diperbarui dengan Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan) dan
Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Peraturan Pokok Pertambangan. Kedua
undang-undang tersebut tidak mencantumkan UUPA pada bagian menngingatnya, namun langsung mengacu pada pasal 33 Undang
Undang Dasar 1945. Hal demikian mengakibatkan sering terjadi ketumpangtindihan
pemberian hak keagrariaan atas sebidang tanah dari instansi yang terkait
seperti Badan Pertanahan Nasional ; Departemen Kehutanan, dan Departemen
Pertambangan yang mengakibatkan terjadinya sengketa atas sebidang tanah milik masyarakat yang dengan pandangan formal penguasa dapat
beralih kepada pengusaha. Semakin lemahnya kedudukan hak-hak agraria masyarakat
hukum adat/hak ulayat lebih diperparah dengan diundangkannya UU Nomor 5 Tahun
1979 tentang Pemerintahan Desa.
Di Sumatera
Selatan, sebagai pelaksanaan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Gubernur Sumatera
Selatan menghapuskan marga dan membentuk desa
dengan keputusannya Nomor 142/Kpts/III/1983. Penghapusan marga mengakibatkan terhapusnya
tanah ulayat yang dikenal dengan tanah marga. Penghapusan marga mengakibatkan
berubahnya dasar pengikatnya dari kesatuan genealogis menjadi administratif. Perubahan tersebut mengakibatkan masyarakat
yang pada masa pemerintahan marga mengerjakan tanah marganya sendiri
berubah menjadi perambah hutan secara
liar, karena tanah hutan di Sumatera Selatan seluas 5.343.058 hektar, dengan bebas
telah diberikan kepada pengusaha HPH
seluas 1.916.050 hektar, bahkan diperparah lagi dengan HTI yang memberikan hak atas tanah dengan
menebangi lahan yang ada dan menanami dengan tanaman industri.
Dalam satu
setengah tahun perjalanan Pelita VI telah diserap dana investasi sebesar 4,447
trilyun rupiah dari 41 proyek PMDN dan 9 proyek
Penanaman Modal Asing. Dari sektor perkebunan diketahui bahwa kepada
66 pengusaha perkebunan besar telah diberikan lahan seluas 1.409.092 hektar, sedangkan areal perkebunan rakyat hanyalah
seluas 1.045.044 hektar. Di sektor pertambangan diperkirakan
paling sedikit terdapat tiga buah perusahaan pertambangan besar dengan kuasa
pertambangan sekitar 500.000 hektar[1]. Sebagian besar hutan marga dikonversi
menjadi Hutan Produksi dan
diserahkan kepada pemegang HTI atau pengusaha perkebunan swasta[2]. Hal ini mengakibatkan timbulnya berbagai
sengketa tanah di Sumatera Selatan. Pada 1944, LBH Palembang mencatat 12 kasus,
dan pada 1995 kasus meningkat menjadi 18 kasus. Delapan dari 10 Dati II di Sumatera
Selatan mempunyai sengketa tanah, terbanyak dan krusial terjadi di Muara Enim. Pada 1998-1999 terjadi
peningkatan tajam menjadi 113 kasus pertanahan (Sumatera Ekspress dan Sriwijaya Post).
Persoalan berkisar pada: ketidakjelasan status tanah, pengambilan hak keagrariaan adat untuk
HTI, pembebasan hak keagrariaan adat secara paksa, kebakaran hutan rakyat dll.
Kajian terhadap
eksistensi hak-hak keagrarian adat dalam kaitannya dengan pelaksanaan politik
agraria di era globalisasi dan otonomi daerah menjadi sesuatu yang menarik,
karena fakta sejarah menunjukkan bahwa hak-hak keagrariaan adat di dalam masyarakat Indonesia sejak dulu
hingga sekarang dan masa yang akan datang mempunyai peranan penting dalam
menjamin kehidupan masyarakat, khususnya kesatuan masyarakat hukum adat,
sedangkan pada sisi lain pelaksanaan HMN; globalisasi perdagangan dunia yang
menuntut setiap negara untuk membuka diri bagi berbagai produk perdagangan dan
investasi akan terus mendesak hak-hak keagrarian masyarakat hukum adat. Kondisi
demikian mengharuskan para pembuat
kebijakan dalam politik hukum agrarianya memperhatikan hak-hak keagrariaan adat
dalam arus globalisasi dan era otonomi daerah ini.
Permasalahan
1. Bagaimanakah sesungguhnya keberadaan
hak-hak keagrariaan adat di dalam masyarakat Indonesia pada masyarakat eks
marga benakat ?
2. Apakah kedudukan hak-hak keagrariaan
adat ini telah diperhitungkan dalam politik hukum agraria kita ?
3. Mengapa pemerintah bersikap demikian dalam politik hukum agrarianya?
Tinjauan
Pustaka
Pada waktu kita
merdeka terkandung maksud untuk mempunyai hukum agraria nasional dan selama
belum ada digunakan kebijakan dan penafsiran baru. Eigendom dirasakan tidak
sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat karena terlalu bersifat individual dan
liberal. Karena itu, dikandung maksud untuk menghilangkannya dari muka bumi
Republik Indonesia dan sementara itu hak domein yang juga bersifat
individual-liberal itu ditafsirkan sebagai Hak Menguasai sebagai yang diatur di
dalam pasal 33 ayat 1 Undang Undang Dasar 1945 dan terdapat dalam hak menguasai
yang ada di tangan kepala persekutuan hukum adat.
Pada 24
September 1960 diundangkanlah Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria yang menurut diktum kelimanya dapat disebut
dengan Undang Undang Pokok Agraria. UUPA bermaksud mengadakan hukum agraria
nasional yang menurut pasal 5 nya adalah hukum adat sedangkan di dalam hukum
adat itu sendiri terdapat kebhinekaan. Dalam hukum adat, hanya dapat ditemukan
persamaan prinsip antara wilayah hukum adat[3]. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa
terdapat ‘bineka tunggal ika’ di dalam hukum agraria nasional ,[4] atau seperti yang dikatakan orang, adalah
adanya pluralisma hukum di dalam hukum agraria kita.
Uraian di atas memberi
pengertian, terjadinya perubahan terhadap eksistensi hak-hak keagrariaan adat
dalam politik hukum agraria. Jika pada zaman Hindia Belanda dikenal Hak Domein Negara berdasarkan Domein Verklaring. Dengan hak semacam
ini negara bertindak dalam lapangan hukum perdata: memiliki, sama dengan
warganya karena pandangan yang individual-liberal. Dengan konsep pemilikan ini,
negara dengan kelebihannya sebagai badan hukum publik dapat bertindak leluasa
karena milik adalah hak yang bersifat mutlak, tertinggi, dan tak dapat diganggu
gugat. Pada masa ini keberadaan hak-hak
keagrariaan adat hampir tidak diperhitungkan sama sekali.
Sedangkan sekarang kita
mengenal Hak Menguasai Negara yang dikatakan diangkat oleh negara sebagai
organisasi kekuasaan tertinggi dari hak menguasai yang terdapat pada masyarakat
hukum adat. Dengan konsep ini negara adalah manifestasi kekuasaan seluruh
rakyat sehingga negara itu, dari, oleh, dan untuk rakyat. Ditegaskan bahwa
hak-hak keagrariaan adat diakui keberadaannya. Hukum yang berlaku atas
sumber-sumber keagrariaan adalah hukum adat.
Dengan acuan kepada hukum adat ini diharapkan politik hukum agraria kita
dapat sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat.
Introduksi Hak
Pengusahaan Hutan dan Hutan Tanaman Industri telah banyak menguras isi hutan
milik persekutuan hukum adat dan mengundang konflik berkepanjangan. Pasal 6 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan
menyatakan bahwa hak-hak masyarakat hukum adat dan anggotanya untuk memungut
hasil hutan sepanjang kenyataannya masih ada perlu ditertibkan sehingga tidak
mengganggu pelaksanaan hak pengusahaan hutan. Bahkan di dalam ayat 3 ditegaskan
bahwa demi keselamatan umum di areal hutan yang sedang dikerjakan dalam rangka
pengusahaan hutan, pelaksanaan hak-hak rakyat untuk memungut hasil hutan
dibekukan.
Praktek pendesakan
hak-hak keagrariaan adat atau hak-hak asli masyarakat (indigenous rights) demi kepentingan ekonomi penguasa ini memang
banyak terjadi di negara-negara berkembang yang lambat laun akan menghilangkan
akses publik atas hak-hak tersebut dan
dalam kepustakaan dikenal dengan Tragedy
of the Commons yang dikemukakan oleh Garrett Hardin[5]. Beberapa contoh dapat dilihat sebagai
berikut: Di Filipina pemerintah jajahan Spanyol melakukan beberapa usaha untuk
mensistematisasikan hak milik di antaranya dengan menerbitkan hak-hak baru atas
tanah dengan kesombongan hukum baratnya yang memandang rendah hukum rakyat
setempat sehingga menyebabkan rakyat bersikap acuh tak acuh.[6] Keadaan diperburuk dengan adanya principalia (tuan tanah) yang menghaki
tanah bersebelahan dengan tanahnya ketika melakukan klaimnya. Hal ini lebih meningkat
pada waktu pemerintah jajahan Amerika menerapkan prosedur pendaftaran tanah
formal yang serupa dengan yang dilakukan di Amerika sendiri tanpa menghiraukan
ketidakmengertian rakyat yang tidak mengenal prosedur sedemikian dalam hukum
adatnya. Akibatnya banyak tanah rakyat yang diambil oleh para tuan tanah yang
melakukan prosedur formal yang benar dengan mengambil tanah rakyat yang
bersebelahan. Pengambil-alihan penguasaan sumber-sumber keagrariaan secara
besar-besaran terjadi pada kebijakan perikanan pemerintah di Papua Nugini.[7] Hal serupa juga terjadi di Malaysia Barat. [8]
Perkembangan politik
hukum agraria Indonesia dan dibeberapa negara di atas menjelaskan bahwa hukum
itu tidak berdiri sendiri, terlepas dari masyarakat karena hukum adalah salah
satu dari subsistem sosial menurut teori fungsional-strukturalnya Talcott
Parson, sistem sosial terdiri atas: [9]
1.
Tingkah laku
organisasi dengan fungsi adaptasi melalui penyesuaian dan transformasi seperti
ekonomi;
2.
Sistem
kepribadian dengan fungsi pencapaian tujuan melalui tujuan sistem dan
mobilisasi misalnya politik;
3.
Sistem sosial
dengan fungsi integrasi melalui kendali komponen masyarakat termasuk hukum;
4.
Sistem budaya
dengan fungsi laten. Pemeliharaan pola melalui norma dan nilai misalnya
kepercayaan.
Dengan menyimak
perubahan politik hukum agraria tersebut yang terjadi karena sudut pandang dan
kepentingan penguasa yang berbeda dapat dikatakan bahwa hal ini sesuai dengan
pendapat Sampford[10] bahwa terjadi perubahan set interaksi dalam
perjuangan kompleks antara sejumlah besar kelompok dan lembaga. Anggotanya akan
mempunyai kepentingan subjektif yang bertentangan dan nilai-nilai lain yang
mereka dapat dan pertahankan, kadang secara pribadi namun biasanya lewat
lembaga. Dengan demikian hukum itu meleleh di tangan penggunanya sehingga
tergantung kepada pandangan dan kepentingan para fihak dalam hal politik hukum
adalah para pembuat kebijakan negara atau penguasa.
Sebagai suatu
sistem, selayaknya pola politik hukum agraria Indonesia lebih mengacu kepada
tatanan hukum responsif[11] yang berfungsi sebagai fasilitator tanggap
terhadap kepentingan dan aspirasi sosial karena itu harus fungsional,
pragmatis, bertujuan dan rasional. Dengan demikian, pemikirannya purposif yang
bertujuan atau berorientasi kebijakan dengan keadilan yang prosedural dan
substantif[12].
Mengacu kepada cita negara hukum Indonesia fungsi primer hukum yang ada dalam
Pembukaan UUD 1945 harus terwujud:[13]
1.
Perlindungan masyarakat baik dari pemerintah, sesama maupun dari luar
2.
Keadilan dengan menjaga dan melindungi nilai-nilai keyakinan masyarakat;
3.
Pembangunan dengan sarana penentuan arah, tujuan, pelaksananan serta
pengendaliannya.
Ditegaskan oleh
Sugangga[14] bahwa perubahan nilai dan kesadaran sebagai
akibat informasi dan teknologi akan mempengaruhi isi dan corak sistem hukum
nasional termasuk hukum adat. Hukum adat harus disesuaikan dengan keadaan namun
azas-azasnya harus tetap dipertahankan. Kita harus terbuka dalam menerima
peraturan hukum asing atau yang bersifat internasional. Hukum adat adalah hukum
yang dinamis yang mudah menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, mempunyai
nilai-nilai yang universal, dan lembaga-lembaga hukum yang yang kita ketemukan
dalam hukum internasional. Dengan meminjam pendapat Notonagoro[15]
Politik Hukum
Agraria Indonesia itu hendaklah realistis, etis, religius dalam arti bahwa
politik hukum agraria Indonesia itu memperhatikan realita yang ada, terdapat
dasar etika di dalamnya serta memperhatikan kaidah religi yang ada.
Berdasarkan UUPA
melalui Hak Menguasai Negara sesuai dengan pasal 33 ayat 3 UUD 1945 pemerintah
wajib berusaha agar bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung
di dalamnya yang dikuasai oleh negara dipergunakan untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat. Sesuai pula dengan pasal 2 ayat 4 UUPA yang menekankan
desentralisasi dalam hukum agraria maka politik hukum agraria Indonesia
selayaknya bercorak neo-populis yang menempatkan satuan usaha pada keluarga
dengan pertanggungjawaban yang diatur oleh negara[16]. Kenyataannya banyak sengketa agraria
yang terjadi biasanya dimulai dengan pemberian hak-hak keagrariaan oleh
pemerintah kepada perusahaan modal besar atau bagi proyek pemerintah sendiri.
Hal ini telah menjadi sisi lain dari pengadaan tanah berskala besar bagi proyek
pembangunan pemerintah maupun perusahaan bermodal besar. Sengketa ini bersifat struktural dalam arti
bahwa sengketa atas sebidang tanah beserta segala sesuatu yang tumbuh di
atasnya dan terkandung di dalamnya dimulai dengan pemberian hak atas tanah termaksud
untuk proyek pembangunan dan telah terjadi ikatan kuat antara penduduk dengan
tanah tersebut.[17]
UUPA sebagai
peraturan dasar dan pokok dalam hal keagrariaan seharusnya dapat menjawab
permasalahan yang timbul. Namun kenyataannya masih terjadi sengketa yang
berkepanjangan. Bagaimana seharusnya dengan UUPA sendiri ? Sanggupkah menjawab
tantangan zaman ? Dan bagaimana kita harus bersikap terhadap UUPA ? Terdapat 4
(empat) golongan sikap terhadap UUPA saat ini:[18]
1.
Mereka yang
percaya bahwa semua peraturan termasuk UUPA
dibentuk dengan niat baik untuk jaminan kewajiban dan hak masyarakat
sehingga terandalkan sebagai sarana perlindungan hak masyarakat. Sengketa
terjadi karena penyimpangan yang dilakukan oleh
oknum dalam mempergunakan kewenangannya.
2.
Mereka yang
percaya bahwa UUPA memuat jaminan terhadap hak-hak masyarakat namun peraturan pelaksananya banyak yang
menyimpang darinya. UUPA adalah produk
Orde Lama yang bersifat populis namun banyak peraturan pelaksanaannya sebagai
hasil produksi Orde Baru bersifat kapitalis sesuai dengan pembangunan pada
waktu itu. Sengketa yang terjadi karena orientasi pembangunan Orde Baru yang
lebih mendahulukan pertumbuhan industri dan proyek pemerintah daripada
kepentingan rakyat banyak. Peraturan agraria yang ada waktu itu adalah subsistem dari pertumbuhan ekonomi,
sehingga bercorak ke arah lebih mendukung pemerintah.
3.
Mereka yang
berpendapat bahwa sengketa agraria akan menciptakan high-cost economic dan
merugikan pasar bebas karena itu harus dikurangi seminimal mungkin. Reformasi
agraria perlu dilakukan untuk kenyamanan bisnis. Dengan land-efficient market tanah
harus menguntungkan karena itu diperlukan kepastian hukum atas tanah dengan
pendaftaran tanah. Dan bisnis lancar
tanpa hambatan pertanahan.
4.
Mereka yang
mengkritisi UUPA. Di samping dalam ketiga hal lainnya UUPA juga pemberi saham
terbesar dalam sengketa yang terjadi. UUPA adalah master-piece pada jamannya
namun sudah tidak sesuai lagi dengan masa sekarang dan perlu diganti oleh
Undang Undang baru. Revisi UUPA harus merupakan implementasi hak asasi manusia
sebagaimana semboyan the right to
development dan the right of self
determination.
Dikaitkan dengan
realita, seiring dengan berjalannya waktu, paling tidak terdapat tiga kelompok
masyarakat yang mengharapkan bahwa UUPA sebagai peraturan dasar dan pokok yang
menjadi sandaran politik hukum agraria:
1. Tetap dipertahankan sebagaimana adanya;
2. Dicabut, atau diganti dengan yang baru,
atau;
3. Disempurnakan.
Dilihat dari
substansinya sebenarnya UUPA sendiri sesuai dengan cita keadilan bangsa
Indonesia yang tidak menghendaki adanya exploitation
de l’homme par l’homme dan menghindarkan unsur-unsur pemerasan seperti yang
tercantum dalam pasal 10 ayat 1.
Pembahasan
Di Indonesia banyak kasus pendesakan
hak-hak keagrariaan adat terutama terjadi karena kepentingan ekonomi.
Lebih-lebih dengan otonomi daerah yang lebih banyak memberikan keleluasaan
kepada Pemerintah Daerah setempat untuk mengelola sumber daya keagrariaannya.
Di Sumatera Selatan banyak terjadi pendesakan hak-hak rakyat terutama untuk
perkebunan yang banyak dilakukan oleh kelompok anak Soeharto(Tutut) dan
kroninya Bob Hasan. Tercatat banyak masalah pertanahan dengan PT Musi Hutan
Persada, salah satunya yang masih belum terselesaikan adalah kasus dengan eks
Marga Benakat Sumatera Selatan. Bagaimana sebenarnya posisi keberadaan hak-hak
keagraiaan adat ini dalam politik hukum agraria di masyarakat Indonesia?
Baiklah kita telusuri bagaimana posisi keberadaannya tanah ulayat eks marga
Benakat sejak dulu hingga sekarang.
Dengan diadakannya perjanjian berupa
traktat antara pemerintah Hindia Belanda dengan kesultanan Palembang pada 1822
mulailah Belanda berdaulat sepenuhnya di Sumatera Selatan. Sebelumnya Belanda
menempatkan seorang Komisaris Pemerintahan yang belum melaksanakan pemerintahan
sendiri secara langsung. Pemerintahan aktif dilaksanakan oleh pemerintah
Kesultanan yang melaksanakan keinginan dan perintah pemerintah Belanda.
Pemerintahan langsung masih belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah Hindia
Belanda. Agar pemerintahan efektif,
Belanda menunjuk seorang Asisten Residen. Namun kepentingan dagang pemerintah
Hindia Belanda belum terjamin ekonomis dan dari segi perdagangan, karena itu
pemerintah Kesultanan Palembang dihapus pada 1851, selanjutnya pemerintah
Hindia Belanda melaksanakan pemerintahan langsung terhadap wilayah yang menjadi
Sumatera Selatan sekarang. Wilayah
lingkaran adat Sumatera Selatan terdiri dari, Palembang, Bengkulu (Rejang
Lebong Belalau) dan daerah selatan Danau Ranau. Untuk lebih mengefektifkan lagi
pemerintahan langsungnya, maka sejak 1848 pemerintah Hindia Belanda menempatkan
pejabat pemerintahannya di pedalaman Sumatera Selatan.[19]
Pemerintahan langsung kesultanan
Palembang telah sejak dahulu menggunakan lembaga pemerintahan asli rakyat yaitu
Marga dengan beberapa penyesuaian. Di Sumatera Selatan hal ini akan menyebabkan
dualisme kekuasaan, yaitu pemerintahan marga dan dusun. Hal ini dilanjutkan
oleh pemerintahan langsung Belanda dengan penyeragaman bentuk dan kekuasaan
lembaga tersebut. Hal ini diteruskan juga oleh pemerintah Balatentara Jepang.
Dalam revolusi fisik sesudah kita merdeka pada 1945 hingga penyerahan
kedaulatan pada 1949 pemerintahan Marga berjasa dalam mengobarkan semangat
perjuangan menentang penjajahan.
Pada 1904, sewaktu pemerintah Belanda
masuk ke Benakat, mereka meminta tanah hutan untuk memperluas wilayah hutan
cadangan Kring Semangus. Saat itulah
tanah hutan Benakat diukur dan dipatok batas-batasnya pada tiap ulu tulung sungai. Sungai-sungai kecil
yang airnya mengalir ke sungai Benakat masuk ke dalam lingkaran tanah wilayah
Benakat. Tanah hutan cadangan itu diambil mulai dari muara sungai Rambutan
menuju muara sungai Mengkaras antara Durian Condong menuju ulu sungai Pangkul
terus ke timur menuju suban Sundo terus ke utara menyelusuri sungai Baung kiri
mudik sampai ke perbatasan sungai Keruh, ke barat sampai ke batas wilayah
Ujanmas dan Penanggiran menuju ulu tulung sungai Rambutan. Pemerintah Belanda
tidak mengambil hutan kanan mudik sungai Benakat Besar dari muara sungai Baung
sampai sungai Mengkaras kiri mudik mematah ke kanan lurus ke timur lewat suban Sundo menuju ulu muara sungai
Pangkul karena dalam areal tersebut banyak terdapat tanam tumbuh milik penduduk
desa Merbau, Tegi dan Pagar Dewa. Karena pemerintah Belanda takut hutan
cadangan diganggu oleh penduduk, dusun-dusun yang berada di dalam lingkungan
hutan ditutup, penduduk disuruh pindah. Pada 2 Desember 1908 tanah di Rami
Pasai dipotong, disingkat, agar hubungan sungai tidak berbelit-belit.
Dusun-dusun di lingkungan Benakat bergabung maka terciptalah suku Benakat.
Marga ini bukan pemerintah atau penguasa tetapi kelompok/kesatuan penduduk.
Pada 1916 dikeluarkan Boschbeheerskring
Ordonnantie Tahun 1916 Nomor 420 yang memberi sanksi hukuman denda atas
perusakan terhadap hutan cadangan 100 gulden atau kurungan 1 bulan. Dengan
demikian penduduk daerah tersebut terkeluarkan dan bergabung dengan dusun lain
atau membentuk dusun baru. Dengan perpindahan ini maka makin padatlah dusun
Pagar Dewa dan Tegi sehingga areal pertanian makin sempit. Akibat makin
sempitnya areal perladangan dan sesuai dengan sistem perladangan berpindah
warga pindah lagi ke arah ilir sungai Benakat Besar. Areal tanah dusun Tegi dan
Pagar Dewa yang sejak 1908 menjadi lahan penghidupan sebagian ditinggalkan
tetapi tetap dipelihara dan dibiarkan menjadi rimba serta dimiliki bersama oleh
seluruh warga suku Benakat dan dinamakan Hutan Larangan Rimba Sekampung,
dilestarikan sebagai hutan ramuan, hutan lindung dan menjadi hak ulayat suku
Benakat dan menjadi jungut (kebon
benuaran) bersama: siapa saja penduduk
dusun Benakat yanag mau mengambil buah
bila panen tidak dilarang. Penetapan sebagai Hutan Larangan Rimba Sekampung ini
kemudian disahkan oleh Controlleur
Palembang Botenburg pada 26 April 1920. Hutan ini sampai sekarang masih jelas
keberadaannya dengan batas di sebelah barat dengan hutan kawasan negara sungai
Benakat Besar, di sebelah timur dengan sungai Baung dan di sebelah utara dengan
dengan tanah kawasan dari Durian Condong memotong ke arah ulu sungai muara
sungai Pangkul. Di dalam hutan larangan ini terdapat pula:
1.
Suban
Nanak, tempat pemandian binatang liar dan binatang hutan;
2.
Suban
Sundo tempat pemandian unggas/burung;
Pemeliharaan hutan kawasan negara ini begitu ketat,
tidak boleh dimasuki dan diganggu dan pada 1925 dikeluarkanlah peraturan pemeliharaan
hutan larangan tersebut.
Pada 1932 Boschwezen (Dinas Kehutanan) bermaksud meluruskan perbatasan antara
hutan kawasan negara dengan Hutan Rimba Sekampung bagian Barat yang kemudian
dimusyawarahkan dengan Raad (Dewan)
Marga Benakat. Disepakati bahwa Boschwezen mengambil tanah hutan kanan mudik
sungai Kembahang dan Raad Marga diberi tukaran tanah dari tebing di Ulutulung
sungai Pangkul lurus menuju Talang Marap muara sungai Kepayang dalam sungai
Baung yang sebelumnya berada dalam lingkungan kawasan ke timur arah suban Nanak
dan sungai Baung. Persetujuan ini diatur dalam process verbal bersama antara wakil Boschwezen opzichter Mas Urma dengan dengan pasirah Benakat Saibatulham pada
25 Oktober 1932. Tanah hutan tukaran ini tersambung pada ujung utara hutan
Rimba Sekampung. Sejak saat itu tanah mulai digarap oleh penduduk suku Benakat.
Mereka membangun jungut yang
dikepalai oleh Junto dinamai jungut Junto. Walaupun akhirnya Rimba Sekampung
ditinggalkan namun tetap dipelihara bersama sebagai hutan larangan sebagai hak
milik bersama yang pengelolaannya diserahkan di bawah pengawasan Dewan Marga.
Karena akan membuka industri kayu maka
pada 1939 Boschwezen membebaskan tanah warga dengan ganti rugi atas tanam
tumbuh kebun rakyat sepanjang 12 kilometer dengan lebar 25 meter dari seberang
dusun Pagar Dewa (Lematang lama) liwat talang Peninggiran sampai di Muaralangku
untuk pembuatan jalan lori pengangkut kayu dari hutan Semangus dan Kasai serta
membuat kanal yang memotong dusun Pagar Dewa untuk menghanyutkan kayu dari emplasemen di arena erfpacht di seberang dusun Pagardewa. Pembuatan kanal dilaksanakan
dengan persetujuan Dewan Marga. Waktu itu dibuat perjanjian pembuatan jembatan
permanen di atas kanal oleh Boschwezen yang sampai sekarang belum terpenuhi.
Belum sempat berproduksi, Jepang masuk dan usaha Boschwezen ditinggalkan. Saat
itu rakyat Benakat hidup berkecukupan. Hampir tiap rumah tangga mempunyai tengkiang penyimpanan beras dan padi
paling tidak untuk 1 tahun ke depan. Wilayah ini merupakan daerah surplus beras.
Pada kurun waktu 1970-75 perusahaan
Jepang PT Swoody membuka usaha penebangan kayu dan emplasemen serta sawmill di
muara sungai Ipuh (ilir sungai Bingkas) seluas 200 hektar dan membuat jalan
selebar 8 meter menuju Hutan Negara Rimba Kasai dan Selisingan namun akhirnya
gagal juga. Selanjutnya, dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 624 dan
625/Kpts/II/1992 berlaku 8 Januari 1992 PT Barito Pasifik Grup dengan kroninya
PT Musi Hutan Persada membuka Hutan Tanaman Industri menanam kayu akasia dan sengon
di Suban Jeriji dan Benakat untuk
persediaan bahan baku PT Tanjung Enim Lestari di Niru-Darmo Kasih (pabrik
pulp). Usaha ini dilakukan dalam bentuk
perusahaan patungan seluas 120,74 hektar
dengan modal dalam negeri US$
200.000.000 dari PT Barito Pasifik Grup dan 220,4 hektar dengan modal luar
negeri yaitu Jepang: US$ 45.000.000 dari OECF, US$ 47.000.000 dari Marubeni dan
US$ 8.000.000 dari Nippon P Indonesia serta US$ 700.000.000 dari Morgan Glean
serta hutang Bank Dunia 2,4 triyun rupiah.
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 361/Kpts/II/1991 jo
626/Kpts/II/1992 diberikanlah Hak Pengusahaan Hutan seluas 300.000 hektar di
Sumatera Selatan kepada perusahaan patungan ini untuk menanami lahan tidur,
kritis, belukar, nonproduktif dan padang alang-alang untuk bahan baku pabrik
pulp. Namun, dalam praktiknya bukan lahan sedemikian yang digunakan melainkan
lahan subur milik penduduk yang digusur sedemikian rupa tanpa melalui
musyawarah lebih dahulu dengan para pemilik. Sebagian dilakukan dengan
transaksi jual beli secara paksa dengan harga murah melalui Camat sebagian
dengan rasan kasak-kusuk berdasarkan
Surat Keterangan Tanah asli tapi palsu dan tak sedikit pula yang digusur tanpa
sepengetahuan pemilik, tanpa ganti rugi. Ada pula yang dilakukan dengan jual
beli illegal tanpa melalui prosedur
Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.
Pada 1993 masuklah pemodal besar lain
seperti PT Barito Pasific Group, PT Musi Hutan Persada yaitu PT Cipta Futura,
PT Surya Bumi Argo Langgeng yang ikut menggusur kebun rakyat untuk berusaha
dalam bidang perkebunan kelapa sawit dan karet. Akibatnya tanah pertanian di
Benakat terpecah menjadi 3: di sebelah barat diambil oleh PT Musi Hutan
Persada, sebelah timur oleh PT Surya Bumi Argo Langgeng dan sebelah barat laut
dan selatan oleh PT Cipta Futura. PT Musi Hutan Persada menghancurkan hutan
kawasan negara antara Sungai Rambutan, Kasai dan Benakat Kecil mempergunakan
taktik risau-maling, membuka areal dari dalam (tengah) sehingga dilihat dari
jalan seakan-akan hutan masih utuh. Banyak rakyat jatuh miskin dan mereka
menjadi masyarakat termiskin di Muara Enim. Mulai terjadi perlawanan rakyat
namun rakyat selalu terpukul karena tekanan aparat pemerintah oknum alat negara
pemerintahan Soeharto-Habibie. Pada 17 Juni 1992 didirikan organisasi tani
topeng kelompok tani Tunas Cahaya di bawah pimpinan Zainal Bahusin dan Said
Resap yang berusaha membuka pinggiran hutan bagian utara Hutan Rimba Sekampung
seluas 300 hektar di atas tanah yang diakui sebagai hasil tukaran dengan hutan
Kembahang pada 1925 dengan areal jalan lori berdasarkan surat Camat Gunung
Megang Sumardi Arab nomor 593/112/ 05/92. Jalan lori tersebut sebenarnya adalah
tanah perkebunan perladangan rakyat yang telah digantirugi oleh Boschwezen.
Terjadi permainan antara Sumardi Arab dan Zainal Bahusin dengan PT Musi Hutan
Persada untuk membajak Hutan Larangan Rimba Sekampung. Para Kades mencoba
mencegah hal tersebut dan melaporkan kepada Camat, tetapi tidak mempan. Oleh Kades
Padang Bindu hal ini dilaporkan kepada Dirut PT Barito Pasifik Grup di Jakarta.
Dijawab bahwa mereka tidak memerintahkan PT Musi Hutan Persada untuk membuka
Hutan Larangan Rimba Sekampung dan hal ini disampaikan kepada PT Musi Hutan
Persada di lapangan, namun tidak digubris. Bahkan kegiatan membajak Hutan
Larangan Rimba Sekampung semakin meluas. Dengan surat yang ditandatangani oleh
716 penduduk Benakat pada 19 Mei 1993 oleh Helmi, Ketua LKMD Benakat,
disampaikan permohonan keberatan kepada Bupati Muara Enim Hasan Zen, S.H.
Masalah ini tidak mendapat tanggapan sama sekali. Pada 12 Juni 1993 atas
prakarsa Camat Sumardi Arab diadakan pertemuan antara PT Musi Hutan Persada,
Camat dan Kades Padang Bindu, Subri Halim. Kades dibujuk supaya suka membuka
hutan itu dengan diberi hasil fifty-fifty
(Rp 170.000,- per hektar). Hal itu oleh Kades spontan ditolak sebab dia tidak
berani. Hutan larangan itu adalah milik rakyat, hak ulayat penduduk suku
Benakat seluruhnya. Walau begitu PT Musi Hutan Perdasa tetap dengan gerakan
intervensinya menggunakan Zainal sebagai mitra kerja. Para Kepala Desa Padang
Bindu, Betung, Pagar Dewa, Pagar Jati , Rami Pasai dan pemuka masyarakat dengan
surat pada 16 Juni 1993 meminta kepada Zainal Bahusin, Said Resap dan Kepala
Unit Pemukiman Transmigrasi SP I Benakat untuk menghentikan
tebas-tebang/penjualan hutan lindung eks Marga tersebut. 12 Juli 1993 Kepala
Dinas Kehutanan Muara Enim mengirim laporan kepada Kepala Dinas Kehutanan
Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan tentang dibukanya areal hutan oleh
Kelompok Tani Tunas Cahaya Desa Sungai Baung di bawah pimpinan Said Resap
berdasarkan restu dari Camat Gunung Megang dengan surat Nomor 593/443/05/92 17
Juni 1992. Dijelaskan bahwa pembukaan tersebut ditentang oleh 5 Kepala Desa dan
pemuka masyarakat eks Marga Benakat. Karena yang dibuka adalah Hutan Rimba
Sekampung yang dahulu sebelum diberlakukannya Tata Guna Hutan Kespakatan
terletak di luar kawasan Hutan Register Nomor A 32 Benakat dan dikenal sebagai
Cadangan Hutan Penghasil/eks Hutan Larangan Marga. Ditambahkan bahwa sesuai
telaahan pada peta hutan tersebut terletak di dalam areal kerja PT Musi Hutan
Persada blok tanaman nomor 29. Selain membuka hutan kelompok tersebut juga
menebang kayu jenis sungkai yang diduga merupakan tanaman Proyek Inpres
Reboisasi dahulu. Untuk mencegah keresahan masyarakat penebangan hutan tanpa
izin yang pada hakekatnya bertentangan dengan seruan gerakan Sejuta Pohon
diusulkan untuk segera diterjunkan Tim Koordinasi Pengamanan Hutan Tingkat I
untuk mengatasi masalah tersebut. Pada 19 Juli 1993 para Ketua LKMD Padang
Bindu, Betung, Pagar Dewa dan Rami Pasai mengirim surat kepada Bupati Muara
Enim tentang pengaduan rakyat eks marga Benakat untuk mencegah pembukaan Hutan
Rimba Sekampung. H.A. Koim pada 31 Juli 1993 menyampaikan pendapat kepada
Bupati untuk mengambil langkah tegas terhadap kasus Hutan Rimba Sekampung
berdasarkan peraturan yang berlaku. Ditanyakan apakah hutan tersebut diakui
menjadi hutan negara atau masih milik rakyat dengan hapusnya otonomi marga.
Pada 24 Agustus 1993 H.A. Koim mengirim surat kepada Kepala Cabang Dinas
Kehutanan/KPH Muara Enim tentang biang keladi perambahan hutan termasuk Zainal
Bahusin yang telah mengerahkan orang untuk membuka kembali Hutan Rimba
Sekampung. Diharapkan agar yang bersangkutan segera ditindak dan apabila perlu
diajukan ke Pengadilan penduduk bersedia membantu menangkapnya. Dalam pertemuan
di kantor Cabang Dinas Kehutanan/ Kesatuan Pemangku Hutan (CDK/KPH) Muara Enim
pada 24 Agustus 1993 Kades Padang Bindu dan H.A. Koim menginformasikan bahwa
selain di Benakat perambahan hutan terjadi pula di sekitar hulu sungai Kasai
dan Ipuh. Hal ini dibenarkan oleh Said Resap dalam pertemuan di KPH pada 25
Agustus 1993. Surat Kepala Dinas Kehutanan di atas disusuli lagi pada 25 Agustus 1993 yang lebih
panjang lebar mengutarakan permasalahan tersebut. Inti surat adalah bahwa surat
Camat Gunung Megang diduga sebagai penyebab perambahan hutan sejak 1992 yang
saat ini mencapai 300 hektar. Areal lokasi setelah ditelaah berdasarkan Tata Guna
Hutan Kesepakatan terletak dalam kawasan hutan produksi tetap Benakat seluas
60% yang ditebang oleh Zainal Bahusin dan Said Resap dan seluruhnya merupakan
merupakan blok tanaman HTI Nomor 29 nonregion
Benakat, 40% sisanya terletak di dalam
areal penganti/tukar-menukar dengan kawasan hutan di Kabupaten Musi Rawas untuk
lokasi transmigrasi pada 1988 yang telah disetujui oleh Menteri Kehutanan dan
seyogyanya sekarang sudah menjadi kawasan hutan. Pembabatan yang dilakukan oleh
Zainal Bahusin dkk selaku pemborong tebas tebang dari PT Musi Hutan Persada
dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan lahan tanaman HTI yang sudah sulit
didapat. Hal ini telah ditentang oleh para Kades dan pemuka masyarakat bahkan
rapat LKMD dalam putusan 17 Juli 1993 menuntut pertanggungjawaban Said Resap
atas kerusakan hutan tersebut. Perbuatan tersebut melibatkan pihak aparat
pemerintah, pemuka masyarakat, maupun PT Musi Hutan Persada dan pemborong tebas
tebangnya. Masalah tersebut juga mengundang isu politik GPK BTI/PKI, melanggar
peraturan keamanan hutan terencana, maupun kecemburuan sosial warga.
Disimpulkan bahwa ditinjau dari derajat dan sifatnya kasus perambahan hutan
tersebut sedemikian kompleks sehingga penanganannya harus sudah pada TKPH
Tingkat I namun apabila dilimpahkan ke Daerah Tingkat I siap dilaksanakan.
Laporan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Muara Enim kepada Kepala Dinas
Kehutanan Propinsi Sumatra Selatan pada
26 Agustus 1993 sejalan dengan surat Bupati
Muara Enim Nomor 251/2801/V/1993 pada 19 Agustus 1993 yang baru diterima
pada 25 Agustus 1993 mendesak penentuan langkah yang harus diambil karena kasus
gangguan keamanan hutan di Benakat derajat dan sifatnya sudah mendesak untuk
dilakukan operasi yustisi/tindakan represif.
Bersamaan denga menjawab surat Bupati
Muara Enim Nomor 33/2291/I.1/1993 5 Juli 1993 dan Nomor 522/2755/I.1/93 Camat
Gunung Megang pada 27 Agustus 1993 melaporkan bahwa kegiatan tebas-tebang sudah
tidak ada lagi dan kelompok tani sudah dibubarkan pada 26 Juli 1993. Sesuai
dengan petunjuk PT Barito Pendopo Bapak Zainal Bahusin masih melaksanakan tebas
tebang di sekitar areal Hutan Rimba Sekampung dalam lokasi hutan kawasan
register 32 Benakat/Semangus. Menurut PT dalam hutan tersebut masih akan dibuka
lahan pencadangan HTI. Sebenarnya menurut keterangan PT dan eks pasirah lokasi
hutan yang digarap oleh kelompok tani belum termasuk areal Hutan Rimba
Sekampung sehingga ijin yang dahulu hanya 50 hektar oleh pihak PT diberikan 200
hektar. Berdasarkan keterangan dari Cabang Dinas Kehutanan Kabupaten Muara Enim status Hutan Rimba Sekampung
adalah hutan negara namun batas-batasnya diusulkan oleh Cabang Dinas
Kehutanan untuk ditetapkan oleh Kanwil
Kehutanan.
Selanjutnya, masalah di atas oleh warga
dipercayakan kepada H.A. Koim, pemuka masyarakat Benakat untuk diperjuangkan.
Tanah hak ulayat dipertahankan dari penyerobotan hingga sampai ke Pemerintah
Pusat di Jakarta. Sementara itu gelombang amarah masyarakat makin memuncak.
Secara resmi oleh masyarakat diajukan keberatan atas kegiatan tersebut kepada
Bupati Muara Enim pada 31 Juli 1993, 16 Juni 1994, 27 Juni 1994, dan 15 Juli
1994. Hal ini tidak mendapat tanggapan serius. Puluhan Kepala Keluarga eks
marga Benakat mengadu kepada Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan dan diterima
oleh Karo Pamong Praja pada 17 Juli 1994. Mereka menuding PT MHP telah merusak
Hutan Rimba Sekampung. Mereka meminta Pemda Sumsel menghentikan penebangan
untuk HTI tersebut. Pada saat yang sama pejabat PT MHP menolak tuduhan tersebut
karena yang digarap adalah lokasi yang berdekatan dengan hutan tersebut. Oleh
Pemerintah Kabupaten beberapa kali diturunkan tim di antaranya 21 Juni dan 21
Juli 1994 namun hasilnya tidak ada sama sekali malahan pada tenggang waktu
kedatangan tim dipergunakan oleh PT Musi Hutan Persada untuk menghancurkan
Hutan Larangan di bawah perlindungan
aparat. Para aparat menakut-nakuti Kades dengan berbagai macam ancaman
intimidasi seperti pemecatan apabila mereka ikut aktif mempertahankan Rimba
Sekampung. Terbukti dengan pemecatan Kades Betung dan Pagar Dewa.
Berhubung gelombang amarah penduduk
makin hangat, lalu dibentuklah Panitia Pemulihan Hutan Rimba Sekampung
(Paperis) yang diketuai oleh H.A. Koim yang melanjutkan tuntutan rakyat kepada
segenap instansi terkait baik di daerah maupun di pusat. Dijelaskan bahwa akibat
perbuatan tersebut merugikan rakyat, merusak lingkungan hidup dan menimbulkan
erosi besar-besaran seperti yang diterangkan oleh staf PPLH Unsri, Dr.Ir. Supli
Effendi, M.Sc. bahwa hutan Rimba Sekampung apabila tidak dibuka di musim hujan
akan erosi 5 ton per detik dan apabila dibuka 20-40 ton per detik.
Berturut-turut pada 16 Juli, 25 Juli dan 16 Agustus 1994 diajukan keberatan
kepada Gubernur Sumatera Selatan. Diturunkan Tim Propinsi dengan hasil yang di
luar pengetahuan masyarakat.
Pada tanggal 16 September 1994 Walhi
melakukan investigasi lapangan sebagai tanggapan atas permintaan masyarakat.
Hasil menunjukkan bahwa benar telah terjadi perusakan terhadap hutan tersebut
padahal itu merupakan satu-satunya hutan yang tersisa di lokasi tersebut. 17
September 1994 dibentuk Komite Solidaritas untuk Marga Benakat oleh beberapa
LSM di Jakarta dan Palembang serta Mapala yang mengeluarkan pernyataan
sikap kepada instansi yang terkait baik
pusat maupun daerah agar menghentikan perusakan hutan tersebut. Pada waktu itu
juga Pangdam Sriwijaya meminta agar temuan investigasi LBH dan Walhi Palembang
dikoordinasikan dengan Dephut agar penanganannya tidak menimbulkan sikap saling
mencurigai. Ketika menerima pengurus Walhi pada 20 September 1994 Menteri
Kehutanan menyatakan telah memerintahkan jajarannya untuk menangani kasus
penyerobotan Hutan Rimba Sekampung termasuk mempelajari dan menangani kasus
sejenis di daerah lain. Di tengah sengketa ini,
pada 22-26 September 1994 atas perintah Bupati sebuah tim Kabupaten
melakukan pematokan keliling batas Hutan Rimba Sekampung sebagai berikut: Patok
pertama diletakkan di muara sungai Kuli menuju jembatan sungai Baung (patok
kedua) menuju ke pematang perbatasan dengan Hutan Kawasan Negara (patok ketiga)
menuju ke muara sungai Engkaras (patok keempat) menuju ke muara sungai Kasai
(patok kelima) menuju ke muara sungai Rambutan (patok keenam) menuju ke muara
sungai Peninggiran (patok ketujuh) menuju ke muara sungai Mata Rusa (patok
kedelapan) menuju ke muara sungai Baung (patok kesembilan) menuju ke muara
sungai Bongor (patok kesepuluh) menuju ke muara sungai Pangkul (patok
kesebelas) menuju ke muara sungai Selo (patok keduabelas) menuju ke sungai Kota Gading (patok ketigabelas) menuju ke
muara sungai Muara Dua (patok keempatbelas) di sebelah ulu muara sungai
Kepayang.
Pada 20 September 1994 dinyatakan bahwa
kegiatan penggarapan Hutan Rimba Sekampung dihentikan untuk sementara dan tim
khusus akan mematok ulang batas-batas kawasan tersebut Hal ini disampaikan oleh
Kepala Kodim Muara Enim dalam pertemuan di tengah hutan Benakat dengan warga
dan PT. Pertemuan ini diadakan untuk menindaklanjuti temuan Walhi dan LBH
Palembang. Pada 3 Oktober 1994 oleh Pangdam II Sriwijaya diadakan pertemuan coffee-morning dengan masyarakat marga
Benakat, Walhi dan LBH Palembang, instansi terkait serta PT Barito di Aula
Kodam dan diungkap bahan-bahan masukan dari pihak terkait dan kemudian pada 8
Oktober 1994 tim terpadu Bakorstanasda meninjau kegiatan lapangan. Dilakukan
lagi peninjauan pada 19-20 Oktober 1994 dan memerintahkan penghentian segala kegiatan di hutan tersebut. Kemudian
pada 28 Oktober 1994 berdasarkan koordinasi dengan Bakorstanasda penggusuran hutan dihentikan. Lahan dinyatakan
dalam keadaan status-quo.
Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera
Selatan dengan surat pada 7 Nopember 1994 menyarankan agar Hutan Rimba
Sekampung tidak dikeluarkan dari areal pencadangan Hutan Tanaman Industri PT
Musi Hutan Persada dan tetap dipertahankan sebagai kawasan hutan karena
pengunaannya sesuai dengan peruntukannya, hutan terletak pada areal Hutan
Tanaman Industri yang masih berhutan sebagai areal konservasi, dan hutan
tersebut yang digunakan untuk peramuan pada kenyataannya memberikan peluang
terjadinya penebangan liar. Menjawab surat Ketua Walhi Dirjen Pengusahaan Hutan
pada 24 Nopember 1994 menyampaikan bahwa luas real Hutan Rimba Sekampung
berdasarkan pernyataan Zainal Bahusin hanya seluas 1.000 hektar dan masuk ke
dalam areal pencadangan HTI PT Musi Hutan Persada. Dari hasil pemeriksaan
lapangan oleh aparat Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan II Muara
Enim, dan wakil eks marga Benakat disimpulkan bahwa PT Musi Hutan Persada belum
mengusahakan areal tersebut. Ditegaskan bahwa tidak dikenal lagi hutan marga;
yang ada hanyalah hutan milik dan hutan negara. Dari hasil telaahan Peta Tata
Ruang Wilayah Propinsi Sumatera Selatan areal hutan tersebut adalah kawasan
hutan produksi tetap. Pengakuan terhadap hutan adat tidak mutlak sepanjang
tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Untuk mengakomodir kepentingan
masyarakat hutan maka areal sengketa tidak akan dikonversi menjadi Hutan
Tanaman Industri.
Selama 10-15 Juni 1995
masyarakat bergerak ke Jakarta. Mereka mendatangi Sekretariat Wakil Presiden
agar dapat bertemu dengan Wakil Presiden namun tidak berhasil. Juga didatangi
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Dewan Perwakilan Rakyat, Departemen Dalam
Negeri, Badan Pertanahan Nasional serta pihak yang pernah didatangi sebelumnya
untuk menagih janji bagi penyelesaian kasus. Upaya ini juga belum memberikan
hasil maksimal. Masyarakat Benakat menyatakan pada 11 Juli 1995 bahwa PT Musi
Hutan Persada masih terus melakukan kegiatannya.
Pada tanggal 3 Agustus 1995 tim Lembaga
Bantuan Hukum Palembang bersama H.A. Koim tiba di desa Pagar Dewa menemui
Ardin, contact person. Di Benakat
juga telah ada tim Lembaga Swadaya Masyarakat Eka Nuda dari Jakarta yang
menemui Kades Padang Bindu. Kemudian diadakan pertemuan bersama di rumah Kepala
Desa. Didapat informasi bahwa LSM telah melakukan koordinasi dengan Komando
Daerah Militer dan melakukan peninjauan ke desa Pelawe dan Lubuk Pauh Kecamatan
Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas dan desa Babat di Kecamatan Perwakilan
Penukal Abab Kecamatan Muara Enim. Mereka melakukan itu atas undangan PT Barito
di media massa agar LSM melihat langsung. Hasil yang mereka nyatakan adakah:
Apakah masyarakat puas dengan penghentian kegiatan PT Musi Hutan Persada ?
Benarkah kegiatan tersebut telah dihentikan ? Bagaimana konsep penyembuhan
masyarakat yang telah dilukai oleh PT Musi Hutan Persada. Ditawarkan semacam
pesta adat untuk mengganti kerugian tersebut. Hasil dari pertemuan adalah:
1.
H.A. Koim
menyatakan bahwa Hutan Larangan Rimba Sekampung adalah hutan milik marga (hutan
adat).
2.
PT Barito
menyatakan bahwa Hutan larangan termasuk dalam areal Hutan Tanaman
Industri mereka.
3.
Isi hutan
adalah berbagai jenis kayu seperti merawan, meranti dan jelutung yang
dipergunakan sehari-hari oleh masyarakat sendiri. Penggunaan hutan dilakukan
tanpa merusak kondisi hutan.
4.
Dulunya
kawasan hutan tersebut adalah pemukiman karena itu terdapat juga makam nenek
moyang di sana.Warga menuntut agar hutan dikembalikan seperti keadaan semula.
5.
Kepala Desa
Padang Bindu menyatakan bahwa untuk mengganti beaya pemulihan selain
mengembalikan keadaan hutan PT juga harus membuatkan sawah bagi warga.
Secara tidak
sengaja tim LBH menangkap basah pencurian kayu di hutan. Masyarakat marga
Benakat yang bermukim di wilayah 7 desa: Pagar Dewa, Betung, Pagar Jati, Padang
Bindu, Benakat Minyak, Sungai Baung dan Rami Pasai mempertahankan hutan
larangan Rimba Sekampung karena hutan tersebut perlu untuk menggantungkan hidup
untuk keperluan sehari-hari. Hutan dikelola secara adat dengan menjunjung
tinggi nilai-nilai kelestarian hutan dan hutan dipelihara sebagai kawasan
konservasi mereka. PT Musi Hutan Persada menganggap bahwa areal mereka tidak
termasuk dalam kawasan Hutan Larangan Rimba Sekampung, masih sejauh 3 kilometer
dari hutan larangan tersebut. Kenyataan bahwa PT telah melakukan pembabatan
terhadap hutan larangan seluas 1.000 hektar.
Dalam laporannya
kepada Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 1995, Menteri Kehutanan menyatakan bahwa PT Musi Hutan Persada belum
mengusahakan areal Hutan Rimba Sekampung dan belum mengkonversikannya menjadi
Hutan Tanaman Industri. Sesudah melalui proses panjang bertahun-tahun diam-diam
PT Musi Hutan Persada meninggalkan lahan sengketa namun tak urung sudah 30%
lahan Rimba sekampung rusak dibakar menjadi abu dan kayunya yang berdiameter 60
cm diambil oleh PT tersebut. Paperis menuntut pemulihan hutan dengan penanaman
kembali kayu komersil oleh PT. Masyarakat berusaha menanami kembali Hutan
tersebut. Saat ini sudah mencapai 500 hektar. Di masyarakat beredar keterangan
(palsu?) Bupati dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim
bahwa tiada tuntutan seperti itu. Paperis menyatakan pada 2 Januari 2001 bahwa
walaupun terdapat fatwa Ketua DPRD hal itu palsu tidak dapat dijadikan
pegangan. Belum ada perundingan serius dengan PT Musi Hutan Persada. Pernyataan
permasalahan selesai tidak jelas bentuk dan rinciannya. Walau begitu belum
waktunya dibawa ke Pengadilan. (dalam wawancara pada 5 Februari 2002, Sesepuh
Paperis, H. Koim, beralasan bahwa keadilan di indonesia sukar ditemukan.
Pemerintah tidak tegas, sudah jelas ada kepentingan lain).
Pada 4 Januari
2001 dengan surat kepada masyarakat dan Gubernur oleh Wakil Bupati dinyatakan
masalah sudah selesai. Pihak yang tidak puas dapat menempuh jalur hukum. PT
Musi Hutan Persada pada 22 Mei 2001 mengirim surat kepada Bupati bahwa
perkembangan permasalahan sosial di Benakat merupakan klaim tanpa dasar.
Terjadi pemaksaan kehendak dan masyarakat cenderung bertindak anarkis dengan
syarat yang ditentukan sendiri padahal sudah ada Program Menanam Hutan Bersama
Masyarakat (PMHBM). Karena itu PT minta perhatian dan perlindungan Pemerintah.
27 September 2001 dikeluarkan surat Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim yang
mengharapkan fatwa Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim atas masalah tersebut.
H.A. Koim dalam wawancara pada 5 Februari 2002 menyatakan bahwa sebenarnya
masalah belum selesai; masih dicari cara penyelesaian yang baik dan tidak perlu
ke Pengadilan. Di negara ini keadilan
sukar ditemukan.
Sebenarnya
permasalahan sosial/lahan yang dihadapi oleh PT Musi Hutan Persada bukan hanya
di Benakat saja. Laporan Perkembangan sosial/lahan di Lahan Penguasaan hutan
Tanaman Industri (HPHTI) PT Musi Hutan Persada 2001 yang dikeluarkan oleh
Divisi Legal dan Sosial Biro Binapraja Propinsi Sumatera Selatan menyatakan
terdapat 30 kasus atas 48 areal yang harus dihadapi oleh PT tersebut di seluruh
Muara Enim. Yang paling memuncak dan menyedot perhatian hingga tingkat pusat
dan hingga kini masih belum selesai adalah yang di Benakat.
Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999
memberikan peluang lebih besar kepada daerah untuk melakukan pembenahan hukum
agraria. Pasal 6 ayat 1 dan 2 nya menyatakan bahwa kewenangan daerah mencakup
seluruh bidang pemerintahan kecuali kewenangan dalam hal politik luar negeri,
pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, serta kewenangan lain yaitu
kebijakan pembangunan nasional secara makro, dana peimbangan keuangan, sistem
administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan
sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam, serta teknologi tinggi
yang strategis, konservasi dan standarisasi nasional. Kewenangan yang wajib
dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Kota meliputi bidang: pekerjaan
umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri
dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi dan tenaga kerja.
Pasal 1 huruf o Undang Undang Nomor 22
Tahun 1999 menyatakan bahwa desa atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem
pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten.
Berdasarkan
ketentuan-ketentuan di atas Pemerintah Daerah memiliki peluang untuk
meningkatkan daya dan hasil guna hak-hak keagrariaan adat/hak ulayat. Dalam
pasal 5 Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman
Penyelesaian Masalah Hak Ulayat masyarakat Hukum Adat dinyatakan bahwa
keberadaan tanah ulayat yang masih ada dinyatakan dalam peta dasar pendaftaran
tanah dengan membubuhkan suatu tanda kartografi dan apabila memungkinkan
menggambarkan batas-batasnya serta mencatatnya dalam daftar tanah. Pasal 6 nya
menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal 5 diatur dengan
Peraturan Daerah yang bersangkutan.
Ketentuan-ketentuan di atas
memberikan peranan yang menentukan bagi
Pemerintah Daerah khususnya Kabupaten Muara Enim untuk menentukan keberadaan
dan memberikan pengakuan terhadap hak ulayat yang berada di daerahnya. Dengan
demikian sebenarnya Pemerintah Daerah dapat secara formal memberikan pengakuan
terhadap eksistensi hak ulayat. Namun di Kabupaten Muara Enim terdapat kendala
bagi pengakuan tersebut. Aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim
menyatakan keraguannya bahwa dengan dihapuskannya pemerintahan marga apakah
apakah tanah marga atau tanah ulayat masih ada ?. Jika masih ada bagian manakah
dari tanah marga tersebut yang dapat dikategorikan sebagai tanah ulayat ?.
Kemudian jika tanah marga masih ada siapakah yang berwenang mengatur
pemanfaatannya ?. Keraguan atas keberadaan tanah marga dan hak masyarakat eks
tanah marga untuk mengatur dan menguasai hak ulayatnya ini dinyatakan oleh
Kepala Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim dengan mengutarakan
bahwa marga dianggap sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat teritorial sehingga dengan
dihapuskannya pemerintahan marga kewenangan untuk mengatur pemanfaatan tanah
yang dahulu berada di tangan Pasirah selaku Kepala Marga (Kepala Pemerintahan
dan Ketua Adat) sudah tidak ada lagi. Kepala Desa sebagai gantinya sebagai
aparat administratif tidak mempunyai hak kewenangan adat untuk mengatur
pemanfataan tanah eks marga. Dengan dihapuskannya tanah marga kewenangan pasirah
di bidang pertanahan pindah kepada Pemerintah Kabupaten karena Camat ataupun
Kepala Desa tidak berkedudukan sebagai kepala/penguasa adat. Hal ini sesuai
dengan ketentuan pasal 11 Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang kewenangan
di bidang pertanahan yang diletakkan di pundak pemerintah Kabupaten dan Kota.
Dengan penghapusan pemerintahan marga sedangkan lembaganya masih ada
tanah-tanah eks marga adat yang mana yang masih ada secara adat dan diakui
eksitensinya oleh UUPA ?. Jika sebagian
tanah eks marga (Rimba Sekampung, misalnya)
diberikan pengakuan kepada siapa kewenangan pengaturan dan pemanfaatannya
diberikan? Teoretis, eks marga Benakat.
Namun kesulitannya adalah marga yang dahulu telah terpecah menjadi
kecamatan dan desa. Kadang desa yang dahulu satu marga menjadi berlainan
kecamatan. Kenyataannya warga yang dekat dengan Rimba yang merasa berhak dengan
membukanya sekarang. Bagaimana dengan pembentukan kembali persekutuan desa-desa
eks marga dan diberikan hak untuk
mengurus, mengelola dan memanfaatkannya ? Apakah bentuk lembaga hukumnya ?. Hal
senada juga dikatakan oleh Kepala Seksi Hak atas Tanah Kantor Pertanahan
Nasional Muara Enim. Dengan dihapuskannya Pemerintahan Marga kekuatan hukum
adat makin menipis, serba tidak jelas. Dipersoalkan apakah Kepala Desa sekarang
ini adalah juga Kepala Adat. Dulu Pasirah adalah Kepala Pemerintahan dan juga
Kepala Adat namun dengan penghapusannya dan penyerahannya kepada Kepala Desa
sebagai Kepala Adat tidak jelas. Penafsirannya adalah bahwa hak Kepala Adat
hapus tanpa disertai dengan penyerahannya kepada Kepala Desa. Dengan demikian
tanah marga adalah tanah negara yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dalam hal
ini Bupati. Staf Dinas Kehutanan Kabupaten Muara Enim juga berpendapat bahwa
dengan dihapuskannya pemerintahan marga maka hak atas tanah marga termasuk
Hutan Rimba Sekampung menjadi urusan pemerintah dalam hal ini Departemen
Kehutanan yang bertugas untuk menyelamatkan, mengamankan, mengelola dan
memanfaatkan tanah hutan tersebut. Hutan
marga ditunjuk menjadi kawasan hutan. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan
Nomor 38/Kpts-II/96, 28 Januari 1986 hutan tersebut ditetapkan menjadi cadangan
HTI PT Musi Hutan Persada. Dan ini sebenarnya tidak termasuk Hutan Rimba
Sekampung. Dengan tuntutan masyarakat dan LSM hutan itu menjadi kawasan
bermasalah yang kemudian ditinggalkan oleh PT tersebut. Atas kesepakatan
Pemerintah Kabupaten tanah akan direhabilitasi dan belum dilakukan. Kondisi
vegetasi tertutup kembali menjadi hutan sekunder. Tanah dinyatakan dalam
keadaan status quo. Oleh Wakil Bupati dengan surat kepada Gubernur pada 4
Januari. 2001 dinyatakan bahwa masalah telah selesai apabila para fihak tidak
puas dapat ditempuh jalur hukum.
Kepala Seksi Inventarisasi dan Tata Guna
Hutan Dinas Kehutanan Propinsi Sumatra Selatan menyatakan bahwa dengan
terjadinya euforia reformasi terdapat pihak yang memanfaatkan dengan mengklaim
tanah-tanah yang telah dimanfaatkan oleh pengusaha di bidang kehutanan.
Terkadang cara yang mereka gunakan berbau kriminal. Sebenarnya ini bukan
tuntutan murni dari masyarakat namun diblow-up
oleh banyak pihak yang mempunyai kepentingan atas hal tersebut dan kepentingan
tersebut lebih bernuansa politis. Dengan hilangnya lembaga adat seperti marga
maka diperlukan pendekatan kasus. Terjadi permasalahan dengan masyarakat hukum
adat atau persekutuan hukum adat: Siapa ? Bagaimana kriterianya ? Dengan
hilangnya pasirah karena penghapusan marga maka dengan sendirinya tanah yang
dahulu di bawah kekuasaan marga menjadi tanah negara sedangkan tata batas
kawasan menjadi kabur. Di atas tanah tersebut mungkin terdapat hak milik adat
yang dapat dimiliki secara perseorangan. Setelah tanah tersebut oleh pemerintah diberikan
kepada investor mulailah timbul klaim atas tanah tersebut tanpa dapat dibuktikan
adanya hak tersebut. Dalam masalah ini pemerintah bertindak tidak adil sebagai
mediator dan dan hanya melihat dokumen
terakhir yang berupa tata guna tanah/lahan.
H.A. Koim, Tetua Adat eks Marga Benakat, menjelaskan bahwa terdapat perbedaan
antara tanah marga dan tanah ulayat. Tidak semua tanah yang yang berada di eks
marga dapat dikatakan sebagai tanah marga. Di Benakat terdapat bermacam tanah:
tanah marga, tanah ulayat, tanah perorangan, dan tanah perladangan rakyat.
Tanah marga adalah keseluruhan tanah yang dahulu dikuasai oleh marga, baik yang
masih dikuasai secara bersama untuk didapat manfaatnya ataupun yang sudah
berada di tangan perseorangan, maupun tanah cadangan yang disediakan untuk
masyarakat yang akan membuka hutan bagi
kegiatan pertanian, peternakan dan
lain-lain. Tanah ulayat adalah yang tidak boleh dikuasai secara perseorangan,
diambil manfaatnya untuk kepentingan bersama ataupun perseorangan, diurus
secara terus-menerus dari nenek moyang hingga kini. Tanah perseorangan adalah
tanah perorangan atau tanah milik adat, yang berasal dari tanah ulayat. Tanah
perladangan rakyat adalah tanah yang dicadangkan untuk dibuka bagi beberapa
kepentingan seperti kebun, padang penggembalaan, yang apabila diusahakan secara
terus-menerus akan dapat menjadi tanah
perorangan menurut hukum adat.
Untuk tanah marga yang belum
dibuka/digarap oleh penduduk, dengan dihapuskannya pemerintahan marga akan
sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Daerah untuk mengurus dan
memanfaatkannya. Namun untuk tanah milik adat/perorangan, tanah perladangan
yang telah diusahakan oleh rakyat, dan tanah ulayat, seperti tanah Rimbo Sekampung atau Rimbo Larangan,
Pemerintah Daerah harus memberikan pengakuan haknya. Tanah-tanah tersebut tidak
termasuk lagi dalam tanah eks marga bebas yang beralih kewenangan pengaturan dan
pemanfaatannya kepada Pemerintah Daerah karena di samping telah dimanfaatkan
dan diurus secara turun-temurun oleh warga sejak nenek moyang tanah tersebut
terutama Rimbo Sekampung dan Rimbo Larangan telah mendapat pengakuan tertulis
dari Pemerintah Hindia Belanda sebagai
tanah milik marga /masyarakat Benakat.
Dengan dikeluarkannya Undang Undang
Pemerintah Desa sebenarnya struktur Pemerintahan Adat menjadi kacau. Pendapat
Direktur Walhi Sumatera Selatan ini diterangkannya dengan melihat bahwa Undang
Undang ini yang bernafaskan semangat paradigma pembangunan tidak melihat
masyarakat sehingga posisi dan atau masyarakat hukum adat menjadi tidak jelas.
Lebih-lebih di era globalisasi ini di mana pemerintah sangat memerlukan bantuan
modal dari masyarakat domestik maupun asing pemerintah cenderung memihak ke
perusahaan. Tiada referensi bahwa perusahaan mengembalikan apa yang diklaim
oleh masyarakat adat. Lebih-lebih untuk mengejar PAD pemerintah lebih
mengeksploitasi sumber alam dan sekaligus masyarakat adat. Direktur LBH
Palembang menyatakan bahwa sistem pemerintahan regim yang lalu telah memberikan
represi hukum secara formal kepada masyarakat. Dalam hal hak-hak keagrariaan
adat telah membatasi ruang gerak persekutuan hukum adat. Dengan pembuktian
formal atas sebidang tanah yang berupa sertipikat hak atas tanah telah
menisbikan hak-hak keagrariaan adat tersebut. Demikianlah persepsi masyarakat
dan penguasa tentang hak-hak keagarariaan adat. Untuk lebih memperjelas
bagaimana sikap Pemerintah Daerah (politik hukum agraria) terhadap hak-hak
keagariaan adat di era globalisasai dan otonomi daerah ini.
Muara Enim sebagai daerah potensial yang
mempunyai banyak kekayaan alam dan banyak dilirik investor potensial mengundang
konflik dalam pengadaan tanahnya. Dalam rangka pembangunan pabrik pulp oleh PT Tanjung Enim Lestari Pulp
& Paper seluas 1.600 hektar di desa Muara Niru telah dibebaskan tanah dari
16 desa. Yang terkena langsung adalah desa: Banu Ayu, Muara Niru, Tebat Agung, Gerinam,
Kuripan dan Dalam. Pabrik yang berkapasitas awal 500.000 ton per tahun
memerlukan bahan baku 2.225.000 meter kubik per tahun. Dengan tambahan
kapasitas menjadi 1.000.000 ton per tahun diperlukan dua kali lipat bahan baku.
Dalam proses pengadaan tanah itu terjadi konflik yang berkepanjangan dan
terjadi ekses seperti: pembakaran bahan baku (kayu Akasia Magnium) yang siap
diolah, perusakan pabrik dan penganiayaan beberapa karyawan.
Proses pengadaan tanah dimulai dengan
pengajuan permohonan izin lokasi oleh PT
kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan pada 22 April
1991 dengan surat Nomor 199/PT TEL/IV/1991. Menindaklanjuti permohonan tersebut
telah diadakan peninjauan rencana lokasi pabrik oleh Tim Lahan Daerah Tingkat I
Sumatera Selatan dan Tingkat II Muara Enim dengan hasil: terjadi tumpang tindih
dengan areal PTP 1.100 hektar, terdapat pemukiman 2.400 hektar dan tersedia
areal 1.500 hektar. Kemudian General Manager PT TEL memohon rekomendasi dari
Bupati Kepala Daerah Tingkat II Muara Enim dengan surat Nomor 003/TEL/GM/!994,
28 April 1994 untuk mendirikan pabrik pulp & paper. Hal ini disetujui oleh
Bupati dengan surat Nomor 130/2083/1.1/1994, 6 Juli 1994. Diminta kepada PT
untuk segera mendapatkan ijin lokasi dari Kantor Pertanahan Kabupaten Muara
Enim. Dengan surat Nomor 460/3012/26, 17 April 1995 Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Selatan memberikan petunjuk kepada Kepala
Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim mengenai proses dan persyaratan ijin
lokasi untuk kawasan industri atas nama Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Pada
28 Oktober 1994 dengan Surat Keputusan Nomor 593.82/05884/1 Gubernur Sumatera
Selatan memberikan ijin kepada PT Musi Hutan Persada sebagai perusahaan yang
bergerak di bidang pengusahaan HTI dan masih satu grup dengan PT TEL (Barito
Pacific Group) untuk memanfaatkan lahan seluas 1.250 hektar yang tersedia bagi
pembangunan pabrik pulp & paper. Mulailah PT Musi Hutan Persada membebaskan
lahan untuk keperluan PT TEL tersebut di
antaranya dengan membuka areal Hutan Rimba Sekampung yang bermasalah seperti
telah dibahas di atas. Ternyata ijin diberikan kepada PT Musi Hutan
Persada sedang yang meminta adalah PT
Tanjung Enim Lestari sedang areal yang
diberikan diperuntukkan bagi hutan
tanaman industri, perkebunan karet,
kelapa sawit dan sawah; bukan untuk kawasan industri. Menyadari hal tersebut
Bupati Muara Enim dengan surat Nomor 593/1856/1/1996 pada 29 Juli 1996 meminta
agar pimpinan PT TEL memperhatikan hal
sebagai berikut:
1.
Segera
menghubungi kembali unit kerja terkait di Kantor Gubernur Propinsi Sumatera
Selatan guna penyelesaian nama perusahaan yang mengelola pabrik pulp
& paper yang tertulis atas nama PT Musi Hutan Persada. Seharusnya PT
Tanjung Enim Lestari segera membuat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan
memperoleh persetujuan dari berbagai pihak terkait;
2.
Agar
berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam penggarapan lahan dan pembangunan
pabrik.
Kemudian PT TEL mengajukan rekomendasi untuk wilayah Kecamatan Rambang
Dangku seluas 1.250 hektar dengan surat Nomor 003/TEL/GM/1994 pada 28 April
1994. Menindaklanjuti permohonan tersebut dengan surat Nomor 130/1/1/1994 pada
10 Mei 1994 Bupati memerintahkan dilakukannya peninjauan lapangan terhadap
areal lokasi yang direkomendasikan. Hasilnya adalah bahwa areal yang
direkomendasikan meliputi Kecamatan Rambang Dangku yang terdiri dari desa:
Tebat Agung, Banu Ayu, Gerinam, Niru, Menang dan Kasih Dewa. serta Kecamatan
Gunung Megang yaitu desa Dalam.
Berdasarkan hasil peninjauan lapangan dilakukan inventarisasi para pemilik
tanah/kebun tersebut oleh para Camat wilayah tersebut bersama Kepala Desa yang
terkena proyek. dengan surat Bupati Nomor 130/1584/1.1/1994, 20 Mei 1994.
Setelah itu dilakukan pembebasan tanah berdasarkan:
1.
Surat
Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 593.82/05884/1, 28 Oktober 1994
perihal Ijin Lokasi;
2.
Surat
Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 593.82/05885/1, 28 Oktober 1994
perihal rencana Kawasan Industri Kabupaten Muara Enim ;
3.
Surat
Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 838/BPN/KPTS/HUK/1994 28, November 1994 tentang
Penetapan lokasi tanah seluas lebih kurang 5.000 hektar untuk kepentingan umum
milik Pemerintah yang terletak di desa Dalam, Kecamatan Gunung Megang dan desa
Banu Ayu, Tebat Agung, Gerinam, Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim;
4.
Surat Bupati
Muara Enim Nomor 130/0249/1.1/1995, 25 Januari 1995 perihal penugasan Satuan
Tugas (Satgas) guna pengadaan tanah untuk pembangunan kawasan industri untuk keperluan Pemerintah Daerah;
5.
Surat
Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 909/Sk/IV/1986, 30 Oktober 1986
tentang tarif ganti rugi tanam tumbuh; dan
6.
Surat
Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 244/BPN/KPTS/HUKU/1994, 19 April 1994 tentang
harga dasar tanah.
Berdasarkan ketentuan di atas dilakukan pembebasan lahan pada lokasi
yang direncanakan untuk lokasi pabrik
berdasarkan kebijakan pembebasan lahan untuk kawasan industri pada areal
yang terkena. Bupati menjadi penanggung jawab proyek. Beaya operasional proyek
700 juta rupiah ditanggung oleh PT.
Dalam penetapan lokasi ternyata tumpang tindih dengan perkebunan karet
rakyat dan berada di sebelah hulu pemukiman penduduk. Kegiatan diawali dengan
penyuluhan tentang rencana pembangunan kawasan industri yang dilakukan aparat
Pemerintah Daerah pada 30 Januari 1995 di desa Banu Ayu dan 31 Januari 1995 di
desa Dalam Kecamatan Gunung Megang. Hasilnya adalah sebagian masyarakat membuat pernyataan tertulis
tentang kesediaan melepaskan tanah miliknya berikut segala yang ada di atasnya
untuk keperluan Pemerintah Daerah guna membangun kawasan industri. Di desa
Kuripan diedarkan blanko kosong untuk
ditandatangani yang nantinya berisi pelepasan hak. Beberapa orang pemilik tanah
bersedia menerima ganti rugi berdasarkan tarif
yang ditentukan oleh Gubernur dan harga
yang ditentukan oleh Bupati. Pada 10 Agustus 1995 mereka yang telah
bersedia dapat mengambil uang yang telah disediakan. Pemberian dilakukan
langsung kepada pemilik melalui Simpedes pada BRI Cabang Prabumulih atas nama
yang bersangkutan dengan ketentuan:
1.
Mereka yang
akan segera menggunakan uangnya dapat langsung mengambil dari Simpedes di
Kantor Cabang BRI;
2.
Yang belum
akan menggunakan uangnya dapat terus
menyimpannya dengan Simpedes di BRI.
Hingga akhir
1997 dari 1.250 hektar lahan yang ditargetkan telah berhasil dibebaskan
1.171,903 hektar. Untuk sisanya dilakukan upaya pendekatan. Para pihak yang
belum bersedia menerima tanahnya akan di ‘enclave’
di mana penentuan ganti ruginya atau nilai jual/pelepasan hak per hektar
ditentukan sesuai dengan kesepakatan para pihak. Dalam praktek terjadi
intimidasi dengan menuduh sebagai PKI dan memaksa melepas tanah dengan ganti
rugi 300 rupiah per meter persegi. Keadaan semakin diperburuk dengan hampir
tiada dapat dihadirkannya alat bukti formal yang berupa sertipikat hak atas
tanah karena hampir semuanya adalah tanah-tanah adat yang belum pernah diurus
sertipikatnya. Dalam penerimaan pegawai di PT putra daerah yang bersangkutan
yang melamar tidak satupun dipanggil. Selain itu terdapat beberapa pungutan
liar yaitu: beaya SKT 50.000 per hektar padahal telah dibayar kepada Kepala
Desa, 2,5% dari gantirugi untuk Kecamatan, 1,5% untuk Desa, PBB selama 3 tahun
ke muka. Di desa Dalam aparat melakukan patroli dan razia KTP.Dalam
pelaksanaannya harga yang ditawarkan Panitia/Satgas pengadaan tanah tidak
sesuai dengan harga pasar. Ternyata penetapan Bupati mengacu pada harga 1986,
yaitu 3-5 juta rupiah per hektar, bahkan ada yang hanya 1 juta rupiah per
hektar. Apabila diperhitungkan dengan penghasilan dari menyadap karet sebesar
70.000 rupiah per hektar per minggu itu
hanya akan setara dengan penghasilan petani selama 1 tahun. Padahal kebun karet
itu dapat dinikmati hasilnya selama 20 tahun. Demikian perhitungan yang
dilakukan oleh LBH Palembang. Apabila penetapan ini tidak disetujui Satgas
sering menetapkan bahwa musyawarah dianggap selesai dengan ganti rugi sepihak
tadi.
Hingga awal 1999 pelaksanaan pembayaran
ganti rugi belum selesai. Masyarakat didampingi LBH Palembang menuntut tambahan
ganti rugi yang lebih layak untuk tanah
yang dibebaskan. Masyarakat menuntut tambahan Rp 2.500.000 per hektar sedang PT
TEL hanya bersedia memberi Rp 500.000 per hektar. Dilakukan musyawarah antara
PT TEL dengan wakil masyarakat pada 10
Juni 1999 yang dipandu oleh Asisten Ketataprajaan Setwilda Sumatera Selatan dan
dihadiri oleh tim Satgas dan tim Pemda Sumsel. Disepakati bahwa PT TEL memberi
tambahan sebesar 1.500.000 rupiah per
hektar. Oleh karena itu dikeluarkan SK Gubernur Nomor 367/SK/IV/1999 tentang
kesepakatan nilai imbalan/kompensasi penyelesaian masalah tuntutan masyarakat
desa Banu Ayu, Kuripan, Muara Niru, dan desa Tebat Agung kecamatan Rambang
Dangku Kabupaten Muara Enim dengan tambahan 1.500.000 rupiah per
hektar.Ternyata pembebasan dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 55
Tahun 1993 yaitu Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum. Menurut Keppres
pengadaan tanah harus dilakukan untuk kepentingan pemerintah, dilakukan dan
dimiliki oleh pemerintah, dan tidak mencari keuntungan padahal PT TEL adalah
perusahaan swasta yang tidak melakukan kepentingan dan dimiliki pemerintah,
serta mencari keuntungan. Pembentukan Satgas pembebasan tanah untuk rencana
kawasan industri dilakukan oleh pemerintah untuk kepentingan swasta. Sedangkan
Bupati menjadi penanggung jawab proyek. Hal ini juga menyalah gunakan
kekuasaan. Karena seharusnya tidak
dilakukan oleh pemerintah secara langsung dan dilakukan untuk kepentingan
pemerintah sendiri.
Menurut Surat Edaran Kepala BPN Nomor
580.2/5568/D II/1990 tentang Tim Pengawas dan Pengendali (Wasdal) Pembebasan
tanah untuk keperluan swasta. Tim itu yang terdiri dari :
1.
Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten/Kotamadya sebagai Ketua;
2.
Kepala Seksi
Hak atas Tanah Kantor Pertanahan sebagai
Sekretaris; serta
3.
Kepala Bagian
Pemerintahan Sekretariat Wilayah Daerah;
4.
Kepala Dinas
Pekerjaan Umum/Kepala Dinas Tata Kota/Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman
Pangan/Kepala Dinas Perkebunan, dan
5.
Kepala
Kecamatan setempat.
Semuanya sebagai Anggota Tim bertugas
untuk melaksanakan tugas pengawasan dan
pengendalian pengadaan tanah untuk keperluan swasta. Tugas tim ini adalah:
1.
Memberikan penyuluhan kepada kedua belah pihak tentang bidang
pertanahan;
2.
Membantu
kelancaran pelaksanaan pembebasan tanah dengan memperhatikan kepentingan pihak
yang terkait;
3.
Memberikan
petunjuk kepada para pihak dalam rangka menciptakan suasana musyawarah untuk
mencapai kesepakatan;
4.
Meneliti persyaratan yang diperlukan;
5.
Mencegah ikut
campurnya pihak ketiga yang dapat merugikan para pihak, terutama pemilik tanah;
6.
Mencegah
pembebasan tanpa ijin lokasi;
7.
Menyaksikan
pembayaran atau pemberian ganti rugi antara pemilik yang dengan perusahaan;
8.
Menyampaikan
laporan bulanan kepada Walikota/Bupati tentang pelaksanaan tugas.
Ditegaskan bahwa pembebasan tanah tersebut adalah perbuatan hukum
keperdataan dan pemerintah hanya melakukan pengawasan/pengendalian. Berdasarkan
pasal 2 ayat 2 dan ayat 3 Keputusan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 21 tahun
1994 tentang Tata Cata Perolehan Tanah bagi Kepentingan Perusahaan dalam Rangka
Penanaman Modal dinyatakan bahwa perolehan tanah dilaksanakan langsung antara
perusahaan dengan pemilik hak atas tanah berdasarkan kesepakatan dan pemerintah
melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perolehan tanah tersebut.
Kenyataannya pemerintah bertindak langsung mengadakan tanah dengan alasan bahwa
hal itu dilaksanakan dalam rangka pembangunan kawasan industri Muara
Enim.Ternyata di sini kesiapan Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim dalam
globalisasi sangat besar dalam arti siap membuka diri seluas-luasnya untuk
penanaman modal walaupun harus
mengorbankan diri (rakyat) sendiri. Hal ini dapat dilihat dari:
a. Peranan
besar Pemerintah Daerah bercampurtangan dalam pengadaan tanah bagi penanaman
modal sehingga terjadi penyalah gunaan kekuasaan.
b. Penggunaaan
Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993
sebagai dasar pengadaan tanah untuk kepentingan swasta padahal hal itu khusus
hanya untuk kepentingan umum/pemerintah dengan alasan areal itu termasuk dalam
kawasan industri.
c. Pembentukan
Satgas untuk kepentingan swasta yang langsung melaksanakan pengadaan tanah
padahal mereka hanya bertugas sebagai pengawas dan pengendali.
d. Pengalihan
hak atas tanah dari masyarakat kepada Pemda yang dialihkan lagi kepada PT TEL.
Suatu penyelundupan hukum dalam proses pengadaan tanah dengan dalih untuk kepentingan umum. Kenyataan yang sangat
perih di atas meneguhkan pernyataan Direktur Walhi Palembang bahwa sesungguhnya
dalam rangka pembangunan wilayah dan
pemasukan dana Pemerintah lebih mendahulukan kepentingan pengusaha dibandingkan
dengan masyarakatnya sendiri.
Demikianlah
telah dibahas bagaimana politik hukum agraria dan penerapannya dalam kasus di
Muara Enim, Sumatera Selatan. Hal di atas menunjukkan perbedaan persepsi antara
penguasa dan rakyat sebagai akibat belum idealnya politik hukum agraria kita.
Untuk mengetahui bagaimana selayaknya pola politik hukum agraria ideal ini
baiklah kita bicarakan di bawah ini.
Politik Hukum Agraria Ideal Indonesia Ditegaskan dalam pasal 33 UUD
1945 bahwa politik hukum agraria Indonesia ini ditujukan untuk mencapai
sebesar-besar kemakmuran rakyat. Untuk mencapai tujuan tersebut maka Politik
Hukum Agraria sebagai arah dan petunjuk pelaksanaan hukum agraria Indonesia
selayaknya mengacu pada tatanan
hukum responsif yang dikenalkan
oleh Nonet dan Selznick.[20] Tatanan hukum responsif yang berfungsi sebagai
fasilitator tanggapan terhadap kepentingan dan aspirasi sosial. Dengan demikian
tatanan hukum yang sedemikian ini tentu harus fungsional dalam arti melakukan
fungsinya dalam tatanan hukum agraria; pragmatis yang harus berpandangan jauh
ke depan, mempunyai tujuan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia untuk
mewujudkan masyarakat adil makmur yang berdasarkan Panca Sila; dan juga harus
berwawasan nasional dalam prinsip bineka tunggal ika yaitu satu hukum agraria
nasional dalam keragaman hukum adat yang unik dari satu tempat ke tempat lain
di Indonesia.
Pemikiran yang
berdasar tatanan hukum sedemikian harus
bertujuan atau berorientasi pada kebijakan dengan keadilan yang berdasarkan
prosedur hukum dan bersifat substantif mengutamakan isi dari kebijakan itu
sendiri. Ditegaskan oleh Susanto[21] dengan mengacu kepada cita negara hukum
Indonesia maka politik hukum agraria Indonesia ini harus mewujudkan fungsi
primer hukum yang ada dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu: memberikan perlindungan
kepada masyarakat baik dari pemerintahan, sesama warga maupun ancaman dari
pihak luar; bersikap adil dengan menjaga dan melindungi nilai-nilai yang
diyakini oleh masyarakat; dan melangsungkan pembangunan sebagai sarana
penentuan arah, tujuan dan pelaksanaan, serta pengendaliannya. Secara bijaksana
Notonagoro[22] menjelaskan bahwa politik hukum agraria memberikan arah dan
pedoman bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk bertindak dalam lapangan
keagrariaan sesuai dengan politik hukum agraria tersebut. Politik hukum agaria ini berusaha menyesuaikan
diri dengan keadaan, keperluan dan kepentingan, serta etik hukum agraria umum
yaitu lembaga agraria yang ada, pergolakan pemikiran tentang keagrariaan baik
komunisma/sosialisma maupun individualisma/liberalisma pada umumnya dan etik
hukum agaria khusus di Indonesia yaiu UUD 1945, Panca Sila dan pasal-pasal
UUPA. Politik Hukum Agaraia Indonesia haruslah realistis, religius, dalam arti
bahwa politik hukum agraria tersebut memperhatikan realita yang ada Tidak
hanya: positifis berdasarkan kekuasaan semata, empiris berdasarkan pengalaman
dunia, berpegang pada doktrin dan pendapat ahli; terdapat dasar etika di
dalamnya; serta memperhatikan kaidah religi yang ada. Dengan demikian hendaklah
politik hukum agraria tersebut realistis dengan memperhatikan keadaan yang ada
saat ini baik di Indonesia maupun di dunia baik secara politis, ekonomis,
sosial budaya maupun pertahanan
keamanan; etis dengan tidak lupa memegang teguh dasar kepribadian bangsa
Indonesia, dan religius dengan tidak mengabaikan unsur-unsur yang berdasarkan
pada hukum agama. Mengacu pada Wiradi,
yang dikutip Fauzi[23]
maka selayaknya politik hukum agraria Indonesia ini bercorak neo-populis dengan
menempatkan satuan usaha pada keluarga dengan pertanggung-jawaban yang diatur
oleh negara. Penguasaan tanah dan sarana produksi lainnya tersebar pada
mayoritas keluarga tani. Tenaga kerja adalah tenaga kerja keluarga. Produksi
keseluruahan adalah hasil pekerjaan keluarga tani, walupun tanggung atas
akumulasi modal, biasanya diatur oleh negara. lain halnya dengan strategi
agraria kapitalis. Saran produksi dikuasai oleh individu bukan penggarap.
Penggarapa merupakan pekerja upahan bebas, penjual tenaga yang dibeli dengan
upah oleh pemilik sarana produksi. Dia adalah komoditas. Tanggung jawab
produksi, akumulasi modal, dan investasi, sepenuhnya menjadi tanggung jawab
pemilik sarana produksi.Berkebalikan dengannya adalah strategi agraria
sosialis, tanah dan sarana produksi lainnya dikuasai oleh organisasi (biasanya
negara) atas nama kelompok kerja. Tenaga kerja memperoleh imbalan dari hasil
kerjanya, yang diputuskan oleh organisasi yang mengatas-namakan organisasi
pekerja (negara). Tanggung jawab produksi, akumulasi modal, dan investasi
terletak di tangan organisasi atas nama pekerja (negara). Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 menekankan bahwa
perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Hal
ini sesuai dengan politik agaria populis yang menyatakan bahwa satuan usaha
aadalah keluarga. Ayat 3 pasal ini menandaskan bahwa cabang-cabang produksi
yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan
dipergunakan unrtuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sesuai pula dengan politik
agraria populis yang berkehendak bahwa akumulasi modal diatur oleh negara.
Pasal 6 UUPA menegaskan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.
Jelas bahwa kapitalis/individualis ditentang dan juga sosialis. Bukan kekuasaan
sentral pemerintah namun desentralisasi ekonomi yang diminta. Dalam hal ini
dengan melibatkan partisipasi petani dalam bentuk organisasi masyarakat tani.
Pasal 2 menyatakan bahwa pemerintah mengatur agar sumber-sumber keagrariaan
yang dikuasai oleh negara dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat
sesuai dengan pasal 33 UUD 1945. Politik agraria populis ini sebenarnya sudah
dilaksanakan pada masa Orde Lama (Soekarno) dengan program landreform namun
dengan berkembangnya pemikiran pembangunan pada masa Orde Baru (Soeharto) hal
ini hilang tertelan masa.[24] Notonagoro memberikan 9 (Sembilan) pegangan
yang dapat dijadikan dasar dalam merumuskan dan melaksanakan politik hukum
agraria Indonesia. Dengan berpedoman kepada pemikiran-pemikiran yang telah
dikemukakan di atas diharapkan bahwa politik hukum agraria Indonesia akan dapat
bersifat ideal sesuai dengan kesadaran hukum bangsa Indonesia sehingga
diharapkan untuk paling tidak dapat mengurangi ketegangan yang ada dalam
masalah agraria Indonesia dengan memperkecil konflik antara pengusaha, penguasa
dan masyarat.
Penutup
1. Baik dulu
maupun sekarang keberadaan hak-hak keagrariaan adat dipandang sebagai komoditi bukan asset. Pada
zaman kolonial, hak-hak keagrariaan adat kurang dihargai oleh pemerintah Hindia
Belanda khususnya di eks marga Benakat Sumatera Selatan. Penetapan Hutan
Larangan Rimba Sekampung yang dilestarikan sebagai hutan ramuan, hutan lindung
dan kebun bersama seluruh warga eks marga Benakat dilakukan dalam rangka politik dualisma yang memberlakukan hukum adat terhadap
golongan Bumi Putera. Sekarang keberadaan hak-hak keagariaan adat tidak begitu
dihargai khususnya di eks marga Benakat dengan diberikannya hak untuk
mengusahakan lingkungan hutan di eks marga Benakat kepada para pengusaha baik
nasional maupun asing.
2. Pola politik Hukum Agraria Indonesia terhadap
Hak-hak keagrariaan adat yang seharusnya dirumuskan di masa yang akan datang
adalah politik hukum agraria yang memandang hak-hak keagriaan adat sebagai asset bukan komoditi. Politik hukum agraria
ini seharusnya mewujudkan tiga fungsi primer hukum yang terkandung di dalam
Pembukaan UUD 1945 yaitu: perlindungan, kedailan, dan pembangunan. Politik
Hukum ini bersifat populis yang berdasarkan pada desentralisasi ekonomi seperti
,yang dinyatakan oleh pasal 33 UUD 1945. Politik Hukum agaraia selayaknya
bersifat responsif tehadap kepentinagn sosial dan asdpirasi amsayarakat.
Politik Hukum agraria ini selayaknya mempertimbangkan segala faktor yaitu
subjek, objek, dan hukum serta kekuasaan dan berpedoman kepada 9 (Sembilan) hal
yang berkaitan. Selain itu harus pula mengandung unsur hakiki sifat-sifat yang terkandung di dalam
Pancasila yaitu: Tuhan, Manusia, Satu, Rakyat, dan Adil. Baik pemerintah Hindia
Belanda maupun Orde Baru memandang hak-hak keagrariaan adat sebagai komoditi
yang dapat diambil keuntungan
ekonomisnya sebanyak mungkin bukan sebagai asset yang harus dilindungi
dan dijaga kelestariannya.
3. Pandangan
pemerintah Hindia Belanda berdasarkan semangat kolonialisma dalam mencari
negeri-negri baru sebagai tempat pengambilan sumber ekonomi sedang pandangan
pemerintah Orde Baru berdasarkan semangat pembangunan yang meletakkan hak-hak
keagrariaan adat sebagai sarana utama pelaksanaan pembangunan. Di zaman Hindia
Belanda pandangan kolonialisma ditentang oleh para ahli hukum adat dan para
politisi dengan pandangan Etika-membalas budi mereka.
DAFTAR PUSTAKA
Anderson, Jr E.N, A Malayan Tradition Of The Commons, tanpa
tahun.
Carrier, G. James. Maritim Tenure And Conservation In Papua
New Guinea: Problems In Interpretation, Tanpa
Tahun.
Fauzi, Noer, Penghancuran Populisme Dan
Pembangunan Kapitalisme: Dinamika Politik Agraria Indonesia Pasca Kolonial, dalam Dianto Bachriadi, Erfan Paryadi, dan
Bonnie Setiawan (para penyunting), Reformasi Agraria, Perubahan Politik,
Sengketa dan Agenda Pembaruan di Indonesia. Konsorsium Pembaruan
Agraria dan Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta,
1997.
------,Petani & Penguasa. Dinamika Perjalanan
Politik Agraria Indonesia. INSIST, KPA bekerjasama dengan
PUSTAKA PELAJAR, Yogyakarta; 1998
------,Pluralisme Hukum: Agenda Hukum Agraria Nasional
di Abad 21. Makalah
pada Seminar Hasil Studi atas tanah di Indonesia. Pusat Kajian Pembangunan
Masyarakat Unika Atma Jaya bekerjasama dengan Puslitbang Badan Pertanahan
Nasional, Jakarta, 1998
Harsono, Boedi, Hukum
Agraria Indonesia. Sejarah Pembentukan Undang Undang Pokok Agraria, Isi dan
Pelaksanaannya. Jilid 1, Hukum Tanah Nasional. Penerbit Jambatan, Jakarta,1995.
Slaat, Herman, Peningkatan Kemampuan Institusi BPN dalam
Menghadapi Aturan Pertanahan Masyarakat Majemuk yang Dinamis di Indonesia. Makalah untuk Seminar Hasil Penelitian
Studi Tanah Adat. Pusat Kajian Pembangunan Masyarakat Atma Jaya dan BPN, Jakarta
1998.
Sudiyat, Iman Hukum
Adat, Sketsa AsasPenerbit Liberty, Yogyakarta, 1981.
Mc Cay. Bonnie M. , and James
M. Acheson (eds.),. The Quest of the Commons: The Culture and
Ecology of Communal Resources:. The University of Arizona Press, Tucson,
1987.
Mc Lennan, Marshall
S. . Changing
Human Ecology On The Central Luzon Plain: Nueva Ecija, in Mc Coy, Alfred W.,
and Ed. C. de Jesus (editors), Philippine Social History, Global
Trade and Local Transformations. Ateneo de Manila University Press,
Quezon City, Metro Manila1, 1982.
Mertokusumo,Sudikno,Perundang-undangan
Agraria Indonesia Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1987.
Munarman, Refleksi kasus pertanahan di
Sumatera Selatan, dalam Dianto Bachriadi, Erfan Paryadi, dan Bonnie Setiawan
(para penyunting), Reformasi Agraria, Perubahan Politik, Sengketa dan Agenda Pembaruan di
Indonesia. Konsorsium Pembaruan Agraria dan Lembaga Penerbit Fakultas
Ekonomi Indonesia, Jakarta, 1997.
Notonagoro, Politik Hukum dan Pembangunan
Agraria di Indonesia. CV Pancuran Tujuh, Jakarta,1992.
Warsito Happy , Bineka
Tunggal Ika dalam Hukum Agraria Indonesia: 1. Makalah untuk Mata Kuliah
Teori dan ilmu Hukum. Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro,
Semarang, 1999.
Ritzer,
George
, Modern Sociological Theory, The
McGraw-Hill Companies, Inc. 1996
Romsan, Ahmad, Sertifikasi
Hak-hak atas Tanah Masyarakat Sekitar PT TEL. Unit Penelitian FH-Unsri ,1999.
Nonett, Philippe and Philip
Selznick,. Law
and Society in Transition: Toward Responsive Law. Harper Colophon
Books, New York,1998.
Sampford, Charles , The Disorder of Law. A Critique of Legal Theory. Basil
Blackwell Ltd, Oxford, UK- Basil Blackwell Inc. New York, USA,1989
Sugangga, IGN , Peranan
Hukum Adat dalam Pembangunan Hukum Nasional IndonesiaPidato Pengukuhan
Guru Besar Madya dalam Ilmu Hukum Perdata (Adat) pada Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro, Semarang, 27 November 1999
Susanto, I.S. , Kejahatan
Korporasi di Indonesia Produk kebijakan Rezim Orde Baru, Pidato
Pengukuhan
Gurubesar Madya pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang,1999.
Unger, Roberto
Mangabeira , Law
in Modern Society. Toward a Criticism of
Social Theory. The Free Press.Tanpa Tahun.
Zakaria, Yando , dkk., tt. Mensiasati Otonomi Daerah,Jakarta, KPA.
[1]. Munarman, Refleksi Kasus Pertanahan di
Sumatera Selatan, dalam Dianto Bachriadi, Erfan Paryadi, dan Bonnie
Setiawan (para penyunting), Reformasi Agraria, Perubahan Politik,
Sengketa, dan Agenda Pembaharuan di Indonesia, Konsorsium Pembaharuan
Agraria dan Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta,
1997:342-346.
[2]
Ahmad
Romsan, , Sertifikasi
Hak-hak atas Tanah Masyarakat Sekitar PT TEL. Unit Penelitian FH-Unsri ,1999:56.
[3].
Imam Sudiyat, Hukum adat Sketsa Asas, Luberty, Jakarta, 1981:18.
[4] Happy
Warsito , Bineka
Tunggal Ika dalam Hukum Agraria Indonesia: 1. Makalah untuk Mata Kuliah
Teori dan ilmu Hukum. Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro,
Semarang, 1999:7.
[5] Bonnie M. Mc Cay.. , and James
M. Acheson (eds.),. The Quest of the Commons: The Culture and
Ecology of Communal Resources:. The University of Arizona Press, Tucson,
1987:1,6-7.
6. Mc Lennan, Marshall S. . Changing
Human Ecology On The Central Luzon Plain: Nueva Ecija, in Mc Coy, Alfred W.,
and Ed. C. de Jesus (editors), Philippine Social History, Global
Trade and Local Transformations. Ateneo de Manila University Press,
Quezon City, Metro Manila1, 1982.
.
10.
Charles
, Sampford, The
Disorder of Law. A Critique of Legal Theory. Basil
Blackwell Ltd, Oxford, UK- Basil Blackwell Inc. New York, USA,1989
11.
Philippe
Nonett, and Philip
Selznick,. Law
and Society in Transition: Toward Responsive Law. Harper Colophon
Books, New York,1998.
16. Gunawan Wiradi, dikutif oleh Noer Fauzi,
op.cit.,1991:68
17.
Zakaria, Yando , dkk., tt. Mensiasati Otonomi Daerah,Jakarta, KPA
18.
Noer Fauzi, Petani
& Penguasa. Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia. INSIST, KPA
bekerjasama dengan PUSTAKA PELAJAR, Yogyakarta; 1999. Lihat juga dalam Noer
Fauzi , Pluralisme Hukum: Agenda Hukum
Agraria Nasional Abad 21, Makalah pada Seminar Hasil Studi Atas Tanah
di Indonesia, Pusat Kajian Pembangunan Masyarakat UNIKA Atmajaya bekerjasama
dengan Puslitbang Badan Pertanahan Nasional Jakarta, 1998:3-5.
[19]. Amrah Muslimin, Sejarah Ringkas
Perkembangan Pemerintahan Marga/Kampung Menjadi Pemerintahan Desa/Kelurahan
dalam Propinsi Sumatera Selatan, Penerbit Pemeribntah Propinsi Daerah
Tngkat I Sumatera Selatan, 1986:1-3.
[20]. Philip Nonet dan Philip Selznick, Law
ad Society in Transition: Toward Responsive Law, Harper Colophon,
New York, 1978.
[21]. I S. Susanto, Kejahatan Korporasi di Indonesia Produk Kebijakan Rezim Orde Baru,
Pidato Pengukuhan Guru Besar Madya pada Fakultas Hukum Universitas
Diponegoro, Semarang, 1999.
[22].
Notonagoro,
Politik Hukum dan Pembangunan Agraria di Indonesia, CV Pancuran
Tujuh, Jakarta, 1992.
[23]. Gunawan Wiradi, Reforma Agraria Masalah dan Relevansinya dengan Pembangunan
Jangka Panjang: Suatu Pandangan ke Depan, Bahan diskusi dialog
pertanahan13-14 Agustus 1991, Sekretariat Bina Desa, Jakarta, 1991. Dikutif
oleh Noer Fauzi, Penghancuran Populisme Kapitalisme dan Pembangunan
Kapitalisme: Dinamika Politik Agraria Indonesia Pasca Kolonial, dalam
Dianto Bachriadi, Erfan Paryadi, dan Bonnie Setiawan (para penyunting), Reformasi
Agraria, Perubahan Politik, Sengketa dan Agenda Pembaharuan di Indonesia, Konsorsium
Pembaharuan Agraria dan Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas
Indonesia, Jakarta, 1997.
[24]. Happy Warsito, Studi Terhadap Politik
Hukum Agraria di Indonesia, Simbur Cahaya, Majalah Ilmiah Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya Nomor 19 Tahun VII, Mei 2002, Penerbit Unit Penelitian
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, hal 845-846.