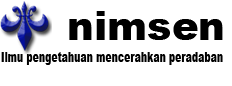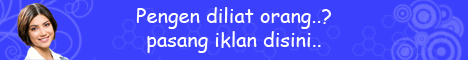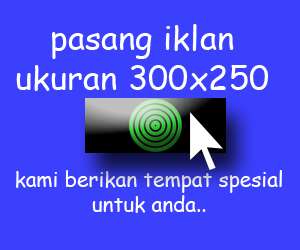PENDAHULUAN
Terima kasih penulis sampaikan dengan ketulusan yang sama kepada seganaptim dosen mata kuliah hokum lingkungan yang telah menyampaikan penulis banyak ilmu yang sebelumnya belum di ketahui.semoga menjadi ilmu yang bermanfaat.
Selain itu terima kasih kepada para dosen pengajar hukum lingkungan yang telah mempercayakan tugas kali ini kepada penulis,yang dengan tugas itu penulis berusaha dengan ketulusan dan ketekunan agar tugas ini selesai dengan baik serta membawa manfaat bagi kita semua.Yang dengan tugas ini pula penulis –dalam proses pengerjaannya-telah banyak menimba ilmu pengetahuan baru seputar obyek tugas ini yaitu undang-undang nomor 23 tahun 1997 yang di perbandingkan dengan undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,beberapa pengetahuan baru yang belum semapat penuis dapatkan di kelas kuliah hokum lingkungan yang senantiasa penulis ikuti.
Selain itu terima kasih kepada para dosen pengajar hukum lingkungan yang telah mempercayakan tugas kali ini kepada penulis,yang dengan tugas itu penulis berusaha dengan ketulusan dan ketekunan agar tugas ini selesai dengan baik serta membawa manfaat bagi kita semua.Yang dengan tugas ini pula penulis –dalam proses pengerjaannya-telah banyak menimba ilmu pengetahuan baru seputar obyek tugas ini yaitu undang-undang nomor 23 tahun 1997 yang di perbandingkan dengan undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,beberapa pengetahuan baru yang belum semapat penuis dapatkan di kelas kuliah hokum lingkungan yang senantiasa penulis ikuti.
Dalam mainstream pemikiran yang berkembang, lingkungan hidup diperlakukan sekedar sebagai obyek manajemen industry dan investasi. Sementara itu kita tahu bahwa misi dari manajemen industrialisasi adalah pemuasan kepentingan para subyeknya yaitu manusia. Lingkungan tidak memiliki makna atau nilai (value) lebih dari sekedar alat pemuas umat manusia.
Dalam kepungan utilitarianism ini menejemen lingkungan hidup terjebak dalam suatu paradoks. Di satu sisi manajemen lingkungan hidup berusaha menekan kerusakan lingkungan hidup, di sisi lain keserakahan ummat tetap diumbar. Lebih dari itu, fokus perhatian kita pada dimensi managerial dalam pengelolaan lingkungan hidup telah menjadikan kita lalai terhadap kenyataan bahwa kemapaanan sistem manajemen sebetulnya juga menyimpan kemampuan umat manusia untuk menghasilkan kerusakan sistemik.
Pandangan yang selama ini telah difahami adalah bahwa, supaya manusia bisa mendapatkan manfaat yang optimal, maka lingkungan hidup harus dikelola. Dalam hal ini, manusia memperlakukan dirinya sebagai subyek dan lingkungan hidup sebagai obyek manajemen. Tersirat di sini, lingkungan hidup yang diatur dan di tata sedemikian rupa sehingga manusia tidak sengsara, umat manusia bisa sejahtera.
Paradigma sustainable lingkungan mengacu pada konsep keadilan yang dimaknai dengan adanya keterwakilan dan pendistribusiannya, terkait dengan bagaimana kebijakan dalam pengelolaan lingkungan hidup dapat menjadi suatu regulasi yang benar-benar mewakili aspirasi dari masyarakat luas.
Paradigma umum berikutnya adalah yang mengacu pada konsep partisipatif. Konsep ini menekankan pada pentingnya pelibatan dari berbagai pihak terkait terutama masyarakat(sebagaimana di jelaskan dalam uu no 32 tahun 2009), dimana didasari dengan adanya kesetaraan dan kebersamaan dalam pengelolaan lingkungan. Diharapkan dengan adanya partisipasi dari berbagai pihak, lingkungan dapat dikelola dengan efektif dan efisien. Mengacu pada kedua paradigma ini, maka perlu ada regulasi hukum yang jelas terkait kepada pengelolaan lingkungan hidup terutama dalam hal pelaksanaannya.
Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Sumber daya alam seperti air, udara, tanah, hutan dan lainnya merupakan sumberdaya yang penting bagi kelangsungan hidup mahkluk hidup termasuk manusia.
Dalam perkembangannya,setidaknya di Indonesia telah di undangkan dua undang-undang spesifik mengenai lingkungan hidup sebagaimana yang akan kita letakkan sejajar sebagai sebuah perbandingan.yang pertama adalah undang-undang nomor 23 tahun 1997 yang kemudian di gantikan dengan undang undang nomor 32 tahun 2009 tentang pemeliharaan dan pengelolaan lingkungan hidup.Seperti halnya kita ketahui bahwa dalam uu 23 tahun 1997 kurang begitu lengkap mengatur tentang masalah lingkungan hidup sehingga perlu banyak tambalan peraturan pemerintah sebagai kedok pelaksana,apalagi jika uu itu tetap di paksakan untuk tetap di terapkan diera sekarang yang mempunyai banyak masalah yang begitu rumitnya yang berhubungan dengan lingkungan hidup.Meski begitu lahirnya uu 32 tahun 2009 bukan lantas semua permasalahan ada solusinya.Apa benar uu ini adalah resep solusi yang mutakhir dan jitu serta berpihak dan memudahkan masyarakat?Ataukah uu ini hanya daur ulang dari undang-undang sebelumnya?
TABEL PERBANDINGAN ANTARA UU NO.23 TAHUN 1997 DENGAN UU NO.32 TAHUN 2009
Undang-undang 23 tahun 1997 | Undang-undang 32 tahun 2009 |
1. Konsideran mengingatberdasarkan UUD 1945 sebelum amandemen. | 1. Konsideran mengingat berdasarkan UUD 1945 pasca amandemen. |
2. Dalam pasal 1 tentang ketentuan umum di jelaskan mengenai pelestarian daya dukung lingkungan. | 2. Tidak di jelaskan mengenai pelestarian daya dukung lingkungan. |
3. Di jelaskan mengenai pelestarian day tampung lingkungan. | 3. Tidak di jelaskan mengenai pelestarian daya tamping lingkungan. |
4. Sumber daya adalah unsur lingkungan bidup yang terdiri atas sumber daya manusia, sumber daya alam, baik hayati maupun nonhayati, dan sumber daya buatan; | 4. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem. |
5. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan; | 5. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. |
6. Tidak ada. | 6. Kajian lingkungan hidup strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS,adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. |
7. Tidak ada. | 7. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. |
8. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya; | 8. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. |
9. Membedakan antara konservasi SDA tak terbaharui dengan SDA terbaharui. | 9. Tidak membedakan SDA tak terbaharui dengan SDA terbaharui. |
10. Tidak ada. | 10. Perubahan iklim. |
11. Tidak ada. | 11. Pengelolaan limbah B3. |
12. Tidak ada. | 12. Pembuangan(dumping). |
13. Audit lingkungan hidup adalah suatu proses evaluasi yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk menilai tingkat ketaatan terhadap persyaratan hukum yang berlaku dan/atau kebijaksanaan dan standar yang ditetapkan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan;Tidak ada ketentuan khusus terhadap perusahaan yang melakukan usaha berresiko tinggi. | 13. Audit lingkungan hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah mendorong penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kinerja lingkungan hidup. Pelaksanaan audit lingkungan hidup terhadap kegiatan tertentu yang berisiko tinggi dilakukan secara berkala. |
14. Tidak ada. | 14. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup. |
15. Tidak ada. | 15. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. |
16. Tidak ada. | 16. Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi,politik, sosial, dan hukum. |
17. Tidak ada. | 17. Instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong Pemerintah, pemerintah daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup. |
18. Tidak ada. | 18. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. |
19. Ruang lingkup lingkungan hidup Indonesia meliputi ruang, tempat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ber-Wawasan Nusantara dalam melaksanakan kedaulatan, hak berdaulat, dan yurisdiksinya. | 19. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi: a. perencanaan; b. pemanfaatan; c. pengendalian; d. pemeliharaan; e. pengawasan; dan f. penegakan hukum. |
20. Pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan, dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. | 20. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas: a. tanggung jawab negara; b. kelestarian dan keberlanjutan; c. keserasian dan keseimbangan; d. keterpaduan; e. manfaat; f. kehati-hatian; g. keadilan; h. ekoregion; i. keanekaragaman hayati; j. pencemar membayar; k. partisipatif; l. kearifan lokal; m. tata kelola pemerintahan yang baik. n. otonomi daerah. Tujuan Pasal 3 Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan: a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia; c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem; d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup; e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup; f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan; g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia; h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana; i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan j. mengantisipasi isu lingkungan global. |
21. Sasaran pengelolaan lingkungan hidup adalah : 1. tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup; 2. terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup; 3. terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan; 4. tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup; 5. terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana; 6. terlindungnya Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha dan/atau kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; | 21. Tidak ada. |
22. Tidak ada. | 22. Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup |
23. Tidak ada. | 23. Pemanfaatan. |
24. Pengendalian dampak lingkungan hidup sebagai alat pengawasan dilakukan oleh suatu lembaga yang dibentuk khusus untuk itu oleh Pemerintah.AMDAL merupakan bentuk pengendalian dampak lingkungan hidup. | 24. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah,pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing. meliputi: a. pencegahan; b. penanggulangan; dan c. pemulihan. |
25. Tidak ada. | 25. Kajian Lingkungan Hidup Strategis. |
26. Di sebut secara singkat dalam bagian perizinan. |
|
27. Disebut secara singkat. |
a. baku mutu air; b. baku mutu air limbah; c. baku mutu air laut; d. baku mutu udara ambien;e. baku mutu emisi; f. baku mutu gangguan; dang. baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. |
28. Di sebut secara singkat serta tidak di atur lebih lanjut. |
|
29. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup untuk memperoleh izin melakukan usaha dan/atau kegiatan. |
|
30. Tidak ada. |
|
31. Tidak ada. |
Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis risiko lingkungan hidup. meliputi: a. pengkajian risiko; b. pengelolaan risiko; dan/atau c. komunikasi risiko. |
32. Tidak ada. |
|
33. Tidak ada. |
a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar; b. remediasi; c. rehabilitasi; d. restorasi; dan/atau e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. |
34. Tidak ada. |
|
35. Tidak ada. |
a. konservasi sumber daya alam; b. pencadangan sumber daya alam; dan/atau c. pelestarian fungsi atmosfe. |
36. 1. Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun.2. Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun meliputi menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, menggunakan dan/atau membuang.3. Ketentuan mengenai pengelolaan bahan berbahaya dan beracun diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. |
|
37. System informasi tidak di atur. |
|
38. Pemerintah berwenang: 1. mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup; 2. mengatur penyediaan, peruntukan, penggunaan, pengelolaan lingkungan hidup, dan pemanfaatan kembali sumber daya alam, termasuk sumber daya genetika; 3. mengatur perbuatan hukum dan hubungan hukum antara orang dan/atau subyek hukum lainnya serta perbuatan hukum terhadap sumber daya alam dan sumber daya buatan, termasuk sumber daya genetika; 4. mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak sosial; 5. mengembangkan pendanaan bagi upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. |
a. menetapkan kebijakan nasional; b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH nasional; d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai KLHS; e. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKLUPL; f. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam nasional dan emisi gas rumah kaca; g. mengembangkan standar kerja sama; h. mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; i. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai sumber daya alam hayati dan nonhayati, keanekaragaman hayati, sumber daya genetik, dan keamanan hayati produk rekayasa genetik; j. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pengendalian dampak perubahan iklim dan perlindungan lapisan ozon; k. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai B3, limbah,serta limbah B3; l. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai perlindungan lingkungan laut; m. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas batas negara; n. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan nasional, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah; o. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan; p. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup; q. mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antardaerah serta penyelesaiansengketa; r. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan pengaduan masyarakat; s. menetapkan standar pelayanan minimal; t. menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; u. mengelola informasi lingkungan hidup nasional; v. mengoordinasikan, mengembangkan, dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup; w. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan; x. mengembangkan sarana dan standar laboratorium lingkungan hidup; y. menerbitkan izin lingkungan; z. menetapkan wilayah ekoregion; dan aa. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup. (2) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,Pemerintah provinsi bertugas dan berwenang: a. menetapkan kebijakan tingkat provinsi; b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat provinsi; c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH provinsi; d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKLUPL; e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat provinsi; f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan; g. mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas kabupaten/kota; h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah kabupaten/kota; i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungandan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; j. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup; k. mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antarkabupaten/antarkota serta penyelesaian sengketa; l. melakukan pembinaan, bantuan teknis, dan pengawasan kepada kabupaten/kota di bidang program dan kegiatan; m. melaksanakan standar pelayanan minimal; n. menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat provinsi; o. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat provinsi; p. mengembangkan dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup; q. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan; r. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat provinsi; dan s. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat provinsi. (3) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kabupaten/kota bertugas dan berwenang: a. menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota; b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten/kota; c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH kabupaten/kota; d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKLUPL; e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota; f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan; g. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup; h. memfasilitasi penyelesaian sengketa; i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan; j. melaksanakan standar pelayanan minimal; k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota; l. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota; m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota; n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan; o. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten/kota; dan p. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota. |
39. Hak dan kewajiban masyarakat. Pasal 5 1. Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. 2. Setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup.3. Setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 6 1. Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. 2. Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup. |
Pasal 65 (1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.(2) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. (3) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. (4) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.(5) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 66 Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Kewajiban Pasal 67 Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Pasal 68 Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:a. memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu; b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan c. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau criteria baku kerusakan lingkungan hidup. Larangan Pasal 69 (1) Setiap orang dilarang: a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;b. memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundangundangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia; d. memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; e. membuang limbah ke media lingkungan hidup; f. membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup; g. melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan; h. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar; i. menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal;dan/atau j. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing. |
40. Peran serta masyarakat : 1. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan; 2. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat 3. menumbuhkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; 4. memberikan saran pendapat; 5. menyampaikan informasi dan/atau menyampaikan laporan. |
a. pengawasan sosial; b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau c. penyampaian informasi dan/atau laporan. Peran masyarakat dilakukan untuk: a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan; c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat; d. Menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. |
41. 1. Menteri melakukan pengawasan terhadap penaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.2. Untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat menetapkan pejabat yang berwenang melakukan pengawasan.3. Dalam hal wewenang pengawasan diserahkan kepada Pemerintah Daerah, Kepala Daerah menetapkan pejabat yang berwenang melakukan pengawasan. |
|
42. Setiap orang dilarang melakukan impor limbah bahan berbahaya dan beracun. |
a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; b. memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundangundangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia; d. memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; e. membuang limbah ke media lingkungan hidup; f. membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup; g. melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan; h. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar; i. menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; dan/atau j. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi,merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar. |
43. Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I berwenang melakukan paksaan pemerintahan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran, serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran, melakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan, dan/atau pemulihan atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-undang. |
a. teguran tertulis; b. paksaan pemerintah; c. pembekuan izin lingkungan; atau d. pencabutan izin lingkungan.Paksaan pemerintah berupa: a. penghentian sementara kegiatan produksi; b. pemindahan sarana produksi; c. penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi; d. pembongkaran; e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran; f. penghentian sementara seluruh kegiatan; atau g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup. |
44. Kepala Daerah dapat mengajukan usul untuk mencabut izin usaha dan/atau kegiatan kepada pejabat yang berwenang. |
|
45. 1. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang usaha dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, dan/atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun, bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan, dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. 2. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup disebabkan salah satu alasan di bawah ini: 1. adanya bencana alam atau peperangan; 2. adanya keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia; 3. adanya tindakan pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. |
|
46. Jika diketahui bahwa masyarakat menderita karena akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sedemikian rupa sehingga mempengaruhi perikehidupan pokok masyarakat, maka instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat. Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan/atau melaporkan ke penegak hukum mengenai berbagai masalah lingkungan hidup yang merugikan perikehidupan masyarakat. |
|
47. Organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memenuhi persyaratan : 1. berbentuk badan hukum atau yayasan; 2. dalam anggaran dasar organisasi lingkungan hidup yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; 3. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya. |
a. berbentuk badan hukum; b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun. |
48. Tidak di atur mengenai hak gugat pemerintah dan pemerintah daerah. |
|
49. Tidak di atur mengenai gugatan administratif. |
|
50. Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang : 1. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup; 2. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang lingkungan hidup; 3. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang lingkungan hidup; 4. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;5. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang lingkungan hidup; 6. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang lingkungan hidup. |
a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain; f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; h. menghentikan penyidikan; i. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual; j. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan,dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana; dan/atau k. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana. |
51. Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. |
|
52. Tidak di atur pengenai penyidik terpadu. |
|
53. Penyidikan tindak pidana lingkungan hidup di perairan Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif dilakukan oleb penyidik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. |
|
54. Tidak di atur mengenai alat bukti. |
a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. surat; d. petunjuk; e. keterangan terdakwa; dan/atau f. alat bukti lain, termasuk alat bukti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. |
55. Tidak jelas dalam undang-undang ini, tindak pidana yang di lakukan tergolong pelanggaran ataukah kejahatan. |
|
56. Secara keseluruhan sanksi pidanayang di terapkan dalam undang-undang ini telah tertinggal serta tidak lagi sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat Indonesia saat ini.secara umum,denda yang di ancamkan dalam undang-undang ini berkisar antara puluhan juta hingga ratusan juta rupiah. |
|
KESIMPULAN
Undang-undang nomor 32 tahun 2009 ini terdiri dari 17 bab dan 127 pasal yang mengatur secara lebih menyeluruh tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perbedaan mendasar antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Undang-Undang ini adalah adanya penguatan yang terdapat dalam Undang-Undang ini tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan
Beberapa point penting dalam UU No. 32 Tahun 2009 antara lain:
- Keutuhan unsur-unsur pengelolaan lingkungan hidup;
- Kejelasan kewenangan antara pusat dan daerah;
- Penguatan pada upaya pengendalian lingkungan hidup;
- Penguatan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, Pendayagunaan perizinan sebagai instrumen pengendalian;
- Pendayagunaan pendekatan ekosistem;
- Kepastian dalam merespons dan mengantisipasi perkembangan lingkungan global;
- Penguatan demokrasi lingkungan melalui akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan serta penguatan hak-hak masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- Penegakan hukum perdata, administrasi, dan pidana secara lebih jelas;
- Penguatan kelembagaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih efektif dan responsif; dan
- Penguatan kewenangan pejabat pengawas lingkungan hidup dan penyidik pegawai negeri sipil lingkungan hidup.
Melalui Undang-Undang ini juga, Pemerintah memberi kewenangan yang sangat luas kepada pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah masing-masing yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Yang dimaksud perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam undang-undang tersebut meliputi:
- Aspek Perencanaan yang dilakukan melalui inventarisasi lingkungan hidup, penetapan wilayah ekoregion dan penyusunan RPPLH
- Aspek Pemanfaatan Sumber daya Alama yang dilakukan berdasarkan RPPLH. Tetapi dalam undang-undang ini telah diatur bahwa jika suatu daerah belum menyusun RPPLH maka pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- Aspek pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup yang meliputi pencegahan, penanggulangan dan pemulihan.
- Dimasukkan pengaturan beberapa instrumen pengendalian baru, antara lain: KLHS, tata ruang, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, AMDAL, UKL-UPL, perizinan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup, analisis resiko lingkungan hidup, audit lingkungan hidup, dan instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.
- Pemeliharaan lingkungan hidup yang dilakukan melalui upaya konservasi sumber daya alam, pencadangan sumber daya alam, dan/atau pelestarian fungsi atmosfer.
- Aspek pengawasan dan penegakan hukum, meliputi :
- Pengaturan sanksi yang tegas (pidana dan perdata) bagi pelanggaran terhadap baku mutu, pelanggar AMDAL (termasuk pejabat yang menebitkan izin tanpa AMDAL atau UKL-UPL), pelanggaran dan penyebaran produk rekayasa genetikan tanpa hak, pengelola limbah B3 tanpa izin, melakukan dumping tanpa izin, memasukkan limbah ke NKRI tanpa izin, melakukan pembakaran hutan,
- Pengaturan tentang pajabat pengawas lingkungan hidup (PPLH) dan penyidik pengawai negeri sipil (PPNS), dan menjadikannya sebagai jabatan fungsional.
o Ada pasal-pasal yang mengatur sanksi pidana dan perdata
Dari 127 pasal yang ada, 23 pasal diantaranya mengatur tentang AMDAL. Tetapi pengertian AMDAL pada UU No. 32 Tahun 2009 berbeda dengan UU No. 23 Tahun 1997, yaitu hilangnya “dampak besar”. Jika dalam UU No. 23 Tahun 1997 disebutkan bahwa “AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup ......”, pada UU No. 32 Tahun 2009 disebutkan bahwa “ AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan .....”.
Hal-hal penting baru yang terkait dengan AMDAL yang termuat dalam UU No. 32 Tahun 2009, antara lain:
- Penyusun dokumen AMDAL wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun dokumen AMDAL;
- Komisi penilai AMDAL Pusat, Propinsi, maupun kab/kota wajib memiliki lisensi AMDAL;
- Amdal dan UKL/UPL merupakan persyaratan untuk penerbitan izin lingkungan;
- Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai kewenangannya
DAFTAR ISI
- Undang –undang nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup.
- undang- undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkukangan hidup.
- http://amdal.intakindo.info
- http://www.menlh.go.id
- http://www.wikipedia.com
- http://www.beswandjarum.com/bakti